Skylashtar Maryam's Blog: Mimpi dan Ilusi, page 13
April 27, 2014
[Cerpen] Ngahyang
(Tribun Jabar, Minggu, 27 April 2014)
 Di desa kami yang sunyi, Sindangwangi, semua orang tak pernah lupa tentang Sukandar. Ia bukan hanya dikenal karena hidupnya yang bagai legenda berjalan, tapi juga karena cara kematiannya yang masih menyisakan pertanyaan janggal. Sampai hari ini, tak ada yang tahu cara paling tepat bagaimana dia mati. Kami hanya tahu bahwa dia mati, tanpa jenazah untuk dikafani, tanpa jejak apa pun untuk kami tangisi. Sukandar hilang begitu saja laksana kabut di belakang bukit yang dimamah matahari. Cerita-cerita tentang Sukandar masih menyisakan semacam kebanggaan sekaligus kisah-kisah seram di benak kami. Bangga karena Sukandar adalah jawara yang di masa hidupnya kerap kali menyelamatkan kami dari kebengalan tukang pukul para tengkulak yang di setiap musim panen selalu merongrong kami. Seram karena kisah tentang Sukandar menjadi semacam legenda yang tak pernah memiliki akhiran. Tak seorang pun, baik yang tua maupun muda, berani mengamini kebenaran apa pun tentang kematian Sukandar. Sepanjang ingatanku yang kini bertambah buram, sosok Sukandar adalah apa yang disebut Emak sebagai lodaya, penjaga makam para raja. Mungkin itu karena tato berbentuk harimau di lengan kanannya. Mungkin juga karena gingsul tepat di sebelah gigi taringnya yang sebelah kiri. Namun, menurut cerita Emak (dalam setiap cerita pengantar tidurnya), Sukandar bukan sembarangan jawara. Sejak usiaku sepuluh tahun, tahun ketika Sukandar menghilang, Emak menganggap Sukandar sebagai pahlawan dan menceritakan kisahnya kepadaku dan adik perempuanku. Tak banyak cerita Emak yang masih bisa kuingat, karena walau bagaimanapun ingatan selalu dibebat hantu bernama masa. Sukandar dalam cerita Emak adalah lelaki yang memiliki keberanian seperti layaknya harimau. Dialah yang menolong Bapak ketika orang-orang berbaju hijau mengangkutnya ke dalam truk karena keributan di kota yang sebetulnya tidak ada sangkut-pautnya dengan Bapak. Sukandar, datang ke (Emak menyebutnya markas) tempat orang-orang berbaju hijau itu. Bapak dibebaskan, dibawa pulang kembali kepada kami. Di desa kami yang sunyi, siapa yang tak mengenal Sukandar? Yang hidup dan matinya masih saja menyisakan pertanyaan. Ada yang bilang ia diculik setan-setan berbaju hijau di tengah malam buta lalu tak kembali. Ada yang bilang ia mengasingkan diri ke gunung, bergabung dengan para pemuda semacamnya; yang di mata negara disebut sebagai ancaman sedangkan di mata kami mereka semua adalah pahlawan. Tapi dari semua isu-isu yang berkeliaran dari tahun ke tahun, kata-kata Emak di suatu malamlah yang sampai sekarang tak dapat hilang dari ingatan. “Sukandar tidak mati, dia hanya ngahyang. Rohnya pergi ke alam keabadian, begitu juga dengan jasadnya. Sehingga mayatnya tidak akan pernah ditemukan. Tapi kita harus percaya bahwa dia akan terus bersama kita dan tak berhenti menjaga.” Jadi Sukandar tidak sempurna pergi. Tidak hidup, tidak pula mati. Ia hanya … ngahyang.*
Di desa kami yang sunyi, Sindangwangi, semua orang tak pernah lupa tentang Sukandar. Ia bukan hanya dikenal karena hidupnya yang bagai legenda berjalan, tapi juga karena cara kematiannya yang masih menyisakan pertanyaan janggal. Sampai hari ini, tak ada yang tahu cara paling tepat bagaimana dia mati. Kami hanya tahu bahwa dia mati, tanpa jenazah untuk dikafani, tanpa jejak apa pun untuk kami tangisi. Sukandar hilang begitu saja laksana kabut di belakang bukit yang dimamah matahari. Cerita-cerita tentang Sukandar masih menyisakan semacam kebanggaan sekaligus kisah-kisah seram di benak kami. Bangga karena Sukandar adalah jawara yang di masa hidupnya kerap kali menyelamatkan kami dari kebengalan tukang pukul para tengkulak yang di setiap musim panen selalu merongrong kami. Seram karena kisah tentang Sukandar menjadi semacam legenda yang tak pernah memiliki akhiran. Tak seorang pun, baik yang tua maupun muda, berani mengamini kebenaran apa pun tentang kematian Sukandar. Sepanjang ingatanku yang kini bertambah buram, sosok Sukandar adalah apa yang disebut Emak sebagai lodaya, penjaga makam para raja. Mungkin itu karena tato berbentuk harimau di lengan kanannya. Mungkin juga karena gingsul tepat di sebelah gigi taringnya yang sebelah kiri. Namun, menurut cerita Emak (dalam setiap cerita pengantar tidurnya), Sukandar bukan sembarangan jawara. Sejak usiaku sepuluh tahun, tahun ketika Sukandar menghilang, Emak menganggap Sukandar sebagai pahlawan dan menceritakan kisahnya kepadaku dan adik perempuanku. Tak banyak cerita Emak yang masih bisa kuingat, karena walau bagaimanapun ingatan selalu dibebat hantu bernama masa. Sukandar dalam cerita Emak adalah lelaki yang memiliki keberanian seperti layaknya harimau. Dialah yang menolong Bapak ketika orang-orang berbaju hijau mengangkutnya ke dalam truk karena keributan di kota yang sebetulnya tidak ada sangkut-pautnya dengan Bapak. Sukandar, datang ke (Emak menyebutnya markas) tempat orang-orang berbaju hijau itu. Bapak dibebaskan, dibawa pulang kembali kepada kami. Di desa kami yang sunyi, siapa yang tak mengenal Sukandar? Yang hidup dan matinya masih saja menyisakan pertanyaan. Ada yang bilang ia diculik setan-setan berbaju hijau di tengah malam buta lalu tak kembali. Ada yang bilang ia mengasingkan diri ke gunung, bergabung dengan para pemuda semacamnya; yang di mata negara disebut sebagai ancaman sedangkan di mata kami mereka semua adalah pahlawan. Tapi dari semua isu-isu yang berkeliaran dari tahun ke tahun, kata-kata Emak di suatu malamlah yang sampai sekarang tak dapat hilang dari ingatan. “Sukandar tidak mati, dia hanya ngahyang. Rohnya pergi ke alam keabadian, begitu juga dengan jasadnya. Sehingga mayatnya tidak akan pernah ditemukan. Tapi kita harus percaya bahwa dia akan terus bersama kita dan tak berhenti menjaga.” Jadi Sukandar tidak sempurna pergi. Tidak hidup, tidak pula mati. Ia hanya … ngahyang.*
Tadinya kupikir kepercayaan Emak terhadap legenda Sukandar akan berkurang bahkan hilang setelah berpuluh tahun, tapi ternyata tidak. Maka ketika kusampaikan kabar bahwa Aisyah, adik perempuan semata wayangku itu hilang, Emak menerima kabar itu dengan tenang.
“Ngahyang,” gumamnya. Tentu saja aku tak setuju. Aisyah bukan jawara, tak memiliki ilmu kanuragan lain selain hafalan Quran dan keimanan. Kami hanya dua orang bersaudara meski setelah dewasa masing-masing dari kami mengambil jalan yang jauh berbeda. Aku lulus dari Fakultas Ekonomi dengan susah payah lalu merintis usaha percetakan di Bandung sedangkan Aisyah lulus dengan gemilang dari Fakultas Hukum kemudian merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai jurnalis. Aku sendiri heran, dengan kemampuannya, Aisyah bisa saja jadi pengacara, bekerja di firma hukum ternama atau mengabdi kepada negara. Tapi bukan Aisyah namanya kalau tidak keras kepala. Baginya, mengejar-ngejar berita dan (menurut istilahnya) mengungkapkan kebenaran adalah sebenar-benar profesi yang ingin ia jalani. Emak dan Bapak, setelah memeras keringat dan air mata untuk dapat menyekolahkan kedua anaknya tetap bersikukuh tinggal di desa. Kecintaan mereka terhadap tanah dan bertani hanya bisa dikalahkan oleh satu kata: mati. Bahkan setelah Bapak meninggal karena usia tua, Emak tak mau juga kubawa hijrah ke Bandung. Padahal aku sudah memiliki penghasilan lebih dari cukup untuk membuatnya hidup senang. Maka kumintalah anak gadis tetangga untuk menjaga dan menemani Emak dengan bayaran yang menurutku pantas. Sebetulnya, aku lebih mengharapkan Emak yang menangis, meraung-raung, meradang atau mencakar-cakar dinding ketika kusampaikan berita tentang menghilangnya Aisyah. Sayangnya, yang kuterima hanyalah gumaman Emak. Tidak ada air mata, tidak ada nada berduka, tidak ada apa-apa. Ketika kuberitahu bahwa Aisyah sudah dua minggu hilang dalam perjalanan dinasnya meliput ladang sawit di Jambi, Emak tetap bergeming. Ketika kusampaikan bahwa kepolisian belum menemukan kemajuan atas penyelidikan yang mereka lakukan, Emak masih saja bungkam. Maka aku menyerah, pulang kembali ke Bandung setelah sebelumnya berjanji untuk terus mengabari. * Mencari orang hilang di Indonesia sama sulitnya seperti menjemput orang mati dari neraka; sia-sia. Pihak kepolisian bahkan sampai kepada spekulasi bahwa Aisyah memang lari atas kemauan sendiri, kawin lari dengan lelaki yang tidak direstui oleh keluarga, mungkin karena beda agama, mungkin juga beda warga negara. Aku sampai harus menahan diri mati-matian untuk tidak menyumpal mulut kotor mereka. Bagaimana tidak, adikku itu bukan tipe perempuan yang bisa menggadaikan keyakinan hanya untuk urusan percintaan. Lagipun, meski kami tinggal berjauhan, kami masih tetap berhubungan. Selama ini, tak sekalipun Aisyah memperkenalkan lelaki sebagai kekasih, apalagi calon suami. Hanya kawan-kawan Aisyah sesama jurnalislah yang percaya bahwa adikku tidak hilang begitu saja. Setelah berbulan-bulan tidak mendapatkan perkembangan, orang-orang AJI dan Kontras mulai rajin datang ke rumah. Tak ada yang bisa kami lakukan kecuali terus mencari dan saling berbagi informasi. Selama berbulan-bulan itulah, aku menghubungi semua orang yang berada di lingkaran Aisyah: teman-teman kuliah, teman-teman tarbiyah, aktivis dakwah, serta teman-temannya sesama relawan di rumah singgah. Tak ada petunjuk berarti kecuali bahwa semasa kuliah sampai terjun menjadi jurnalis, Aisyah memang bisa dikategorikan sebagai perempuan yang “berbahaya”. Berbahaya? Aku nyaris tersedak karena menahan tawa. Selain omongan sadisnya tentang situasi negara dan betapa miskinnya rakyat Indonesia, di mataku Aisyah hanyalah seorang adik perempuan yang selalu nyinyir menyuruhku salat, tak lebih. Tapi kemudian pendapatku terbukti salah ketika suatu hari lima orang berpakaian preman menyatroni rumahku setelah azan Subuh. Mereka membawa surat perintah penggeledahan yang tak kutahu artinya apa. “Menyita dokumen-dokumen yang berbahaya bagi negara.” Hanya itu yang mereka ucapkan sementara aku tak sempat melawan. Komputerku dibuka, semua surel dari Aisyah dibaca, semua berkas yang menurut mereka penting dibawa. Paginya aku membaca berita bahwa majalah tempat Aisyah bekerja dibredel dan ditutup paksa. Beberapa jurnalis juga dinyatakan hilang. Aku mengerti, Aisyah tak akan pernah ditemukan. * Dan di sinilah aku, di sebuah diskusi publik, duduk di kursi pembicara sebagai pihak keluarga korban yang dihilang-paksa. Foto Aisyah, dengan kerudung berwarna jingga, tangan kanan menenteng kamera dan tangan kiri berpegangan pada tiang bendera, dipajang di lorong ruang diksusi. Bersama sederet wajah-wajah lain yang sejak dua tahun lalu, saat Aisyah dinyatakan hilang, kerap kali mendatangkan mimpi buruk untukku. Orang-orang bertanya, menyampaikan bela sungkawa, menepuk pundak dan sesekali melarungkan pelukan. Mungkin ingin berbagi rasa simpati, mungkin ingin sedikit mengurangi rasa nyeri. Emak, yang kupaksa sekuat tenaga untuk hijrah ke Bandung sejak setahun lalu ada di barisan penonton. Tak sanggup berbicara ataupun menyampaikan cerita. Di dalam kepalanya yang sudah berangkat renta, kenyataan mulai meninggalkannya diam-diam. Jadi ia hanya duduk, sesekali matanya memandangi orang-orang, sesekali berdiri lalu duduk kembali. Di tebing acara, seorang lelaki membacakan orasi budaya dengan gempita. Suaranya yang serak meliuk-liuk di telingaku. Dia mengatakan bahwa orang-orang seperti Aisyah adalah pahlawan kemanusiaan. Pahlawan yang tak gentar mencari dan menyampaikan kebenaran, meskipun nyawa sebagai taruhan. Masih dalam orasinya, dia mengatakan bahwa akan lahir Aisyah-Aisyah yang baru. Orang-orang yang tak segan memperjuangkan hak-hak petani, hak-hak kaum minoritas, hak-hak rakyat Indonesia yang senantiasa ditindas. Di dalam telingaku, kembali terngiang legenda Sukandar, pahlawan kampung kami yang tak henti-hentinya diceritakan Emak dalam waktu setahun ini. Pahlawan yang kebenaran hidup dan matinya tidak bisa dijelaskan maupun dipetakan. Tanpa jenazah untuk dikafani, tanpa jejak apa pun untuk kami tangisi. Pun Aisyah, hilang begitu saja laksana kabut di belakang bukit yang dimamah matahari. “Aisyah … ngahyang,” gumaman Emak kembali terngiang. Persetan! Umpatku dalam hati. Aku akan tetap mencarinya meski sampai ke ujung bumi.
(Cimahi, 2014)

 Di desa kami yang sunyi, Sindangwangi, semua orang tak pernah lupa tentang Sukandar. Ia bukan hanya dikenal karena hidupnya yang bagai legenda berjalan, tapi juga karena cara kematiannya yang masih menyisakan pertanyaan janggal. Sampai hari ini, tak ada yang tahu cara paling tepat bagaimana dia mati. Kami hanya tahu bahwa dia mati, tanpa jenazah untuk dikafani, tanpa jejak apa pun untuk kami tangisi. Sukandar hilang begitu saja laksana kabut di belakang bukit yang dimamah matahari. Cerita-cerita tentang Sukandar masih menyisakan semacam kebanggaan sekaligus kisah-kisah seram di benak kami. Bangga karena Sukandar adalah jawara yang di masa hidupnya kerap kali menyelamatkan kami dari kebengalan tukang pukul para tengkulak yang di setiap musim panen selalu merongrong kami. Seram karena kisah tentang Sukandar menjadi semacam legenda yang tak pernah memiliki akhiran. Tak seorang pun, baik yang tua maupun muda, berani mengamini kebenaran apa pun tentang kematian Sukandar. Sepanjang ingatanku yang kini bertambah buram, sosok Sukandar adalah apa yang disebut Emak sebagai lodaya, penjaga makam para raja. Mungkin itu karena tato berbentuk harimau di lengan kanannya. Mungkin juga karena gingsul tepat di sebelah gigi taringnya yang sebelah kiri. Namun, menurut cerita Emak (dalam setiap cerita pengantar tidurnya), Sukandar bukan sembarangan jawara. Sejak usiaku sepuluh tahun, tahun ketika Sukandar menghilang, Emak menganggap Sukandar sebagai pahlawan dan menceritakan kisahnya kepadaku dan adik perempuanku. Tak banyak cerita Emak yang masih bisa kuingat, karena walau bagaimanapun ingatan selalu dibebat hantu bernama masa. Sukandar dalam cerita Emak adalah lelaki yang memiliki keberanian seperti layaknya harimau. Dialah yang menolong Bapak ketika orang-orang berbaju hijau mengangkutnya ke dalam truk karena keributan di kota yang sebetulnya tidak ada sangkut-pautnya dengan Bapak. Sukandar, datang ke (Emak menyebutnya markas) tempat orang-orang berbaju hijau itu. Bapak dibebaskan, dibawa pulang kembali kepada kami. Di desa kami yang sunyi, siapa yang tak mengenal Sukandar? Yang hidup dan matinya masih saja menyisakan pertanyaan. Ada yang bilang ia diculik setan-setan berbaju hijau di tengah malam buta lalu tak kembali. Ada yang bilang ia mengasingkan diri ke gunung, bergabung dengan para pemuda semacamnya; yang di mata negara disebut sebagai ancaman sedangkan di mata kami mereka semua adalah pahlawan. Tapi dari semua isu-isu yang berkeliaran dari tahun ke tahun, kata-kata Emak di suatu malamlah yang sampai sekarang tak dapat hilang dari ingatan. “Sukandar tidak mati, dia hanya ngahyang. Rohnya pergi ke alam keabadian, begitu juga dengan jasadnya. Sehingga mayatnya tidak akan pernah ditemukan. Tapi kita harus percaya bahwa dia akan terus bersama kita dan tak berhenti menjaga.” Jadi Sukandar tidak sempurna pergi. Tidak hidup, tidak pula mati. Ia hanya … ngahyang.*
Di desa kami yang sunyi, Sindangwangi, semua orang tak pernah lupa tentang Sukandar. Ia bukan hanya dikenal karena hidupnya yang bagai legenda berjalan, tapi juga karena cara kematiannya yang masih menyisakan pertanyaan janggal. Sampai hari ini, tak ada yang tahu cara paling tepat bagaimana dia mati. Kami hanya tahu bahwa dia mati, tanpa jenazah untuk dikafani, tanpa jejak apa pun untuk kami tangisi. Sukandar hilang begitu saja laksana kabut di belakang bukit yang dimamah matahari. Cerita-cerita tentang Sukandar masih menyisakan semacam kebanggaan sekaligus kisah-kisah seram di benak kami. Bangga karena Sukandar adalah jawara yang di masa hidupnya kerap kali menyelamatkan kami dari kebengalan tukang pukul para tengkulak yang di setiap musim panen selalu merongrong kami. Seram karena kisah tentang Sukandar menjadi semacam legenda yang tak pernah memiliki akhiran. Tak seorang pun, baik yang tua maupun muda, berani mengamini kebenaran apa pun tentang kematian Sukandar. Sepanjang ingatanku yang kini bertambah buram, sosok Sukandar adalah apa yang disebut Emak sebagai lodaya, penjaga makam para raja. Mungkin itu karena tato berbentuk harimau di lengan kanannya. Mungkin juga karena gingsul tepat di sebelah gigi taringnya yang sebelah kiri. Namun, menurut cerita Emak (dalam setiap cerita pengantar tidurnya), Sukandar bukan sembarangan jawara. Sejak usiaku sepuluh tahun, tahun ketika Sukandar menghilang, Emak menganggap Sukandar sebagai pahlawan dan menceritakan kisahnya kepadaku dan adik perempuanku. Tak banyak cerita Emak yang masih bisa kuingat, karena walau bagaimanapun ingatan selalu dibebat hantu bernama masa. Sukandar dalam cerita Emak adalah lelaki yang memiliki keberanian seperti layaknya harimau. Dialah yang menolong Bapak ketika orang-orang berbaju hijau mengangkutnya ke dalam truk karena keributan di kota yang sebetulnya tidak ada sangkut-pautnya dengan Bapak. Sukandar, datang ke (Emak menyebutnya markas) tempat orang-orang berbaju hijau itu. Bapak dibebaskan, dibawa pulang kembali kepada kami. Di desa kami yang sunyi, siapa yang tak mengenal Sukandar? Yang hidup dan matinya masih saja menyisakan pertanyaan. Ada yang bilang ia diculik setan-setan berbaju hijau di tengah malam buta lalu tak kembali. Ada yang bilang ia mengasingkan diri ke gunung, bergabung dengan para pemuda semacamnya; yang di mata negara disebut sebagai ancaman sedangkan di mata kami mereka semua adalah pahlawan. Tapi dari semua isu-isu yang berkeliaran dari tahun ke tahun, kata-kata Emak di suatu malamlah yang sampai sekarang tak dapat hilang dari ingatan. “Sukandar tidak mati, dia hanya ngahyang. Rohnya pergi ke alam keabadian, begitu juga dengan jasadnya. Sehingga mayatnya tidak akan pernah ditemukan. Tapi kita harus percaya bahwa dia akan terus bersama kita dan tak berhenti menjaga.” Jadi Sukandar tidak sempurna pergi. Tidak hidup, tidak pula mati. Ia hanya … ngahyang.* Tadinya kupikir kepercayaan Emak terhadap legenda Sukandar akan berkurang bahkan hilang setelah berpuluh tahun, tapi ternyata tidak. Maka ketika kusampaikan kabar bahwa Aisyah, adik perempuan semata wayangku itu hilang, Emak menerima kabar itu dengan tenang.
“Ngahyang,” gumamnya. Tentu saja aku tak setuju. Aisyah bukan jawara, tak memiliki ilmu kanuragan lain selain hafalan Quran dan keimanan. Kami hanya dua orang bersaudara meski setelah dewasa masing-masing dari kami mengambil jalan yang jauh berbeda. Aku lulus dari Fakultas Ekonomi dengan susah payah lalu merintis usaha percetakan di Bandung sedangkan Aisyah lulus dengan gemilang dari Fakultas Hukum kemudian merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai jurnalis. Aku sendiri heran, dengan kemampuannya, Aisyah bisa saja jadi pengacara, bekerja di firma hukum ternama atau mengabdi kepada negara. Tapi bukan Aisyah namanya kalau tidak keras kepala. Baginya, mengejar-ngejar berita dan (menurut istilahnya) mengungkapkan kebenaran adalah sebenar-benar profesi yang ingin ia jalani. Emak dan Bapak, setelah memeras keringat dan air mata untuk dapat menyekolahkan kedua anaknya tetap bersikukuh tinggal di desa. Kecintaan mereka terhadap tanah dan bertani hanya bisa dikalahkan oleh satu kata: mati. Bahkan setelah Bapak meninggal karena usia tua, Emak tak mau juga kubawa hijrah ke Bandung. Padahal aku sudah memiliki penghasilan lebih dari cukup untuk membuatnya hidup senang. Maka kumintalah anak gadis tetangga untuk menjaga dan menemani Emak dengan bayaran yang menurutku pantas. Sebetulnya, aku lebih mengharapkan Emak yang menangis, meraung-raung, meradang atau mencakar-cakar dinding ketika kusampaikan berita tentang menghilangnya Aisyah. Sayangnya, yang kuterima hanyalah gumaman Emak. Tidak ada air mata, tidak ada nada berduka, tidak ada apa-apa. Ketika kuberitahu bahwa Aisyah sudah dua minggu hilang dalam perjalanan dinasnya meliput ladang sawit di Jambi, Emak tetap bergeming. Ketika kusampaikan bahwa kepolisian belum menemukan kemajuan atas penyelidikan yang mereka lakukan, Emak masih saja bungkam. Maka aku menyerah, pulang kembali ke Bandung setelah sebelumnya berjanji untuk terus mengabari. * Mencari orang hilang di Indonesia sama sulitnya seperti menjemput orang mati dari neraka; sia-sia. Pihak kepolisian bahkan sampai kepada spekulasi bahwa Aisyah memang lari atas kemauan sendiri, kawin lari dengan lelaki yang tidak direstui oleh keluarga, mungkin karena beda agama, mungkin juga beda warga negara. Aku sampai harus menahan diri mati-matian untuk tidak menyumpal mulut kotor mereka. Bagaimana tidak, adikku itu bukan tipe perempuan yang bisa menggadaikan keyakinan hanya untuk urusan percintaan. Lagipun, meski kami tinggal berjauhan, kami masih tetap berhubungan. Selama ini, tak sekalipun Aisyah memperkenalkan lelaki sebagai kekasih, apalagi calon suami. Hanya kawan-kawan Aisyah sesama jurnalislah yang percaya bahwa adikku tidak hilang begitu saja. Setelah berbulan-bulan tidak mendapatkan perkembangan, orang-orang AJI dan Kontras mulai rajin datang ke rumah. Tak ada yang bisa kami lakukan kecuali terus mencari dan saling berbagi informasi. Selama berbulan-bulan itulah, aku menghubungi semua orang yang berada di lingkaran Aisyah: teman-teman kuliah, teman-teman tarbiyah, aktivis dakwah, serta teman-temannya sesama relawan di rumah singgah. Tak ada petunjuk berarti kecuali bahwa semasa kuliah sampai terjun menjadi jurnalis, Aisyah memang bisa dikategorikan sebagai perempuan yang “berbahaya”. Berbahaya? Aku nyaris tersedak karena menahan tawa. Selain omongan sadisnya tentang situasi negara dan betapa miskinnya rakyat Indonesia, di mataku Aisyah hanyalah seorang adik perempuan yang selalu nyinyir menyuruhku salat, tak lebih. Tapi kemudian pendapatku terbukti salah ketika suatu hari lima orang berpakaian preman menyatroni rumahku setelah azan Subuh. Mereka membawa surat perintah penggeledahan yang tak kutahu artinya apa. “Menyita dokumen-dokumen yang berbahaya bagi negara.” Hanya itu yang mereka ucapkan sementara aku tak sempat melawan. Komputerku dibuka, semua surel dari Aisyah dibaca, semua berkas yang menurut mereka penting dibawa. Paginya aku membaca berita bahwa majalah tempat Aisyah bekerja dibredel dan ditutup paksa. Beberapa jurnalis juga dinyatakan hilang. Aku mengerti, Aisyah tak akan pernah ditemukan. * Dan di sinilah aku, di sebuah diskusi publik, duduk di kursi pembicara sebagai pihak keluarga korban yang dihilang-paksa. Foto Aisyah, dengan kerudung berwarna jingga, tangan kanan menenteng kamera dan tangan kiri berpegangan pada tiang bendera, dipajang di lorong ruang diksusi. Bersama sederet wajah-wajah lain yang sejak dua tahun lalu, saat Aisyah dinyatakan hilang, kerap kali mendatangkan mimpi buruk untukku. Orang-orang bertanya, menyampaikan bela sungkawa, menepuk pundak dan sesekali melarungkan pelukan. Mungkin ingin berbagi rasa simpati, mungkin ingin sedikit mengurangi rasa nyeri. Emak, yang kupaksa sekuat tenaga untuk hijrah ke Bandung sejak setahun lalu ada di barisan penonton. Tak sanggup berbicara ataupun menyampaikan cerita. Di dalam kepalanya yang sudah berangkat renta, kenyataan mulai meninggalkannya diam-diam. Jadi ia hanya duduk, sesekali matanya memandangi orang-orang, sesekali berdiri lalu duduk kembali. Di tebing acara, seorang lelaki membacakan orasi budaya dengan gempita. Suaranya yang serak meliuk-liuk di telingaku. Dia mengatakan bahwa orang-orang seperti Aisyah adalah pahlawan kemanusiaan. Pahlawan yang tak gentar mencari dan menyampaikan kebenaran, meskipun nyawa sebagai taruhan. Masih dalam orasinya, dia mengatakan bahwa akan lahir Aisyah-Aisyah yang baru. Orang-orang yang tak segan memperjuangkan hak-hak petani, hak-hak kaum minoritas, hak-hak rakyat Indonesia yang senantiasa ditindas. Di dalam telingaku, kembali terngiang legenda Sukandar, pahlawan kampung kami yang tak henti-hentinya diceritakan Emak dalam waktu setahun ini. Pahlawan yang kebenaran hidup dan matinya tidak bisa dijelaskan maupun dipetakan. Tanpa jenazah untuk dikafani, tanpa jejak apa pun untuk kami tangisi. Pun Aisyah, hilang begitu saja laksana kabut di belakang bukit yang dimamah matahari. “Aisyah … ngahyang,” gumaman Emak kembali terngiang. Persetan! Umpatku dalam hati. Aku akan tetap mencarinya meski sampai ke ujung bumi.
(Cimahi, 2014)

Published on April 27, 2014 03:44
April 26, 2014
[Cerpen] Riwayat Hujan

“Tidak ada yang salah dengan cinta, Ken. Yang salah barangkali adalah kita yang selalu berusaha mendefinisikan dan mengkotak-kotakkannya tiada henti, dari hari ke hari,” matamu mengeja hujan di luar yang berlari-lari liar, sementara tanganmu menggenggam sebuah kunci kamar.
“Aku harus pergi,” kemudian secepat kilat engkau melesat, membelah hujan. Tak menyisakan sedetik pun waktu untukku mencegah langkahmu.
Ay, malamku sempurna hitam, penuh arsiran legam saat tubuhmu beranjak dari ambang pintu. Menuju kelam, dan hujan di luar. Bau parfummu masih tercium di dalam ruang, mengajakku menziarahi tawa yang bergelimpangan. Bahkan helai-helai rambutmu tersisa di atas bantal sofa.
Malam menjadi begitu asing, begitu genting. Kita berdua menjadi sepasang kunang-kunang di beranda tempat peribadatan dan harus melulu berkelit dari rajaman. Tapi sesakit apakah mencintai kamu, Ay? Setikam apakah merindukan kamu?
Diam-diam, masih diam-diam. Kusebut namamu di belantara doa yang begitu lelap. Kurapal wajah dan tubuhmu di baris sajak-sajak. Agar mengabadi engkau di sini, di dalam dadaku.
Sedetik yang lalu aku adalah laki-laki yang sedang jatuh cinta, di detik kemudian aku berubah menjadi tak merasakan apa-apa. Ada yang hampa, ada yang tak mungkin kusua. Lalu ke mana cinta bermuara? Ke mana seluruh rasa sakit meniada? Akan lebih baik jika dadaku berdarah, bernanah, mulutku berteriak mengeluarkan berbagai macam kelepak amarah. Akan lebih baik tanganku berontak, kakiku menjejak-jejak. Tapi tidak, tidak ada. Ay … hujan membawamu pergi, semoga kelak hujan yang sama membawamu kembali.*
“Andaikan aku bisa,” tanganmu gelagapan, bibirmu bergetar-getar.
Kenapa pernyataan cinta saja bisa begitu menyedihkan? Bisa begitu mendidihkan perasaan? Tidakkah seharusnya cinta disambut dengan semringah dan tepuk tangan meriah?
Aku sedang membayangkan sepasang kekasih yang tangannya saling menggenggam seperti di film-film roman ketika bahumu berguncang. Cokelat panas yang tadi kaupesan mulai mendingin di dalam cangkir. Cangkir yang kaugenggam erat dengan getar yang semakin hebat.
“Jangan menangis,” bisikku.
Seharusnya aku segera pindah duduk ke sampingmu, kemudian merengkuh kamu dalam pelukanku. Seharusnya aku menggenggam tangan getarmu, menenangkan kamu dengan kalimat-kalimat penghiburan yang aku tahu. Tapi hanya bisik itulah yang mampu keluar, sebab orang-orang mulai menatap kita dengan nanar dan liar.
“Ay … kumohon jangan menangis,” bisikku lagi.
Kepalamu menggeleng kuat-kuat. “Jangan jatuh cinta kepadaku, Ken,” kau menggumam.
Apa kau tahu? Bagaimana sulitnya menyetir hati agar berderap ke arah yang diinginkan kepala kita, Ay? Aku lebih baik jadi Sisifus yang mendorong batu ke puncak bukit seumur hidup daripada harus mengingkari debar yang kupunya untukmu.
“Tapi aku jatuh cin ….”
“Jangan!” kau memotong kalimatku cepat. “Jangan …” kepalamu kembali menggeleng kuat.
“Ay … dengarkan aku,” jemariku berlayar ke pipimu. “Andaikan aku bisa memilihkan takdir untuk cintaku sendiri, mungkin aku akan memilih untuk mencintai orang lain saja. Tapi seperti yang kita tahu, cinta memiliki takdirnya sendiri, menyetir kita berdua seperti dua perahu yang diseret gelombang. Kita tak pernah tahu akan ke mana kita sampai.”
“Ken, aku tidak pantas dicintai oleh kamu,” katamu.
“Berhentilah mengkotak-kotakkan cinta, berhentilah memasang jeruji di dalam asmara, Ay. Cinta ya cinta, pantas atau tidak, layak atau tidak. Cinta tidak akan berubah,” kataku. Walau aku sendiri tak yakin dengan semua kalimat yang berloncatan itu.
Bukannya berhenti, kamu malah semakin tersedu, senja seketika berubah biru. Padahal, apa yang salah dengan saling mencinta? Tahukah kau? Toh kita tidak sedang melakukan apa pun kecuali duduk di bangku-bangku di pelataran pusat perbelanjaan ini. Kita hanya duduk, menikmati senja, uar roti panas, dan secangkir cokelat hangat. Dan tentu saja, dengan debar di dada yang semakin hebat. Tidak ada yang salah dengan itu, bukan?
“Jangan cintai, aku ...” kau kembali bergumam.
“Lalu bagaimana dengan kamu? Cintakah kamu padaku?” wajahku getas, suaraku layaknya gemerisik kertas di tengah sunyi yang renggas.
Kau mendongak. Tak usah kau jawab, Ay. Matamu telah mengatakan apa saja yang tak akan keluar dari bibirmu. Kau … juga jatuh, kepadaku.
“Mari kuantar kamu pulang,” kataku ketika tak ada lagi kata-kata yang sanggup kita rapal.
“Tidak usah, terima kasih. Aku pulang sendiri saja,” kau segera menolak, lalu beranjak. Aku pun berjalan gontai, menuju arah yang berlawanan.
Engkau selalu menjadi hantu dalam tidurku, Ken.
Larik pesanmu dahulu kembali terngiang. Ah, Ay …. Tidur adalah juga riwayat, cerita-cerita tentang ritual purba ketika tangan-tangan angin memeluk tubuh kemudian berakhir dengan jenuh. Dan aku kembali berbaring dalam gigil, karena mimpi alpa untuk mampir. Sehingga aku dirajam keterjagaan, dibebat keinginan demi keinginan. Ketika kenyataan tak sesuai dengan apa pun yang kita harapkan. *“Andai kita bertemu dan saling jatuh cinta bertahun-tahun yang lalu, sebelum keadaan tidak sebegitu suram,” katamu di malam terakhir kita bertemu.
Aku tahu, untuk sampai kepadaku, dirimu telah berjuang dengan kebohongan-kebohongan, menasbihkan pembenaran di dada kita masing-masing agar kebersamaan tidak sedemikian asing. Sementara aku, untuk sampai kepadamu tidak harus melewati onak, barangkali hanya debur riuh, itu pun dari dadaku sendiri. Aku hanya perlu keluar dari kamar kos, turun ke jalan, menyambutmu datang, lalu sampai kepadamu. Kau, Ay …. Harus mengarang banyak alasan, harus berjibaku dengan jawaban atas beragam pertanyaan. Pertanyaan yang dilontarkan orang-orang, pertanyaan yang dilontarkan oleh tunanganmu.
“Kita tidak bisa memutar waktu, Ay. Pun tidak bisa mengekang keadaan sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan,” aku menunduk, memandangi ujung kuku yang tadi kau potongi.
“Andai aku tidak menyetujui lamaran orang tua Yusuf, andai aku lebih mengenalmu sewaktu kita sama-sama di SMU dulu. Andai kita memutuskan untuk saling jatuh cinta sejak dulu, bukan sekarang, bukan saat ini,” suaramu berubah dingin.
“Mungkin cinta hanya mengambil jalan memutar,” aku tenggelam ke dalam berbagai andai yang kau sebutkan.
“Jalan berputar yang begitu jauh,” matamu beralih kepada debar layar kaca tak jauh dari sofa.
Entahlah, Ay. Aku sendiri tak mampu menerka jarak perjalanan hidup kita. Lagipula, bukankah cinta datang secara tiba-tiba dan tanpa dipaksa? Kita pun tak tahu kapan ia datang. Yang kita tahu, tiba-tiba saja kita berdua telah dibuat mabuk olehnya. “Kapan kita pertama kali bertemu kembali?” tanyamu tiba-tiba.
“Sore di tengah gerimis di bulan September, empat minggu yang lalu,” jawabku.
Engkau terdiam, matamu menerawang, mungkin memandangi sudut dinding tempat laba-laba bersarang, atau mungkin tenggelam ke dalam kenang.
Ya, aku masih ingat, waktu itu di tengah serbuk gerimis kau berlari kecil, menyebrangi tempat parkir, menujuku yang tengah menunggu di bawah tingkap pusat perbelanjaan. Engkau tersenyum canggung, ragu-ragu mengulurkan tangan sementara sebelah tanganmu kalut merapikan rambut. Kau nyaris kuyup, tapi wajahmu semringah tanpa kabut.
Sebelum itu kita memang sudah sering bertukar pesan di telepon genggam, berbagi catatan demi catatan di media sosial. Engkau penulis, mudah saja bagimu menanak kata-kata hingga matang dan kau suguhkan ke dalam catatan. Sementara aku? Aku harus mengais-ngais segala pelajaran, semua tentang teknis mengolah pesan agar kata-kata tidak lagi tersendat melainkan berlarian. Aku hanya mahasiswa biasa, tanpa keahlian apa-apa.
“Dan kapan tepatnya kita mulai merasa saling jatuh cinta?” pertanyaanmu melemparkan aku kembali dari lamunan.
“Mungkin …” aku berhenti sebentar. “Sejak aku menyatakan cinta di pelataran pusat perbelanjaan waktu itu, waktu kamu menangis dan mengatakan supaya aku jangan jatuh cinta padamu. Lalu setelah itu kamu pulang.”
“Tidak, sepertinya lebih lama dari itu. Ken,” kau menggenggam tanganku. “Cobalah mengingat. Kapan tepatnya kita mulai jatuh cinta? Aku hanya ingin mengurai, sejak kapan kita mulai tersesat.”
Tolong jangan paksa aku mengais-ngais kembali gorong-gorong rasa sakit, Ay. Jatuh cinta kepadamu tidak mudah, pun menghitung detik-detik ketika merindukanmu. Lalu aku harus mulai dari mana? Mungkin sejak kita bertemu kembali di dunia maya setelah bertahun-tahun dipisahkan rentang jarak. Mungkin sejak pesan-pesanmu sampai, sejak catatan-catatanmu bersemai. Atau sejak suaramu kerap membingkai telinga pada malam-malam yang temaram. Barangkali juga sejak waktu itu, ketika kita pertama kali bertemu kembali dan kau menghadiahkan bingkai berisi bunga kering dan daun-daun yang kau rangkai sendiri.
Sejak saat itukah? Aku tak tahu pasti, Ay. Yang aku tahu pelupuk mataku tak hanya berisi pesan dan catatan-catatan, melainkan juga berisi derai tawa dan binar mata. Binar matamu.
“Aku jatuh cinta kepadamu sejak aku memberikan bingkai itu,” nah kan, akhirnya kau mengaku bahwa kau juga jatuh cinta kepadaku.
“Kenapa?” kutelusuri matamu, mencari kebenaran, mencari pembenaran.
Kau menggedikkan bahu. “Bukankah cinta tidak memerlukan alasan? Persis seperti katamu. Cinta ya cinta, jatuh begitu saja. Lalu kenapa kamu mencintai aku?” kau mengajukan pertanyaan yang sama.
“Hanya mengikuti jalur nasib, hanya mengikuti debar-debar di dada,” jawabku asal-asalan.
Kau tertawa, renyah. “Aku yang penulis, kenapa justru kamu yang puitis?”
Cinta bisa menyulap siapa pun menjadi penulis dan puitis, Ay. Aku tidak perlu menjadi Neruda atau Gibran hanya untuk merayumu. Aku mengangkat bahu. “Mungkin karena aku terlalu sering membaca dan mengoleksi catatan-catatan facebook-mu.”
“Kita telah terlalu jauh tersesat,” tiba-tiba suaramu tercekat. Tawamu yang barusan berjatuhan hilang, berganti kembali menjadi muram.
“Lalu di mana jalan pulang yang benar?” aku tersenyum, sinis dan miris.
Kau mendengus, matamu menghunjam mataku dengan tatapan penuh hunus. Ada gelegak amarah yang barangkali sebentar lagi akan tumpah. “Apa sebaiknya kita berhenti bertemu? Aku tak bisa terus-menerus begini, menemuimu secara sembunyi-sembunyi, berusaha menahan nyeri,” kau menggigit bibir.
Aku tertawa, terbahak-bahak, seperti orang gila. Apakah kalimatmu benar-benar berasal dari pikiran paling benar dan nalar?
“Cinta tak dapat dikekang, Ay. Tidak semudah itu,” akhirnya aku berhenti tertawa setelah kau meninju bahuku.
“Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tak bisa begitu saja membatalkan pertunangan hanya karena mencintai kamu, laki-laki yang berasal dari masa lalu.”
“Mungkin kita memang tak harus bertemu waktu itu,” ujarku, mulai kehabisan kata-kata.
“Mungkin kita tak harus bertemu lagi nanti,” kemudian kau mencangklongkan tas, bangkit dari sofa dan bersiap pergi.
“Apa yang salah dengan cinta?” aku ikut bangkit, berusaha mencegahmu pergi. “Apa yang salah dengan mencintai kamu?”
“Tidak ada yang salah dengan cinta, Ken. Yang salah barangkali adalah kita yang selalu berusaha mendefinisikan dan mengkotak-kotakannya tiada henti, dari hari ke hari,” matamu mengeja hujan di luar yang berlari-lari liar, sementara tanganmu menggenggam sebuah kunci kamar.
“Aku harus pergi,” kemudian secepat kilat engkau melesat, membelah hujan. Tak menyisakan sedetik pun waktu untukku mencegah langkahmu. * Selalu saja ada yang berdetak hebat ketika tanggal di kalender perlahan menyelusup, diam-diam berhembus dan menggusur hari semakin jauh. Aku kerap tidak pernah beranjak dari jalan itu, tercekam keramaian tapi tetap saja merasa sendirian. Sesakit apakah harus mencintaimu?
Jika saja, ya jika saja aku diberi kekuasaan untuk membunuh waktu, maka saat itu juga akan kutikam detik agar ia berhenti berderik. Akan aku ganjal semesta supaya tak usah berputar. Agar aku akan terkapar selamanya di senyummu, lirik matamu, dan tawa tertahanmu. Tapi imaji dibuat untuk selalu dikhianati, Ay. Begitupun aku, terlebih lagi kamu.
Aku tenggelam dalam jutaan kata jika dan andai saja. Sama seperti kamu dahulu. Tahukah kau bahwa betapa cekam segala risau yang menikam ketika hujan akhirnya berhenti dan engkau harus pergi? Aku ingin hujan bertahun turun agar kau tak harus pulang. Tapi kenyataan selalu saja lebih menyakitkan dari impian paling liar, bukan?
Hujan itu, senja itu, jalan itu, dan tanggal di penghujung musim itu adalah stasi yang tak akan lagi kita miliki. Sebab aku, juga kamu, telah sama-sama menolak untuk bertolak. Bahkan ketika cinta berteriak di dalam kotak. Ketika asmara ingin berlari dan mendobrak.
Namun, Ay. Aku akan selalu kembali ke jalan itu, ke tanggal itu. Demi segala kenang, riwayat, dan sejarah yang telah kita rajahkan di atas trotoar. Aku menunggu, semoga hujan tidak usah reda dan engkau akan selalu bergelung di dalam dada, meski hanya sebatas sebuah nama.
Ayesha ....
***

Published on April 26, 2014 06:12
April 25, 2014
[Resensi] Memasak Cerpen-Cerpen Damhuri Muhammad
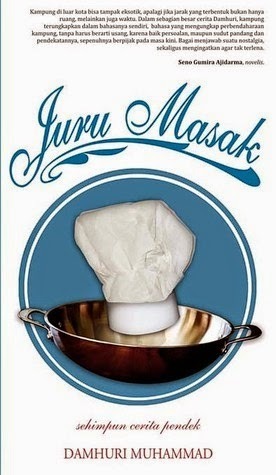
Judul: Juru Masak (Kumpulan Cerpen)
Penulis: Damhuri Muhammad
Penerbit: Penerbit Koekoesan (Maret, 2009)
Halaman: xii+158 halaman
ISBN: 978-979-1442-23-7
Menulis cerpen, bagi saya, seperti meraut sepasang bilah layang-layang. Butuh ketelatenan untuk terus-menerus meraut kedua bilah itu dari pangkal hingga ujung, sampai permukaannya benar-benar halus, dan imbang bila ditimbang.
-Damhuri Muhammad-
Kelebihan cerpen-cerpen Damhuri Muhammad adalah pengolahan dan penyajiannya yang paripurna. Setiap tema, alur, penokohan, bahkan kata per kata seperti dipilih dengan hati-hati dan diracik dengan sempurna.
Seperti dalam kata pengantarnya, Bang Dam (begitu saya kerap memanggilnya) mengatakan bahwa menulis cerpen baginya seperti meraut sepasang bilah layang-layang. Butuh ketelatenan untuk terus-menerus meraut kedua bilah itu dari pangkal hingga ujung, sampai permukaannya benar-benar halus, dan imbang bila ditimbang.
Jika Anda mengikuti perkembangan atau memerhatikan cerpen-cerpen Bang Dam, di berbagai buku kumplulan cerpen atau karya-karyanya yang terserak di berbagai media, Anda akan menemukan kualitas karya yang senantiasa terjaga. Sekarang saya mengerti tentang "pabrikasi" cerpen yang sering beliau sampaikan.
Nah, sebetulnya saya ingin sekali memberikan empat bintang untuk kumcer ini, kalau perlu lima bintang. Karena saya sudah jatuh cinta bahkan sejak membaca kata pengantarnya.
Sayangnya bintang itu terpaksa saya kurangi karena ending di dalam setiap cerpen di dalam kumcer ini. Di setiap awal dan tengah cerpen-cerpennya, alur dan narasi masih terjaga, tapi ketika masuk ke bagian ending, benang layang-layang itu mulai kendor. Entah karena kehabisan tenaga, atau karena memang disengaja. Bukan, bukan ending yang dibuat dengan tergesa, lebih karena ada semacam keterputusan antara konstruksi cerpen; awal-tengah-akhir.
But overall, cerpen-cerpen di dalam kumcer ini keren.

Published on April 25, 2014 18:45
April 22, 2014
Talk Show Neo Srikandi Jurnalistik "Power of Women"

Acara: Talk Show Neo Srikandi Jurnalistik "Power of Women"
Pembicara: Langit Amaravati (Penulis), Citra Mustikawati (Penyiar PR FM), Tristia Riskawati (Pemred Salman Media)
Hari/Tanggal: Rabu, 23 April 2014
Waktu: 09.00-12.00
Tempat: Aula Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN SGD, Bandung

Published on April 22, 2014 02:48
April 21, 2014
[Cerpen] Anak Matahari
(Juara II Lomba Cerpen LPM Edukasi Dasar, 2012)
 Foto: Irvan Mulyadie
Foto: Irvan Mulyadie
Kau berdiri gamang di atas trotoar, tepat di perempatan jalan. Matamu melirik lampu yang menyala hijau kemudian berganti kuning. Gelisah. Wajahmu yang kumal karena memang dibuat kumal dan dihiasi coretan debu serta lumpur mengernyit-ngernyit, menahan rasa sakit. Ketika lampu berubah merah, kau terpincang-pincang, tertatih menyusuri jalan, mendatangi kendaraan demi kendaraan. Dadamu berdebar-debar kencang saat tak satu pun dari pengemudi atau penumpang memasukkan uang ke dalam kaleng yang kausodorkan. Hari ini pasti mengerikan, lebih mengerikan dari kemarin. Benakmu merapal sesal, sedikit kesal. Ya, hari kemarin kau terpaksa pulang dengan pendapatan seadanya yang tentu saja membuat perempuan yang kau panggil emak menandak-nandak dalam amarah. Ia, perempuan dengan gincu merah menyala dan maskara tebal membingkai mata itu melayangkan pukulan demi pukulan kepada kakimu yang ringkih. “Dasar anak tak tahu diri! Pemalas benar kamu ini. Apa saja yang kamu lakukan di jalan, hah? Main-main?” gagang sapu mendarat di kakimu, ditingkahi teriakan dan cacian perempuan itu. Kau menangis, meraung-raung meminta ampun, dan berjanji akan bekerja lebih keras lagi, tapi pukulan itu tak jua berhenti hingga kakimu bengkak, lebam, berderak-derak ketika dibawa berjalan. Mungkin kakimu sempurna patah, tapi kau tak peduli sepanjang nyawa masih ada di kerongkongan, sepanjang kau masih bisa menatap matahari esok pagi. Bagimu, hidup yang keras bukan hanya cerita-cerita di atas kertas. Masih terpincang-pincang, kau meringis, menerus menyusuri jalan dan menyodorkan kaleng kosong kepada setiap pengemudi dan penumpang kendaraan. Sebagian dari mereka tentu berpikir bahwa kakimu yang tertatih hanyalah pura-pura, wajahmu yang letih juga palsu belaka. Tapi tak seorang pun tahu apa yang sedang berlarian di dalam kepalamu; rasa takut sekaligus putus asa yang kalut dan berlarut-larut. Tepat di pinggir sebuah angkutan kota, kau kembali menyodorkan kaleng kepada para penumpang, bergumam-gumam meminta rasa kasihan. Sebetulnya engkau tahu, bahwa hal itu lebih hina dari apa pun, tapi kau tak bisa menyangkal karena memang hidup tak memberi banyak pilihan. Seorang anak perempuan seusiamu, masih memakai seragam sekolah, duduk di angkot sambil menjilati es krim di dalam corong. Anak perempuan itu bersandar kepada seorang perempuan yang kautebak sebagai ibunya. Ada beberapa kantong belanjaan di pangkuan mereka, dua kotak sepatu dan entah apa lagi. Kau melirik jengah kepada dua kotak sepatu itu, memandang kakimu sendiri yang telanjang sedari tadi. Kau juga melirik gelisah, nyaris iri kepada pakaian seragam anak perempuan itu dan mulai membandingkan dengan pakaian kumalmu. Kau berpikir, betapa orang lain memiliki segalanya dan kau tak memiliki apa-apa. Lamunanmu dicekal oleh bunyi kelontang di dalam kaleng, kau mendongak, kemudian mengucapkan terima kasih dan doa-doa yang diajarkan Emak. Anak perempuan itu memandangimu, lalu dari sakunya ia mengeluarkan selembar uang dan memasukkannya ke dalam kalengmu. Kau tercekat, memandang warna merah dan lima buah angka yang tercetak. “Te … te … rima kasih…” suaramu tergagap-gagap. Anak perempuan itu menyunggingkan senyum. Seketika harimu yang pasi berisi banyak sekali sinar matahari. Kau pun tersenyum, lalu kembali tertatih ke pinggir jalan, lampu merah sudah berakhir dan kau harus menunggu untuk melakukan hal yang sama di lampu merah berikutnya. Perputaran yang seakan tak pernah usai. *** Kau terduduk di trotoar, menghitung uang dari dalam kaleng. Seperti petuah Emak, kaleng tak boleh dibiarkan terisi di putaran berikutnya, maka kau memasukkan uang-uang di dalam kaleng ke dalam kantung belacu dan menjejalkannya di saku baju. Sambil menatapi jalanan berdebu dan panas yang menjerang, kau kembali teringat senyum anak perempuan di angkot itu, teringat kepada baju seragam dan dua kotak sepatu. Dalam hidupmu yang baru delapan tahun, tak pernah sekali pun kau memakai seragam. “Sekolah tak akan membuatmu kaya,” begitu selalu kata Emak. Padahal kau ingin sekali pergi ke sekolah, menyandang ransel berwarna merah muda dan memakai sepatu baru. Kau ingin bisa membaca supaya plang jalan dan berbagai macam iklan bukan hanya pendar gambar-gambar. Agar coretan tanganmu di buku tulis bekas bukan hanya cabikan ceker ayam. Sayangnya keinginan, sesederhana apa pun itu, tak pernah sempurna terlukis di dalam hidupmu. Mereka, keinginan-keinginan dan harapan itu selalu saja menyublim tak berbekas, ditelan udara, ditelan kehidupan nyata. Kau tak dapat mengingat, sejak kapan tepatnya terdampar di pinggir jalan raya dengan kaleng kosong di tangan dan gumaman-gumaman doa yang bahkan tak kauketahui artinya. Yang kau ingat adalah, bahwa Emak akan mengantarmu pagi buta lalu menjemputmu ketika malam tiba. Setelah itu Emak akan merenggut kantung belacu di sakumu, memeriksa setiap lekuk tubuhmu, menyuruhmu mandi, dan memberimu makan lalu kau bisa pergi tidur. Makan adalah sepiring nasi nyaris basi dengan lauk oseng kangkung atau genjer dan seiris tempe atau tahu goreng. Tak pernah lebih dari itu. Bahkan di hari raya Idul Adha kau harus menelan kecewa ketika daging-daging yang berhasil kaukumpulkan segera berpindah tangan, berganti dengan lembaran uang, yang tentu saja tak diserahkan kepadamu melainkan terlipat dan menyusup di belahan dada Emak. Tidur adalah juga perkara yang lain, ketika angin dingin selalu saja memiliki jalan untuk menyelusup ke dalam selimutmu yang berlubang-lubang. Tak ada kasur maupun bantal, yang ada hanyalah tumpukan kardus dan sebuntal kain yang kaugunakan sebagai alas kepala agar lehermu tak sakit ketika terbangun di pagi hari. Sementara Emak, tentu saja memiliki sebuah ranjang dengan kasur busa empuk dan selimut tebal di dalam kamarnya. Kau tak pernah tahu apa saja isi kamar tidur Emak karena kamar itu senantiasa terkunci, hanya sesekali terbuka di malam hari ketika datang tamu lelaki dan kau bisa sedikit mengintip Lampu hijau di perempatan berubah kuning dengan cepat, berubah merah dengan kecepatan yang sama. Kau tergopoh, ada siang yang harus kautaklukkan sebelum Emak menjemputmu pulang nanti malam. Namun di setiap perempatan, anak-anak sepertimu tak pernah berjumlah satu, selalu saja ada anak lain dengan wajah kumal dan pakain kusam yang sama, juga kaleng kosong yang sama. Kau memandang salah satu di antara mereka sambil tetap tertatih menyusuri jalan, beralih dari satu kendaraan yang satu ke kendaraan yang lain. Di sebelah kananmu, seorang anak perempuan yang lebih tua menggendong seorang bayi laki-laki yang kerap meronta karena cuaca begitu panas dan ganas. Kau ingin sekali merenggut bayi laki-laki itu kemudian membawanya ke tempat teduh, memberinya minuman dingin atau membawanya ke taman bermain. Kau tak pernah memiliki saudara, tidak adik, tidak juga kakak. Kata Emak kau sebatang kara. Dan memang itulah yang kau rasakan meski Emak masih kau anggap sebagai keluarga. Tapi Emak bukanlah anggota keluarga yang engkau damba. Kau menginginkan ibu yang tidak memukul, tidak mencaci, tidak selalu menerima tamu lelaki, dan tidak membiarkanmu terdampar di jalan ini. “Dapat banyak?” anak perempuan yang menggendong bayi laki-laki menghampirimu ketika lampu lalu-lintas sudah kembali berubah hijau. Kau hanya menganggkat bahu. “Lumayan,” jawabmu. “Setiap hari aku harus setor seratus ribu, kamu harus setor berapa?” anak perempuan itu kembali bertanya dengan logat Jawa yang kental. Kau segera tahu bahwa anak perempuan di depanmu bukan berasal dari kota yang sama denganmu. “Seratus lima puluh ribu,” jawabmu singkat. Matamu beralih kepada bayi laki-laki yang sekarang menangis keras. “Hah? Besar sekali. Bossmu pasti rakus,” anak perempuan itu menimbang-nimbang bayi lelaki di pangkuannya. “Itu adikmu?” tanyamu. “Bukan, ini entah anak siapa. Sengaja dibawa agar orang-orang merasa kasihan,” geligi anak perempuan itu tersembul ketika ia tersenyum. “Kasihan dia, panas-panas begini ada di jalanan. Kenapa tak kamu simpan saja di tempat teduh?” “Dan mengurangi penghasilanku? Karena ada anak ini aku bisa menghasilkan uang seratus ribu, tahu. Kalau tak ada dia penghasilanku selalu ada di bawah itu. Dan itu artinya aku harus tidur di luar dan tak mendapat jatah makan.” Kau ingin meracau, menjawab pernyataan anak perempuan itu dengan kekesalan dan keberatan. Tapi kau tahu sendiri bahwa hidupmu dan hidupnya berada di pusaran yang sama, tak memiliki banyak pilihan kecuali bertahan dari hari ke hari. Maka kau hanya mengangkat bahu, memasukkan uang ke dalam saku. Ingatanmu kembali kepada Emak, perempuan yang selalu mengatakan bahwa kau harus banyak bersyukur karena tak membiarkanmu mati di selokan delapan tahun lalu. Engkau memang tahu bahwa Emak bukanlah ibu kandungmu. Emak hanya perempuan yang masih memiliki hati ketika seluruh manusia di gang tempatmu tinggal tak peduli. Kadang kau berpikir, barangkali lebih baik berakhir di selokan dan mati selagi masih bayi daripada harus berakhir di jalanan dengan kaleng kosong di tangan.*** Malam ini Emak tidak menjemputmu pulang, padahal penghasilanmu sudah mencukupi dan kau bisa terbebas dari pukulan di kaki. Dengan rasa lelah tak terhingga, kau menumpang angkutan kota, menuju tempat yang masih kau panggil rumah meski tempat itu tak begitu indah. Kakimu masih tertatih, menyusuri gang becek berbau bacin. Di sepanjang gang, kau melihat banyak perempuan dengan gincu tebal dan berpakaian seadanya. Seorang lelaki dengan napas beraroma tajam menjawil dagumu ketika kau berbelok, kau mempercepat langkah, merasa takut, teramat takut. Di dalam rumah, tak kautemukan siapa-siapa kecuali ruangan gelap dan pengap. Tak ada suara cekikian Emak, tak ada suara percakapan samar dari dalam kamar. Tak ada apa-apa. Memang, kau sempat berharap bahwa kelengangan rumah akan menyambutmu setiap kali pulang. Namun rumah tanpa Emak ternyata begitu sunyi, begitu sepi. Kau menggigil, tanganmu gelagapan mencari tombol lampu di dinding. Perlahan, kau mendekati pintu kamar. Mungkin Emak tengah tertidur pulas entah dengan siapa dan lupa menjemputmu. Atau barangkali Emak pergi entah ke mana. Kau mengetuk, berharap cemas ada orang di dalam kamar sana. Ketukanmu bersambut sunyi yang sama. Maka dengan amat perlahan kau membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. “Hei, mau apa kamu ke kamarku?” suara perempuan dari belakangmu. Seketika kau menoleh dan merasa teramat lega karena itu suara Emak. Tak pernah kau merasa selega itu. “Emak tidak datang menjemput?” tanyamu takut-takut. “Halah, kamu kan sudah besar. Sudah bisa pulang sendiri,” Emak mencibir, tangannya menengadah. Tanpa banyak bicara kau menyerahkan kantung belacu dari saku. Emak tersenyum cerah, bibir merahnya merekah setelah menghitung jumlah uang di dalam kantung. Kali ini ia tak menggeledah bajumu melainkan mengajakmu duduk di kursi rotan tua di ruang tamu. Tangan Emak merangkul bahumu, suaranya sudah berubah dari cibiran dan dengusan ke nada yang lebih ramah. Engkau tentu senang, belum pernah Emak seramah itu. Seorang lelaki menyambutmu dengan senyum aneh ketika kau duduk. Kau tak pernah melihat lelaki itu. Emak punya banyak langganan, ada juga tamu yang baru sekali datang, tapi kau tak pernah sekalipun melihat lelaki itu. Tubuhmu gemetar, ada ketakutan tak wajar yang diam-diam bergelenyar. “Ini anaknya?” lelaki itu bertanya pada Emak dengan binar mata yang tak bisa kaubaca. Emak mengangguk. “Cantik kan? Memang sih, dia agak kumal. Tapi kalau sudah dibersihkan, dia cantik juga kok.” Engkau menggigil sementara dua orang di hadapanmu mengeluarkan percakapan-percakapan yang membuatmu semakin ketakutan. Kau memandang Emak, lalu beralih pada lelaki itu. Di benakmu terserak banyak pertanyaan. “Ada apa? Saya mau dibawa ke mana?” akhirnya pertanyaan itu pecah dari mulutmu. Emak, masih dengan senyumnya yang ramah dan raut semringah membelai rambut dan pipimu. Tubuhmu semakin gemetar, sentuhan Emak tidak menenangkan melainkan berubah menikam. “Neng, kamu belum pernah naik pesawat, kan? Nah, Bapak yang baik ini mau membawa kamu naik pesawat. Nanti di sana kamu bisa pakai pakaian bagus, makan enak. Di sana juga ada laut, kamu belum pernah melihat laut, kan?” bujuk Emak. Suara Emak terdengar asing di telingamu. Kau memang belum pernah naik pesawat, belum pernah memiliki pakaian bagus, belum pernah makan enak, kau juga belum pernah melihat laut. “Saya akan dibawa ke mana?” tanyamu lagi. “Kepuluan Karimun, di sana tempat yang menyenangkan,” jawab lelaki yang duduk di depanmu. Dan di manakah tempat itu? Benakmu kembali merapal pertanyaan. Kakimu yang kecil hanya sempat mengarungi Bandung, itu pun dari lampu merah ke lampu merah yang lain, bukan dari tempat wisata yang satu ke tempat wisata yang lain. “Saya hanya ingin sekolah, apakah di sana ada sekolah?” Lelaki itu menatap Emak kemudian menjawab dengan gugup. “Bisa, bisa …, di sana tentu ada sekolah. Kamu bisa sekolah di mana saja kamu suka.” Emak mengeluarkan senyumnya lagi, tangan Emak kembali membelai rambutmu. “Mandilah dulu, Neng. Nanti kamu bisa ikut bapak ini untuk sekolah.” Kau tidak banyak berbicara, kakimu melangkah menuju kamar mandi di belakang rumah. Kau memang ingin sekali meninggalkan Emak, meninggalkan suara-suara desah samar setiap malam, meninggalkan jalanan, meninggalkan hidup yang terjal. Jika lelaki tadi bisa membawamu kepada sekolah, maka kau akan ikut dengan senang hati. Terlintas wajah anak perempuan di angkot dengan seragam putih merah dan kotak-kotak sepatunya, engkau tersenyum, rasa takutmu perlahan hilang. Tapi rasa takutmu kembali datang saat kau berpakaian di balik dinding papan, tempat kau bisa mendengar dengan jelas percakapan-percakapan di ruang tamu. “Bagaimana? Kamu suka kan sama anak itu? Kira-kira dia bisa dijual berapa?” suara Emak. Terdengar suara lelaki terkekeh-kekeh. “Anakmu memang cantik, Sumi. Klienku pasti suka.” “Dia bukan anakku,” suara Emak berubah dingin. “Berapa uang yang akan kuterima? Dua puluh juta sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya? Kalau kurang, aku tak akan menyerahkan anak itu. Lebih baik kudidik sendiri, sepuluh tahun lagi dia bisa menjadi kembang di sini.” Kekeh laki-laki lagi. “Sumi …, Sumi …. Kau memang tak pernah mau rugi. Tenang saja, uangnya sudah aku sediakan asal anak itu benar-benar bisa diatur.” “Dia sudah tahu apa pekerjaanku, pasti sudah terbiasa dengan itu.” Tubuhmu bergeletar. Kepalamu sibuk mencerna. Pekerjaan Emak? Cantik? Dua puluh juta? Tapi kau hanya ingin sekolah, kenapa untuk sekolah harus cantik dan harus bekerja seperti Emak? Kau tak ingin menerima tamu lelaki, tak ingin bekerja seperti Emak. Lebih baik kau mengemis seumur hidup daripada harus bekerja seperti Emak. “Hei, mana anak itu? Kenapa lama sekali?” suara lelaki itu kembali menggelegar. Perlahan-lahan kau berjingkat, keluar melalui pintu belakang, berlari menuju gang kecil berbau bacin. Telingamu masih dapat menangkap teriakan Emak ketika mendapatimu tak ada. Kau berlari, semakin kencang, semakin kencang. Kaki kecilmu menerobos genangan air, menerobos udara malam yang kelam. Napasmu memburu dan dadamu terasa nyaris pecah. Tapi kau harus lari. Kau harus menyelamatkan diri. Maka kau berlari meski dada dan kakimu teramat nyeri. Dia bukan anakku! Suara Emak terngiang-ngiang di telingamu. Engkau sudah lama tahu itu, tapi ketika sekali lagi mendengarnya dari mulu Emak, perempuan yang seumur hidup telah engkau anggap sebagai ibu, mau tak mau hatimu tersayat sembilu. Barangkali engkau memang tak terlahir dari rahim perempuan mana pun. Engkau anak matahari, Neng. Anak yang dibesarkan oleh terik. Anak yang diasuh oleh semesta. Dan dunia adalah rumah yang selama ini engkau damba. “Aku hanya ingin sekolah, bukan bekerja seperti Emak,” di sela isak mulutmu bergumam-gumam. Kakimu terus berlari, menuju malam, menuju kelam.
(Bandung, 8 Desember 2012)
 Foto: Irvan Mulyadie
Foto: Irvan MulyadieKau berdiri gamang di atas trotoar, tepat di perempatan jalan. Matamu melirik lampu yang menyala hijau kemudian berganti kuning. Gelisah. Wajahmu yang kumal karena memang dibuat kumal dan dihiasi coretan debu serta lumpur mengernyit-ngernyit, menahan rasa sakit. Ketika lampu berubah merah, kau terpincang-pincang, tertatih menyusuri jalan, mendatangi kendaraan demi kendaraan. Dadamu berdebar-debar kencang saat tak satu pun dari pengemudi atau penumpang memasukkan uang ke dalam kaleng yang kausodorkan. Hari ini pasti mengerikan, lebih mengerikan dari kemarin. Benakmu merapal sesal, sedikit kesal. Ya, hari kemarin kau terpaksa pulang dengan pendapatan seadanya yang tentu saja membuat perempuan yang kau panggil emak menandak-nandak dalam amarah. Ia, perempuan dengan gincu merah menyala dan maskara tebal membingkai mata itu melayangkan pukulan demi pukulan kepada kakimu yang ringkih. “Dasar anak tak tahu diri! Pemalas benar kamu ini. Apa saja yang kamu lakukan di jalan, hah? Main-main?” gagang sapu mendarat di kakimu, ditingkahi teriakan dan cacian perempuan itu. Kau menangis, meraung-raung meminta ampun, dan berjanji akan bekerja lebih keras lagi, tapi pukulan itu tak jua berhenti hingga kakimu bengkak, lebam, berderak-derak ketika dibawa berjalan. Mungkin kakimu sempurna patah, tapi kau tak peduli sepanjang nyawa masih ada di kerongkongan, sepanjang kau masih bisa menatap matahari esok pagi. Bagimu, hidup yang keras bukan hanya cerita-cerita di atas kertas. Masih terpincang-pincang, kau meringis, menerus menyusuri jalan dan menyodorkan kaleng kosong kepada setiap pengemudi dan penumpang kendaraan. Sebagian dari mereka tentu berpikir bahwa kakimu yang tertatih hanyalah pura-pura, wajahmu yang letih juga palsu belaka. Tapi tak seorang pun tahu apa yang sedang berlarian di dalam kepalamu; rasa takut sekaligus putus asa yang kalut dan berlarut-larut. Tepat di pinggir sebuah angkutan kota, kau kembali menyodorkan kaleng kepada para penumpang, bergumam-gumam meminta rasa kasihan. Sebetulnya engkau tahu, bahwa hal itu lebih hina dari apa pun, tapi kau tak bisa menyangkal karena memang hidup tak memberi banyak pilihan. Seorang anak perempuan seusiamu, masih memakai seragam sekolah, duduk di angkot sambil menjilati es krim di dalam corong. Anak perempuan itu bersandar kepada seorang perempuan yang kautebak sebagai ibunya. Ada beberapa kantong belanjaan di pangkuan mereka, dua kotak sepatu dan entah apa lagi. Kau melirik jengah kepada dua kotak sepatu itu, memandang kakimu sendiri yang telanjang sedari tadi. Kau juga melirik gelisah, nyaris iri kepada pakaian seragam anak perempuan itu dan mulai membandingkan dengan pakaian kumalmu. Kau berpikir, betapa orang lain memiliki segalanya dan kau tak memiliki apa-apa. Lamunanmu dicekal oleh bunyi kelontang di dalam kaleng, kau mendongak, kemudian mengucapkan terima kasih dan doa-doa yang diajarkan Emak. Anak perempuan itu memandangimu, lalu dari sakunya ia mengeluarkan selembar uang dan memasukkannya ke dalam kalengmu. Kau tercekat, memandang warna merah dan lima buah angka yang tercetak. “Te … te … rima kasih…” suaramu tergagap-gagap. Anak perempuan itu menyunggingkan senyum. Seketika harimu yang pasi berisi banyak sekali sinar matahari. Kau pun tersenyum, lalu kembali tertatih ke pinggir jalan, lampu merah sudah berakhir dan kau harus menunggu untuk melakukan hal yang sama di lampu merah berikutnya. Perputaran yang seakan tak pernah usai. *** Kau terduduk di trotoar, menghitung uang dari dalam kaleng. Seperti petuah Emak, kaleng tak boleh dibiarkan terisi di putaran berikutnya, maka kau memasukkan uang-uang di dalam kaleng ke dalam kantung belacu dan menjejalkannya di saku baju. Sambil menatapi jalanan berdebu dan panas yang menjerang, kau kembali teringat senyum anak perempuan di angkot itu, teringat kepada baju seragam dan dua kotak sepatu. Dalam hidupmu yang baru delapan tahun, tak pernah sekali pun kau memakai seragam. “Sekolah tak akan membuatmu kaya,” begitu selalu kata Emak. Padahal kau ingin sekali pergi ke sekolah, menyandang ransel berwarna merah muda dan memakai sepatu baru. Kau ingin bisa membaca supaya plang jalan dan berbagai macam iklan bukan hanya pendar gambar-gambar. Agar coretan tanganmu di buku tulis bekas bukan hanya cabikan ceker ayam. Sayangnya keinginan, sesederhana apa pun itu, tak pernah sempurna terlukis di dalam hidupmu. Mereka, keinginan-keinginan dan harapan itu selalu saja menyublim tak berbekas, ditelan udara, ditelan kehidupan nyata. Kau tak dapat mengingat, sejak kapan tepatnya terdampar di pinggir jalan raya dengan kaleng kosong di tangan dan gumaman-gumaman doa yang bahkan tak kauketahui artinya. Yang kau ingat adalah, bahwa Emak akan mengantarmu pagi buta lalu menjemputmu ketika malam tiba. Setelah itu Emak akan merenggut kantung belacu di sakumu, memeriksa setiap lekuk tubuhmu, menyuruhmu mandi, dan memberimu makan lalu kau bisa pergi tidur. Makan adalah sepiring nasi nyaris basi dengan lauk oseng kangkung atau genjer dan seiris tempe atau tahu goreng. Tak pernah lebih dari itu. Bahkan di hari raya Idul Adha kau harus menelan kecewa ketika daging-daging yang berhasil kaukumpulkan segera berpindah tangan, berganti dengan lembaran uang, yang tentu saja tak diserahkan kepadamu melainkan terlipat dan menyusup di belahan dada Emak. Tidur adalah juga perkara yang lain, ketika angin dingin selalu saja memiliki jalan untuk menyelusup ke dalam selimutmu yang berlubang-lubang. Tak ada kasur maupun bantal, yang ada hanyalah tumpukan kardus dan sebuntal kain yang kaugunakan sebagai alas kepala agar lehermu tak sakit ketika terbangun di pagi hari. Sementara Emak, tentu saja memiliki sebuah ranjang dengan kasur busa empuk dan selimut tebal di dalam kamarnya. Kau tak pernah tahu apa saja isi kamar tidur Emak karena kamar itu senantiasa terkunci, hanya sesekali terbuka di malam hari ketika datang tamu lelaki dan kau bisa sedikit mengintip Lampu hijau di perempatan berubah kuning dengan cepat, berubah merah dengan kecepatan yang sama. Kau tergopoh, ada siang yang harus kautaklukkan sebelum Emak menjemputmu pulang nanti malam. Namun di setiap perempatan, anak-anak sepertimu tak pernah berjumlah satu, selalu saja ada anak lain dengan wajah kumal dan pakain kusam yang sama, juga kaleng kosong yang sama. Kau memandang salah satu di antara mereka sambil tetap tertatih menyusuri jalan, beralih dari satu kendaraan yang satu ke kendaraan yang lain. Di sebelah kananmu, seorang anak perempuan yang lebih tua menggendong seorang bayi laki-laki yang kerap meronta karena cuaca begitu panas dan ganas. Kau ingin sekali merenggut bayi laki-laki itu kemudian membawanya ke tempat teduh, memberinya minuman dingin atau membawanya ke taman bermain. Kau tak pernah memiliki saudara, tidak adik, tidak juga kakak. Kata Emak kau sebatang kara. Dan memang itulah yang kau rasakan meski Emak masih kau anggap sebagai keluarga. Tapi Emak bukanlah anggota keluarga yang engkau damba. Kau menginginkan ibu yang tidak memukul, tidak mencaci, tidak selalu menerima tamu lelaki, dan tidak membiarkanmu terdampar di jalan ini. “Dapat banyak?” anak perempuan yang menggendong bayi laki-laki menghampirimu ketika lampu lalu-lintas sudah kembali berubah hijau. Kau hanya menganggkat bahu. “Lumayan,” jawabmu. “Setiap hari aku harus setor seratus ribu, kamu harus setor berapa?” anak perempuan itu kembali bertanya dengan logat Jawa yang kental. Kau segera tahu bahwa anak perempuan di depanmu bukan berasal dari kota yang sama denganmu. “Seratus lima puluh ribu,” jawabmu singkat. Matamu beralih kepada bayi laki-laki yang sekarang menangis keras. “Hah? Besar sekali. Bossmu pasti rakus,” anak perempuan itu menimbang-nimbang bayi lelaki di pangkuannya. “Itu adikmu?” tanyamu. “Bukan, ini entah anak siapa. Sengaja dibawa agar orang-orang merasa kasihan,” geligi anak perempuan itu tersembul ketika ia tersenyum. “Kasihan dia, panas-panas begini ada di jalanan. Kenapa tak kamu simpan saja di tempat teduh?” “Dan mengurangi penghasilanku? Karena ada anak ini aku bisa menghasilkan uang seratus ribu, tahu. Kalau tak ada dia penghasilanku selalu ada di bawah itu. Dan itu artinya aku harus tidur di luar dan tak mendapat jatah makan.” Kau ingin meracau, menjawab pernyataan anak perempuan itu dengan kekesalan dan keberatan. Tapi kau tahu sendiri bahwa hidupmu dan hidupnya berada di pusaran yang sama, tak memiliki banyak pilihan kecuali bertahan dari hari ke hari. Maka kau hanya mengangkat bahu, memasukkan uang ke dalam saku. Ingatanmu kembali kepada Emak, perempuan yang selalu mengatakan bahwa kau harus banyak bersyukur karena tak membiarkanmu mati di selokan delapan tahun lalu. Engkau memang tahu bahwa Emak bukanlah ibu kandungmu. Emak hanya perempuan yang masih memiliki hati ketika seluruh manusia di gang tempatmu tinggal tak peduli. Kadang kau berpikir, barangkali lebih baik berakhir di selokan dan mati selagi masih bayi daripada harus berakhir di jalanan dengan kaleng kosong di tangan.*** Malam ini Emak tidak menjemputmu pulang, padahal penghasilanmu sudah mencukupi dan kau bisa terbebas dari pukulan di kaki. Dengan rasa lelah tak terhingga, kau menumpang angkutan kota, menuju tempat yang masih kau panggil rumah meski tempat itu tak begitu indah. Kakimu masih tertatih, menyusuri gang becek berbau bacin. Di sepanjang gang, kau melihat banyak perempuan dengan gincu tebal dan berpakaian seadanya. Seorang lelaki dengan napas beraroma tajam menjawil dagumu ketika kau berbelok, kau mempercepat langkah, merasa takut, teramat takut. Di dalam rumah, tak kautemukan siapa-siapa kecuali ruangan gelap dan pengap. Tak ada suara cekikian Emak, tak ada suara percakapan samar dari dalam kamar. Tak ada apa-apa. Memang, kau sempat berharap bahwa kelengangan rumah akan menyambutmu setiap kali pulang. Namun rumah tanpa Emak ternyata begitu sunyi, begitu sepi. Kau menggigil, tanganmu gelagapan mencari tombol lampu di dinding. Perlahan, kau mendekati pintu kamar. Mungkin Emak tengah tertidur pulas entah dengan siapa dan lupa menjemputmu. Atau barangkali Emak pergi entah ke mana. Kau mengetuk, berharap cemas ada orang di dalam kamar sana. Ketukanmu bersambut sunyi yang sama. Maka dengan amat perlahan kau membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. “Hei, mau apa kamu ke kamarku?” suara perempuan dari belakangmu. Seketika kau menoleh dan merasa teramat lega karena itu suara Emak. Tak pernah kau merasa selega itu. “Emak tidak datang menjemput?” tanyamu takut-takut. “Halah, kamu kan sudah besar. Sudah bisa pulang sendiri,” Emak mencibir, tangannya menengadah. Tanpa banyak bicara kau menyerahkan kantung belacu dari saku. Emak tersenyum cerah, bibir merahnya merekah setelah menghitung jumlah uang di dalam kantung. Kali ini ia tak menggeledah bajumu melainkan mengajakmu duduk di kursi rotan tua di ruang tamu. Tangan Emak merangkul bahumu, suaranya sudah berubah dari cibiran dan dengusan ke nada yang lebih ramah. Engkau tentu senang, belum pernah Emak seramah itu. Seorang lelaki menyambutmu dengan senyum aneh ketika kau duduk. Kau tak pernah melihat lelaki itu. Emak punya banyak langganan, ada juga tamu yang baru sekali datang, tapi kau tak pernah sekalipun melihat lelaki itu. Tubuhmu gemetar, ada ketakutan tak wajar yang diam-diam bergelenyar. “Ini anaknya?” lelaki itu bertanya pada Emak dengan binar mata yang tak bisa kaubaca. Emak mengangguk. “Cantik kan? Memang sih, dia agak kumal. Tapi kalau sudah dibersihkan, dia cantik juga kok.” Engkau menggigil sementara dua orang di hadapanmu mengeluarkan percakapan-percakapan yang membuatmu semakin ketakutan. Kau memandang Emak, lalu beralih pada lelaki itu. Di benakmu terserak banyak pertanyaan. “Ada apa? Saya mau dibawa ke mana?” akhirnya pertanyaan itu pecah dari mulutmu. Emak, masih dengan senyumnya yang ramah dan raut semringah membelai rambut dan pipimu. Tubuhmu semakin gemetar, sentuhan Emak tidak menenangkan melainkan berubah menikam. “Neng, kamu belum pernah naik pesawat, kan? Nah, Bapak yang baik ini mau membawa kamu naik pesawat. Nanti di sana kamu bisa pakai pakaian bagus, makan enak. Di sana juga ada laut, kamu belum pernah melihat laut, kan?” bujuk Emak. Suara Emak terdengar asing di telingamu. Kau memang belum pernah naik pesawat, belum pernah memiliki pakaian bagus, belum pernah makan enak, kau juga belum pernah melihat laut. “Saya akan dibawa ke mana?” tanyamu lagi. “Kepuluan Karimun, di sana tempat yang menyenangkan,” jawab lelaki yang duduk di depanmu. Dan di manakah tempat itu? Benakmu kembali merapal pertanyaan. Kakimu yang kecil hanya sempat mengarungi Bandung, itu pun dari lampu merah ke lampu merah yang lain, bukan dari tempat wisata yang satu ke tempat wisata yang lain. “Saya hanya ingin sekolah, apakah di sana ada sekolah?” Lelaki itu menatap Emak kemudian menjawab dengan gugup. “Bisa, bisa …, di sana tentu ada sekolah. Kamu bisa sekolah di mana saja kamu suka.” Emak mengeluarkan senyumnya lagi, tangan Emak kembali membelai rambutmu. “Mandilah dulu, Neng. Nanti kamu bisa ikut bapak ini untuk sekolah.” Kau tidak banyak berbicara, kakimu melangkah menuju kamar mandi di belakang rumah. Kau memang ingin sekali meninggalkan Emak, meninggalkan suara-suara desah samar setiap malam, meninggalkan jalanan, meninggalkan hidup yang terjal. Jika lelaki tadi bisa membawamu kepada sekolah, maka kau akan ikut dengan senang hati. Terlintas wajah anak perempuan di angkot dengan seragam putih merah dan kotak-kotak sepatunya, engkau tersenyum, rasa takutmu perlahan hilang. Tapi rasa takutmu kembali datang saat kau berpakaian di balik dinding papan, tempat kau bisa mendengar dengan jelas percakapan-percakapan di ruang tamu. “Bagaimana? Kamu suka kan sama anak itu? Kira-kira dia bisa dijual berapa?” suara Emak. Terdengar suara lelaki terkekeh-kekeh. “Anakmu memang cantik, Sumi. Klienku pasti suka.” “Dia bukan anakku,” suara Emak berubah dingin. “Berapa uang yang akan kuterima? Dua puluh juta sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya? Kalau kurang, aku tak akan menyerahkan anak itu. Lebih baik kudidik sendiri, sepuluh tahun lagi dia bisa menjadi kembang di sini.” Kekeh laki-laki lagi. “Sumi …, Sumi …. Kau memang tak pernah mau rugi. Tenang saja, uangnya sudah aku sediakan asal anak itu benar-benar bisa diatur.” “Dia sudah tahu apa pekerjaanku, pasti sudah terbiasa dengan itu.” Tubuhmu bergeletar. Kepalamu sibuk mencerna. Pekerjaan Emak? Cantik? Dua puluh juta? Tapi kau hanya ingin sekolah, kenapa untuk sekolah harus cantik dan harus bekerja seperti Emak? Kau tak ingin menerima tamu lelaki, tak ingin bekerja seperti Emak. Lebih baik kau mengemis seumur hidup daripada harus bekerja seperti Emak. “Hei, mana anak itu? Kenapa lama sekali?” suara lelaki itu kembali menggelegar. Perlahan-lahan kau berjingkat, keluar melalui pintu belakang, berlari menuju gang kecil berbau bacin. Telingamu masih dapat menangkap teriakan Emak ketika mendapatimu tak ada. Kau berlari, semakin kencang, semakin kencang. Kaki kecilmu menerobos genangan air, menerobos udara malam yang kelam. Napasmu memburu dan dadamu terasa nyaris pecah. Tapi kau harus lari. Kau harus menyelamatkan diri. Maka kau berlari meski dada dan kakimu teramat nyeri. Dia bukan anakku! Suara Emak terngiang-ngiang di telingamu. Engkau sudah lama tahu itu, tapi ketika sekali lagi mendengarnya dari mulu Emak, perempuan yang seumur hidup telah engkau anggap sebagai ibu, mau tak mau hatimu tersayat sembilu. Barangkali engkau memang tak terlahir dari rahim perempuan mana pun. Engkau anak matahari, Neng. Anak yang dibesarkan oleh terik. Anak yang diasuh oleh semesta. Dan dunia adalah rumah yang selama ini engkau damba. “Aku hanya ingin sekolah, bukan bekerja seperti Emak,” di sela isak mulutmu bergumam-gumam. Kakimu terus berlari, menuju malam, menuju kelam.
(Bandung, 8 Desember 2012)

Published on April 21, 2014 12:07
April 16, 2014
Karena di Indonesia, Tak Hanya Ada Satu Agama
 Gambar dipinjam dari sini
Gambar dipinjam dari siniSaya tidak sedang membicarakan tentang fanatisme, sekulerisme, pluralisme, liberalisme, atau isme-isme lain yang membuat isi kepala kita terkotak-kotakkan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari saya ingatkan tentang konflik-konflik besar di Indonesia yang sampai sekarang masih menyisakan luka. Poso, Ambon, Situbondo, Cikeusik, Sampang, lalu ada Tasikmalaya di tahun 1996 yang menjadi salah satu pemicu kerusuhan Mei 1998. Kalau kita mundur lebih jauh lagi, kita akan menemukan G-30S PKI. Bukan, yang menjadikan PKI isu seksi untuk memporak-porandakan Indonesia bukanlah paham komunisme, melainkan karena PKI dianggap atheis. Anda tentu juga masih ingat mengenai DI TII. Kita juga punya FPI, HTI, LDII, dan pemicu lain yang jika ditarik garis lurus maka akan kita temukan satu kata keramat: AGAMA.
Dari semua konflik itu, konon ada temuan-temuan berupa keterlibatan Amerika, Rusia, Filipina, sampai Al-Qaeda. Anda tahu ini artinya apa? Teori konspirasi? Bahwa kita tidak bersalah? Bukan, itu karena kita hanyalah bangsa tolol yang tak sadar ketika dijadikan BONEKA.
Dulu, Indonesia bisa membusungkan dada di hadapan dunia karena dianggap negeri paling majemuk tapi bisa merdeka. Dulu, Indonesia dipuja-puja sebagai negeri yang bisa menjaga keamanan dan kedamaian padahal terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, dan bahasa. Sekarang? Kita tak lebih dari lautan bensin yang jika dicetus api sedikit saja bisa terbakar seluruhnya. Tidakkah kita merasa malu?
Oke, kita berhenti dulu sampai di sini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu:
Apa Anda tahu ada berapa banyak agama di Indonesia?Apa Anda tahu bahwa setiap agama meyakini bahwa agamanya adalah yang paling benar?Apa Anda tahu bahwa setiap kitab suci mengajarkan umatnya tentang kebaikan?Apa Anda percaya bahwa Tuhan ... tidak butuh dibela?Lalu kenapa kita terus-terusan berperang atas nama Tuhan dan agama-Nya?
Yang Muslim menolak Pancasila karena konon tidak sesuai dengan syariah. Menyebut para pemimpin yang tidak seagama dengan sebutan "musuh-musuh Allah". Mengidap paranoia akut sehingga menciptakan delusi-delusi bahwa setiap pemimpin yang tidak seiman sedang berkonspirasi dengan Yahudi, atau sedang berusaha "mengkafirkan" negeri ini. Mereka lupa bahwa seorang pemimpin bukan hanya dinilai dari agamanya, melainkan juga dari kredibilitasnya memimpin negara. Mereka lupa bahwa di Indonesia agama bukan Islam saja.
Menjadikan Indonesia sebagai negara Islam adalah ide paling utopis sekaligus tolol. Mimpinya orang-orang yang tidak siap menjadi bagian dari masyarakat global. Ilusinya orang-orang yang tidak tahu cara lain untuk memperbaiki Indonesia sehingga menjadikan agama sebagai tolak ukur tanpa menyediakan langkah-langkah aplikatif yang solutif.
Mengadaptasi kebijakan-kebijakan ajaran agama Islam tak harus dengan cara menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.
Yang Nasrani, dengan berbagai aliran dan konflik di dalam agama sendiri, diam-diam "menggalang" kekuatan. Hadir di setiap bencana alam dengan semangat menyebarkan kebenaran, bahasa halus dari pemurtadan. Para evangelist berkeliaran dari mulai perseorangan sampai yang terorganisir. Dari memakai modus personal (pacari, hamili, pindah agama, nikahi) sampai modus ekonomi; menukar beberapa bungkus mie instant dengan keimanan.
Umat di luar kedua agama besar itu jadi oposisi. Para penonton yang tersisih (atau disisihkan?) seakan-akan mereka tidak ada. Seakan-akan mereka bukan bagian dari Indonesia. Seakan-akan mereka tidak berhak bersuara.
Sementara kita sibuk mengurusi konflik agama, aset negara dijual kepada negara lain. Kekayaan negara dieksploitasi negara lain. Manusia-manusia Indonesia disiksa di negara lain. Kita ... cuma jadi BONEKA.
Indonesia adalah sebuah bangunan yang terdiri dari berbagai elemen. Ada pondasi, ada dinding, ada lantai, ada atap, ada pintu, ada jendela, ada pekarangan, dll. Tak masalah yang atap adalah China, yang dinding adalah Sunda, yang lantai adalah Jawa, misalnya. Toh ketika bangunan itu sudah berdiri, ia hanya akan memiliki satu nama: RUMAH.
Mau sampai kapan kita seperti ini? Mau sampai kapan kita menghancurkan negeri dari dalam tubuh sendiri? Kapan kita bosan saling membantai? Kapan kita bosan saling menyudutkan? Kapan kita bisa berjalan bersama-sama sambil berpegangan tangan tanpa harus mempermasalahkan yang satu makan babi sedang yang lain tidak? Kapan?
-Re-post dari catatan facebook

Published on April 16, 2014 23:43
April 11, 2014
Poligami, "Surga" di Atas Pecahan Kaca

Saya tidak akan membahas poligami dari kacamata agama karena akan terlalu banyak pro dan kontra dan itu artinya tulisan saya akan sia-sia. Praktik poligami ada di berbagai peradaban, dari zaman ke zaman. Ada kisah-kisah bahagia, lebih banyak lagi yang mengandung luka. Saya ingin mengemukakan pandangan dari sisi perempuan sebagai individu.
Melalui tulisan ini, saya juga menegaskan bahwa sikap saya terhadap poligami adalah kontra. Bagi yang beda partai, tidak usah misuh-misuh atau kirim link ayat. Buat saja esai sanggahan.
Ada beberapa alasan mengapa saya tidak setuju dengan poligami:
1. Jumlah perempuan lebih banyak daripada lelaki
Yang benar? Yakin? Menurut data BPS sampai tahun 2012, penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki adalah 50.35% sedangkan perempuan 49.65%. Kalau Anda lupa pelajaran matematika, mari saya ingatkan bahwa 50 lebih besar daripada 49.
2. Surga
Aih, ada banyak jalan menuju Roma. Lebih banyak lagi jalan menuju surga.
3. Cinta
Sebuah hubungan tak layak dibangun di atas kehancuran hubungan lain. Ketika Anda sedang bersama lelaki yang Anda cintai, di suatu tempat ada perempuan lain yang tengah Anda lukai. Ketika Anda sedang bersama perempuan yang Anda cintai, di rumah ada istri yang tengah Anda sakiti. Bagian dari cinta yang manakah ini?
4. Ekonomi
Itu sebabnya perempuan harus mandiri secara ekonomi, agar tak harus mencari jalan selamat dengan cara menjadi istri kedua, ketiga, atau kesekian.
5. Politis
Kalau dengan berpoligami Anda bisa mencegah perang dunia ketiga atau ledakan nuklir di suatu negara, mungkin layak dipertimbangkan. Kalau cuma dengan alasan harta warisan, sebaiknya jangan.
6. Biologis
Bentuk vagina kan semuanya sama saja. Daripada cari istri baru, lebih murah memperbaiki kehidupan sex Anda dan istri Anda.
Istri tidak sanggup melayani karena alasan kesehatan? Coba ingat-ingat, apa alasan Anda menikah? Istri Anda sakit lalu Anda menikah lagi, gitu? What a fuck! Lagi pula Anda tidak akan bercinta setiap saat. Belilah sex doll atau udahlah, pake sabun aja. #Plak
7. Keturunan
Mamen, ada jutaan anak yatim piatu yang bisa Anda adopsi. Ingin punya anak tak harus nambah istri.
8. Rasa kemanusiaan atau kasihan
Nah, ini dia alasan paling menyebalkan. Laki-laki selalu ingin tampil sebagai pahlawan dan perempuan selalu pandai menjual kemalangan. Tidak semua perempuan yang hidupnya menderita harus Anda nikahi kalau Anda sudah punya istri. Toh Anda bukan panti sosial atau badan amal. Tidak usah repot-repot.
---
Kepada perempuan:
Ketika Anda mencintai lelaki beristri, Anda harus tahu bahwa kalian tidak akan pernah bisa utuh saling memiliki. Coba raba hati Anda, tegakah menyakiti hati perempuan lain? Tegakah Anda merampas milik orang lain? Hal lain mungkin bisa dibagi, tapi tidak suami.
Kepada para lelaki:
Istri bukan barang yang jika Anda bosan bisa Anda tukar atau tambah dengan yang baru. Setiap saat Anda akan senantiasa didera dan digoda. Namun percayalah, setia akan selalu memiliki harga.
Salam,
~eL
(Repost dari catatan FB)

Published on April 11, 2014 07:22
April 5, 2014
[Cerpen] Perempuan Geladak
(Bali Post, 6 April 2014)
Kita berdua berbaring. Telentang sambil menatap langit-langit kamar. Mata kita mengikuti perputaran kipas angin sambil menerka-nerka kapan kipas renta itu akan lelah bekerja. Setelah habis batang rokok kedua -ritual wajib sehabis bercinta- kita mulai berbicara tentang cuaca, sesekali bergumam tentang sesuatu yang tak bisa kita terka.
Kamar hotel ini berbau asap dan keringat. Tak ada pengharum ruangan agar bau tubuhmu hilang dari tubuhku. Sebetulnya aku agak terhina kaubawa ke kamar seperti ini, kamar yang harga sewanya bahkan lebih murah dari harga sebelah sepatuku. Tapi hanya seharga inilah yang sanggup kaubayar, kamar hotel bintang dua jauh di tepi kota.
“Di sini aman, tak pernah ada razia,” katamu.
Aku sendiri heran, dari dulu sampai sekarang kau lebih takut terhadap manusia daripada terhadap dosa.
Berkali-kali kau menoleh, mungkin mencari mataku, mungkin mencari bibirku, mungkin juga mencari-cari payudaraku agar kau bisa kembali tersungkur seperti balita yang haus serta rakus. Engkau berbalik, berbaring menyamping, jemarimu mulai menelusuri kembali jejak yang sempat kautinggalkan malam tadi. Maka tubuh kita kembali saling bertukar kabar. Menandak-nandak seperti penari yang lama hidup dalam jeruji. Melenguh-lenguh seperti binatang lapar dan sangar.
Berkali-kali tubuh kita saling bertamu. Berkali-kali pula aku menahan pilu. Bukan di selangkangan, melainkan di tempat lain yang tak bisa kupetakan.
"Kamu memang luar biasa," kau mengecup bibir setelah engahmu berakhir.
Tentu saja aku luar biasa. Kukenal tubuhmu sejak bertahun lalu.
"Istriku tidak bisa apa-apa. Bercinta dengannya seperti meniduri pohon pisang yang hanya bisa diam," kau mengeluh. Keluhan yang biasa. Yang sering aku dengar sehabis kita bercinta.
"Istrimu kan cantik, lebih cantik dari aku," aku duduk. "Dia juga tidak merokok, mulutnya tidak berbau tembakau seperti mulutku," aku mengacungkan rokok yang terjepit di jemariku.
Kau mengerlingkan mata. "Percuma cantik kalau hanya tahu posisi misionaris. Aku bahkan harus mengiba-ngiba agar dia mau bercinta di atas meja."
Keluhan yang sama. Masalah yang biasa. Mungkin benar bahwa kau tergila-gila padanya, perempuan dengan rambut panjang, tubuh ramping, wajah cantik, dan mengagumimu tulisan-tulisanmu setengah mampus. Baginya kau adalah dewa kata-kata, bagimu dia adalah pemuja yang harus kaupelihara.
Sedangkan denganku, kau bisa mewujudkan segala fantasi liarmu. Aku hafal Kamasutra di luar kepala, kau bisa meminta teknik yang mana saja. Aku juga bisa diajak bercinta di mana saja. Tapi kau tidak mencintaiku, bagimu aku hanya semacam pemuas nafsu.
"Aku sudah menyandang gelar doktor sejak enam bulan lalu," mungkin kau sudah tahu, tapi berpura-pura tidak tahu.
Kau berdecak kagum. "Hebat kamu ya, bisa sampai kuliah S3 segala, di luar negeri pula. Istriku bahkan tak pernah mau membaca buku, kerjanya cuma masak, nyuci, ngurus rumah, ngurus anak."
Kau kembali membandingkan. Lingkaran setan yang tak akan pernah selesai. Aku sendiri heran, jika ia sebebal itu, mengapa kau masih mau menikahinya? Menghabiskan bertahun-tahun hidup dengan perempuan yang katamu tak bisa apa-apa.
"Istriku itu ...."
"Bisa tidak kita tak usah membicarakan istrimu terus?" aku memotong sebelum kau mulai lagi. Kumatikan rokok di asbak dan berjalan ke lemari es untuk mengambil sekaleng San Miguel. Meski aku tahu untuk berbicara denganmu aku butuh minuman yang lebih keras.
"Minggu lalu cerpenku dimuat di Kompas, kamu sudah baca?" kau berusaha mengalihkan pembicaraan, setengahnya lagi pamer kemampuan. Kemampuan yang sudah tak bisa lagi kaubanggakan. Setidaknya di depanku.
"Oh. Baguslah. Aku belum baca," kalimatku pendek-pendek. "Tahun depan aku dicalonkan oleh 6 partai untuk menjadi walikota," kukatakan itu sambil lalu saja, mereguk bir dari kaleng lalu kembali duduk di samping ranjang.
Matamu membelalak. Ini jelas berita baru. Lalu kau meraih tubuhku, mendaratkan kecupan di leher dan membisikkan selarik puisi (puisimu bertahun lalu, aku sudah hafal satu per satu) dan mengakhirinya dengan kalimat keramat "aku mencintaimu". Kemudian kata-kata itu terlontar dengan lancar seolah-olah mulutmu adalah senapan tanpa pengaman: menikahlah denganku.
Aku ingin tertawa, terpingkal-pingkal, terbahak-bahak. Kau memang pandai sekali membuat lelucon. Aku bahkan tak ingat kapan terakhir kali kata-kata cinta itu kauhantarkan. Yang aku ingat adalah bahwa dulu aku harus memohon-mohon, merengek-rengek seperti anak kecil agar kau mau mencintaiku. Tapi tak pernah, kau tak pernah mencintaiku.
Dulu, mungkin kau sudah lupa tapi aku tidak, kau mengataiku sebagai perempuan tolol. Persis seperti sebutan untuk istrimu yang sekarang. Dulu, kau menganggapku benda mati yang tak layak kauperlakukan dengan baik. Selalu ada cacian yang kaumuntahkan, bahkan untuk kesalahan yang tidak aku lakukan.
Tapi lihat aku sekarang. Setelah aku memiliki rumah mewah yang harganya 20 kali lipat dari harga rumah petak yang kautempati bersama istri dan tiga anakmu. Setelah aku memiliki dua mobil sementara kau hanya sanggup mengendarai sepeda motor tua warisan yang selalu mogok di tengah jalan. Setelah aku menjadi calon walikota, pemilik perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia sementara kau hanya penulis dan pegawai biasa. Setelah aku menyandang gelar doktor sementara kau tak lulus sarjana dan istrimu hanya tamatan SMA.Kau kembali datang padaku. Tiba-tiba kau jadi menginginkan aku lebih dari segalanya.
"Sayang, kamu mau kan jadi istriku?" bibir dan tanganmu berlomba bertamu ke tubuhku.
“Lalu istrimu? Kau akan menceraikannya?” alisku terangkat.
Kau termenung sebentar, mungkin menimbang-nimbang. “Terserah kamu saja, kalau kamu mau aku menceraikannya, akan kuceraikan. Seorang walikota tentu membutuhkan pendamping, bukan?” matamu berkedip-kedip nakal.
Aku tiba-tiba muak. Kau yang dulu mengangap dirimu raja tiba-tiba menjadi sahaya di hadapan uang dan jabatan. Kupikir hanya perempuan yang memilih jalan keselamatan semacam itu, ternyata lelaki juga.
“Maryam, menikahlah lagi denganku. Kembali menjadi istriku,” bibirmu kembali berbisik. Ada rasa sakit menjalar dari kepala ke dada. Barangkali tepat seperti inilah yang kaulakukan kepada perempuan itu, istrimu, bertahun lalu. Kau menidurinya, membisikkan kata-kata puitis di telinganya, mengeluh soal aku dan segala kebanalanku.
Mungkin kau tak tahu bahwa selama kita bercinta aku tidak menyerahkan tubuhku padamu, melainkan hanya ingin membuktikan bahwa lelaki sepertimu pun bisa tunduk di bawah kuasa tubuhku. Kau tidak sadar, siapa yang tuan dan siapa yang budak. Aku menunggu saat-saat seperti ini selama bertahun-tahun.
“Sayangnya aku sedang tak berminat memiliki suami orang miskin, berpendidikan lebih rendah dariku, bajingan pula. Bermimpilah terus,” kataku sambil membenahi barang-barang, bersiap pergi meninggalkanmu.
Matamu menyala, entah tersinggung, entah merasa bahwa kata-kataku benar adanya. Mungkin kau tak tahu. Setiap kali sehabis bercinta, aku selalu mengeluarkan akta cerai kita dari laci meja hanya untuk memastikan bahwa namaku dan namamu masih ada di sana. Memastikan bahwa kau bukan siapa-siapa kecuali lelaki dari masa lalu dan akan tetap begitu.
Menikahlah denganku ....
Suara keparatmu masih terngiang ketika aku melangkah ke arah pintu, sementara jauh di sana istri dan anak-anakmu pasti tengah menunggumu. Sama seperti aku, beberapa tahun lalu.
(Bandung, 27 Januari 2014)
Kita berdua berbaring. Telentang sambil menatap langit-langit kamar. Mata kita mengikuti perputaran kipas angin sambil menerka-nerka kapan kipas renta itu akan lelah bekerja. Setelah habis batang rokok kedua -ritual wajib sehabis bercinta- kita mulai berbicara tentang cuaca, sesekali bergumam tentang sesuatu yang tak bisa kita terka.
Kamar hotel ini berbau asap dan keringat. Tak ada pengharum ruangan agar bau tubuhmu hilang dari tubuhku. Sebetulnya aku agak terhina kaubawa ke kamar seperti ini, kamar yang harga sewanya bahkan lebih murah dari harga sebelah sepatuku. Tapi hanya seharga inilah yang sanggup kaubayar, kamar hotel bintang dua jauh di tepi kota.
“Di sini aman, tak pernah ada razia,” katamu.
Aku sendiri heran, dari dulu sampai sekarang kau lebih takut terhadap manusia daripada terhadap dosa.
Berkali-kali kau menoleh, mungkin mencari mataku, mungkin mencari bibirku, mungkin juga mencari-cari payudaraku agar kau bisa kembali tersungkur seperti balita yang haus serta rakus. Engkau berbalik, berbaring menyamping, jemarimu mulai menelusuri kembali jejak yang sempat kautinggalkan malam tadi. Maka tubuh kita kembali saling bertukar kabar. Menandak-nandak seperti penari yang lama hidup dalam jeruji. Melenguh-lenguh seperti binatang lapar dan sangar.
Berkali-kali tubuh kita saling bertamu. Berkali-kali pula aku menahan pilu. Bukan di selangkangan, melainkan di tempat lain yang tak bisa kupetakan.
"Kamu memang luar biasa," kau mengecup bibir setelah engahmu berakhir.
Tentu saja aku luar biasa. Kukenal tubuhmu sejak bertahun lalu.
"Istriku tidak bisa apa-apa. Bercinta dengannya seperti meniduri pohon pisang yang hanya bisa diam," kau mengeluh. Keluhan yang biasa. Yang sering aku dengar sehabis kita bercinta.
"Istrimu kan cantik, lebih cantik dari aku," aku duduk. "Dia juga tidak merokok, mulutnya tidak berbau tembakau seperti mulutku," aku mengacungkan rokok yang terjepit di jemariku.
Kau mengerlingkan mata. "Percuma cantik kalau hanya tahu posisi misionaris. Aku bahkan harus mengiba-ngiba agar dia mau bercinta di atas meja."
Keluhan yang sama. Masalah yang biasa. Mungkin benar bahwa kau tergila-gila padanya, perempuan dengan rambut panjang, tubuh ramping, wajah cantik, dan mengagumimu tulisan-tulisanmu setengah mampus. Baginya kau adalah dewa kata-kata, bagimu dia adalah pemuja yang harus kaupelihara.
Sedangkan denganku, kau bisa mewujudkan segala fantasi liarmu. Aku hafal Kamasutra di luar kepala, kau bisa meminta teknik yang mana saja. Aku juga bisa diajak bercinta di mana saja. Tapi kau tidak mencintaiku, bagimu aku hanya semacam pemuas nafsu.
"Aku sudah menyandang gelar doktor sejak enam bulan lalu," mungkin kau sudah tahu, tapi berpura-pura tidak tahu.
Kau berdecak kagum. "Hebat kamu ya, bisa sampai kuliah S3 segala, di luar negeri pula. Istriku bahkan tak pernah mau membaca buku, kerjanya cuma masak, nyuci, ngurus rumah, ngurus anak."
Kau kembali membandingkan. Lingkaran setan yang tak akan pernah selesai. Aku sendiri heran, jika ia sebebal itu, mengapa kau masih mau menikahinya? Menghabiskan bertahun-tahun hidup dengan perempuan yang katamu tak bisa apa-apa.
"Istriku itu ...."
"Bisa tidak kita tak usah membicarakan istrimu terus?" aku memotong sebelum kau mulai lagi. Kumatikan rokok di asbak dan berjalan ke lemari es untuk mengambil sekaleng San Miguel. Meski aku tahu untuk berbicara denganmu aku butuh minuman yang lebih keras.
"Minggu lalu cerpenku dimuat di Kompas, kamu sudah baca?" kau berusaha mengalihkan pembicaraan, setengahnya lagi pamer kemampuan. Kemampuan yang sudah tak bisa lagi kaubanggakan. Setidaknya di depanku.
"Oh. Baguslah. Aku belum baca," kalimatku pendek-pendek. "Tahun depan aku dicalonkan oleh 6 partai untuk menjadi walikota," kukatakan itu sambil lalu saja, mereguk bir dari kaleng lalu kembali duduk di samping ranjang.
Matamu membelalak. Ini jelas berita baru. Lalu kau meraih tubuhku, mendaratkan kecupan di leher dan membisikkan selarik puisi (puisimu bertahun lalu, aku sudah hafal satu per satu) dan mengakhirinya dengan kalimat keramat "aku mencintaimu". Kemudian kata-kata itu terlontar dengan lancar seolah-olah mulutmu adalah senapan tanpa pengaman: menikahlah denganku.
Aku ingin tertawa, terpingkal-pingkal, terbahak-bahak. Kau memang pandai sekali membuat lelucon. Aku bahkan tak ingat kapan terakhir kali kata-kata cinta itu kauhantarkan. Yang aku ingat adalah bahwa dulu aku harus memohon-mohon, merengek-rengek seperti anak kecil agar kau mau mencintaiku. Tapi tak pernah, kau tak pernah mencintaiku.
Dulu, mungkin kau sudah lupa tapi aku tidak, kau mengataiku sebagai perempuan tolol. Persis seperti sebutan untuk istrimu yang sekarang. Dulu, kau menganggapku benda mati yang tak layak kauperlakukan dengan baik. Selalu ada cacian yang kaumuntahkan, bahkan untuk kesalahan yang tidak aku lakukan.
Tapi lihat aku sekarang. Setelah aku memiliki rumah mewah yang harganya 20 kali lipat dari harga rumah petak yang kautempati bersama istri dan tiga anakmu. Setelah aku memiliki dua mobil sementara kau hanya sanggup mengendarai sepeda motor tua warisan yang selalu mogok di tengah jalan. Setelah aku menjadi calon walikota, pemilik perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia sementara kau hanya penulis dan pegawai biasa. Setelah aku menyandang gelar doktor sementara kau tak lulus sarjana dan istrimu hanya tamatan SMA.Kau kembali datang padaku. Tiba-tiba kau jadi menginginkan aku lebih dari segalanya.
"Sayang, kamu mau kan jadi istriku?" bibir dan tanganmu berlomba bertamu ke tubuhku.
“Lalu istrimu? Kau akan menceraikannya?” alisku terangkat.
Kau termenung sebentar, mungkin menimbang-nimbang. “Terserah kamu saja, kalau kamu mau aku menceraikannya, akan kuceraikan. Seorang walikota tentu membutuhkan pendamping, bukan?” matamu berkedip-kedip nakal.
Aku tiba-tiba muak. Kau yang dulu mengangap dirimu raja tiba-tiba menjadi sahaya di hadapan uang dan jabatan. Kupikir hanya perempuan yang memilih jalan keselamatan semacam itu, ternyata lelaki juga.
“Maryam, menikahlah lagi denganku. Kembali menjadi istriku,” bibirmu kembali berbisik. Ada rasa sakit menjalar dari kepala ke dada. Barangkali tepat seperti inilah yang kaulakukan kepada perempuan itu, istrimu, bertahun lalu. Kau menidurinya, membisikkan kata-kata puitis di telinganya, mengeluh soal aku dan segala kebanalanku.
Mungkin kau tak tahu bahwa selama kita bercinta aku tidak menyerahkan tubuhku padamu, melainkan hanya ingin membuktikan bahwa lelaki sepertimu pun bisa tunduk di bawah kuasa tubuhku. Kau tidak sadar, siapa yang tuan dan siapa yang budak. Aku menunggu saat-saat seperti ini selama bertahun-tahun.
“Sayangnya aku sedang tak berminat memiliki suami orang miskin, berpendidikan lebih rendah dariku, bajingan pula. Bermimpilah terus,” kataku sambil membenahi barang-barang, bersiap pergi meninggalkanmu.
Matamu menyala, entah tersinggung, entah merasa bahwa kata-kataku benar adanya. Mungkin kau tak tahu. Setiap kali sehabis bercinta, aku selalu mengeluarkan akta cerai kita dari laci meja hanya untuk memastikan bahwa namaku dan namamu masih ada di sana. Memastikan bahwa kau bukan siapa-siapa kecuali lelaki dari masa lalu dan akan tetap begitu.
Menikahlah denganku ....
Suara keparatmu masih terngiang ketika aku melangkah ke arah pintu, sementara jauh di sana istri dan anak-anakmu pasti tengah menunggumu. Sama seperti aku, beberapa tahun lalu.
(Bandung, 27 Januari 2014)

Published on April 05, 2014 23:33
March 26, 2014
Kepada Perempuan Lain
:Entah
Satu-satunya kesalahan yang kulakukan adalah jatuh cinta kepadanya dan membiarkan dia juga jatuh kepadaku. Meski aku insyaf bahwa hidup adalah perputaran ritual. Kemarin orang lain mengambil milikku, hari ini aku nyaris mengambil milikmu. Tapi engkau boleh bertenang hati, karma ini hanya akan sampai di sini.
Puan, sebetulnya aku ingin sekali menyalahkan makhluk bernama cinta yang tiba-tiba mengerangkeng kami berdua; aku dan dia. Sayangnya di dalam kisah seperti ini, akulah ular yang memaksa Adam memakan buah neraka. Di dalam kisah seperti ini, akulah yang harus dirajam; perempuan lain yang tiba-tiba hadir dalam sebuah kapal.
Jika kata maaf bisa ditakar, maka permintaan maafku padamu akan meruntuhkan segala timbangan. Aku tahu bagaimana menjadi engkau, rasa nyeri seakan ada ribuan pisau menari-nari di dalam hati itu pernah aku alami. Maka terkutuklah aku si pelacur yang menjebak kita dalam perputaran ini. Terkutuklah aku!
Puan, demi Tuhan yang namaNya masih tetap kurapal, aku tak pernah ingin mencuri. Bahkan aku tak pernah memintamu untuk berbagi. Kami hanya dua orang yang tersesat, tak tahu jalan untuk kembali. Engkaulah peta petunjuk jalannya, cinta dan kesungguhanmu akan membawa dia kepadamu. Sedangkan aku hanyalah rambu timpang yang ia temukan di tepi jalan, tak akan bisa membuatnya sampai ke manapun.
Di dalam setiap pertempuran, akulah perempuan yang senantiasa menanggung beban kekalahan. Maka demi hatimu yang kujaga agar tak berserak, kukembalikan ia meski hatiku sendiri lantak.
Engkau sudah lebih lama bersamanya sementara aku hanya persimpangan yang membuat langkahnya kadang tegap kadang lindap. Di dalam rengkuh pelukmu, tentu ia akan menyala lebih terang sedangkan di lingkup dadaku, ia hanya akan menjadi kunang-kunang yang cahayanya semakin remang.
Kau tak akan lagi melihat, mendengar, atau tahu apa pun tentang aku. Milikmu sudah kukembalikan dengan utuh. Berbahagialah.
Berbahagialah.
Aku tak mengenal engkau, engkau tak mengenal aku.
Tapi saat ini engkau sedang bersama seseorang yang kepadanya aku ingin pulang.
Satu-satunya kesalahan yang kulakukan adalah jatuh cinta kepadanya dan membiarkan dia juga jatuh kepadaku. Meski aku insyaf bahwa hidup adalah perputaran ritual. Kemarin orang lain mengambil milikku, hari ini aku nyaris mengambil milikmu. Tapi engkau boleh bertenang hati, karma ini hanya akan sampai di sini.
Puan, sebetulnya aku ingin sekali menyalahkan makhluk bernama cinta yang tiba-tiba mengerangkeng kami berdua; aku dan dia. Sayangnya di dalam kisah seperti ini, akulah ular yang memaksa Adam memakan buah neraka. Di dalam kisah seperti ini, akulah yang harus dirajam; perempuan lain yang tiba-tiba hadir dalam sebuah kapal.
Jika kata maaf bisa ditakar, maka permintaan maafku padamu akan meruntuhkan segala timbangan. Aku tahu bagaimana menjadi engkau, rasa nyeri seakan ada ribuan pisau menari-nari di dalam hati itu pernah aku alami. Maka terkutuklah aku si pelacur yang menjebak kita dalam perputaran ini. Terkutuklah aku!
Puan, demi Tuhan yang namaNya masih tetap kurapal, aku tak pernah ingin mencuri. Bahkan aku tak pernah memintamu untuk berbagi. Kami hanya dua orang yang tersesat, tak tahu jalan untuk kembali. Engkaulah peta petunjuk jalannya, cinta dan kesungguhanmu akan membawa dia kepadamu. Sedangkan aku hanyalah rambu timpang yang ia temukan di tepi jalan, tak akan bisa membuatnya sampai ke manapun.
Di dalam setiap pertempuran, akulah perempuan yang senantiasa menanggung beban kekalahan. Maka demi hatimu yang kujaga agar tak berserak, kukembalikan ia meski hatiku sendiri lantak.
Engkau sudah lebih lama bersamanya sementara aku hanya persimpangan yang membuat langkahnya kadang tegap kadang lindap. Di dalam rengkuh pelukmu, tentu ia akan menyala lebih terang sedangkan di lingkup dadaku, ia hanya akan menjadi kunang-kunang yang cahayanya semakin remang.
Kau tak akan lagi melihat, mendengar, atau tahu apa pun tentang aku. Milikmu sudah kukembalikan dengan utuh. Berbahagialah.
Berbahagialah.

Published on March 26, 2014 17:37
Detak yang Berangkat Lantak

:IM
Mungkin kita memang harus berpisah dengan cara seperti ini. Cara paling menyakitkan dengan sumpah serapah sebagai pengantar ucapan selamat jalan. Dengan semua pintu yang kaututup rapat-rapat, dengan rindu yang kausimpan erat.
Aku tahu, kita akan benar-benar sampai pada hari ini.
eV, berbulan-bulan kita bersama. Saling berebut tempat tentang siapa yang paling mencintai siapa. Menghitung rindu lalu berdebat bahwa rindumu lebih banyak dari rinduku. Tak peduli terhadap ribuan pasang mata yang mungkin saja mencaci aku sebagai badai di dalam kapalmu yang tenteram. Kita hanya tahu untuk mabuk, terus-menerus minum tuak hingga lambung kita dihiasi tukak demi tukak.
Tapi kita memang harus sampai pada hari ini.
Meski jutaan janji pernah berkelindan dalam udara. Tentang kau yang konon akan selalu menjadi debur air laut, menemani dermaga kesepian sepertiku. Tentang kau yang katanya akan menyediakan bahu dan punggung tempatku bersandar, tempatku pulang. Tentang kau yang bersedia berangkat tua, bersamaku.
Lalu aku, dengan rasa mabuk yang sama juga menguarkan janji demi janji. Bahwa namamu akan menjadi satu-satunya nama lelaki di dalam sini. Bahwa aku akan bersetia hingga mati. Bahwa aku akan menunggumu hingga saatnya kau bisa membawaku pergi.
Sayangnya kita harus sampai pada hari ini.
Ketika kenyataan merajam cinta hingga karam. Ketika masing-masing dari kita tidak bisa bertahan dari pisau yang dihunjamkan orang-orang. Ketika kita, sama-sama dipaksa untuk saling merelakan.
eV, kekasihku.
Aku mengerti bahwa sulit bagi kita untuk melepaskan jangkar di dada masing-masing. Sulit bagiku untuk membuang ingatan tentang jejakmu di tubuhku. Juga sulit bagimu untuk kembali sembuh dari rindu yang selalu menunggu untuk berlabuh, kepadaku. Namun apalah kita, eV? Hanya dua orang yang pernah dipertemukan, saling jatuh cinta, untuk kemudian mengambil setapak yang berbeda. Bukankah, memang seperti itulah cinta?
Lalu sampailah kita pada hari ini.
Hari ketika kita harus mengemas setiap luka yang kian meranggas. Maka simpanlah aku rapat-rapat di dalammu. Jangan pernah kaubuka kembali sebab akan mendatangkan nyeri. Maka aku akan menyimpanmu juga, lekat di dalam sini. Mungkin suatu saat aku akan ingat bahwa ada lelaki yang mencintaiku dengan benar; kamu.
Aku juga akan menyimpan kunci kamar nomor 313, dan kamu bisa menyimpan gambar-gambar lukisanmu di tubuhku. Hanya sebagai memorabilia, mungkin juga penanda luka.
Ya, akhirnya kita sampai pada hari ini.
Saat kau harus benar-benar pergi.
Dan aku ditinggal sendiri.
P.S. Setiap hujan turun, kau akan selalu ingat aku.

Published on March 26, 2014 06:00
Mimpi dan Ilusi
- Skylashtar Maryam's profile
- 8 followers
Skylashtar Maryam isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.



