Skylashtar Maryam's Blog: Mimpi dan Ilusi, page 16
December 3, 2013
[Cerpen] Nadran_Pikiran Rakyat, 1 Desember 2013

Permusuhanku dengan Ibu selalu dimulai dari pertanyaan yang sama: “Kapan kamu akan nadran ke makam anakmu?”. Pertanyaan itu pun berulang setiap tahun di setiap kali kepulanganku ke Babakan. Bagi Ibu, nadran bukan hanya amalan mengingat kematian melainkan sudah menjadi semacam ritual. Dia melakukannya setiap bulan selama bertahun-tahun. Semakin banyak anggota keluarga kami yang mati, maka semakin giranglah dia, karena itu artinya Ibu memiliki satu lagi alasan untuk tetap nadran dan berlama-lama di pemakaman.
Jadwal nadran Ibu adalah di hari Jumat pertama setiap bulan. Jadwal yang kerap kali memusuhi jadwal membayar listrik ataupun pengajian. Jika ada perhelatan di hari Jumat pertama, maka sudah dipastikan Ibu tak akan datang. Dia lebih memilih untuk nadran; menganyam doa di pinggiran makam.
Ibu, di usianya yang merangkak menuju tengah baya, akan menyisihkan sebagian uang belanja yang diberikan Bapak untuk ritualnya itu. Dia memasak satu boboko nasi kuning serta lauk pauk yang tak akan pernah Ibu hidangkan di atas meja makan kami. Ayam panggang, pindang ikan mas, pais peda, urap, sambal terasi, beberapa potong tahu dan tempe yang yang ukurannya cukup untuk tiga orang. Bukan hanya itu, Ibu juga menyiapkan beberapa botol air dalam kemasan ukuran satu setengah liter, sekeranjang bunga rampai yang sepertinya cukup untuk membuat badanmu berbau seperti taman.
Benda-benda yang dianggap sebagai bakti terhadap anggota keluarga yang sudah mati itu dibawa Ibu ke Mak Iti, perempuan paling tua di Babakan. Mak Iti, sepanjang ingatanku adalah indung beurang yang memiliki banyak sekali keahlian. Anehnya,semua kehlian Mak Iti selalu berhubungan dengan kelahiran dan kematian. Di dalam ritual Ibu, Mak Iti berperan sebagai pendoa. Benda-benda yang Ibu bawa akan didoakan, diamini, tapi tak dikembalikan.
“Itu kan sedekah untuk keluarga kita yang sudah meninggal, Sum. Jika semasa hidup aku tak bisa memberikan makanan mewah seperti itu untuk uyutmu, maka sekaranglah masa yang tepat untuk membalas jasa-jasanya. Jadi tutup saja mulut nyinyirmu itu.”
Itu selalu yang dikatakan Ibu jika sedikit saja aku memperlihatkan ketidaksetujuan. Lagi pula, bagaimana mungkin aku mengamini semua yang dilakukan Ibu jika itu malah mendatangkan nasib celaka bagi perut kami, anak-anaknya? Selain menyunat uang belanja yang diberikan Bapak, tak jarang Ibu berutang pada tetangga untuk ritual nadrannya.
Setelah aku dewasa, menikah, memiliki anak, bercerai, merantau ke Batam, sampai aku pulang kembali ke kampung halaman, ritual Ibu itu tak juga usai. Maka setiap kali aku pulang, pertanyaan itulah yang sering kali ia ulang.
*
“Tadi malam aku bermimpi buruk sekali, Sum,” bisik Ibu begitu aku masuk ke dapur. Tangannya yang sedang menyiapkan sarapan sejenak berhenti.
“Mimpi apa?” pertanyaan yang kuajukan tidak berisi keingintahuan barang setetes. Tapi Ibu tak akan berhenti berbicara terlepas apakah aku bertanya atau tidak.
“Aku bermimpi anakmu telanjang sambil menangis di tepi makam, katanya dia kedinginan.”
Aku mendengus. Apa lagi ini? “Lalu?”
“Dia minta dikirimi pakaian,” bisik Ibu. Dengan pandai ia mengatur intonasi suaranya agar dramatis dan mistis.
“Lalu?” aku mengangkat alis, sesuatu yang sangat dibenci Ibu.
“Belilah barang sepotong dua potong pakaian di Pasar Cibogo lalu kirimkan pada anakmu itu. Kalau kamu tak mau, biar aku yang pergi ke pasar dan mengantarkannya ke Mak Iti,” suara Ibu mulai meninggi.
Aku hanya mengeleng-gelengkan kepala, mulai menyapu lantai dapur tanpa banyak bersuara.
“Sum!” panggil Ibu ketika dilihatnya aku tak menggubrisnya lagi. “Kalau kamu tak mau, biar Ibu yang membelinya ke pasar,” ulangnya.
“Bu …,” kubuat suaraku serendah mungkin. “Apa Ibu tahu bahwa anak Teteh sudah meninggal?”
“Ya tentu saja aku tahu, aku kan yang memandikan dan ikut menguburkannya.”
“Apa Ibu yakin kalau Najwa masuk surga?” aku berdiri di ambang pintu dapur sementara tanganku masih menggenggam sapu.
“Bicara apa kamu ini? Tentu saja anakmu yang meninggal sewaktu bayi itu akan masuk surga, juga menjadi pembuka pintunya untukmu, barangkali juga untukku,” suara Ibu masih tinggi.
“Kalau dia masuk surga, berarti dia tak akan pernah kekurangan apa-apa. Untuk apa kita harus repot-repot mengirimkan barang-barang dunia kepadanya?”
Setelah kalimat itu kukeluarkan, Ibu sempurna diam. Entah karena kata-kataku yang bertemu dengan kebenaran di dalam kepalanya, atau karena alasan-alasan yang tidak dapat kuterka. Yang jelas Ibu sama sekali berhenti berbicara.
Tadinya kukira bahwa diamnya Ibu adalah semacam pertobatan, tapi bukan Ibu namanya kalau kegandrungannya terhadap memuaskan mereka yang sudah mati dapat begitu saja dihentikan. Siangnya Ibu justru pergi ke pasar, membeli tiga stel pakaian bayi, mainan, selimut, satu dus susu formula, dan tiga dus makanan bayi. Barang-barang itu dibawanya kepada Mak Iti, dan tentu saja tak kembali.
Setelah berpuas diri dengan mengirimkan sesaji dan ritual nadran yang semakin lama waktunya semakin panjang, Ibu pulang ke rumah dengan raut wajah semringah. Tak lupa ia membawa bekal sebotol air mineral yang telah diberi doa dan memberikannya kepadaku. Agar aku tak lupa pada tradisi, katanya.
Dua hari kemudian seorang tetangga bertandang untuk menagih utang. Utang apalagi kalau bukan utang Ibu, utang yang dipakainya untuk memuaskan mimpi-mimpi dan ritual nadrannya. Tentu saja aku meradang, meski utang itu tetap kubayar.
Mestinya Ibu tahu bahwa kepulanganku ke Babakan tidaklah berbekal berkarung uang. Berapalah gaji seorang buruh pabrik tamatan SMU yang usianya tak muda lagi sepertiku? Aku hanya berhasil menabung tak lebih dari dua juta rupiah, itu artinya aku harus cepat mendapatkan pekerjaan di Bandung jika tak ingin hidupku terkatung-katung. Sebab bagiku, menumpang hidup di rumah orang tua –apalagi dengan kegemaran Ibu- tidak berarti aku bisa menumpang makan dan tidur seenaknya.
*
Permusuhanku dengan Ibu kemudian dimulai dengan pembukaan yang berbeda: “Tadi malam aku bermimpi ….”. Jika di suatu pagi Ibu mengatakan bahwa ia bermimpi, maka aku akan cepat menjawabnya bahwa mimpi baik itu berasal dari Tuhan sedangkan mimpi buruk asalnya dari setan. Dan mimpi buruk jelas tak layak diceritakan.
Biasanya, Ibu akan menutup mulutnya rapat-rapat setelah mendengar sanggahanku. Ia akan dengan senang hati menganggapku batu, tak ingin berbicara atau bertegur sapa. Kedua adikku sudah menikah dan tinggal di rumah yang berbeda, ikut dengan suami-suami mereka. Otomatis, jika Bapak pergi bekerja, aku dan Ibulah yang ada di rumah seharian. Aku tahu, Ibu sengaja menjadikanku orang asing semata-mata karena mulut nyinyirku.
Meski mimpi-mimpi Ibu kerap kali tidak kutanggapi, ia tak lantas berhenti. Ritual nadrannya seakan tak memiliki tepi. Aku sendiri heran, mengapa banyak sekali orang mati yang mengajukan permintaan? Permintaan yang membuat Ibu semakin khusyuk nadran dan berdoa di atas makam, juga semakin khusyuk berutang. Utang yang tentu saja harus aku atau Bapak bayar.
Semakin aku geram, semakin seringlah Ibu pergi ke makam. Karena menolak berbicara denganku, Ibu akan menggerutu sendirian di dapur dengan suara keras agar aku juga bisa mendengar. Dalam gerutuannya, sesekali Ibu seolah-olah sedang berbincang dengan Najwa, almarhum putriku. Dikatakannya bahwa sebagai nenek ia tak akan membiarkan cucunya nelangsa di akhirat sana, tak seperti aku ibunya.
Dalau gerutuannya, sering pula Ibu mengatakan bahwa aku adalah anak sulung yang tak tahu tradisi, tak mengerti agama. Sering kali Ibu menuding-nuding jilbab yang kukenakan dan mengatakan bahwa itu hanya pakaian yang membuatku justru semakin kurang ajar. Semakin tak tahu aturan.
Jika gerutuannya kubalas dengan pertanyaan “Apakah Ibu sudah salat atau belum?”, maka ia akan semakin berang. Semakin memiliki alasan untuk pergi ke makam dan melakukan ritual nadran, meski belum awal bulan. Dan aku, dengan keras kepala akan terus-menerus menolaknya. Sebab bagiku, kematian bukan sesuatu yang harus selalu dirayakan. Bagiku, bersebrangan dengan kepercayaan Ibu, doa tak harus dilarungkan di atas nisan, apalagi jika harus melalui ritual yang dipaksakan. Jika beras di dapur kami yang masih hidup ini kadang ada kadang tiada, untuk apa aku harus berutang kesana-kemari hanya untuk memuaskan keinginan mereka yang jelas-jelas sudah mati?
Bagi Ibu, aku adalah anak yang mengingkari tradisi. Bagiku, Ibu adalah manusia yang selalu menolak untuk mengerti.
*
Setelah bertahun-tahun, permusuhanku dengan Ibu tidak lantas berhenti. Bahkan setelah ia sendiri dihampiri maut; sesuatu yang semasa hidup ia puja sekaligus ia takuti. Ibu, kerap datang ke dalam mimpi dan menggumamkan hal yang sama berulang kali.
“Kapan kamu akan nadran ke makamku, Sum? Aku begitu kesepian dan kedinginan.”
Rupanya Bapak tidak pernah memimpikan hal yang sama. Ketika kubisikkan mimpi itu ke telinga tuanya, ia hanya terbatuk-batuk lantas menghunuskan mata penuh pertanyaan. Mungkin ia sedang menerka, apakah anak sulungnya ini sedang mengarang cerita ataukah sudah berangkat gila?
Namun mimpi itu selalu kembali, selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sehingga aku nyaris tak tahan.
“Pergilah berziarah. Toh doa bisa dipanjatkan kapan dan di mana saja,” kata Bapak setelah beribu kali aku mengeluhkan mimpi yang sama.
“Ibu juga minta dikirimi baju dan selimut,” suaraku parau, berusaha menepis ingatan tentang Ibu yang duduk telanjang di tepian makam dengan mata murka.
Mata Bapak menerawang, mungkin sedang mencari jawaban. “Lakukan apa saja yang kaupercayai, Sum. Ini hanya ikhtiar untuk membuat tidurmu tenang,” katanya.
Maka aku pergi ke makam Ibu tanpa berbekal apa-apa sebab Surat Yasin yang sering dirapal orang-orang ketika ziarah sudah kuhafal di luar kepala, tidak juga berbekal baju atau selimut seperti yang diminta Ibu di dalam mimpi. Sesampainya di pemakaman, kubersihkan ilalang dan daun-daun kering yang berkeliaran di atas kuburannya. Lalu aku mulai berdoa, untuk keselamatan Ibu, untuk ketentramannya di akhirat sana. Itu adalah doa yang sama yang kupanjatkan setiap kali sehabis salat. Tak ada yang berbeda. Benar kata Bapak, toh doa bisa dipanjatkan di mana saja.
Ibu pun berhenti datang ke dalam mimpi. Permusuhan kami telah menemukan tepi.
(Bandung, 27 November 2013)

Published on December 03, 2013 10:37
November 22, 2013
Out; Setiap Orang Bisa Menjadi Pembunuh
 Foto dicuri dari Uthera Kalimaya
Foto dicuri dari Uthera KalimayaJudul: Bebas [Out]
Penulis: Natsuo Kirino
Penerbit: GPU (2007)
ISBN: 979-22-2760-1
Halaman: 576 halaman
Di daerah pinggiran Tokyo, empat wanita bekerja shift malam di pabrik makanan kotak. Beban hidup yang berat dan utang menumpuk membuat Yayoi, salah satu dari mereka, tak tahan lagi. dia membunuh suaminya yang penjudi dan suka main perempuan, kemudian meminta bantuan pada Masako, teman sekerjanya yang paling karib. Masako bersedia membantu, dan bersama wanita-wanita lainnya, mereka menyingkirkan mayat itu. Ketika bagian-bagian tubuh mayat ditemukan, polisi mulai melacak pembunuhnya. Tapi bukan hanya polisi yang mengejar mereka, melainkan juga musuh-musuh yang sangat berbahaya---seorang lintah darat yang berkaitan dengan yakuza dan mengetahui rahasia mereka, serta seorang pemilik kelab malam yang kejam, yang dituduh sebagai pembunuh oleh polisi. Akibatnya dia kehilangan segala harta miliknya, dan kini dia berniat membalas dendam.
---
Setelah selesai membaca novel ini, saya menemukan fakta mengerikan; para pengarang dan sineas Jepang ternyata lebih 'sakit' daripada para pengarang dan sineas dari negara manapun. Natsuo Kirino hanyalah satu dari pengarang Jepang yang menulis dalam genre yang sama. Jepang punya Ryunosuke Akutagawa, cerpennya Lukisan Neraka mampu menghadirkan mimpi buruk bagi pembacanya, entah karena cara dia menulisnya, atau karena imaji itu sendiri begitu meresap sehingga kengerian yang dihadirkan begitu menghantui. Jepang juga punya Shoji Shimada dengan The Tokyo Zodiac Murders-nya yang bisa dengan mudah menyaingi novel-novel Agatha Christie. Saya juga tidak akan lupa bahwa film-film horor paling menakutkan berasal dari para sineas yang sama; Jepang. Anda tentu masih ingat mimpi buruk yang dihadirkan oleh The Ring.
Saya sebetulnya ingin mengatakan, beginilah seharusnya sebuah novel thriller ditulis. Tapi rasanya agak mengkhawatirkan jika novel-novel seperti Out makin banyak beredar di pasaran. Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan literasi, Out memang benar-benar menakutkan.
Karena sudah terlanjur membandingkan novel-novel para pengarang Jepang dengan negara lain yang menulis genre sejenis, jadi sebaiknya saya membuat semacam analisis komparasi.

Entahlah, tapi setelah membaca novel-novel Jepang, sepertinya psikopat atau DID sudah bukan isu yang seksi lagi.

Published on November 22, 2013 11:13
[Resensi] Out_Setiap Orang Bisa Menjadi Pembunuh

Foto dicuri dari Uthera Kalimaya
Judul: Bebas [Out]
Penulis: Natsuo Kirino
Penerbit: GPU (2007)
ISBN: 979-22-2760-1
Halaman: 576 halaman
Di daerah pinggiran Tokyo, empat wanita bekerja shift malam di pabrik makanan kotak. Beban hidup yang berat dan utang menumpuk membuat Yayoi, salah satu dari mereka, tak tahan lagi. dia membunuh suaminya yang penjudi dan suka main perempuan, kemudian meminta bantuan pada Masako, teman sekerjanya yang paling karib. Masako bersedia membantu, dan bersama wanita-wanita lainnya, mereka menyingkirkan mayat itu. Ketika bagian-bagian tubuh mayat ditemukan, polisi mulai melacak pembunuhnya. Tapi bukan hanya polisi yang mengejar mereka, melainkan juga musuh-musuh yang sangat berbahaya---seorang lintah darat yang berkaitan dengan yakuza dan mengetahui rahasia mereka, serta seorang pemilik kelab malam yang kejam, yang dituduh sebagai pembunuh oleh polisi. Akibatnya dia kehilangan segala harta miliknya, dan kini dia berniat membalas dendam.
---
Setelah selesai membaca novel ini, saya menemukan fakta mengerikan; para pengarang dan sineas Jepang ternyata lebih 'sakit' daripada para pengarang dan sineas dari negara manapun. Natsuo Kirino hanyalah satu dari pengarang Jepang yang menulis dalam genre yang sama. Jepang punya Ryunosuke Akutagawa, cerpennya Lukisan Neraka mampu menghadirkan mimpi buruk bagi pembacanya, entah karena cara dia menulisnya, atau karena imaji itu sendiri begitu meresap sehingga kengerian yang dihadirkan begitu menghantui. Jepang juga punya Shoji Shimada dengan The Tokyo Zodiac Murders-nya yang bisa dengan mudah menyaingi novel-novel Agatha Christie. Saya juga tidak akan lupa bahwa film-film horor paling menakutkan berasal dari para sineas yang sama; Jepang. Anda tentu masih ingat mimpi buruk yang dihadirkan oleh The Ring.
Saya sebetulnya ingin mengatakan, beginilah seharusnya sebuah novel thriller ditulis. Tapi rasanya agak mengkhawatirkan jika novel-novel seperti Out makin banyak beredar di pasaran. Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan literasi, Out memang benar-benar menakutkan.
Karena sudah terlanjur membandingkan novel-novel para pengarang Jepang dengan negara lain yang menulis genre sejenis, jadi sebaiknya saya membuat semacam analisis komparasi.

Entahlah, tapi setelah membaca novel-novel Jepang, sepertinya psikopat atau DID sudah bukan isu yang seksi lagi.

Published on November 22, 2013 11:13
November 18, 2013
Wisata Kata Bersama Telimpuh
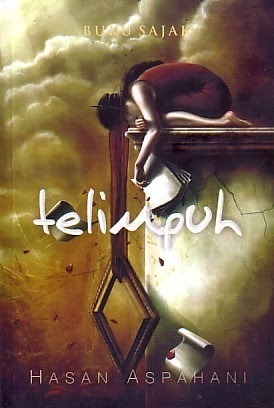
Judul: Telimpuh (Kumpulan Puisi)
Penulis: Hasan Aspahani
Penerbit: Penerbit Koekoesan (Juni 2009)
Halaman: 107 + xiii
ISBN: 978-979-1442-28-2
Saya kerap tercengang dan iri ketika membaca puisi-puisi Hasan Aspahani di Telimpuh. Tercengang karena di tangan Hasan, segala benda di hadapan yang tadinya biasa saja ternyata bisa menjadi momen dan diksi puitis. Iri karena kepekaan seperti itu belum bisa saya miliki.
Teknik pengolahan Hasan sedikit banyak mengingatkan saya kepada Arif Fitra Kurniawan (penyair muda asal Semarang) meski pendekatan metafora keduanya tidak bisa dibilang seragam. Eksplorasi pemilihan kata Hasan mau tidak mau mendobrak unsur-unsur puitis yang selama ini kita tahu, semisal: hujan, malam, daun, gerimis, dan lain sebagainya.
Melalui telimpuh, saya diajak untuk menyusuri petak-petak kamus bahasa Indonesia yang jarang sekali saya buka dan baru menyadari bahwa banyak kata yang disebutkan itu memang benar-benar ada. Ah, betapa bodohnya saya.
Yang sering saya amati dari sebuah puisi adalah kenikmatan membaca. Memamah Telimpuh bisa diibaratkan dengan menyantap sepotong kue beraroma teh hijau; legit, harum, gurih. Bahkan setelah potongan terakhir habis dimamah perut, rasa legit masih tersisa di mulut.
Sayangnya Hasan seperti mulai kehilangan tenaga di Bab IV "Tetapi, Aku Penyair!". Entah karena puisi-puisi yang ada di bab itu diperuntukkan kepada kawan-kawan sesama penyair sehingga ia harus menggali ingatan (yang terus terang memang melelahkan), atau karena ia terlalu berhati-hati. Di bab ini saya tidak lagi bisa merasakan kebebasan Hasan seperti di bab-bab sebelumnya.
Overall, Telimpuh berhasil menjadi salah satu buku puisi favorit saya.

Published on November 18, 2013 19:54
[Resensi] Wisata Kata Bersama Telimpuh
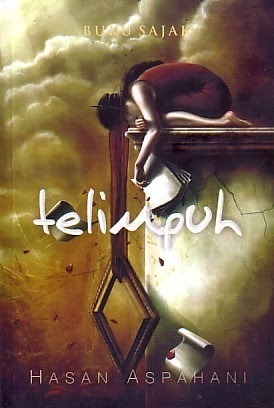
Judul: Telimpuh (Kumpulan Puisi)
Penulis: Hasan Aspahani
Penerbit: Penerbit Koekoesan (Juni 2009)
Halaman: 107 + xiii
ISBN: 978-979-1442-28-2
Saya kerap tercengang dan iri ketika membaca puisi-puisi Hasan Aspahani di Telimpuh. Tercengang karena di tangan Hasan, segala benda di hadapan yang tadinya biasa saja ternyata bisa menjadi momen dan diksi puitis. Iri karena kepekaan seperti itu belum bisa saya miliki.
Teknik pengolahan Hasan sedikit banyak mengingatkan saya kepada Arif Fitra Kurniawan (penyair muda asal Semarang) meski pendekatan metafora keduanya tidak bisa dibilang seragam. Eksplorasi pemilihan kata Hasan mau tidak mau mendobrak unsur-unsur puitis yang selama ini kita tahu, semisal: hujan, malam, daun, gerimis, dan lain sebagainya.
Melalui telimpuh, saya diajak untuk menyusuri petak-petak kamus bahasa Indonesia yang jarang sekali saya buka dan baru menyadari bahwa banyak kata yang disebutkan itu memang benar-benar ada. Ah, betapa bodohnya saya.
Yang sering saya amati dari sebuah puisi adalah kenikmatan membaca. Memamah Telimpuh bisa diibaratkan dengan menyantap sepotong kue beraroma teh hijau; legit, harum, gurih. Bahkan setelah potongan terakhir habis dimamah perut, rasa legit masih tersisa di mulut.
Sayangnya Hasan seperti mulai kehilangan tenaga di Bab IV "Tetapi, Aku Penyair!". Entah karena puisi-puisi yang ada di bab itu diperuntukkan kepada kawan-kawan sesama penyair sehingga ia harus menggali ingatan (yang terus terang memang melelahkan), atau karena ia terlalu berhati-hati. Di bab ini saya tidak lagi bisa merasakan kebebasan Hasan seperti di bab-bab sebelumnya.
Overall, Telimpuh berhasil menjadi salah satu buku puisi favorit saya.

Published on November 18, 2013 19:54
November 16, 2013
Firefly
 Aku hanyalah kunang-kunang yang berpendar di pepucuk dedaunan ketika hujanmu menepi dan terdiam. Aku pengecut, Fe. Kunang-kunang yang senantiasa bersembunyi dari badai, pun dari gerimis tipis karena takut sayapku lantak oleh jarum-jarum air yang menghunjam.
Aku hanyalah kunang-kunang yang berpendar di pepucuk dedaunan ketika hujanmu menepi dan terdiam. Aku pengecut, Fe. Kunang-kunang yang senantiasa bersembunyi dari badai, pun dari gerimis tipis karena takut sayapku lantak oleh jarum-jarum air yang menghunjam. Dan engkau bagiku adalah gelegak matahari; panas dan bara dalam kemegahanmu. Mataku selalu saja pasi ketika berhadapan denganmu. Jika dibandingkan dengan sinar yang menjalar dari lengan dan bahumu, kerlip kunang-kunangku adalah semu.
“Cintai aku sampai tua dan mati,” bisikmu.
“Aku tak akan lagi menolak, kemanapun takdir bermuara. Bila itu bersamamu, maka aku akan bersamamu,” bisikmu lagi.
Ah, Fe. Andaikan engkau tahu bahwa perempuan seperti aku sudah lelah dicumbui berbagai rindu yang tak pernah usai dan sampai. Jadi ke mana harus kukepakkan sayapku yang kian gontai? Cinta kini hanya suara-suara dari negeri nan jauh. Cinta kini hanya membuat pendarku sedemikian lusuh.
Bukan aku, Fe. Bukan aku perempuan yang kau inginkan selama ini, kan? Sebab takdir tak pernah memiliki tangan kecuali jika kita membawanya serta menapaki jejalan. Engkau selalu mengatakan bahwa nasib membawamu mengair dan mengalir. Tapi engkau lupa mengatakan bahwa muara segala sungai tak pernah bisa digenggam. Tak pernah bisa diramal.
“Pernahkah kamu mencintai aku? Sekali saja?” suaraku selalu getar parau ketika kata-kata cinta teruar.
Kamu diam. Suaramu juga bagai ditelan kelepak kelelawar.
“Sekali saja, jawab pertanyaanku. Apakah kamu mencintaiku, Fe?” kulipat jemari di genggamanmu dengan harapan menghantar hangat, untukmu, terlebih lagi untukku.
“Apa dengan bersamamu saja tidak cukup?” matamu terlempar ke arah jendela. Di luar hujan, deras dan kuyup.
“Kadang cinta butuh pengakuan,” hujan berpindah ke mataku.
Ya, Fe. Kadang cinta butuh diteriakkan. Bukan hanya kata yang mengawang di langit-langit kamar. Ia bisa saja lelah lalu goyah, berpindah.
“Jangan pernah tanya hatiku, Na. Jangan pernah…” kepalamu menggeleng perlahan sementara matamu masih tertawan di luar.
Mataku menderas, meranggas, retas.
“Jangan menangis,” bisikmu.
Bahuku berguncang, ingin sekali melolosi segala beban. “Jangan siksa aku seperti ini, Fe. Kamu ingin aku mencintaimu, ingin terus langkahku berderap ke arahmu. Tapi kamu … kamu tak pernah ingin tahu, tak pernah sekalipun mencoba mencintaiku,” bibirku terasa pahit, sisa rasa obat-obat yang dijejalkan para perawat. Tapi hatiku lebih pahit, dan tak ada obat apa pun yang bisa mendistraksi setiap rasa sakit.
Kemudian tanganku dihantarkan ke dadamu. “Kamu rasakan denyutan di sana, Na? Ia berisi nama kamu, bukan nama orang lain seperti yang kamu sangka selama ini. Jika itu bisa diartikan cinta, maka artikanlah itu sebagai cinta.”
Aku menggeleng. “Kunang-kunang yang berpendar …” bibirku gemetar.
“Kamu adalah kunang-kunang yang menari sehabis hujanku,” bisikmu.
“Rapuh, jenuh,” bibirku masih bergetar.
Matamu lalu liar merayapi dinding kamar. Ibu jari menjalar ke pergelangan tanganku yang dibentengi perban. “Jangan berniat pergi dengan cara seperti ini. Aku akan sakit jika kamu pergi, mungkin juga akan mati.”
“Matahari tidak pernah mati.”
“Jangan pergi dengan cara seperti ini ….”
Botol infus bergoyang-goyang di atas tiang di samping kiri. Pergelangan tangan kiriku seketika dicumbu ngilu. Aku, Fe. Ingin sekali menjelma kunang-kunang dalam bayangmu, tapi sayapku sendiri kerap berkhianat. Lihat ini, Fe. Perempuan seperti aku bahkan tidak bisa bertahan dari tikaman perasaan.
“Tapi kamu tidak pernah mencintaiku. Di hatimu hanya ada nama dan wajah perempuan itu. Kamu bersamaku hanya karena kamu tahu bahwa aku serapuh daun luruh. Kamu … hanya kasihan. Karena kamu tahu bahwa dengan bersamaku maka entah bagaimana caranya kamu bisa mencegahku menghabisi hidupku sendiri dengan cara paling menyakitkan.”
Aku tahu engkau tidak mampu menjawab, tidak mampu menyangkal. Kata-kata mungkin telah lama menyublim menjadi udara di mulutmu. Engkau kerap menjadi bisu.
“Aku mencoba bunuh diri bukan karena kamu,” kuhapus sisa air mata dengan punggung tangan. “Aku ingin pergi karena mungkin dengan begitu aku tak lagi melihat tubuhmu tertawan bersamaku sementara hatimu kaupersembahkan bagi perempuan lain. Perempuan yang namanya kerap kamu rapalkan di setiap percakapan tentang apa saja. Tentang hujan, tentang malam, tentang kenangan. Remeh temeh macam apa pun selalu mengingatkanmu akan dia.”
Engkau masih bisu, gengaman tanganmu mengendur.
“Aku juga tahu bahwa nama yang sering kamu sebut di setiap doa bukanlah namaku. Bagaimana mungkin aku tega menyaksikanmu tetap bersamaku hanya karena aku begitu mencintaimu sementara kamu tidak? Bagaimana mungkin aku tega menyaksikanmu terluka setiap kali bibir kita bertemu karena yang kamu bayangkan menyentuh bibirmu adalah perempuan itu? Aku sakit ketika melihat kamu sakit, Fe.”
Gengggamanmu genap terlepas. Matamu tidak lagi mengembara di luar melainkan menancap kepada mataku.
“Apa maumu, Na?” keras, getas, suaramu menyimpan begitu banyak pecahan gelas.
“Kenapa bukan kamu yang mengatakan apa maumu?” kembali kuhujam maumu.
“Aku tak ingin apa-apa, percayalah,” pandanganmu kembali berlari. Ada sorot yang tidak aku kenali.
Nafasku menghembus, perlahan. “Pergilah, Fe. Cinta tidak berlaku adil kepadamu selama ini. Mungkin ini waktunya kamu bersama perempuan yang kamu cintai. Kejar dia, Fe. Bahagiakanlah ia,” seperti ada berton-ton beban terlepas dari bahuku.
“Tapi kamu …”
“Fe!” kupotong kalimatmu. “Aku berjanji, ini darah terakhir yang aku tumpahkan demi cinta. Dengan begini aku jadi tahu bahwa batasku sudah habis. Pergilah ….”
Matamu tersaput embun, ada air menggenang, siap tumpah. “Kamu adalah kunang-kunangku …” suaramu parau.
“I always be,” kuanggukkan kepala.
“Aku ingin sekali kita bisa tetap bersama,” katamu.
Aku menggelengkan kepala. “Jika kebersamaan artinya luka bagi kita berdua. Lalu apa yang akan kita dapatkan? Aku terluka karena ketika bersamaku pun, kamu tidak bisa belajar mencinta. Dan kamu terluka karena harus bersama dengan orang yang tidak kamu cinta.”
“Tapi kamu mencintaiku, sedemikian besar,” matamu penuh pendar.
“Tapi kamu tidak mencintaiku …” mataku juga berpendar.
“Aku mencintainya,” gumammu. Di dalam suaramu yang dibawa selisik angin itu, dapat aku baca bongkahan rindu. Rindu yang tak pernah sekalipun kamu simpan untukku.
“Aku tahu,” tanganku menggenggam tanganmu.
Matamu mengerjap. “Berjanjilah kamu akan tetap baik-baik saja meski tanpa aku.”
“Aku berjanji,” kuanggukan kepala.
Kamu pun melangkah keluar dari kamar. Senyummu pudar, langkahmu gontai.
“Be good!” ucapmu sebelum sosokmu sempurna hilang.
Tidak ada kecupan di kening. Tidak ada jabatan tangan. Tidak ada kata-kata perpisahan. Aku kembali merenungi langit-langit ketika pintu tertutup dari luar.
“Aku akan tetap menjadi kunang-kunangmu, Fe,” bisikku parau pada dinding. Air mata keluar satu per satu meski tanpa isak. Sungguh, ini tangis paling hening.
***
"Fe ... aku akan mencintaimu, sampai mati."
Kemudian kakiku melangkah kepada udara. Tubuhku melayang, menyambut gerombolan kendaraan di tempat parkir rumah sakit. Menyambut beton yang akan memecahkan kepalaku, meremukkan tubuhku. Menyambut kematian yang akan menggenapkan janjiku padamu.
"Aku akan mencintaimu sampai mati ...."
========Ini cerpen lama, termaktub dalam antologi cerpen Katastrofa (Pustaka Jingga, 2012)

Published on November 16, 2013 00:16
[Cerpen] Firefly
 Aku hanyalah kunang-kunang yang berpendar di pepucuk dedaunan ketika hujanmu menepi dan terdiam. Aku pengecut, Fe. Kunang-kunang yang senantiasa bersembunyi dari badai, pun dari gerimis tipis karena takut sayapku lantak oleh jarum-jarum air yang menghunjam.
Aku hanyalah kunang-kunang yang berpendar di pepucuk dedaunan ketika hujanmu menepi dan terdiam. Aku pengecut, Fe. Kunang-kunang yang senantiasa bersembunyi dari badai, pun dari gerimis tipis karena takut sayapku lantak oleh jarum-jarum air yang menghunjam. Dan engkau bagiku adalah gelegak matahari; panas dan bara dalam kemegahanmu. Mataku selalu saja pasi ketika berhadapan denganmu. Jika dibandingkan dengan sinar yang menjalar dari lengan dan bahumu, kerlip kunang-kunangku adalah semu.
“Cintai aku sampai tua dan mati,” bisikmu.
Tapi cinta seperti apa yang aku punya untuk menggenapi satu-satunya harapan yang kaulapalkan? Bahuku telah seluruhnya kopong dilolosi gigitan angin; gigil.
“Aku tak akan lagi menolak, kemanapun takdir bermuara. Bila itu bersamamu, maka aku akan bersamamu,” bisikmu lagi.
Ah, Fe. Andaikan engkau tahu bahwa perempuan seperti aku sudah lelah dicumbui berbagai rindu yang tak pernah usai dan sampai. Jadi ke mana harus kukepakkan sayapku yang kian gontai? Cinta kini hanya suara-suara dari negeri nan jauh. Cinta kini hanya membuat pendarku sedemikian lusuh.
Bukan aku, Fe. Bukan aku perempuan yang kau inginkan selama ini, kan? Sebab takdir tak pernah memiliki tangan kecuali jika kita membawanya serta menapaki jejalan. Engkau selalu mengatakan bahwa nasib membawamu mengair dan mengalir. Tapi engkau lupa mengatakan bahwa muara segala sungai tak pernah bisa digenggam. Tak pernah bisa diramal.
“Pernahkah kamu mencintai aku? Sekali saja?” suaraku selalu getar parau ketika kata-kata cinta teruar.
Kamu diam. Suaramu juga bagai ditelan kelepak kelelawar.
“Sekali saja, jawab pertanyaanku. Apakah kamu mencintaiku, Fe?” kulipat jemari di genggamanmu dengan harapan menghantar hangat, untukmu, terlebih lagi untukku.
“Apa dengan bersamamu saja tidak cukup?” matamu terlempar ke arah jendela. Di luar hujan, deras dan kuyup.
“Kadang cinta butuh pengakuan,” hujan berpindah ke mataku.
Ya, Fe. Kadang cinta butuh diteriakkan. Bukan hanya kata yang mengawang di langit-langit kamar. Ia bisa saja lelah lalu goyah, berpindah.
“Jangan pernah tanya hatiku, Na. Jangan pernah…” kepalamu menggeleng perlahan sementara matamu masih tertawan di luar.
Mataku menderas, meranggas, retas.
“Jangan menangis,” bisikmu.
Bahuku berguncang, ingin sekali melolosi segala beban. “Jangan siksa aku seperti ini, Fe. Kamu ingin aku mencintaimu, ingin terus langkahku berderap ke arahmu. Tapi kamu … kamu tak pernah ingin tahu, tak pernah sekalipun mencoba mencintaiku,” bibirku terasa pahit, sisa rasa obat-obat yang dijejalkan para perawat. Tapi hatiku lebih pahit, dan tak ada obat apa pun yang bisa mendistraksi setiap rasa sakit.
Kemudian tanganku dihantarkan ke dadamu. “Kamu rasakan denyutan di sana, Na? Ia berisi nama kamu, bukan nama orang lain seperti yang kamu sangka selama ini. Jika itu bisa diartikan cinta, maka artikanlah itu sebagai cinta.”
Aku menggeleng. “Kunang-kunang yang berpendar …” bibirku gemetar.
“Kamu adalah kunang-kunang yang menari sehabis hujanku,” bisikmu.
“Rapuh, jenuh,” bibirku masih bergetar.
Matamu lalu liar merayapi dinding kamar. Ibu jari menjalar ke pergelangan tanganku yang dibentengi perban. “Jangan berniat pergi dengan cara seperti ini. Aku akan sakit jika kamu pergi, mungkin juga akan mati.”
“Matahari tidak pernah mati.”
“Jangan pergi dengan cara seperti ini ….”
Botol infus bergoyang-goyang di atas tiang di samping kiri. Pergelangan tangan kiriku seketika dicumbu ngilu. Aku, Fe. Ingin sekali menjelma kunang-kunang dalam bayangmu, tapi sayapku sendiri kerap berkhianat. Lihat ini, Fe. Perempuan seperti aku bahkan tidak bisa bertahan dari tikaman perasaan.
“Tapi kamu tidak pernah mencintaiku. Di hatimu hanya ada nama dan wajah perempuan itu. Kamu bersamaku hanya karena kamu tahu bahwa aku serapuh daun luruh. Kamu … hanya kasihan. Karena kamu tahu bahwa dengan bersamaku maka entah bagaimana caranya kamu bisa mencegahku menghabisi hidupku sendiri dengan cara paling menyakitkan.”
Aku tahu engkau tidak mampu menjawab, tidak mampu menyangkal. Kata-kata mungkin telah lama menyublim menjadi udara di mulutmu. Engkau kerap menjadi bisu.
“Aku mencoba bunuh diri bukan karena kamu,” kuhapus sisa air mata dengan punggung tangan. “Aku ingin pergi karena mungkin dengan begitu aku tak lagi melihat tubuhmu tertawan bersamaku sementara hatimu kaupersembahkan bagi perempuan lain. Perempuan yang namanya kerap kamu rapalkan di setiap percakapan tentang apa saja. Tentang hujan, tentang malam, tentang kenangan. Remeh temeh macam apa pun selalu mengingatkanmu akan dia.”
Engkau masih bisu, gengaman tanganmu mengendur.
“Aku juga tahu bahwa nama yang sering kamu sebut di setiap doa bukanlah namaku. Bagaimana mungkin aku tega menyaksikanmu tetap bersamaku hanya karena aku begitu mencintaimu sementara kamu tidak? Bagaimana mungkin aku tega menyaksikanmu terluka setiap kali bibir kita bertemu karena yang kamu bayangkan menyentuh bibirmu adalah perempuan itu? Aku sakit ketika melihat kamu sakit, Fe.”
Gengggamanmu genap terlepas. Matamu tidak lagi mengembara di luar melainkan menancap kepada mataku.
“Apa maumu, Na?” keras, getas, suaramu menyimpan begitu banyak pecahan gelas.
“Kenapa bukan kamu yang mengatakan apa maumu?” kembali kuhujam maumu.
“Aku tak ingin apa-apa, percayalah,” pandanganmu kembali berlari. Ada sorot yang tidak aku kenali.
Nafasku menghembus, perlahan. “Pergilah, Fe. Cinta tidak berlaku adil kepadamu selama ini. Mungkin ini waktunya kamu bersama perempuan yang kamu cintai. Kejar dia, Fe. Bahagiakanlah ia,” seperti ada berton-ton beban terlepas dari bahuku.
“Tapi kamu …”
“Fe!” kupotong kalimatmu. “Aku berjanji, ini darah terakhir yang aku tumpahkan demi cinta. Dengan begini aku jadi tahu bahwa batasku sudah habis. Pergilah ….”
Matamu tersaput embun, ada air menggenang, siap tumpah. “Kamu adalah kunang-kunangku …” suaramu parau.
“I always be,” kuanggukkan kepala.
“Aku ingin sekali kita bisa tetap bersama,” katamu.
Aku menggelengkan kepala. “Jika kebersamaan artinya luka bagi kita berdua. Lalu apa yang akan kita dapatkan? Aku terluka karena ketika bersamaku pun, kamu tidak bisa belajar mencinta. Dan kamu terluka karena harus bersama dengan orang yang tidak kamu cinta.”
“Tapi kamu mencintaiku, sedemikian besar,” matamu penuh pendar.
“Tapi kamu tidak mencintaiku …” mataku juga berpendar.
“Aku mencintainya,” gumammu. Di dalam suaramu yang dibawa selisik angin itu, dapat aku baca bongkahan rindu. Rindu yang tak pernah sekalipun kamu simpan untukku.
“Aku tahu,” tanganku menggenggam tanganmu.
Matamu mengerjap. “Berjanjilah kamu akan tetap baik-baik saja meski tanpa aku.”
“Aku berjanji,” kuanggukan kepala.
Kamu pun melangkah keluar dari kamar. Senyummu pudar, langkahmu gontai.
“Be good!” ucapmu sebelum sosokmu sempurna hilang.
Tidak ada kecupan di kening. Tidak ada jabatan tangan. Tidak ada kata-kata perpisahan. Aku kembali merenungi langit-langit ketika pintu tertutup dari luar.
“Aku akan tetap menjadi kunang-kunangmu, Fe,” bisikku parau pada dinding. Air mata keluar satu per satu meski tanpa isak. Sungguh, ini tangis paling hening.
***
"Fe ... aku akan mencintaimu, sampai mati."
Kemudian kakiku melangkah kepada udara. Tubuhku melayang, menyambut gerombolan kendaraan di tempat parkir rumah sakit. Menyambut beton yang akan memecahkan kepalaku, meremukkan tubuhku. Menyambut kematian yang akan menggenapkan janjiku padamu.
"Aku akan mencintaimu sampai mati ...."
========Ini cerpen lama, termaktub dalam antologi cerpen Katastrofa (Pustaka Jingga, 2012)

Published on November 16, 2013 00:16
November 12, 2013
Memeluk Bapak

Bapak adalah lelaki pertama yang mengajarkan saya bagaimana menjadi perempuan berhati karang. Ia tak pernah banyak berbicara, tak pernah banyak memerintah atau mengemukakan keberatan atas kebanalan apa pun yang saya lakukan. Barangkali ia sudah mafhum bahwa putri sulungnya adalah pengelana yang selamanya akan berada di trotoar dunia.
Saya tahu, di balik mata apinya, ia masih menyimpan semacam kebanggaan karena sayalah satu-satunya anak yang mirip sekali dengannya baik secara fisik maupun kemampuan. Dari kecil saya selalu merasa bahwa wajah dan bentuk tubuh saya tidak pernah mirip Ibu. Saya mewarisi alis lengkung dan bulu mata lentik Bapak. Saya juga mewarisi kulitnya yang cokelat tua. Satu-satunya yang saya warisi dari Ibu adalah suara, selebihnya tidak.
Ketika remaja, saya juga sudah tahu bahwa saya adalah seorang kreator otodidak, sama seperti Bapak. Bapak itu, lelaki yang penuh dengan potensi. Ia bisa membuat apa saja dari mulai sangkar burung berukiran indah sampai membangun rumah. Keahlian Bapak (yang sering kali menjadi rebutan para 'atasannya') tidak didapat dari pendidikan yang layak. Ia mempelajarinya sendiri, mengasah keahliannya sendiri. Sama seperti saya.
Bodohnya adalah, saya tidak pernah ingat berapa usia Bapak sekarang. Mungkin sekitar 55 tahun. Di usianya yang menginjak setengah abad ia masih giat bekerja, masih bersemangat menciptakan apa saja.
Mengenang Bapak berarti menelusuri gorong-gorong ingatan masa lalu saya. Menghadirkan kembali slide-slide yang tadinya sempat saya lupa.
KANAK-KANAK
Jika saya berkelahi dengan anak laki-laki, Bapak tidak pernah membela. Sering saya pulang dengan bibi lebam dan air mata berurai, tapi Bapak tidak lantas meradang lalu memukuli anak tetangga. Ia akan menyuruh saya duduk di hadapannya, mengambil kapak atau pisau lalu meletakkannya di atas meja.
"Kamu masih suka berkelahi?" tanyanya.
Saya diam.
"Kamu ingin Bapak membela dan membantu melawan teman berkelahi kamu?"
Saya mengangguk.
Bapak menggelengkan kepala. "Kalau kamu masih suka berkelahi, berarti kamu harus belajar melawan sendiri. Ini kapak dan pisau, silakan pakai. Tapi kalau kamu memang ingin jadi jagoan, lawanlah dengan tangan kosong."
Sejak saat itu saya tidak pernah bercerita apabila saya berkelahi dengan anak laki-laki. Bapak hanya akan mendengar kabar dari tetangga atau menyaksikan saya pulang dengan lebam-lebam yang lebih banyak. Barangkali itulah sebabnya mengapa ketika SMP Bapak memasukkan saya ke klub karate :D.
Sejak kecil juga Bapak selalu mengajarkan saya agar mandiri. Ketika saya mengeluh tentang genting bocor di atas kamar saya, diajaknya saya untuk ikut membetulkan genting. Ketika saya ingin kamar saya dicat dengan warna ungu, dia membelikan sekaleng cat dan kuas lalu mempersilakan saya mencat kamar sendiri.
REMAJA
Sampai sekarang, satu-satunya orang yang membuat saya nyaman dan percaya berboncengan motor adalah Bapak. Ialah yang mengantarkan saya ke mana-mana. Subuh-subuh mengantarkan saya ke Pusdiklatsar Paskibraka, setiap hari selama seminggu padahal dia juga harus bekerja. Pernah, ketika motor Vespanya mogok di tengah jalan di pagi buta, dia mengangsurkan uang lima rupiah (jumlah yang besar ketika saya SMK) dan menyuruh saya naik becak agar saya tidak terlambat datang ke Pusdiklatsar. Ia yang mengantarkan saya ke asrama. Ya, ialah yang selalu siap sedia mengantarkan saya ke mana saja.
Bapak jugalah yang memersiapkan saya untuk seleksi masuk TNI AU. Setiap hari saya harus lari pagi mengelilingi Kelurahan Sukagalih, jarak tempuh yang serasa bisa membunuh saya. Kalau kebetulan ada latihan sepakbola (Bapak adalah pelatih sepakbola tim karang taruna), maka saya akan diajaknya pemanasan, lari keliling lapangan, peregangan, dan lain sebagainya.
Saat ada pemuda dari kampung tetangga yang menyatakan cinta, diam-diam dia memanggil pemuda itu dan memperingatkannya bahwa saya masih sekolah dan tidak boleh diganggu. Tentu saja tanpa sepengetahuan saya.
Karena tahu bahwa suara saya bagus (waktu remaja saya belum mengenal rokok), maka dia membeli mik dan menemani saya berlatih menyanyi. Saya masih ingat kalau Bapak pandai sekali bermain gitar. Sepertinya segala jenis musik bisa ia mainkan, dari mulai lagu-lagu slow rock seperti Scorpion sampai lagu dangdut yang konon susah dimainkan.
Ketika saya menjadi juara umum di sekolah, Bapak dan Ibu diundang pada acara perpisahan. Mereka disambut bak pejabat oleh kepala sekolah, duduk di kursi paling depan sebuah ballroom hotel bintang lima. Saat itu, mata Bapak berkilat bangga. Saat itu pula, saya berpikir bahwa membuat orang tua bahagia tidaklah terlalu sulit, hanya dengan membuat mereka bangga atas prestasi saya.
DEWASA
Saat paling haru adalah ketika Bapak menjadi wali pernikahan saya yang pertama. Matanya berkaca-kaca. Mungkin ia enggan melepas saya menikah muda. Mungkin masih ada harapan yang ingin ia tanam. Mencium tangannya setelah ijab kabul serasa mencerabut jantung dari dada saya. Saat itu saya sadar bahwa Bapak tak akan lagi menjadi satu-satunya lelaki yang menjadi imam saya. Tugasnya berganti ke pundak lelaki lain bernama suami.
Saya mulai kehilangan.
Setelah pernikahan kedua dan ketiga, saya mulai menjauh dari rumah, menjauh dari Bapak. Karena saya pernah berjanji bahwa saya akan kembali setelah saya bahagia. Ba
rangkali, saat itu tak lama lagi.
*
Selamat Hari Ayah, Pak. Selamat menjadi bapak paling keren sedunia :D

Published on November 12, 2013 02:30
November 10, 2013
Penis Anda Saja Tidak Akan Cukup
Saya sering berbicara mengenai perempuan dan kecerdasan intelektual. Saya juga sering mengatakan bahwa menjadi perempuan cerdas itu penting agar para perempuan memiliki 'hak tawar' baik itu di ranah domestik maupun di ranah publik. Namun saya lengah, bahwa laki-laki juga sudah sepantasnya memiliki kecerdasan.
Bukan tanpa alasan ketika saya mengatakan bahwa saya menemukan banyak sekali laki-laki yang bodoh. Tidak, saya tidak sedang membicarakan mengenai gelar akademis karena lulusan perguruan tinggi tidak akan menjamin kecerdasan seseorang. Di sini saya sedang berbicara mengenai kecerdasan baik itu intelektual, emosional, maupun sosial.
Mari saya bagi ke dalam poin per poin:
A. Kecerdasan Intelektual
Karena jujur saja, perempuan urban sekarang sudah sangat selektif ketika memilih pasangan. Ketika wawasan seorang perempuan semakin berkembang, tentu saja ia menginginkan pasangan yang memiliki wawasan yang setara atau lebih. Sebagai laki-laki Anda tentu tidak mau terlongo dan tampak bodoh ketika pasangan Anda membicarakan topik-topik yang ternyata tidak Anda kuasai, bukan?
Saran saya sih, banyak-banyaklah membaca buku.
Penis kekar perkasa kuku bima memang sangat menggoda untuk dinikmati, tapi otak yang berisi itu lebih seksi.
B. Kecerdasan Emosional
Tak ada satupun perempuan yang ingin memiliki pasangan yang menderita gangguan jiwa. Perempuan hari ini adalah perempuan yang berani mengambil langkah seribu ketika Anda membuat mereka tidak nyaman.
Berikut gangguan jiwa yang sering diidap lelaki:
Posesif akut: semacam penyakit yang nyaris menyamai rambu-rambu lalu lintas ==> melarang ini, melarang itu, harus begini, harus begitu. Pasangan Anda bukan Putri Indonesia atau Ratu Inggris yang harus Anda kawal setiap hari, ia adalah perempuan mandiri yang sudah bisa mengaktualisasikan diri. Jangan biarkan dia hidup dalam jeruji.GPS disorder: selalu bertanya lagi di mana. Tahukah Anda bahwa pertanyaan semacam itu sangat membosankan dan mengintimidasi? Anda bukan atasan, bukan orang tua, bukan ketua RT yang mengharuskan pasangan Anda wajib lapor 1x24 jam. Kalau Anda selalu ingin tahu posisi pasangan Anda, Anda bisa menyewa semacam detektif atau CIA sekalian untuk menguntit daripada harus merepotkannya setiap saat.Scheduller Fever: selalu bertanya sedang apa. Anda bukan agenda, bukan kalender, bukan sekretaris pribadi, bukan juga alarm. Anda tidak harus tahu kegiatan pasangan Anda setiap saat. Percayalah, pertanyaan seperti itu bukanlah bentuk perhatian melainkan kata lain dari menyebalkan.C. Kecerdasan Sosial
Poin inilah yang sedang saya soroti. In my opinion, kecerdasan sosial harus dimiliki seorang laki-laki sebagai front line pada saat PDKT. Poin ini juga berhubungan dengan cara Anda berkomunikasi. Lelaki yang menyenangkan diajak ngobrol lebih menggairahkan daripada lelaki yang menggairahkan secara fisik. Jadi percuma saja Anda menguasai berbagai macam posisi dan teknik bercinta atau penis Anda selalu siap sedia tapi tidak menyenangkan diajak bercerita. Kalau seperti itu, Anda hanya akan menjadi mesin.
*Percayalah, menjadi laki-laki goblok lebih menyakitkan daripada menjadi laki-laki impoten. Tidak ada salahnya menjadi pintar dan teman diskusi yang menyenangkan, bukan?
Bukan tanpa alasan ketika saya mengatakan bahwa saya menemukan banyak sekali laki-laki yang bodoh. Tidak, saya tidak sedang membicarakan mengenai gelar akademis karena lulusan perguruan tinggi tidak akan menjamin kecerdasan seseorang. Di sini saya sedang berbicara mengenai kecerdasan baik itu intelektual, emosional, maupun sosial.
Mari saya bagi ke dalam poin per poin:
A. Kecerdasan Intelektual
Karena jujur saja, perempuan urban sekarang sudah sangat selektif ketika memilih pasangan. Ketika wawasan seorang perempuan semakin berkembang, tentu saja ia menginginkan pasangan yang memiliki wawasan yang setara atau lebih. Sebagai laki-laki Anda tentu tidak mau terlongo dan tampak bodoh ketika pasangan Anda membicarakan topik-topik yang ternyata tidak Anda kuasai, bukan?
Saran saya sih, banyak-banyaklah membaca buku.
Penis kekar perkasa kuku bima memang sangat menggoda untuk dinikmati, tapi otak yang berisi itu lebih seksi.
B. Kecerdasan Emosional
Tak ada satupun perempuan yang ingin memiliki pasangan yang menderita gangguan jiwa. Perempuan hari ini adalah perempuan yang berani mengambil langkah seribu ketika Anda membuat mereka tidak nyaman.
Berikut gangguan jiwa yang sering diidap lelaki:
Posesif akut: semacam penyakit yang nyaris menyamai rambu-rambu lalu lintas ==> melarang ini, melarang itu, harus begini, harus begitu. Pasangan Anda bukan Putri Indonesia atau Ratu Inggris yang harus Anda kawal setiap hari, ia adalah perempuan mandiri yang sudah bisa mengaktualisasikan diri. Jangan biarkan dia hidup dalam jeruji.GPS disorder: selalu bertanya lagi di mana. Tahukah Anda bahwa pertanyaan semacam itu sangat membosankan dan mengintimidasi? Anda bukan atasan, bukan orang tua, bukan ketua RT yang mengharuskan pasangan Anda wajib lapor 1x24 jam. Kalau Anda selalu ingin tahu posisi pasangan Anda, Anda bisa menyewa semacam detektif atau CIA sekalian untuk menguntit daripada harus merepotkannya setiap saat.Scheduller Fever: selalu bertanya sedang apa. Anda bukan agenda, bukan kalender, bukan sekretaris pribadi, bukan juga alarm. Anda tidak harus tahu kegiatan pasangan Anda setiap saat. Percayalah, pertanyaan seperti itu bukanlah bentuk perhatian melainkan kata lain dari menyebalkan.C. Kecerdasan Sosial
Poin inilah yang sedang saya soroti. In my opinion, kecerdasan sosial harus dimiliki seorang laki-laki sebagai front line pada saat PDKT. Poin ini juga berhubungan dengan cara Anda berkomunikasi. Lelaki yang menyenangkan diajak ngobrol lebih menggairahkan daripada lelaki yang menggairahkan secara fisik. Jadi percuma saja Anda menguasai berbagai macam posisi dan teknik bercinta atau penis Anda selalu siap sedia tapi tidak menyenangkan diajak bercerita. Kalau seperti itu, Anda hanya akan menjadi mesin.
*Percayalah, menjadi laki-laki goblok lebih menyakitkan daripada menjadi laki-laki impoten. Tidak ada salahnya menjadi pintar dan teman diskusi yang menyenangkan, bukan?

Published on November 10, 2013 08:17
November 9, 2013
Senyum Tuhan di Perempatan Jalan
Banyak orang yang kerap kali beranggapan bahwa Tuhan berada di tempat yang paling jauh dan sukar diraih. Banyak orang juga yang berpikir bahwa Tuhan adalah entitas Sang Maha yang berjarak, padahal Tuhan teramat dekat. Padahal Tuhan teramat lekat.Dua minggu yang lalu, sehari setelah saya menerima honor pemateri, berangkatlah saya ke toko buku untuk melengkapi koleksi Anak Matahari Book Corner. Membeli buku selain sebagai investasi juga semacam menepati janji bahwa AMBC akan menjadi taman bacaan berisikan buku-buku sastra yang kompeten.
Sepulangnya dari sana, saya menumpang angkot Cicaheum - Ledeng untuk kembali ke Kebun Seni. Ketika angkot berhenti di lampu merah depan Baltos, ada seorang pengamen yang menyanyikan sebuah lagu (saya lupa judulnya), tapi saya masih ingat suaranya. Jika mau membandingkan, suaranya agak-agak mirip dengan Firman Idol tapi yang ini lebih bagus, petikan gitarnya pun enak di telinga. Satu lagi, dia tidak memakai embel-embel orasi yang menyebalkan seperti pengamen kebanyakan.
Honor yang saya terima tidak besar, tapi ada kesadaran bahwa di sana juga ada hak orang lain. Meskipun saya sudah membayar pajak kepada negara, sudah memenuhi kewajiban saya sebagai ibu sekaligus bapak kepada anak saya, sudah pula menyisihkan sebagian untuk orang tua saya, tapi saya masih yakin kalau rezeki yang saya terima juga pantas dibagi agar orang lain merasa bahagia.
Sisa uang saya hanya 20 ribu. Tiga ribu untuk ongkos angkot, sepuluh ribu untuk membeli makan, lima ribu saya berikan untuk sang pengamen bersuara bagus itu, sisa dua ribu saya simpan. Saya tahu bahwa uang dua ribu rupiah tidak akan cukup untuk makan saya esok harinya. Saya juga tahu bahwa uang lima ribu rupiah yang saya berikan pada pengamen itu tidaklah seberapa. Mungkin itu tidak akan cukup untuk mengganjal perut istri dan anaknya. Mungkin itu tidak akan bisa memenuhi biaya sekolah putra-putrinya. Saya tidak bisa membantu banyak, hanya itu yang mampu saya berikan.
Saat lampu berganti hijau, angkot pun kembali berjalan. Sang pengamen kembali ke trotoar, memindahkan uang kolekan ke saku bajunya. Ketika mendapati selembar uang lima ribuan, ia bersorak girang dan memamerkan kepada teman-temannya. Matanya jelalatan, mencari-cari saya di angkot yang tengah berjalan (ia tahu bahwa sayalah yang memberi uang itu). Saat mata kami berpapasan, ia memamerkan senyum paling riang sambil melambai. Lalu dari mulutnya tercetak frasa "nuhun", kepalanya mengangguk dalam-dalam. Saya membalas senyumnya dari kejauhan sementara angkot terus saja berjalan.
Senyum itulah, kata-kata terima kasih dan teriakan bahagia itulah yang menghantarkan kehangatan ke dada saya. Hari itu saya merasa benar-benar menjadi manusia. Hari itu saya benar-benar merasa berguna. Ketika kita membuat orang lain berbahagia, saat itu pulalah kita telah membahagiakan diri kita sendiri, bukan?
*Maka ketika pagi keesokan harisnya saya bangun dan merasa lapar, saya pergi ke depan, melewati penjual nasi bungkus langganan, menuju kios dan membeli secangkir kopi hitam. Karena memang uang dua ribu rupiah hanya cukup untuk itu.
Saat lapar semakin melilit perut, yang bisa saya lakukan hanya tertawa dan berbahagia. Sebab ketika masih bisa merasakan lapar, itu artinya saya masih hidup.
Seperti yang sering saya katakan, ketika kita menitipkan diri kepada Sang Maha Kaya maka kita tidak akan pernah kekurangan apa-apa. Saat memutuskan untuk keluar dari kantor dan serius terjun di dunia penulisan, saya membuat semacam deal-deal-an dengan Tuhan.
"Aku akan melakukan usaha sekuat yang aku bisa. Untuk itu, aku menyerahkan segala hasilnya ke tanganMu. Dan aku menitipkan diriku serta kehidupan putriku juga kepadaMu. Lakukanlah apa saja yang menurutMu terbaik bagi kami. Lakukanlah apa saja."
Saya memang manusia banal, tak tahu cara paling tepat untuk berdoa. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mengerti berbagai macam bahasa. Dan yang paling penting, saya menaruh rasa percaya kepadaNya melebihi kepercayaan saya terhadap siapapun. Bukankah kekuatan dari bertuhan adalah keimanan?
Lapar semakin menggigit sementara tak sepeser pun uang untuk membeli makanan. Anehnya saya tidak lantas merasa khawatir ataupun getir. Toh, lapar bukan sesuatu yang harus saya lawan.
Semakin siang, rasa lapar semakin tak tertahankan. Untuk meredam itu, saya mengingat kembali sebuah senyum yang saya dapat di perempatan jalan, senyum yang membuat si empunya bahagia, senyum yang juga membuat saya berbahagia. Jadi, meskipun lapar, saya tetap berbahagia.
"Tuhan, aku tahu Engkau ada," gumam saya, masih dengan senyuman.
Sepuluh menit setelah gumaman itu, ponsel saya berdering, tanda ada pesan masuk. Anda ingin tahu isinya? Isinya adalah sms dari seseorang yang mengabarkan bahwa dia telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening saya sebagai honor karena saya membantunya mengerjakan sebuah proyek biografi. Padahal saya sudah lupa mengenai piutang honor yang satu itu.
Saat itu juga saya tertawa, terbahak-bahak, bahu saya menandak-nandak. Bukan hanya karena jumlah kiriman honor yang jauh lebih besar daripada yang saya harapkan, tapi juga karena honor itu datang pada saat yang paling tepat.
"Ya, Engkau memang ada."
Saya kembali bergumam dengan desir yang kali itu lebih riuh karena ada buncahan rasa syukur yang tak dapat saya ukur.
Ya, Tuhan memang ada.

Published on November 09, 2013 00:49
Mimpi dan Ilusi
- Skylashtar Maryam's profile
- 8 followers
Skylashtar Maryam isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.



