Skylashtar Maryam's Blog: Mimpi dan Ilusi, page 17
November 4, 2013
Vagina vs Penis; Fungsi, Atau Esensi?
"Diskriminasi gender sudah ditanamkan terus-menerus oleh masyarakat sejak kita kecil."
(Kang Guruh_Ruang Publik)
Tanpa kita sadari, masyarakat telah menanamkan doktrin-doktrin menyesatkan sejak kita kecil. Di Indonesia, kalimat-kalimat larangan, perintah, maupun anjuran selalu diawali dengan frasa 'kamu kan laki-laki/kamu kan perempuan'. Contoh: 'Kamu kan perempuan, jadi harus bisa memasak'. 'Kamu kan laki-laki, jadi tidak boleh menangis'. Mungkin orang tua kita beranggapan bahwa ini semacam sex education, tapi salah arah. Padahal organ-organ reproduksi tidak akan lantas menyimpang hanya karena seorang perempuan tidak bisa memasak atau hanya karena anak laki-laki kerap menangis.
Jadi inilah kita, produk generasi yang mentato vagina dan penis di kening masing-masing. Jenis kelamin dijadikan border line untuk membatasi; semacam kawat berduri di daerah perbatasan yang kalau dilanggar maka kepala kita harus siap dihadiahi tembakan.
Saya tidak sedang berbicara mengenai kesetaraan atau feminisme dalam konteks radikal. Saya sedang berbicara mengenai paradigma masyarakat yang mengaku modern tapi isi kepalanya luar biasa konservatif, tak jauh dengan zaman jahiliyah ketika bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Saya sedang berbicara mengenai masyarakat kita, yang menjadikan gender sebagai dalih semata.
Persetan dengan emansipasi Kartini yang diagung-agungkan bersama tapi pada praktiknya diingkari bersama pula; oleh laki-laki dan perempuan. Toh dalam masyarakat Indonesia, perempuan cerdas selalu dianggap entitas yang berbahaya.
Anda pernah bekerja di kantor atau tempat lain dengan struktur organisasi resmi? Susah dipromosikan bukan karena Anda tidak kompeten, tapi karena Anda perempuan? Hanya karena bawahan yang harus Anda pimpin mayoritas laki-laki? Jangan khawatir, Anda memiliki banyak kawan seperjalanan.
Apakah Anda tahu bahwa jabatan untuk anggota dewan perempuan itu memakai kuota? Bukan karena di Indonesia sukar menemukan perempuan pintar untuk duduk di kursi tersebut, tapi karena posisi perempuan lebih sering dianggap sebagai hiasan. Menyedihkan, bukan?
Pernahkah Anda, sewaktu kecil, dihardik karena terlalu banyak bertanya dan tidak mendapatakan jawaban yang memuaskan hanya karena Anda perempuan? Pernahkah Anda, gagal menjadi ketua OSIS dan ditempatkan sebagai wakil atau sekretaris, bukan karena Anda tidak layak tapi karena para bedebah di institusi pendidikan itu beranggapan kalau laki-laki adalah pemimpin sejati dan perempuan adalah pendamping?
Pernahkah Anda, bertengkar dengan suami hanya gara-gara argumen Anda valid tapi ia segan mengakui? Biasalah, ego laki-laki yang ditanamkan sejak ia kecil. Istri yang terlalu cerdas atau bahkan lebih cerdas dari suami kadang menjadi 'aib' di masyarakat. Dan istri biasanya berpura-pura bodoh hanya karena enggan membuat konflik.
Lucu juga, masyarakat kita sering kali menjadikan agama dan budaya sebagai senjata untuk 'menempatkan' laki-laki dan perempuan di posnya masing-masing. Padahal jika dilihat dari sejarah (dalam hal ini Sirah Nabawiyah Muhammad SAW), belum pernah saya menemukan perempuan-perempuan yang 'dibodohkan' seperti sekarang. Khadijah adalah enterpreneur sejati, bahkan Muhammad sendiri adalah karyawannya. Dengan aset sebesar itu, Khadijah tentu perempuan yang cerdas. Apakah Nabi lantas mempermasalahkan itu? Tidak tuh. Laki-laki zaman sekarang saja yang enggan mengakui kebenaran ini. Aisyah adalah perawi hadis-hadis Nabi. Beliau penulis, salah satu perempuan paling cerdas yang pernah saya tahu. Hellow! Laki-laki tidak akan bisa membaca hadis-hadis Nabi yang sekarang sering dijadikan senjata kalau saja Aisyah sebodoh keledai.
Budaya Indonesia bahkan dibangun dengan blue print perempuan; ibu.
Bahkan setelah para feminis berteriak tentang kesetaraan gender sampai harus jadi imam salat Jumat segala (tunggu, saya ingin tertawa dulu kalau ingat ini), kesadaran gender tetap saja mengalami distorsi dari hari ke hari. Seiring kemajuan zaman dan derasnya arus informasi serta teknologi, pola pikir perempuan-perempuan Indonesia mengalami semacam revolusi. Ada yang tetap berada di jalur konvensional, ada juga yang radikal. Ini tentu dipengaruhi oleh kesempatan mengecap pendidikan yang semakin terbuka lebar. Sayangnya, pola pikir laki-laki tidak serta merta mengimbangi. Tetap saja berkutat di urusan kelamin dan superioritas.
Ya, sekarang perempuan memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan dengan laki-laki. Tapi dalam tataran sosial, perempuan yang S3 dan laki-laki dengan tingkat pendidikan sama tetap memiliki 'harga' berbeda. Ya, sekarang perempuan sudah lumrah memiliki karier di luar rumah. Tapi tetap saja, laki-laki masih merasa perlu malu terhadap masyarakat kalau jabatan istrinya lebih tinggi atau kalau gaji istrinya lebih besar. Ya, sekarang ini perempuan bisa berargumen apa saja, tapi siapa yang mau mendengar lantas sadar?
Ya, kita para perempuan dituntut untuk pintar karena harus mendidik anak-anak yang kelak jadi penerus bangsa. Tapi berapa banyak dari kita yang mau mengakui bahwa kecerdasan perempuan sebagai hak integritas manusia? Bukan sebagai fungsi sampingan semata?
Sampai kapan kita akan menjadikan gender sebagai sekat pembeda untuk hal-hal yang tidak esensial? Bagaimana kita akan memperbaiki peradaban kalau kelamin saja kerap menjadi pertentangan yang tak pernah usai?

Published on November 04, 2013 04:25
October 30, 2013
Lelaki yang Terluka*

“Kenapa
kita harus berpisah dengan cara seperti ini?” itu adalah kalimat pertamamu
sejak kita duduk di kafe ini.
Tatapanmu dingin, sedingin gelas
porselen yang kamu genggam sejak satu jam lalu. Gelas berisi macchiato caramel yang kamu isap
pelan-pelan bukan karena uar panasnya melainkan karena hanya hal itulah yang
bisa kamu lakukan untuk mengisi jeda yang terasa amat panjang. Aku tahu, satu
pertanyaanmu itu mengandung bereon-eon rasa sakit. Namun kamu pun harus tahu
bahwa aku tak memiliki jawaban yang kamu inginkan.
Setiap manusia harus bertemu dengan
musuh yang paling ditakuti; kehilangan. Mestinya kamu mau bertemu dengannya,
cepat atau lambat, siap tak siap. Bukan cara perpisahan ini yang sebetulnya
kamu takuti, melainkan kekosongan setelahnya. Bukankah begitu?
“Kenapa kita harus berpisah dengan
cara seperti ini?” kamu mengulang pertanyaan yang sama, kesakitan dan kegetiran
yang sama.
Barangkali, kamu belum mengerti
bahwa selama tiga tahun kebersamaan, aku adalah perempuan yang hidupnya tak
pernah bisa kamu pegang. Aku selalu bergerak dari satu kasus ke kasus lain,
dari satu demonstrasi ke demonstrasi yang lain.
Kamu tak pernah merasa sendiri
karena setiap kali kamu membuka mata aku selalu ada. Kamu sadari atau tidak.
Sedangkan aku kerap merasa sendirian karena duniaku jauh tertinggal di
belakang. Mungkin itu sebabnya aku kerap mencari-cari pegangan di luar, mencari
keramaian meski tetap berada di kesunyian.
“Tapi kamu mencintai aku,” bisikmu
sumbang. Menyaingi deru mesin pendingin udara di latar belakang.
Akhirnya kamu sadar, bukan? Bahwa
perempuan di depanmu ini adalah ia yang mencintaimu setengah mampus. Yang
memujamu seperti Ikarus memuja matahari. Namun kamu tidak pernah sadar bahwa
cinta tak pernah selamanya berlayar di laut yang kamu inginkan. Kadang ia
menepi untuk menggenapkan takdirnya sendiri.
“Tapi aku mencintaimu, Ayya,”
bibirmu bergetar, matamu kini menatap nanar.
Andaikan kata-kata cinta yang kamu
ucapkan barusan aku dengar tiga tahun,
dua tahun, satu tahun, atau empat hari yang lalu, mungkin aku akan segera
tenggelam dalam pelukanmu beserta tangisan dan rengekan permintaan maaf seperti
biasa. Tapi tidak hari ini, Am. Aku lelah menanggung cinta yang sedemikan
besar, cintaku, juga cintamu.
“Aku tidak ingin kamu pergi,”
tanganmu berusaha meraih tanganku.
Tanganmu bertemu dengan kekosongan.
Aku tak ingin sedikit pun kulit kita bersentuhan sebab bermilyar-milyar ingatan
akan ikut membuncah seperti air bah. Sebab sentuhanmu akan seketika
mengingatkanku pada malam-malam yang janggal ketika tubuhku merengek meminta
pemenuhan dan kamu dengan muka masam memasang dalih layaknya panglima perang. “Hidup bukan hanya tentang kelamin,”
katamu nyaris berulang.
Maka bertahun-tahun aku belajar
untuk memendam, untuk menahan. Hingga tubuhku nyaris seperti pekuburan yang
kamu singgahi kapan-kapan, bila kamu ingat, bila kamu sempat. Aku harus
bersaing dengan dokumen-dokumen kantormu, dengan pertemuan-pertemuanmu, dengan
semua rasa lelahmu. Ya, hidup bukan hanya tentang kelamin, Am. Hidup, seperti
katamu, hanyalah menunggu kematian.
“Minggu depan ulang tahun yang
ketiga pernikahan kita,” suaramu sesak, ditelan gelegak tangis yang
mendesak-desak.
Entahlah, Am. Bagiku kalender hanyalah deretan
angka-angka tanpa makna. Beratus-ratus hari aku mencoreti angka-angka yang
tertera dengan tanda cakra, menghitung berapa hari yang terlewat,
berharap-harap cemas kapan kamu akan merasa pantas untuk menziarahi tubuhku.
Penantian seperti itu mendatangkan rasa sakit yang berlebih-lebih, Am. Rasa
sakit yang lebih besar daripada kehilanganmu kali ini. Mungkin kamu harus tahu,
bagaiamana pedihnya menjadi istri yang tidak diinginkan suaminya.
Di dalam kalender itu pulalah aku
menandai tanggal demi tanggal, tanggal ulang tahunku, tanggal ulang tahunmu,
tanggal pernikahan kita, setiap tanggal yang menurutku berarti, tapi kamu
selalu berkata bahwa tidak ada tanggal yang harus dirayakan, tidak ada tanggal
yang sakral. Jadi mengapa kamu menyebut-nyebut hari ulang tahun pernikahan? Itu
hanya sederet angka, hanya memoar dari sebuah peristiwa.
Ah, Am. Mestinya kamu lihat
bagaimana sanggahan-sanggahanmu bahkan telah mencuci kepalaku. Dulu, mungkin
aku akan memertahankan pendapat mati-matian, walau semua pendapatku akan kamu
gilas dan kamu mentahkan. Pada akhirnya, akulah perempuan yang selalu
menanggung kesalahan, bahkan untuk sesuatu yang tidak aku lakukan.
“Aku tidak ingin kamu pergi, dengan
cara seperti ini, atau dengan cara apa pun,” kamu menatap bebayang di sudut
ruangan. Separit sungai mengalir di pipimu.
Sudah pernah kubilang bahwa selama
tiga tahun ini kamu tak pernah merasa memilikiku, aku hanyalah arca penghias
sudut rumahmu. Jadi mengapa kamu baru menderita sekarang? Setelah segala
sesuatunya tak bisa kita kembalikan?
“Aku menyesal telah berkata-kata
kasar padamu, aku menyesal tak pernah mempedulikanmu,” katamu.
Waktu tidak bisa diputar ulang,
begitu juga cinta. Kita hanya sepasang pemain sandiwara di panggung bernama
kehidupan. Kamu boleh saja meraung-raung meneriakkan penyesalan, tapi itu tak
akan berarti banyak, aku tak akan kembali, tak akan pernah. Nikmati saja setiap
sayat luka, Am. Sebab itulah yang aku lakukan setiap kali makian keluar dari
mulutmu, atau setiap kali kau berubah menjadi patung yang bisu.
Aku tahu, kau menikahiku dengan
cinta yang meniada, hanya ingin
menenggelamkan jejak-jejak masa lalu. Bagimu, pernikahan hanyalah menggenapkan
jalan nasib, sekadar mengikuti arus sungai, berlayar untuk sampai kepada muara
dan lautan. Sedangkan bagiku, menikah denganmu adalah sebuah kesempurnaan
hidup. Belum pernah aku mencintai laki-laki sebesar aku mencintaimu.
Aku sudah tuli terhadap makianmu, Am.
Kata-kata tak lagi menjadi pedang yang menikam. Ketika kamu boleh mengatakan
apa saja karena telingaku sudah tidak bekerja, mengapa kamu justru mengatakan
penyesalan? Tidakkah itu sia-sia?
“Aku menemui Lara hanya agar ia
menjauh dan tidak lagi merongrong kehidupan kita, Ayya. Tak lebih dari itu,”
tanganmu yang menggenggam cangkir bergetar-getar.
Apa? Mestinya kamu mencerna
kata-katamu barusan. Menemuinya? Bukankah ia yang menemuimu? Di rumah kita. Di
kamar kita. Dan mataku nyaris buta sebab aku menemukan kalian di atas ranjang
sambil telanjang. Itu yang kamu sebut sebuah pertemuan? Am, aku bukan anak umur
lima tahun yang bisa kamu bohongi tentang apa itu fungsi vagina dan payudara.
Kamu selalu bilang bahwa perempuan itu telah menjadi hantu masa lalu, tapi
suratnya masih kamu simpan, fotonya masih menghiasi folder-folder di dalam
komputer, semua tulisanmu tentangnya tak pernah kamu buang. Persetan tentang
hidup bukan hanya tentang kelamin, toh pada akhirnya kamu menyerah pada
setan-setan yang kamu ingkari tapi kamu puja sampai ke seluk sanubari.
“Aku tidak mengerti, apa sebetulnya
yang tengah kamu perjuangkan?” kamu menggeleng-gelengkan kepala.
Ya, kamu memang tidak pernah
mengerti. Di dunia kita yang kecil, pemikiran selalunya saling berbenturan
untuk kemudian menghambur keluar. Bagiku, pekerjaan kantormu telah menyita
banyak sekali waktu. Bagimu, perjuanganku menuntut keadilan bagi
perempuan-perempuan korban kekerasan hanyalah omong kosong semu. Kamu hanya
ingin istri yang diam di rumah, tidak memiliki keahlian apa-apa selain memasak,
menyapu, mencuci, dan berdandan cantik, tepat seperti Lara.
Pernahkah kamu sadar bahwa selama
ini aku hanya menjadi bayang-bayang?
“Ayya, aku tidak ingin kamu pergi.
Seharusnya aku mencegahmu ikut demonstrasi,” kamu resmi menangis. Matamu
bergerimis. Berpasang-pasang mata menoleh ke arahmu, lelaki yang tengah duduk
sendirian dengan dua gelas macchiato
caramel di hadapan.
Menangislah, Am. Meraung-raung dan
merasa menyesalah, tapi aku tak akan pernah kembali kepadamu. Tidak akan
pernah. Waktumu untuk bersamaku telah habis sejak orang-orang menemukan tubuhku
tergolek tak bernyawa di gorong-gorong dengan dua peluru bersarang di kepalaku,
tiga hari lalu.
Janji yang pernah kubuat telah
kutepati; bahwa aku akan meninggalkanmu dengan cara yang teramat menyakitkan.
___
*lirik lagu Ferry Curtis; Lelaki di Persimpangan

Published on October 30, 2013 20:18
Mimpi-Mimpi Buruk Itu Kembali, eL
eL, mimpi-mimpi itu datang lagi. Mimpi buruk yang menyeretku ke dalam labirin paling pekat sehingga aku kembali tersesat. Bukan, ini bukan tentang anak perempuan yang mengajakku pulang di halte bus tempat aku terbaring sambil berlumuran darah. Mimpi yang itu sudah berhasil kutidurkan berbarengan dengan lenyapnya makam putriku. Ini mimpi yang lain lagi, mimpi yang lebih menakutkan lagi.
Aku kembali diseret ke tahun 2009, kembali berada di kamar pengap penuh baju kotor bergelantungan. Seseorang menyiramkan satu jeriken minyak tanah ke tubuhku hinga payudaraku melepuh dan rambutku berbau tungku. Di dalam mimpiku itu, aku tidak berteriak meminta pertolongan, tidak menangis ataupun meronta-ronta seperti seharusnya ketika sepercik api berada di pinggiran pipi. Perlahan, rambutku terbakar. Alisku terbakar. Wajahku terbakar. Lalu api itu menjalar, menikmati gemeretak daging dan tulangku yang mendesis-desis.
Aku ingin bangun, sungguh aku ingin bangun.
Yang terjadi kemudian adalah aku yang nyaris telanjang di belantara pasar dan tatapan orang-orang. Kau masih ingat tanggalnya? Aku tidak, mungkin kita bisa mencarinya nanti di buku harian yang kutuliskan atau di blog ini. Ya, aku kembali ke sana. Ke Nagoya Center yang ramai dengan para pejalan kaki; remaja-remaja kurang hiburan dan orang-orang yang tak tahu bagaimana bersenang-senang. Seorang lelaki mendatangiku dari arah belakang, menyeretku pulang. Aku meronta, kali ini aku meronta. Lalu ia mulai merobek-robek bajuku, menampariku sambil mengataiku perempuan sundal. Dengan pakaian compang-camping aku diseretnya ke tengah jalan, menantang berbagai kendaraan yang berlalu-lalang. Bahkan di dalam mimpi, aku ingin sekali mati.
Seharusnya aku bangun agar mimpi buruk itu tak terus berlanjut, tapi aku tak bangun.
Lalu, tiba-tiba aku berada di penghujung tahun 2011. Masih dapat kudengar gempita terompet di kejauhan ketika seorang lelaki menampar wajahku berkali-kali hingga bibirku berdarah. Apa yang dia katakan, eL? Entahlah, tak begitu jelas kudengar. Ia mabuk, mulutnya berbau alkohol. Pelan-pelan ia mengeluarkan gunting, mendudukanku di bangku. Sambil terkekeh-kekeh, lelaki itu menggunting habis rambutku. Aku menangis, di dalam mimpi itu aku menangis ketika helai demi helai rambutku jatuh ke pangkuan. Samar-samar, masih dapat kudengar lelaki itu tertawa.
Aku tak juga bangun, eL.
Mungkin kau heran bagaimana mimpi bisa ditandai dengan tahun. Aku juga heran. Tapi ada kalender yang berjejalan di dalam kepalaku sehingga tahun-tahun itu kerap kali tak dapat kupisahkan dari berbagai peristiwa.
Mimpi buruk itu masih berlanjut. Aku dan seorang lelaki berada di depan penghulu. Bapak dengan baju batiknya yang berwarna hijau ada di depanku dengan wajah ditenggelamkan kesedihan. Itu pasti ritual pernikahan. Aneh memang, seharusnya pernikahan adalah kabar paling menggembirakan setelah kabar kelahiran. Tapi wajah Bapak seolah-olah akan mengantarku ke neraka.
Setelah itu, aku melihat diriku sendiri di dalam sebuah peti mati. Tahukah kau, eL bahwa selain Tuhan, Izrail adalah lelaki (kalau malaikat memiliki jenis kelamin) yang paling aku cintai. Dalam mimpi itu aku bergembira karena pada akhirnya aku berhasil mati. Tapi mimpi buruk itu memang keparat. Lelaki yang kunikahi membawa pisau dan membelah perutku, tangannya yang berlumuran darah merenggut janin yang tengah kukandung dengan sebelah tangan sementara tangannya yang lain menikam-nikam perutku berkali-kali. Tapi aku tak mati.
Peti mati itu, dari baunya sepertinya itu kayu mahoni, tertutup rapat, mayat putriku berada di dalam sementara aku menggedor-gedor ingin masuk bersamanya.
Mimpi itu berakhir dengan hilangnya semua orang. Aku sendirian di tengah kepekatan yang tak bisa kuterjemahkan. Samar-samar, ada tangis bayi di latar belakang.
Saat itulah aku bangun dari tidur, berteriak janggal seolah-olah tengah dikejar tukang jagal. Samar-samar, masih dapat kudengar tangis bayi di latar belakang.
Aku kembali diseret ke tahun 2009, kembali berada di kamar pengap penuh baju kotor bergelantungan. Seseorang menyiramkan satu jeriken minyak tanah ke tubuhku hinga payudaraku melepuh dan rambutku berbau tungku. Di dalam mimpiku itu, aku tidak berteriak meminta pertolongan, tidak menangis ataupun meronta-ronta seperti seharusnya ketika sepercik api berada di pinggiran pipi. Perlahan, rambutku terbakar. Alisku terbakar. Wajahku terbakar. Lalu api itu menjalar, menikmati gemeretak daging dan tulangku yang mendesis-desis.
Aku ingin bangun, sungguh aku ingin bangun.
Yang terjadi kemudian adalah aku yang nyaris telanjang di belantara pasar dan tatapan orang-orang. Kau masih ingat tanggalnya? Aku tidak, mungkin kita bisa mencarinya nanti di buku harian yang kutuliskan atau di blog ini. Ya, aku kembali ke sana. Ke Nagoya Center yang ramai dengan para pejalan kaki; remaja-remaja kurang hiburan dan orang-orang yang tak tahu bagaimana bersenang-senang. Seorang lelaki mendatangiku dari arah belakang, menyeretku pulang. Aku meronta, kali ini aku meronta. Lalu ia mulai merobek-robek bajuku, menampariku sambil mengataiku perempuan sundal. Dengan pakaian compang-camping aku diseretnya ke tengah jalan, menantang berbagai kendaraan yang berlalu-lalang. Bahkan di dalam mimpi, aku ingin sekali mati.
Seharusnya aku bangun agar mimpi buruk itu tak terus berlanjut, tapi aku tak bangun.
Lalu, tiba-tiba aku berada di penghujung tahun 2011. Masih dapat kudengar gempita terompet di kejauhan ketika seorang lelaki menampar wajahku berkali-kali hingga bibirku berdarah. Apa yang dia katakan, eL? Entahlah, tak begitu jelas kudengar. Ia mabuk, mulutnya berbau alkohol. Pelan-pelan ia mengeluarkan gunting, mendudukanku di bangku. Sambil terkekeh-kekeh, lelaki itu menggunting habis rambutku. Aku menangis, di dalam mimpi itu aku menangis ketika helai demi helai rambutku jatuh ke pangkuan. Samar-samar, masih dapat kudengar lelaki itu tertawa.
Aku tak juga bangun, eL.
Mungkin kau heran bagaimana mimpi bisa ditandai dengan tahun. Aku juga heran. Tapi ada kalender yang berjejalan di dalam kepalaku sehingga tahun-tahun itu kerap kali tak dapat kupisahkan dari berbagai peristiwa.
Mimpi buruk itu masih berlanjut. Aku dan seorang lelaki berada di depan penghulu. Bapak dengan baju batiknya yang berwarna hijau ada di depanku dengan wajah ditenggelamkan kesedihan. Itu pasti ritual pernikahan. Aneh memang, seharusnya pernikahan adalah kabar paling menggembirakan setelah kabar kelahiran. Tapi wajah Bapak seolah-olah akan mengantarku ke neraka.
Setelah itu, aku melihat diriku sendiri di dalam sebuah peti mati. Tahukah kau, eL bahwa selain Tuhan, Izrail adalah lelaki (kalau malaikat memiliki jenis kelamin) yang paling aku cintai. Dalam mimpi itu aku bergembira karena pada akhirnya aku berhasil mati. Tapi mimpi buruk itu memang keparat. Lelaki yang kunikahi membawa pisau dan membelah perutku, tangannya yang berlumuran darah merenggut janin yang tengah kukandung dengan sebelah tangan sementara tangannya yang lain menikam-nikam perutku berkali-kali. Tapi aku tak mati.
Peti mati itu, dari baunya sepertinya itu kayu mahoni, tertutup rapat, mayat putriku berada di dalam sementara aku menggedor-gedor ingin masuk bersamanya.
Mimpi itu berakhir dengan hilangnya semua orang. Aku sendirian di tengah kepekatan yang tak bisa kuterjemahkan. Samar-samar, ada tangis bayi di latar belakang.
Saat itulah aku bangun dari tidur, berteriak janggal seolah-olah tengah dikejar tukang jagal. Samar-samar, masih dapat kudengar tangis bayi di latar belakang.

Published on October 30, 2013 04:31
October 27, 2013
Tentang Lelaki yang Membunuh Bayinya Sendiri
Lelaki itu mengirimiku pesan, menunggu balasan. Mungkin ia sedang mencari sekadar alasan untuk bertemu, atau bisa jadi ia benar-benar merasa rindu. Aku tak pernah tahu.
Karena pesannya tak kujawab juga, ia meneleponku dan aku menjawabnya pada dering kedua karena kebetulan saja jariku refleks melakukannya. Ia tak menanyakan kabar, tak ingin tahu apakah aku baik-baik saja, apakah aku sudah makan atau belum, apakah aku sedang sibuk atau tidak. Ia hanya mengatakan hal-hal yang menurutku tak perlu kuladeni sebab waktu itu aku sedang berada dalam diskusi publik tentang HAM yang piruk pikuk. Aku sibuk.
Setelah telepon satu menitnya yang bagiku terasa seperti neraka itu terputus (ulah operator yang diam-diam kusyukuri), ia kembali mengirimiku pesan dan mengatakan hal yang sama seperti yang ia bicarakan sebelumnya, sedikit menambahkan tanda tanya agar aku mau membalas. Tapi yang kulakukan adalah langsung menghapus pesannya begitu selesai kubaca.
Kemudian aku mulai menebak-nebak. Pernahkah ia berpikir bahwa rasa marahku padanya tak pernah berhenti berderak? Ya, aku memang melanjutkan hidup. Tapi tak pernah sekalipun aku memaafkan atas neraka yang ia berikan. Atas kematian putriku, putrinya.
Lalu aku bertanya lagi (hanya di dalam hati). Bagaimana mungkin ia tak pernah merasa bersalah? Mungkin ia bisa berbangga hati di hadapan ibunya bahwa ia telah menghancurkan hidup seorang perempuan. Menikahinya, menghamilinya, membuangnya, lalu ia pergi dengan perempuan lain. Sebuah prestasi luar biasa untuk ukuran seorang lelaki yang konon tahu tentang agama.
Ya, mungkin ia masih merasa bangga karena telah berhasil membunuhku berkali-kali. Meski aku tak lantas mati.

Karena pesannya tak kujawab juga, ia meneleponku dan aku menjawabnya pada dering kedua karena kebetulan saja jariku refleks melakukannya. Ia tak menanyakan kabar, tak ingin tahu apakah aku baik-baik saja, apakah aku sudah makan atau belum, apakah aku sedang sibuk atau tidak. Ia hanya mengatakan hal-hal yang menurutku tak perlu kuladeni sebab waktu itu aku sedang berada dalam diskusi publik tentang HAM yang piruk pikuk. Aku sibuk.
Setelah telepon satu menitnya yang bagiku terasa seperti neraka itu terputus (ulah operator yang diam-diam kusyukuri), ia kembali mengirimiku pesan dan mengatakan hal yang sama seperti yang ia bicarakan sebelumnya, sedikit menambahkan tanda tanya agar aku mau membalas. Tapi yang kulakukan adalah langsung menghapus pesannya begitu selesai kubaca.
Kemudian aku mulai menebak-nebak. Pernahkah ia berpikir bahwa rasa marahku padanya tak pernah berhenti berderak? Ya, aku memang melanjutkan hidup. Tapi tak pernah sekalipun aku memaafkan atas neraka yang ia berikan. Atas kematian putriku, putrinya.
Lalu aku bertanya lagi (hanya di dalam hati). Bagaimana mungkin ia tak pernah merasa bersalah? Mungkin ia bisa berbangga hati di hadapan ibunya bahwa ia telah menghancurkan hidup seorang perempuan. Menikahinya, menghamilinya, membuangnya, lalu ia pergi dengan perempuan lain. Sebuah prestasi luar biasa untuk ukuran seorang lelaki yang konon tahu tentang agama.
Ya, mungkin ia masih merasa bangga karena telah berhasil membunuhku berkali-kali. Meski aku tak lantas mati.

Published on October 27, 2013 08:07
October 26, 2013
Sepatu Ungu untuk Ziarre

Saya berdiri di depan toko dengan badan canggung dan wajah mendung. Bukan, bukan karena toko di depan saya itu tidak memiliki apa yang saya inginkan. Bukan karena barang-barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan bayangan. Bukan karena itu.
Di toko perlengkapan bayi tersebut, berjejer berbagai barang yang bisa membuat semua perempuan tiba-tiba ingin menjadi seorang ibu. Popok, gaun, mainan, sepatu, apa saja ada. Tapi mata saya terpaku pada sepasang sepatu ungu berpita yang dipajang di etalase. Saya sedang membayangkan kaki kecil putri saya tengah memakainya. Saya lalu membayangkan bahwa kami akan pergi ke taman bermain; dia berteriak-teriak riang dan saya tertawa senang.
Tapi saya tidak berani masuk.
Di dalam sana, berkeliaran banyak sekali perempuan seperti saya. Tapi wajah mereka terang seperti matahari yang membuat saya silau. Beberapa memilih perlengkapan bayi ditemani oleh pasangannya masing-masing sehingga 'pertengkaran' kecil mereka terdengar keluar. Mereka ribut soal warna, soal fungsi, soal apa saja yang terbaik bagi calon bayi mereka. Demi Tuhan, saya ingin sekali tuli saat itu juga. Beberapa perempuan ditemani keluarga yang lain; ibu, adik, kakak, atau anak sulungnya. Barangkali suami mereka tengah bekerja atau bertugas ke luar kota.
Sedangkan saya hanya sendirian. Hanya sendirian.
"Ada yang bisa saya bantu?" seorang pramuniaga yang berpakaian seperti baby sitter berdiri di pintu toko, memandangi saya dengan rasa iba yang nyaris membuat saya gila.
"Sepatu ini," jemari saya mengetuk-ngetuk kaca. "Untuk bayi umur berapa bulan?" suara saya terbata-bata, bersaing dengan udara dan sakit yang menghunjam dada.
Dia tersenyum. "Untuk 3 sampai 5 bulan."
Jadi tidak bisa dipakai untuk berjalan dan bermain di ayunan? Pikir saya.
"Berapa usia bayi Ibu?" ia berjalan mendekat.
"Tujuh minggu, masih di dalam sini," jawab saya menunjuk perut yang kian menggembung.
"Dan Ibu sudah mau membeli sepatu bayi?" ia keheranan, tapi wajahnya menunjukkan jutaan pemakluman.
Saya mengangguk. "Saya hanya ingin memiliki teman," suara saya ditelan geleguk. Mata saya bahkan sudah berkaca-kaca.
"Mau masuk dan melihat-lihat yang lain?" dia melangkah lebih dekat.
Saya ingin sekali masuk, melihat, menyentuh, membeli semua barang yang akan dibutuhkan Zi nanti. Tapi di dalam sana ada banyak perempuan dengan raut wajah bahagia yang membuat saya ingin sekali muntah. Di dalam sana banyak perempuan yang ditemani suaminya. Di dalam sana banyak perempuan yang sedang berbahagia sedangkan saya tidak. Saya tidak ingin masuk. Tidak ingin.
"Di dalam sana banyak sepatu yang bisa dipilih, lho," dia membujuk.
Gelengan kepala saya semakin kuat. Tangan saya mengusap-usap perut untuk meyakinkan diri bahwa saya tidak sendiri. Ada Zi dalam rahim saya. Ada Zi yang menemani saya.
Pramuniaga itu menelengkan kepala, mengamati raut wajah saya.
Saya menghela napas dan mengembuskannya dengan pelan namun terasa begitu menyakitkan. "Nanti ... saya kemari lagi," sebuah senyum pura-pura saya hantarkan. "Nanti ... saya ke sini bersama ... suami."
Pramuniaga di depan saya tersenyum, mengangguk mahfum.
Perlahan, saya mundur dari depan etalase meski mata saya masih terpancang pada sepatu ungu berpita itu. Perlahan, saya mencabuti duri di dalam hati. Perlahan, saya beranjak pergi.
"Nanti, aku akan ke sini dan membeli sepatu bayi bersama suami."
Kalimat di atas saya ucapkan di dalam hati, bersama doa tiada henti, bersama tangis yang berusaha saya tahan agar tak keluar. Ya, barangkali saya akan membeli sepatu bayi itu suatu hari nanti, bersama suami yang ... tidak pernah saya miliki.
(Bandung, 8 Juni 2013)

Published on October 26, 2013 21:23
Untuk Putriku: Ziarre Amaravati
Lengking peluit kereta apigelas styrofoam berisi kopiakan menghantarmu kembali
padaku
Nak, jika kelak kita bertemu, akan kuceritakan padamu tentang riwayat paling jengat. Riwayat yang akan selalu kauingat. Cerita yang barangkali akan menjadi mimpi buruk paling mengerikan di pelepah tidurmu. Tapi jangan khawatir, bahkan ketika di dalam rahim, kau telah menjadi pejuang paling tangguh. Mimpi buruk tak akan menyurutkan langkahmu, sebab ibumu adalah aku. Sebab engkau adalah putriku.
Laki-laki itu, yang menanamkan engkau ke dalam rahimku tak pernah pantas kau panggil ayah, bapak, abi, atau sebutan apa pun. Aku bahkan tak yakin apakah ia manusia, seperti kita. Maka jangan harap suatu hari nanti akan ada laki-laki yang mengajarimu bermain sepeda atau memangkumu ketika kau jatuh dan terluka. Tidak, kau akan berada di dalam perlindunganku, sepenuhnya.
Ziarre sayang ....
Perlu kautahu bahwa bumi yang akan engkau huni adalah tempat paling rapuh. Kau akan bertemu dengan manusia-manusia yang seperti daun luruh; mengangap hidup hanya sebagai jalan tempuh. Tapi engkau akan terlahir sebagai manusia yang utuh; petarung paling tangguh.
Laki-laki itu, yang seringkali merapal nama Tuhan di sela doa-doa yang ia panjatkan. Doa yang konon untuk kita, untuk kesembuhan kita, untuk keselamatan kita. Laki-laki itu, yang sering mengutuki kita sebagai anjing sehingga aku belajar berkata anjing, yang sering mengataiku gila sehingga aku betul-betul gila, yang sering menganggap engkau dan aku tak ada sehingga kita memang meniada.
Laki-laki itu, yang kini tengah melolong bersama sekawanan anjing di bukit Golgota dan memanggil-manggil namaku. Tahukah ia bahwa aku telah mati sejak tanggal 20 Mei? Tahukah ia bahwa benih yang ia tancapkan di rahimku kelak akan menjadi prajurit paling depan yang meminta keadilan? Tahukah ia bahwa menjadi ibu telah mendatangkan kekuatan maha besar?
Ia ... laki-laki yang tak bertuhan, Nak. Sebab jika doanya dipanjatkan kepada tuhan yang benar, tentu ia tak akan sesetan sekarang; melarungmu kepada ketiadaan. Menganggapmu makluk yang tak pantas dipertahankan dan dilahirkan.
Ya, ia dan keluarganya begitu membenciku. Karena aku, dan kau, tetap bertahan hidup setelah badai yang mereka kirimkan. Kita salah karena bertahan, kita salah karena tak mati di tepi jurang atau membakar diri.
Ziarre ...
Aku tak akan melepasmu. Tak akan pernah. Tak akan pernah. Ibu dan anak tidak pernah saling meninggalkan. Bertenanglah di dalam rahimku hingga kelak engkau hadir. Berserahlah kepada takdir paling getir. Sebab engkau anakku, anak semesta.
Mari kita berdoa. Semoga nama Tuhan yang sering laki-laki itu rapal kelak menyelamatkannya dari dosa-dosa yang ia tanam. Amin.

Published on October 26, 2013 11:04
October 25, 2013
Menikmati Kesakitan, Memaknai Kehilangan
:Muhammad Zibril Bayu Perbawa
Sekarang, setelah engkau dan aku memiliki jarak yang sama-sama tidak bisa kita pangkas, sebuah kerelaan mulai tumbuh di dadaku. Pun, kesakitan demi kesakitan yang engkau sebabkan mulai dikelantang hantu bernama hantu. Sebab seperti yang sering aku katakan, cinta selalu memilihkan jalan paling benar.
Zib, kata maaf yang sering engkau uarkan lama-kelamaan membuatku merasa kebal. Barangkali, ya, hanya barangkali, hati di dalam sini sudah memaafkan atas seluruh luka yang engkau hadiahkan. Barangkali juga tidak. Sebab ketika nama dan wajahmu berkelebat, aku kerap kalap. Ingatan tentangmu membawaku ke kawah berisi rasa marah.
Hingga saat ini aku hidup dengan menyimpan berbagai macam rasa sakit tak tertahankan, rasa sakit yang engkau tinggalkan. Aku masih ingat bagaimana tanganmu menjambak rambutku. Aku masih ingat tanganmu menampar wajahku. Aku masih ingat tanganmu memukuliku. Aku masih ingat tanganmu nyaris membakarku.
Tapi aku juga ingat ketika tangan yang sama menelusuri punggungku. Ketika tangan yang sama merangkul bahuku. Ketika tangan yang sama .... Ya, tangan yang sama, tanganmu.
Meski aku kerap bertanya, di manakah cinta saat itu?
Zib, aku tak pernah punya senjata untuk mengenyahkan semua luka. Aku juga tidak pernah berhasil sampai pada kata lupa. Nama dan wajahmu masih kerap berdesak-desak di dalam kepala. Mungkin saja aku bisa berpura-pura bahwa segala macam remuk tidak pernah ada. Bahwa kita tidak pernah bersama. Bahwa aku dan kamu bukan dua orang yang pernah saling jatuh cinta.
Tapi apa yang akan aku dapat dengan berpura-pura?
Zib, aku pernah mencintaimu, dan kau pernah tergila-gila padaku. Terlepas dari apakah sesudah itu kita saling membantai atau tidak, toh nyatanya kita pernah jatuh cinta. Itu saja.
Maka yang aku inginkan saat ini adalah berterima kasih kepadamu. Setelah bertahun-tahun aku menyimpan rasa sakit yang kausebabkan, sudah saatnya aku belajar untuk menerima, menyimpan, sekaligus melepaskan. Aku tak pernah menyesal menjadi bagian dari hidupmu, pun ketika kau menjadi bagian dari nadiku. Karena tanpamu, mungkin aku akan tetap menjadi perempuan paling lemah. Karena tanpamu, mungkin aku tak akan pernah belajar bagaimana memamah badai.
Segala rasa sakit itu akan aku simpan, memasukkannya ke dalam kotak yang aku tutup rapat-rapat. Kesakitan demi kesakitan itu akan aku nikmati sendirian agar aku bisa kuat bertahan. Kehilanganmu hanyalah harga yang harus aku bayar untuk sebuah hidup yang -mungkin saja- lebih terjal.
Selamat tinggal, Zib. Kini aku sudah sampai pada kerelaan menerimamu sebagai bagian dari hidupku. Aku ... lepas. Aku ... bebas.

Cinta tidak pernah salah, tidak juga Tuhan yang memilihkan jalan begitu terjal bagiku, juga bagimu.
Sekarang, setelah engkau dan aku memiliki jarak yang sama-sama tidak bisa kita pangkas, sebuah kerelaan mulai tumbuh di dadaku. Pun, kesakitan demi kesakitan yang engkau sebabkan mulai dikelantang hantu bernama hantu. Sebab seperti yang sering aku katakan, cinta selalu memilihkan jalan paling benar.
Zib, kata maaf yang sering engkau uarkan lama-kelamaan membuatku merasa kebal. Barangkali, ya, hanya barangkali, hati di dalam sini sudah memaafkan atas seluruh luka yang engkau hadiahkan. Barangkali juga tidak. Sebab ketika nama dan wajahmu berkelebat, aku kerap kalap. Ingatan tentangmu membawaku ke kawah berisi rasa marah.
Hingga saat ini aku hidup dengan menyimpan berbagai macam rasa sakit tak tertahankan, rasa sakit yang engkau tinggalkan. Aku masih ingat bagaimana tanganmu menjambak rambutku. Aku masih ingat tanganmu menampar wajahku. Aku masih ingat tanganmu memukuliku. Aku masih ingat tanganmu nyaris membakarku.
Tapi aku juga ingat ketika tangan yang sama menelusuri punggungku. Ketika tangan yang sama merangkul bahuku. Ketika tangan yang sama .... Ya, tangan yang sama, tanganmu.
Meski aku kerap bertanya, di manakah cinta saat itu?
Zib, aku tak pernah punya senjata untuk mengenyahkan semua luka. Aku juga tidak pernah berhasil sampai pada kata lupa. Nama dan wajahmu masih kerap berdesak-desak di dalam kepala. Mungkin saja aku bisa berpura-pura bahwa segala macam remuk tidak pernah ada. Bahwa kita tidak pernah bersama. Bahwa aku dan kamu bukan dua orang yang pernah saling jatuh cinta.
Tapi apa yang akan aku dapat dengan berpura-pura?
Zib, aku pernah mencintaimu, dan kau pernah tergila-gila padaku. Terlepas dari apakah sesudah itu kita saling membantai atau tidak, toh nyatanya kita pernah jatuh cinta. Itu saja.
Maka yang aku inginkan saat ini adalah berterima kasih kepadamu. Setelah bertahun-tahun aku menyimpan rasa sakit yang kausebabkan, sudah saatnya aku belajar untuk menerima, menyimpan, sekaligus melepaskan. Aku tak pernah menyesal menjadi bagian dari hidupmu, pun ketika kau menjadi bagian dari nadiku. Karena tanpamu, mungkin aku akan tetap menjadi perempuan paling lemah. Karena tanpamu, mungkin aku tak akan pernah belajar bagaimana memamah badai.
Segala rasa sakit itu akan aku simpan, memasukkannya ke dalam kotak yang aku tutup rapat-rapat. Kesakitan demi kesakitan itu akan aku nikmati sendirian agar aku bisa kuat bertahan. Kehilanganmu hanyalah harga yang harus aku bayar untuk sebuah hidup yang -mungkin saja- lebih terjal.
Selamat tinggal, Zib. Kini aku sudah sampai pada kerelaan menerimamu sebagai bagian dari hidupku. Aku ... lepas. Aku ... bebas.

Published on October 25, 2013 09:35
Komedi Sepahit Kopi; Potret Suram Indonesia di Era Reformasi
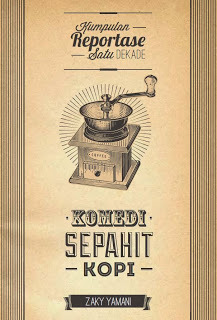
Judul: Komedi Sepahit Kopi (Kumpulan Reportase Satu Dekade)
Penulis: Zaky Yamani
Penerbit: SvaTantra (Oktober, 2013)
ISBN: 978-602-14321-2-9
Halaman: 318 halaman
Komedi Sepahit Kopi (KSK), sesuai dengan judulnya, berisi 10 reportase penulis yang bisa diibaratkan seperti secangkir espresso double shoot; nendang, pahit, getir. No sugar allowed. No sugar at all.
Bab pertama masih bisa membuat saya tertawa ketika membayangkan dua orang jurnalis muda (Zaky dan Bangkit) mengencingi laut seperti dua bocah laki-laki bertemu dengan permainan baru. Saya masih bisa tersenyum membayangkan mereka nyaris mabuk laut meski setelah itu dipaksa merenung tentang betapa para nelayan di Santolo mempertaruhkan nyawa demi 'bayaran' tak seberapa untuk menyediakan ikan-ikan laut yang saya makan, yang Anda makan, yang kita makan.
Bab kedua, saya masih bisa tertawa, menertawakan kekonyolan penulis dan kawannya Bangkit. Tapi bersamaan dengan halaman demi halaman yang saya mamah kemudian, tawa itu kian hilang. Berganti dengan raut suram dan dada yang berdebur geram. Tidak pernah saya merasa sesedih itu ketika membaca sebuah buku nonfiksi. Mungkin karena tokoh-tokoh yang ada di KSK adalah nyata, karena orang-orang yang dibelit kemiskinan itu benar-benar ada, karena keanjingan pemerintah Indonesia juga sama-sama saya rasa.
Bab ketiga dan seterusnya, saya sama sekali tidak sanggup tertawa. Yang ada adalah rasa sedih dan marah. Bagaimana tidak, kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, ketimpangan sosial itu bukan terjadi jauh di belahan lain Indonesia sana melainkan di provinsi yang sekarang saya tinggali, bahkan di kota yang sekarang saya diami.
***
Melalui KSK, kita tidak hanya diajak untuk mencermati proses sebuah karya (dalam hal ini berita), tapi juga segala sesuatu di balik itu. Kita (terutama saya) jadi tahu bagaimana potret sebetulnya masyarakat Garut pedalaman; para petani yang kelaparan, para nelayan yang menggunakan ban untuk menangkap ikan, para peternak transmigrasi lokal (translok) yang dikebiri janji demi janji tanpa ditepati.
Potret suram masyarakat marjinal inilah yang menjadi garis merah KSK. Potret yang mengerucut ke sumber yang sama; kelalaian pemerintah.
KSK membawa kesadaran tak terbantahkan; bahwa Indonesia masih menjadi negeri terbelakang.
***
Dengan sampul buku bergaya vintage yang sedang inn karya Domus, buku ini tentu dapat menarik pembeli jika dipajang di rak toko buku manapun. Sayangnya masih ada beberapa (lebih dari 3) typo yang menjadikan kenyamanan membaca berkurang. Di cetakan berikutnya, saya harap proof reader-nya bekerja lebih keras lagi.
Kebun Seni, 25 Oktober 2013

Published on October 25, 2013 03:27
October 23, 2013
Ubud; Secarik Ingatan Tentang Tubuhmu di Tubuhku
:Kamu
"But I have to go."

Hanya kata-kata itu yang masih aku ingat. Lima kata yang seperti pisau lipat; menyayat dengan tepat. Kamu harus pergi, kembali kepada dunia yang selama ini kamu tinggali. Kadang, aku ingin bertanya, adakah namaku tertoreh di barisan dadamu itu?
Bertahun-tahun aku menyimpan asmara yang tak kunjung padam, untukmu.
"Sini, mari kupeluk," katamu.
Maka aku dengan ingatan kanak-kanak menyelusup ke rengkuhan tanganmu untuk kemudian tubuhku merekat erat ke tubuhmu. Tahukah kau bahwa satu buah pelukan berarti banyak bagiku? Satu, sebab kamu memang berutang itu. Dua, karena bagiku kamu adalah satu-satunya lelaki yang tak pernah berhenti aku cintai. Ketiga, karena pelukanmu adalah tempat pulangku.
Tapi akhirnya kamu pergi seperti selama ini.
Sebetulnya aku berharap malam itu ada hujan badai atau banjir bandang agar kita berdua bisa mendekam di dalam kamar, menari sampai malam usai atau sampai kita berdua lelah dibakar gairah. Tapi kamu harus pergi, seperti selama ini.
Sebetulnya aku tak ingin kamu pergi agar kita bisa bercinta sekali lagi.
Tapi kamu pergi.
Dan aku harus kembali ... sendiri.

"But I have to go."

Hanya kata-kata itu yang masih aku ingat. Lima kata yang seperti pisau lipat; menyayat dengan tepat. Kamu harus pergi, kembali kepada dunia yang selama ini kamu tinggali. Kadang, aku ingin bertanya, adakah namaku tertoreh di barisan dadamu itu?
Bertahun-tahun aku menyimpan asmara yang tak kunjung padam, untukmu.
"Sini, mari kupeluk," katamu.
Maka aku dengan ingatan kanak-kanak menyelusup ke rengkuhan tanganmu untuk kemudian tubuhku merekat erat ke tubuhmu. Tahukah kau bahwa satu buah pelukan berarti banyak bagiku? Satu, sebab kamu memang berutang itu. Dua, karena bagiku kamu adalah satu-satunya lelaki yang tak pernah berhenti aku cintai. Ketiga, karena pelukanmu adalah tempat pulangku.
Tapi akhirnya kamu pergi seperti selama ini.
Sebetulnya aku berharap malam itu ada hujan badai atau banjir bandang agar kita berdua bisa mendekam di dalam kamar, menari sampai malam usai atau sampai kita berdua lelah dibakar gairah. Tapi kamu harus pergi, seperti selama ini.
Sebetulnya aku tak ingin kamu pergi agar kita bisa bercinta sekali lagi.
Tapi kamu pergi.
Dan aku harus kembali ... sendiri.

Published on October 23, 2013 06:01
October 22, 2013
AirMataAirMata

Malam itu Ijah benar-benar menyaru jadi hantu. Hantu paling bengis karena hatinya sering kali teriris. Namun, hati yang teriris itu telah ia tinggalkan di pelataran rumah, tepat sebelum ia berjalan mengendap-endap mengarungi malam gelap. Napasnya memburu sementara udara semakin biru. Ijah menyeka bulir air mata yang bergulir di pipinya tepat sebelum kakinya berjingkat memasuki tanah pemakaman. Ada yang harus ia tuntaskan. Segera.
. . .
“Hah? Berapa?” tenggorokan Ijah tercekat mendengar angka yang menghambur dari mulut Bapak.
“Lima ratus ribu, Neng. Tapi katanya bisa kurang karena Mang Atep masih saudara jauh Bapak.”
“Lima ratus ribu cuma untuk memperbaiki makam sekecil itu?” mata Ijah semakin melotot.
Bapak mengangkat bahu. “Bisa kurang jadi empat ratus lima puluh ribu.”
“Kenapa bukan Bapak saja yang nembok? Pan Bapak juga bisa. Biar saya yang beli semen, pasir dan batu batanya. Bisa lebih murah kan? Pasti nggak sampai segitu.”
Bapak menghela napas, wajah Bapak yang digerus usia terlihat sedemikian lelah. “Nggak bisa, Neng. Harus penjaga makamnya yang nembok. Nggak boleh sembarangan orang. Bapak nggak berani.”
“Nggak berani atau nggak boleh?”
Bapak diam sebentar. “Nggak boleh, juga nggak berani.”
“Memangnya kenapa?” Ijah semakin bertanya-tanya.
“Aduh, Neng. Yang nembok makam itu tidak bisa sembarangan orang. Harus penjaga makamnya, atau orang yang memang ‘bisa’.”
“Pamali kalau Bapak yang nembok?”
“Iya, pamali,” Bapak menyerah.
Omong kosong! Rutuk Ijah. Yang mati dan terbujur di dalam tanah itu adalah putrinya, cucu kedua Bapak. Kenapa justru orang lain yang harus memperbaiki makam? Dan kenapa justru harus memakai uang seharga hampir tiga karung beras? Beras yang bisa menyambung hidup keluarganya selama tiga bulan.
Ijah mengembuskan napas, kesal. “Kalau begitu, tidak usah ditembok, biarkan saja begitu.”
“Tapi makam anak kamu itu sudah rusak, tanahnya sudah hampir amblas. Nanti kalau tidak ditembok, malah hilang. Tanah makam di daerah sini kan sudah jarang, Neng. Bisa-bisa makam anak kamu ditimpa dengan makam orang lain,” suara Bapak memelas.
“Itu hampir satu bulan gaji saya di pabrik, Pak. Kalaupun saya pakai untuk memperbaiki makam, nanti siapa yang akan membeli beras, membayar listrik, membeli gas dan kebutuhan dapur?”
Mata Bapak berkaca-kaca. Ini kali kedua Ijah menyaksikan Bapak nyaris menangis. Pertama saat pemakaman putrinya, kedua adalah saat ini.
“Maafkan Bapak, Neng. Gaji Bapak hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Andaikan Bapak bisa membantu.”
Ada lubang di hati Ijah yang kian menganga. Ia meraih tangan Bapak dan menggenggamnya.
“Bukan salah Bapak. Saya akan mengambil lebih banyak lembur supaya bisa mengumpulkan uang lebih banyak.”
Bapak mengangguk. Ijah juga mengangguk. Hatinya teraduk-aduk.
. . .
. . .
Ijah meremas amplop cokelat berisi uang gajinya bulan ini. Ia hanya buruh harian lepas di pabrik dengan gaji tiga ribu lima ratus per jam. Gajinya bulan ini mencapai delapan ratus lima ribu rupiah karena beberapa kali lembur, cukup untuk memperbaiki makam putrinya. Tapi putri sulungnya harus membeli buku pelajaran, seragam baru, dan sepatu di tahun ajaran baru. Ibunya harus segera dibawa berobat karena sudah dua minggu sesak napas.
Ada beras yang harus ia beli, ada uang listrik yang harus ia bayarkan, ada gas, ada minyak, ada gula, ada uang jajan anak, ada segalanya kebutuhan orang hidup. Mereka anggota keluarga yang keberlangsungan hidupnya bergantung di atas pundak Ijah. Dan ada pula kebutuhan orang mati yang kini juga bergelayut di pundak Ijah.
Ijah tak lagi memiliki suami. Ijah hanya memiliki Ibu, Bapak, dan putri sulungnya yang harus ia beri makan. Ia meremas kembali amplop di tangannya, meremas hatinya sendiri.
“Ibu nggak usah ke dokter, Neng. Uangnya kamu simpan untuk membetulkan makam anakmu,” suara Ibu lemah.
“Ibu masih hidup, anak saya sudah meninggal. Ibu lebih membutuhkan obat daripada dia,” rahang Ijah mengeras.
Ibu membelalak. Ada luka yang dibaca Ijah. Ah … luka yang tak bisa ia sembuhkan.
“Kasihan anak kamu, Neng …” bisik Ibu. “Makamnya sudah rusak.”
Dada Ijah retak. Kian menyesak.
. . .
Ijah mengusap nisan, bibirnya gemeletar dengan mata tak berhenti berurai. Tangan Ijah yang semakin kurus menumpuk satu per satu batu bata, merekatnya dengan adukan semen dan pasir. Ia bekerja dalam diam, ditemani air mata dan gelap malam.
. . .
Kata Ibu, juga kata Bapak, mereka yang masih muda dan memang bukan penjaga makam dilarang keras memperbaiki makam kerabatnya sendiri. Bisa membawa sial, bahkan kematian. Masih menurut cerita Ibu, mereka yang memperbaiki makam kerabatnya sendiri bisa dijauhkan dari rezeki. Usahanya bangkrut, atau kesialan lain yang tentu saja tak berani Bapak tanggung. Karena Bapak percaya.
Tapi Ijah tidak percaya. Hidup sudah cukup mengajarkan bagaimana cara memamah luka, mengenyam kemiskinan. Kalaupun larangan itu benar adanya, Ijah bersedia. Ia rela tidak diberi rezeki seumur hidup, bahkan rela menukar penggalan napasnya sendiri demi memperbaiki makam putrinya tanpa mengorbankan senggal napas kedua orang tuanya, juga putri sulungnya yang masih hidup.
Persetan dengan uang lima ratus ribu, aku bisa memperbaiki makam putriku sendiri, dengan tanganku sendiri. Raung hati Ijah.
. . .
Malam itu Ijah benar-benar menyaru jadi hantu. Hantu paling bengis karena hatinya sering kali teriris. Namun, hati yang teriris itu telah ia tinggalkan di pelataran rumah, tepat sebelum ia berjalan mengendap-endap mengarungi malam gelap. Napasnya memburu sementara udara semakin biru. Ijah menyeka bulir air mata yang bergulir di pipinya tepat sebelum kakinya berjingkat keluar dari tanah pemakaman. Ia lega karena tugasnya telah tuntas.
“Izrail sang pencabut nyawa, ataukah Mikail sang pemberi rezeki, mari berperang denganku. Tak ada dosa yang aku lakukan karena memperbaiki makam putriku sendiri,” gumam Ijah.
Kemudian ia berjalan mengarungi malam yang kian jengat, meninggalkan makam putrinya yang ia seduh dengan air mata.
Bandung, 9 November 2011

Published on October 22, 2013 21:20
Mimpi dan Ilusi
- Skylashtar Maryam's profile
- 8 followers
Skylashtar Maryam isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.



