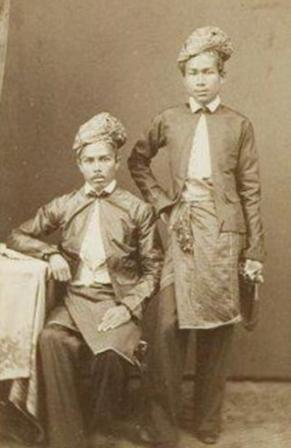Suryadi's Blog, page 19
June 15, 2013
PENGINJILAN
Orang zaman saisuak menyebutnya misi zending. Dulu di zaman kolonial pusatnya ada beberapa negara Eropa, seperti Nederlands Bijbelgenootschaap dari Belanda atau Rhenis Missionary Society dari Jerman. Masyarakat Melayu lebih sering menyebutnya misi peginjilan. Ada juga yang menyebutnya misi misionaris. Mereka sudah bertapak di Singapura sejak pertengahan abad ke-19.
Di zaman lampau sekali, ketika bangsa kita masih banyak yang telanjang dan suka mengoleksi tengkorak manusia, misi pengingjilan telah menunjukkan manfaatnya. Banyak kelompok etnis di Indonesia yang sudah dimerdekakan dari kepercayaan paganisme oleh para penginjil yang kegigihannya memang membuat kita salut. Mereka berani tinggal di pedalaman di antara orang-orang yang masih ‘liar’. Kita tidak usah menengok jauh-jauh: orang Batak yang masih mempercayai paganisme di abad ke-19 menjadi tercerah-kan berkat misi penginjilan yang dilakukan oleh Ingwer Ludwig Nommensen (1834-1918). Demikian pula halnya zending yang pertama kalinya masuk ke Kepulauan Mentawai di tahun 1901 yang dibawa oleh Pendeta Let, telah berhasil pula memper-kenalkan tradisi keberaksaraan kepada orang Mentawai.
Di bagian timur Nusantara seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, misi-misi penginjilan juga telah berhasil membebas-kan banyak kelompok etnis dari keterbelakangan. Para penginjil telah menerjamahkan Bijbel ke dalam berbagai bahasa daerah: Melayu, Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Mereka juga telah berhasil membukukan berbagai aspek bahasa dan budaya masyarakat lokal tempat mereka diutus.
Jadi, kita patut juga berterima kasih kepada para penginjil itu. Mereka telah melekatkan agama (Kristen) ke dalam hati saudara-saudara kita yang pada waktu itu masih me-nyembah gunung dan gua-gua.
Tapi itu cerita dulu. Seka-rang apakah misi penginjilan itu masih relevan? Apa sebenarnya tujuan misi penginjilan itu didesakkan ke tengah-tengah umat lain yang sudah memeluk agama tertentu? Apakah dalam kitab Injil ada suruhan Tuhan Yesus agar semua manusia di dunia ini memeluk satu agama saja: Kristen? Saya khawatir manusia modern telah merusakkan agamanya sendiri dengan tindakan-tindakannya yang penuh nafsu dengan mengatasnamakan Tuhan.
Misi-misi penginjilan di zaman modern ini, yang mende-sakkan agama Kristen ke dalam masyarakat yang sudah memeluk agama lain, pada hakekatnya lebih merupakan refleksi kerakusan para pemuja duniawi ketimbang suruhan dari Tuhan. Sebab Tuhan cinta damai, dan penetrasi misi-misi penginjilan ke dalam masyara-kat modern sekarang yang sudah memeluk agama tertentu hanya akan menimbulkan kekis-ruhan dan kekacauan ketim-bang kedamaian. Indonesia, sampai batas tertentu, juga menderita karenanya.
Banyak misi penginjilan dikoordinir dari Eropa dan Amerika, tempat agama Kristen sudah lama diletakkan di bawah kolong rumah oleh orang kulit putih, terutama generasi muda-nya. Dewasa ini kebanyakan orang Eropa ateis. Mengapa kiranya bukan mereka yang sudah ‘membunuh’ Tuhan dalam hatinya itu yang menjadi target misi-misi penginjilan? Mengapa orang-orang di dunia timur yang sudah memeluk agama tertentu dan tak kalah tinggi peradabannya dari orang Eropa yang selalu direcoki oleh misi-misi penginjilan?
Di tahun 1930, seorang anak muda Minangkabau (dan sangat mungkin dia seorang Muslim walau sa-parewa apapun dia) menuliskan refleksinya mengenai misi penginjilan. Waktu itu dia sedang berada di geladak sebuah kapal api di Venezia dalam perjalanan pulang ke Indonesia dari lawatannya beberapa bulan di Eropa, jantung agama Roman Katolik. Di kapal itu ia melihat sekelompok pastor dan biarawati yang ditugaskan ke Asia untuk misi penginjilan.
Didadanja tergantoeng silang perak jang sedjangka pandjangnja, dihijasi oleh patoeng Kristoes jang ketjil, tulisnya. Mereka itoe pergi ke Tiongkok, moela-moela kabar-nja ke Shanghai dan dari sana dibagi-bagi ke lain-lain tempat oentoek mengembangkan agama Kristen special Roomsch Katholiek.
Saja bertanja dalam hati saja, kata anak muda Minang itu lagi, apa orang Tionghoa mintak mereka itoe datang ke tanahnja dan inginkan sangat agama Roomsch Katholik? Saja tahoe mereka itoe pergi karena soeroehan Missie sadja jang merasa kewadjiban mengeristenkan seloeroeh doenia.
Adakah Europa berhak (dalam hal ini agama Roomsch Katholik) jang ber-poesat di Rome mengatakan bahwa agamanja itoe lebih baik dari pada pengadjaran pengadjaran Kong Foe Tse atau Boedha jang dipertjajai orang Tionghoa semendjak berabad abad lamanja?
Kalau dibandingkan kultuur Europa, njata sekali bahwa kultuur Tiongkok lebih toea dan tidak alah oleh kultuur Europa. Achli achli Europapoen telah membenarkan hal itoe.
Dalam zaman sekarang ini dimana Tiongkok mema-djoekan kenasionalannja orang Tionghoa maoe menga-toer penghidoepannja sendiri sebagaimana tersoerat dalam kitab-kitab jang tertoelis dalam zaman poerbakala sebeloem ada bijbel. Dan kedapatan bahwa isi kitab-kitab itoe masih modern sampai sekarang ini.
Saja tahoe orang Tionghoa tidak dipaksa akan menoeroet agama Kristen. Meskipoen demikian tidak ada saja lihat satoe djalan jang terang mengapa non-non dan pastor itoe dikirim kenegeri-negeri jang tidak memintanja datang.
Apa jang soedah saja persaksikan di Europa dalam perlawatan saja kesana sini? Ada boekti-boekti jang menoendjoekkan kepada saja bahwa dalam hal boedi, dalam hal moral orang Eropah boleh beladjar ke Asia. Menahan hawa nafsoe jang berlebih-lebih, orang Eropa oemoemnja tidak tahoe, karena bathinnja soedah hilang lenjap. Keadaan Eropa pada zaman sekarang perloe dapat reform jang da-lam, dan berhoeboeng dengan hal itoe kenapa segala pastor itoe tidak bekerdja di tanahnja sendiri akan memperbaiki keadaan ranah airnja?
Eropa kekoerangan pastor dan non jang bekerdja memperbaiki keadaan disana, tetapi meskipoen begitoe tiap tahoen bilang ratoesan pastor dan non orang koelit poetih dikirim kenegeri asing akan mengadjari orang Asia perka-ra-perkara jang di Eropa sen-diri mengandoeng tanda tanja jang besar dibelakangnja.
Orang Europa sendiri sering saja tanja-tanjai penda-patnja tentang perkara zen-dingnja agama Roomsch Katholik. Mereka itoe mengangkat bahoe karena dia djoega tidak mengerti itoe. Katanja dalam zaman seka-rang soedah liwat waktoenja boeat menakloek[k]an bangsa-bangsa asing menoeroeti sesoeatoe agama seperti Roomsch Katholik[,] apalagi setelah bangsa Asia soedah bangoen dan pandai serta mengetahoei sendiri bagaimana letaknja agama didalam penghidoepan orang koelit poetih. Perang besar jang terlampau [Perang Dunia I] telah menggambarkan bagaimana kristennja orang Europa dan menggambarkan kepada sedoenianja bahwa sebetoelnja orang Europa djaoeh sekali dari tempat tjita-tjitanja jang soetji. Djoega anak-anak moeda angkatan sekarang berdiri dengan pandangan jang skeptisch (bimbang) sekali terhadap kepada missie dari Roomsch Katholik itoe.
Apa jang koerang pada Asia jaitoe boekannja agama dan boedi, melainkan ilmoe pengetahoean dan technik.
Anak muda Minangkabau itu adalah [Djamaluddin] Adinegoro. Kutipan di atas, yang saya salin menurut ejaan aslinya dari bukunya Kembali dari Perlawatan ke Europa, Djilid I (Medan-Deli: N.V. Handel Mij. & Drukkerij Sjarikat Tapanoeli, 1930: 12-14), merefleksikan pandangan kritis wartawan yang terkenal di zamannya itu mengenai misi-misi penginjilan ke Asia. Dan apa yang dikatakannya tampaknya banyak benarnya.
Sekarang, 83 tahun setelah Adinegoro menulis pandangannya di atas, watak misi-misi penginjilan ke Timur tetap belum berubah. Sementara itu jumlah orang Eropa yang membelakangi Tuhan pasti jauh lebih banyak dibandingan tahun 1930-an. Mengingat hal ini, kiranya para penginjil Barat mungkin harus mempertimbangkan kata-kata Adinegoro di atas: memang di abad ke-21 ini kita makin tidak melihat satoe djalan jang terang mengapa [para penginjil] itoe dikirim kenegeri-negeri jang tidak memintanja datang. [K]enapa segala pastor itoe tidak bekerdja ditanahnja sendiri akan memperbaiki keadaan ranah airnja?
Bukankah misi penginjilan harus ditujukan kepada orang-orang yang belum atau tidak beragama, tidak kepada mereka yang sudah memeluk agama tertentu, seperti disentil oleh Adinegoro dalam bukunya itu. Dan dalam konteks sekarang, sudah semestinya haluan misi-misi penginjilan dibelokkan ke Eropa, sebab memang di benua itulah kini banyak ditemukan orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan.
Suryadi - Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Leiden, Belanda
Rubrik Refleksi METRO Payakumbuh Edisi 15 Juni 2013
June 9, 2013
MENAPAKTILASI PERJALANAN SEJARAH PERS [ISLAM] MINANGKABAU
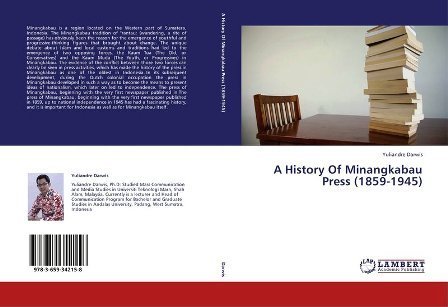 Judul buku : A History of Minangkabau Press (1859 1945)
Judul buku : A History of Minangkabau Press (1859 1945)
Penulis : Yuliandre Darwis
Penerbit : Saarbrucken, Germany: Lambert Academic Publishing
ISBN : 978-3-65934215-8
Cetakan : 1, 2013
Tebal : vii + 413 halaman [appendices; notes]
Peresensi : Suryadi
Berbicara tentang sejarah persuratkabaran di Indonesia, tentunya kita tidak bisa mengabaikan Sumatra Barat. Sejarah sudah mencatat bahwa pada tahun 1850-an kota Padang, bandar yang terpenting di Sumatra selama abad ke-19, telah memiliki surat kabar. Padang adalah kota utama di luar Jawa yang lebih awal menghadirkan tradisi persuratkabaran. (Koran pertama di Hindia Belanda adalah Bataviaasche Nouvelles yang terbit di Batavia tahun 1744).
Seperti dicatat oleh Gerard Termorshuizen dalam bukunya Journalisten en heethoofden: een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers, 1744-1905 (2001), bisnis persuratkabaran di Padang dimulai dengan terbitnya beberapa surat kabar berbahasa Belanda. Pionirnya adalah Sumatra Courant yang terbit di Padang tahun 1859 yang dipimpin oleh L.N.H.A. Chatelin. Lima tahun kemudian (1864) surat kabar berbahasa Melayu yang pertama diterbitkan di Padang, yaitu Bintang Timor. Pers berbahasa Melayu di Padang mulanya dirintis oleh beberapa orang Indo (yang terkenal di antaranya adalah Arnold Snackey), kemudian diikuti oleh orang Cina dan pribumi Minangkabau sendiri. Banyak di antara mereka yang juga berkerjasama dengan orang Eropa.
Seperti terefleksi dari judulnya, buku ini membahas sejarah pers Minangkabau. Buku ini aslinya adalah disertasi Yuliandre Darwis (dosen Universitas Andalas) yang dipertahankannya di Universiti Teknologi Mara, Malaysia, tahun 2011.
The History of Minangkabau Press terdiri dari 5 bab, di luar Introduction yang memaparkan persoalan kunci, signifikansi, ruang lingkup, dan metodologi yang digunakan dalam menyusunan buku ini.
Bab 1 mendeskripsikan sejarah dan budaya Minangkabau untuk memberikan konteks studi ini. Selanjutnya dalam Bab 2 penulis mendeskripsikan sejarah pergerakan Islam di Minangkabau. Yuliandre berargumen bahwa Islam movement di Minangkabau, sebagai efek dari Gerakan Paderi yang terjadi pada paroh pertama abad ke-19, merupakan salah satu faktor yang menggerakkan pers pribumi (vernacular press) di Minangkabau. Bab 3 membahas sejarah perkembangan pers di Minangkabau, sejak kehadiran surat kabar berbahasa Belanda di tahun 1850-an sampai 1945, ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya.
Bab 4 berfokus pada pers Islam di Minangkabau. Yuliandre membicarakan kekhasan pers Islam ini dan tokoh-tokoh pelopornya, seperti Hamka, Abdullah Ahmad, Zainuddin Labay El-Yunusi, dll. Bab ini juga membahas institusi sosial dan pendidikan yang didirikan oleh para pelopor pers Islam, seperti Adabiyah School, Sumatra Thawalib dan Al-Madrasah Al-Diniyah. Masih dalam bab ini, penulis juga membahas perdebatan-perdebatan dalam pers Islam itu, khususnya antara Soeloeh Melajoe dengan Al-Munir dan Al-Akhbar. Pembahasan dalam bab ini diakhiri dengan analisa wacana dalam Soeloeh Melajoe. Bab 5 merupakan kesimpulan dari seluruh pembicaraan dalam bab-bab sebelumnya.
Buku ini dilengkapi dengan dua lampiran sepanjang 106 halaman (hlm. 283-389) yang memuat foto-foto (dengan kualitas yang kurang bagus) beberapa edisi Soloeh Melajoe dan daftar nama 209 harian dan berkala yang terbit di Padang antara 1900-1942, yang hampir sepenuhnya dirujuk dari buku Ahmat Adam, Suara Minangkabau: Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah di Sumatra Barat (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2012 [menurut penulis di hlm. 293, buku ini terbit tahun 1995]). Deskripsi itu meliputi: nama penerbit dan pencetak, direktur, (chief) editor dan administrator, bahasa yang dipakai, tipe (aliran/misi/motto), harga, dan tempat penyimpanannya (storage) sekarang.
Harus saya akui dan kritik yang agak kritis seperti ini tak pernah saya lontarkan dalam meresensi puluhan buku sebelum ini bahwa buku ini memiliki banyak kelemahan. Mungkin harus saya mulai dulu dengan catatan terhadap penerbit(an)nya. Lambert Academic Publishing ternyata tidak melakukan pengeditan apa pun terhadap naskah buku ini sebelum diterbitkan. Banyak kesalahan dalam penulisan istilah (Inggris maupun Indonesia) dan ketidakcermatan dalam perujukan dan penulisan bibliografi. Bahkan untuk layout saja tampaknya penerbit ini banyak melakukan kesembronoan, sehingga dalam halaman Table of Contents saja sudah terlihat ketidakrapian di sana-sini. Menurut dugaan saya, baik penulis maupun penerbit tidak berkomunikasi dengan baik sebelumnya dalam rangka mempersiapkan naskah buku ini yang lebih rancak, rapi dan berkualitas.
Namun, hal yang lebih mendasar lagi adalah tentang isi buku ini sendiri. Tampaknya ruang lingkup buku ini terlalu lebar, sehingga akibatnya ia kehilangan fokus. Mungkin akan lebih baik jika seandainya penulis memokuskan perhatian pada pers Islam Minangkabau saja. Tujuan buku ini tampaknya memang begitu, sebagaimana dijelaskan dalam Significance of Study (hlm. 4), tapi objective itu diterjemahkan secara kurang konsisten dan terfokus dalam bab-bab selanjutnya.
Akibatnya, buku ini kurang berhasil menyajikan identifikasi yang menyeluruh mengenai eksistensi pers Islam di Minangkabau sampai tahun 1945. Konsep pers Islam itu sendiri tidak dibahas secara lebih mendalam. Jelas bahasa Arab atau Arab-Melayu (Jawi) tidak bisa dijadikan kriteria tunggal untuk menentukan apakah sebuah harian atau berkala termasuk pers Islam atau tidak. Dalam banyak pers Islam pun sering dibahas hal-hal yang bersifat sekuler. Istilah ‘Minangkabau press’ juga masih problematis karena rupanya di sini label etnisitas digunakan untuk merujuk aktivitas bisnis media cetak yang sebenarnya melibatkan entrepreneurs lintas etnis (orang Minang, Cina, Batak [seperti Dja Endar Moeda], Indo [seperti Arnold Snackey], dan orang Eropa).
Pembahasan mengenai tokoh-tokoh pelopor pers Islam (Bab 4) yang didahului oleh gambaran konteks sejarahnya (Bab 2) tidak dilengkapi dengan penelusuran ekstensif tentang harian-harian atau berkala-berkala Islam yang terbit di Minangkabau sepanjang dekade-dekade terakhir abad ke-19 sampai pertengahan pertama abad ke-20, yang tidak hanya yang ditemukan di kota-kota seperti Padang, Bukittinggi dan Padang Panjang, tapi juga di nagari-nagari seperti Maninjau, Matur, dll. Penulis juga tidak membahas lebih dalam berbagai penerbit dan percetakan yang mendukung pers Islam itu, seperti Zamzam, Tjerdas, Tsamaratoel Ichwan, Kahamij, Drukkerij Tandikat dan Poestaka Sa’adijah di Fort de Kock (Bukittinggi) dan Padang Panjang - untuk sekedar menyebut contoh. Tentu banyak hal yang bisa dibicarakan seputar penerbit/percetakan tersebut, baik saja dari segi personil yang terlibat, tapi juga dari segi pembiayaannya dan sistem pendistribusian produk-produknya, sebagaimana telah dibahas sedikit oleh Sudamoko dalam artikelnya, “Revisiting A Private Publishing House in the Indonesian Colonial Period: Penjiaran Ilmoe”, Indonesia and The Malay World 38(111), 2010: 181-216 mengenai penerbit Penjiaran Ilmoe di Bukittinggi.
Barangkali tidak maksimalnya capaian buku ini juga disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam mengakses sumber-sumber primer (bronnen), sebagaimana dapat dikesan dari References buku ini, terutama sumber-sumber primer yang tersimpan di luar negeri seperti di Leiden, Berkeley, dll.. Walau bagaimanapun, bagian akhir dari Bab 4 buku ini memberi pengetahuan tambahan kepada pembaca mengenai profil dan wacana-wacana keagamaan yang dominan yang pernah muncul dalam Soeloeh Melajoe serta ciri-ciri kebahasaan berkala ini. Kiranya bab ini cukup untuk sedikit membedakan buku ini dengan kajian-kajian terdahulu mengenai sejarah pers di Minangkabau.
Lepas dari berbagai kekurangan di sana sini, sebuah buku tetap memberi manfaat kepada pembacanya. Hal itu jelas berlaku pula untuk A History of Minangkabau Press. Paling tidak buku ini telah berhasil mengungkapkan beberapa aspek seputar pers Islam di Minangkabau sebelum zaman kemerdekaan. Penelitian tentang topik ini tentu dapat dilanjutkan oleh orang lain, atau diperdalam oleh Yuliandre sendiri untuk proyek post doktoral-nya.
Suryadi, Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Leiden, Belanda | Resensi ini diterbitkan di harian Padang Ekspres, Minggu, 9 Juni 2013
June 1, 2013
PANTUN MINANG: “BIOGRAFI HEROIK” LELAKI MINANGKABAU
Bagian terakhir dari dua tulisan
Urang Padang mandi ka pulau,
Putuih sianik paulehkan,
Anak dagang sakik di rantau,
Hujan di langik mamandikan.
Dalam bagian pertama tulisan ini (Padang Ekspres, 26-5-2013) telah digambarkan bagaimana bait-bait pantun Minang merepresentasikan keberangkatan calon perantau dari Ranah Bundo-nya dan suka-duka yang mereka hadapi dalam perjalanan menuju rantau. Pada bagian kedua ini akan dibicarakan pantun-pantun yang merefleksikan keadaan mereka di perantauan dan panggilan untuk menjenguk kampung halaman.
Banyak bait pantun Minangkabau merekam perasaan si perantau di rantau. Suka-duka hidup di rantau, yang tidak selalu berhasil menghatarkan mimpi-mimpi di perantau, bercampur baur dengan kenangan kepada kampung halaman.
Riak kehidupan di perantauan
Rantau digambarkan sebagai tempat yang sulit dan oleh karena itu perlu perjuangan dan keuletan untuk menaklukkannya. Kesuksesan hanya dapat diraih jika petuah ibu (mandeh) didengarkan, dan jika selama berada di rantau sifat rendah hati dan kerja keras dipakaikan. Namun, seiring dengan itu, suara-suara kerinduan kepada kampung halaman tempat ibu dan kekasih/ istri/tunangan ditinggalkan muncul dominan pantun. Banyak bait menggambarkan perasaan nelangsa hati si perantau dan sepinya hidup mereka karena ketiadaan famili di rantau orang. Sakit-senang dirasakan sendiri, tak ada orang yang membantu. Dalam keadaan seperti itu, suara rindu kepada ibu kerap muncul.
Simak umpamanya bait-bait berikut ini: ‘Tabang anggang di tapi danau / Inggok di rantiang dulang-dulang / Anak dagang sakik di rantau / Baritonyo sajo sampai pulang; Pincalang karam tantang pulau / Udang tajamua ateh batu /Anak dagang sakik di rantau / Urang manjanguak hinggo pintu’.
Dalam bai-bait lain dikatakan: ‘Hujanlah hari di Sipinang / Tampieh di kampung tabu / Manangih di rantau urang / Takana ranah kampuang ibu; Puyuah disangko unggeh pikau / Baranang-ranang di tapian / Mangaluah dagang di rantau / Takana padang pamainan; Barambuih angin di Kurinci / Asam pauh dari subarang / Awan bararak ditangisi / Badan jauah di rantau urang; Usah dirantak bungo tanjuang / Jatuah badarai bungo lado / Usah dikana mandeh kanduang / Jatuah badarai aia mato’.
Peluang untuk sukses dan gagal di rantau sama besarnya. Bagi yang tidak sukses, makin jauh rasanya kampung, seperti terefleksi dalam bait-bait berikut: ‘Kambang bapucuak pudiang geni / Kambang di puncak Gunung Ledang / Jangan diarok badan kami / Kami jauah di rantau urang; Kok didulang pandan bak kini / Kalikih babuah tido / Kok pulang badan bak kini / Bapitih sarimih tido; Urang manumbuak jolong gadang / Ayam nan makan jolong turun / Manangih di rantau urang / Ka pulang baameh balun’.
Kekhawatiran, kerinduan, dan harapan orang kampung kepada perantau, terutama yang diwakili oleh kaum wanita, juga direfleksikan dalam banyak bait, misalnya: ‘Ngilu gigi mamakan jambu / Dimakan duku ngilu pulo / Ingin hati andak batamu / Musim pabilo ka basuo; Tuan Katik manjalo udang / Dimalah biduak di latakan? / Sakik Ajo di rantau urang / Siapo manduduak managakan?; Kampia diganggam Ganto Sori / Barisi samuik salimbado / Kok ampia buliah lakeh dicari / Iko jauah antah dimano’.
Dalam bait ‘Bungo cimpago satu halai / Tumbuah di kubua Tuan Haji / Aia mato salamo carai / Kok sumua elok tampaik mandi’ yang memakai gaya hiperbola dapat dikesan kesedihan hati yang begitu mendalam dari si dia yang ditinggalkan.
Menjelang kampung
Dari pembacaan saya terhadap ratusan bait pantun yang terdapat dalam naskah-naskah schoolchriften Minangkabau koleksi Perpustakaan Universitas Leiden itu, tidak banyak bait yang menggambarkan kepulangan perantau Minangkabau ke kampung halaman. Seringkali kepulangan itu hanya sesuatu yang dijanjikan (sering dipakai kata ‘kok’, ‘jika’), misalnya dalam bait ini: ‘Lah masak buah kayu tulang / Makanan anak barau-barau / Kok untuang kumbali pulang / Tidak untuang mati di rantau’.
Antusiasme kepulangan si perantau ke kampung halaman sangat ditentukan oleh keberhasilan mereka di rantau. Apabila mereka berhasil, maka dorongan untuk pulang sangat besar karena mereka ingin memperlihatkan keberhasilan itu kepada sanak famili dan orang kampung mereka. Faktor ekonomi inilah yang antara lain mencirikan dua tipe merantau orang Minangkabau: ‘merantau pipit’ dan ‘merantau Cina’.
Namun demikian, dalam beberapa bait terkesan adanya rasa optimis: kampung halaman yang dirindukan akan dijelang; orang-orang tersayang yang ditinggalkan akan dikunjungi, misalnya dalam bait-bait ini: ‘Ka dulang padi anyo lai / Dibao urang Tujuah Koto / Ka pulang kami anyo lai / Mananti bulan di muko; Apo takilek di subarang / Rajo Amaik bapacu kudo /Bulan Puaso kami pulang /Adiak balimau kami tibo’.
Seperti telah dibahas dalam banyak publikasi ilmiah, sifat penting dari tradisi merantau etnis Minangkabau adalah keterkaitan emosi yang tinggi dengan kampung halaman mereka. Saya melihat hal ini terkait dengan faktor-faktor sosial budaya yang mendorong orang Minang merantau, yang kemudian juga mendorong mereka untuk memperlihatkan hasil perantauan mereka kepada orang kampung. Jika seorang Minang ‘dipaksa’ pergi merantau karena di rumah dianggap belum berguna (secara ekonomi), maka ketika ia berhasil di rantau, ia akan pulang (secara periodik) ke kampungnya untuk memperlihatkan keberhasilannya, guna menunjukkan bahwa kini ia sudah berguna (sudah menghasilkan kapital). Mungkin hal inilah yang menghadirkan unsur ‘heroik’ dalam sifat perantauan orang Minang, sebagaimana direpresentasikan dalam khazanah pantun mereka. Oleh sebab itu, logis jika mereka yang tidak berhasil di rantau malu untuk pulang ke kampung, karena perantauannya yang gagal itu tidak menimbulkan perubahan pada status dirinya (secara ekonomi).
Epilog
Pantun Minangkabau adalah salah satu dokumen sosial dan sejarah tempat kita dapat ‘membaca’ secara historis apa arti merantau bagi lelaki Minangkabau dan bagaimana budaya merantau itu mempengaruhi hidup mereka. Pantun-pantun tersebut dapat dianggap sebagai rekaman sahih yang mencatat perasaan kaum lelaki Minangkabau terhadap aktivitas merantau yang mereka lakoni. Melalui bait-bait pantun Minang kita dapat ‘membaca’ faktor-faktor yang menonjol yang melatarbelakangi dan mendorong lelaki Minang marantau, yaitu soal ekonomi dan harga diri. Walaupun tradisi marantau orang Minangkabau cenderung derubah mengikuti perjalanan zaman, hal-hal yang bersifat emosional kolektif mengenainya mungkin tak banyak berubah.
Di dalam pantun-pantun Minangkabau yang sudah dibahas terekam pula perasaan dikotomis dalam diri perantau: antara dorongan untuk meninggalkan kampung karena faktor ekonomi dan harga diri dengan kerinduan kepada kampung halaman sendiri apabila mereka sudah berada jauh di rantau. Keterkaitan yang kuat antara perantau dengan figur wanita (ibu, kekasih/tunangan/istri) yang ditinggalkan di kampung dalam banyak bait pantun tersebut sepertinya mengilatkan pentingnya peran wanita dalam sistem matrilineal Minangkabau. Sebaliknya, unsur ayah dan mamak tak begitu menonjol kelihatan.
Membaca pantun-pantun Minang klasik adalah membaca perjalanan hidup lelaki Minangkabau yang berada dalam tarik-menarik antara rantau dan kampung, antara ibu dan istri/kekasih/tunangan. Kiranya R.J. Chadwick benar: bahwa bait-bait pantun-pantun Minangkabau adalah heroic biography kaum lelaki Minangkabau.
Suryadi, Leiden University Institute for Area Studies, Belanda
* Esai ini dimuat di harian Padang Ekspres, Minggu, 2 Juni 2013
May 27, 2013
PANTUN MINANG: “BIOGRAFI HEROIK” LELAKI MINANGKABAU
Bagian pertama dari dua tulisan
Karatau madang di hulu,
Babuah babungo balun,
Marantau bujang daulu,
Di rumah baguno balun
Seperti halnya di banyak etnis lain, kaum lelaki Minangkabau memiliki posisi kultural sendiri dalam masyarakatnya. Salah satu ciri kultural yang melekat pada diri lelaki Minang, yang dengan demikian mempengaruhi kepribadian mereka, individual maupun sosial, adalah kebiasaan mereka untuk pergi merantau.
Merantau adalah salah satu elemen penting yang mencirikan etnis Minangkabau, khususnya kaum lelakinya, di samping dua elemen lainnya: Islam dan sistem kekerabatan matrilineal. Ketiga elemen itu memiliki hubungan sebab-akibat. Sandingan Islam dan matrilineal telah melahirkan ‘paradoks budaya’ (culturalparadox) - meminjam istilah Jeffrey Hadler (2008). Manifestasinya dapat dikesan pada pola-pola wirausaha perantau Minang, yang kebanyakan dilakoni oleh kaum lelakinya, sindrom-sindrom sosio-psikologis yang mereka alami (lihat: Gunawan Mitchell 1969, Tan Pariaman 1980), dan keterikatan mereka secara emosional dengan kampung halaman sendiri.
Esai ini membahas refleksi budaya merantau lelaki Minangkabau dalam pantun Minangkabau. Sebagaimana ditunjukkan oleh R.J. Chadwick (1986), sastra Minangkabau merupakan salah satu laman budaya (culturalsite) yang penting tempat kita dapat memahami masyarakatnya. Pantun adalah salah satu dokumen sosial yang melaluinya kita bisa melihat sejarah sosial Minangkabau di masa lampau.
Dalam esai ini saya coba mengidentifikasi bagaimana pantun Minang klasik merekam ‘prosesi’ merantau kaum lelaki Minangkabau. Sumber-sumber pertama (bronnen) untuk pembicaraan ini saya ambil dari koleksi naskah-naskah pantun Minangkabau yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Naskah-naskah itu kebanyakannya adalah schoolschriften yang ditulis pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (lihat: Van Ronkel 1921). Sebagian besar di antaranya sudah saya perkenalkan kepada pembaca harian ini melalui rubrik mingguan ‘Khazanah Pantun Minang’ (PadangEkspres, 7 November 2010 7 Oktober 2012).
Pantun Minangkabau pekat kiasannya. Sampiran dan isi dihubungkan oleh majas yang jauh lebih halus dan samar dibanding pantun Melayu, sehingga “sulitnya menafsirkan pantun Minangkabau terletak pada watak bahasa yang digunakan yang sangat samar dan susah dipahami” (Chadwick 1994:84). Itulah karakter bahasa literer Minangkabau yang dipakaikan dalam tradisi bersilat lidah (tongue fu) seperti pasambahan (Toorn 1879; Hasselt 1883; Eerde 1879), pertunjukan indang (Kartomi 1986, Suryadi 1994; Ediwar 2007), dll..
Dalam lebih 1600 bait pantun yang saya periksa, tergambar ‘biografi heroik’ lelaki Minangkabau. Pantun-pantun itu merekam perjalanan hidup mereka yang dipengaruhi oleh kampung dan rantau. Istilah ‘biografi heroik’ (heroicbiography), saya pinjam dari R.J. Chadwick dalam artikelnya “Unconsummated Metaphor in Minangkabau Pantun“, Indonesia Circle 62: 83-113 (pada hlm.87). Karena pertimbangan terbatasnya ruang, contoh-contoh bait untuk ilustrasi dalam esai ini sangat dibatasi jumlahnya.
Bertolak ke Rantau
Pantun Minang merekam gerak perjalanan perantau dan perasaan mereka, sejak berangkat dari kampung sampai di berada rantau, seperti terefleksi dalam bait ini: ‘Sitapuang tangah halaman / Ambiak untuak kiliran taji / Tingga kampuang tingga halaman / Tingga tapian tampaik mandi; Manggih hutan tumbuah di korong / Diambiak palantiang pauh / Rilakan kato nan tadorong / Kami kapai bajalan jauah’.
Melalui kutipan bait-bait di atas kita dapat membaca perasaan hati perantau kepada kampung halaman dan orang-orang yang dicintai (lebih menonjol: ibu dan kekasih/tunangan/istri) yang ditinggalkan. Hal itu juga dapat dikesan dalambait-baitberikutini: ‘Kok nasi dimakan patang / Karak dimakan pagi hari / Kok jadi bajalan panjang / Antah tidak babaliak lai; Silayok namonyo kumbang / Tabang jo anak api-api / Ilang lanyouk jangan ditumang / Namonyo anak laki-laki; Ditatak daun si kalawi / Patah ditimpo alang tabang / Tinggalah Adiak di nagari / Denai dibao untuang malang; Karuntuang bari batali / Dijinjiang katapi pulau / Kok untung baliak kumbali / Kok malang hilang di rantau; Tinggi mambacuik lah kau rabuang / Isuak nak kami tabang pulo/ Tingga tacanguik lah kau kampuang / Isuak nak kami jalang pulo’.
Banyak bait merefleksikan faktor-faktor yang mendorong laku merantau itu. Faktor ekonomi cukup menonjol, seperti terkilat dalam bait-bait berikut: ‘Anak buayo dalam tabek / Mati ditubo rang Sicincin / Sadang nan kayo lai larek / Kununlah kami suka miskin; Hari paneh langgam baribuik / Kukuak ayam badarai-darai / Kok tak santano di suka iduik / Satapak tidak amuah carai ; Marapalam di laman tansi / Tampak nan dari kantua urang / Bapilin asok kapa api / Manjampuik bansaik ka tabuang’.
Melalui banyak bait pantun pembaca dapat mengidentifikasi bahwa pihak yang pergi merantau adalah kaum laki-laki (hal ini benar adanya, setidaknya sampai awal abad ke-20), dan kaum perempuan (di)tinggal(kan) di kampung dengan perasaan gamang. Beberapa bait berikut ini merefleksikan perasaan hati mereka: ‘Layang-layang rang Limo Koto / Inggok di rantiang aua duri / Kok bajalan Ajo di siko / Rantau nan mano ka Ajo huni?; Ambacang di Bukiktinggi / Jatuah sabuah ka subaliak / Bajalan Ajo di bulan kini / Musim pabilo ka babaliak?; Talang di rimbo padi Jambi / Padi sipuluik ditugakan / Alangka ibo hati kami / Kami manuruik ditinggakan; Pancaringek di tapi aia / Lah mati mangko babuah / Ingek-ingek Tuan balayia / Lauik sati rantau batuah’.
Perpisahan selalu menimbulkan kesedihan. Dalam bait-bait berikut dapat dikesan betapa berat perasaan hati kedua pihak yang berpisah: ‘Balayia babelok-belok / Balabuah tantang nan tanang / Nan pai hati tak elok / Nan tingga hati tak sanang; Putiah pucuak e limau kapeh / Tampak nan dari kida jalan / Putiah mato e nan malapeh / Ibo hati e nan bajalan’.
Diperjalanan
Perjalanan menuju rantau, yang digambarkan sebagai sebuah pelayaran yang penuh bahaya, direfleksikan secara heroik: rasa gamang dalam hati berpirau dengan tekad bulat. Laut dan kapal mendominasi penggambaran suka-duka yang dialami oleh si perantau di perjalanan. Ini merupakan refleksi kenyataan akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 saat moda transportasi masih didominasi oleh teknologi perkapalan.
Berbagai tantangan yang dihadapi di jalan sering disimbolkan dengan angin / badai, ombak, karang dan bajak laut, seperti terefleksi dalam bait-bait berikut: ‘Ayam gadang si taduang gombak / Disabuang tangah duo tahia / Tujuah kali dilamun ombak / Bagantuang di tonggak layia; Baruang-baruang urang Pariaman / Lah sudah takarang kasau / Taguah-taguah pagang padoman / Angin ka turun jo langkisau; Taluak baliku Gunuang Padang / Tanamlah sapek pajelokan / Angin basiru biduak datang / Sumbarang tapek kito layiakan; Di mano hilang kalakati / Di bawah lapiak katiduran / Di mano hilang laki-laki / Di taluak rantau palayaran’.
Namun, si anak dagang berpantang kembali. Tekad bulat sudah tertanam dalam hati: rantau harus dapat dicapai walau berbagai halangan datang menghambat selama dalam perjalanan. Simaklah bait-bait berikut ini: ‘Urang Nareh bajua kamba / Pambayia utang ka Gumpani / Angin dareh timbangi kapa / Layia nan jangan dikurangi; Urang Padang makan antimun / Dimakan di lua koto / Jangan mamang angin ka turun / Padoman ado pado kito; Urang Aceh bajua kain / Di rumpuik dibantangkannyo / Duo baleh galombang angin / Tatungkuik dipantangkannyo; Tibarau di umbuik gajah / Batang nibuang paga tabeknyo / Parahu Bajau dikutuak Allah / Pelang nan lalu diambeknyo’.
Sementara itu ibu (figur yang penting dalam sistem matrilineal Minangkabau) yang ditinggalkan di kampung mengekpresikan kekhawatirannya, seperti terkilat dalam bait-bait berikut: ‘Panjek karambia parak tingga / Kaubek damam kasibaran / Tapakiak mandeh nan tingga / Di anak tidak kadangaran; Lapeh nan dari Karang Pauah / Andak manjalang Pasa Baru / Anak bajalan makin jauah / Mandeh di rumah Allah nan tau’.
Dan ‘tambatan hati’ (kekasih/tunangan/istri) yang meriang tubuhnya ditinggalkan kekasih mengungkapkan perasaan hati mereka, seperti terefleksi dalam bait-bait berikut: ‘Badatak patah dahan kasumbo / Ambiak paapik kopi daun / Kok bacarai Ambo jo Ajo / Sahari raso duo tahun; Layang-layang jatuah badarai / Dipupuik angin timua Sorkam / Sadang sayang badan bacarai / Nasi dimakan raso sakam; Babiduak tantang Maninjau / Bingkarak samo dikayuahkan / Ajo di baliak gunuang hijau / Taragak samo dikaluahkan’.
Akhirnya, setelah berbagai halangan di jalan berhasil diatasi, tanah rantau berhasil juga dicapai, seperti terefleksi dalam bait-bait ini: ‘Langgundi di tapi aia / Lah rabah dipanjek karo / Jurumudi rampehi layia / Kito lah tibo di kualo; Ayam putiah tabang ka lurah / Tibo di lurah makan padi / Biduak upiah pangayuah bilah / Itu nan sampai di Batawi’.
Awal petualangan si lelaki Minang di rantau baru saja dimulai. *** (bersambung).
* Esai ini dimuat di harian Padang Ekspres, Minggu, 26 Mei 2013
May 26, 2013
Minang Saisuak #136 - Pasar Batusangkar (c. 1895)
Karena struktur geopolitiknya yang khas, setiap nagari di Minangkabau memiliki pasar (balai/pakan). Namun dalam perkembangannya, banyak pasar nagari akhirnya mati. Nagari-nagari yang letaknya strategis, pasarnya akan berkembang. Kota-kota penting di Sumatera Barat di masa sekarang, seperti Bukittinggi, Payakumbuh, Solok, dan lain-lain, pada awalnya adalah pasar-pasar (pakan-pakan) nagari.
Kali ini rubrik ‘Minang Saisuak’ menurunkan sebuah foto klasik yang menggambarkan suasana pasar di Fort van der Capellen yang menjadi cikal-bakal kota Batusangkar sekarang. “Markt in Fort van der Capellen, Padangse Bovenlanden, Sumatra`s Westkust” (pasar di Fort van der Capellen [sekarang: Batusangkar], Padang Darat, Sumatra Barat), demikian judul foto yang berukuran 20 x 27 cm. ini. Foto ini dibuat sekitar 1895. Mat kodak-nya tidak diketahui.
Terlihat suasana keramaian di pasar ini. Di tengah pasar ini tumbuh sepokok beringin yang rindang. Itulah salah satu ciri khas pasar di Minangkabau pada masa lampau, sebagaimana disaksikan oleh pastor M. Buys di darek tahun 1870-an (lih: M. Buys, Twee jaren op Sumatra’s Westkust, Amsterdam: A. Akkeringa, 1886:60) dan catatan J.L. van der Toorn, ‘Dari hal pekan di Minangkabau’ (1898:44). Generasi sebelum perang mungkin masih mengingat adanya pohon beringin di tengah pasar di daerah masing-masing, tempat para “parewa balai” bermain sipak rago setelah pasar usai di sore hari.
Di samping melindungi manusia (pengunjung pasar) dari terik sinar matahari dengan daunnya yang rindang-rimbun, pohon beringin juga memiliki makna simbolis dan mistis dalam banyak kebudayaan lokal di Indonesia. Di Minangkabau, misalnya, kita semua sudah tahu bahwa beringin adalah simbol pemimpin yang kuat dan pengayom masyarakat: ‘baringin di tangah koto, ureknyo tampaik baselo, batangnyo tampaik basanda, daunnyo tampaik balinduang’ ,.., dst.).
Pasar di suatu nagari diadakan pada hari tertentu. Itulah yang disebut sebagai hari balai atau hari pakan. Masing-masing nagari mempunyai hari pakan yang berbeda. Oleh karena itu pasar-pasar mingguan tersebut sering juga disebut menurut hari pekannya, misalnya Pakan Kamih, Pakan Salasa, Pakan Rabaa, dll. Sistem ini telah melahirkan kelompok pedagang keliling yang melakukan aktivitas manggaleh babelok (berdagang keliling). Mereka menggalas dari pasar ke pasar, dari Senin hingga Seninnya lagi. Hari pasar dan suasana di pasar di nagari-nagari itu sering dinukilkan dalam teks-teks lisan Minangkabau seperti kaba dan pantun.
Sebuah pasar mingguan di Minangkabau juga mendapat ciri khas karena satu jenis makanan yang enak yang biasa dijual di pasar itu, misalnya ketupat enak di pasar Pitalah, ketupat gulai tunjang di pasar Kuraitaji, katupek sasak di pasar Sicincin, atau gulai kambing yang enak di pasar Pakandangan. Ini adalah unsur budaya Minangkabau, dalam konteks ini budaya kuliner, yang tentu menarik pula didokumentasikan. Apakah makanan yang menjadi ciri khas pasar Batusangkar?
Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 26 Mei 2013
May 19, 2013
Minang Saisuak #135 - Kingmaker Koto Gadang: Abdul Gani Rajo Mangkuto
Sudah dua kali rubrik ‘Minang Saisuak’ menurunkan profil Abdul Gani Rajo Mangkuto. Yang pertama di Singgalang edisi Minggu, 27 Maret 2011 ketika beliau sudah berusia agak lanjut dan sudah bergelar haji. Yang kedua di Singgalang edisi Minggu, 29 April 2012 ketika beliau masih berusia lebih muda dengan pakaian yang mirip sekali dengan yang terlihat di foto ini, tapi beliau berfoto sendiri dan dalam posisi berdiri.
Foto Abdul Gani Rajo Mangkuto yang disajikan kali ini tampaknya diambil pada saat yang sama dengan fotonya yang kami turunkan dalam edisi 29 April 2012 itu. “Radja Mangkoeto (links) van Kotagedang bij Fort de Kock met zijn zoon” ([Abdul Gani] Rajo Mangkuto (kiri) dari Koto Gadang dekat Fort de Kock dengan anak lelakinya), demikian judul foto ini. Foto ini (10,5 x 6 cm.) dibuat sekitar tahun 1870 oleh Woodbury & Page, sebuah perusahaan fotografi yang terkenal di Jawa pada abad ke-19.
Tidak disebutkan siapa nama anak Abdul Gani yang terlihat di foto ini. Yang jelas kingmaker Koto Gadang di abad ke-19 ini memiliki keluarga besar dan anggota famili yang banyak yang sebagian besar di antaranya menjadi orang mamacik di Sumatra Barat pada masa itu. Kiranya tidak perlu kami sajikan lagi secara detil riwayat hidup Rajo Mangkuto ini yang lahir di Koto Gadang tahun 1817 dan meninggal di Koto Gadang tgl. 29 Januari 1907. Pembaca dipersilakan merujuk kembali kepada dua rubrik ‘Minang Saisuak’ yang telah disebutkan di atas tadi yang bervsi onlinenya dapat dilihat di http://niadilova. blogdetik.com dan http://niadilova.blogdetik.com/index.php/archives/ 934.
Bertelekan (basitakan) di meja adalah salah satu gaya berfoto para bangsawan pribumi di abad ke-19 (lihat:Mikihiro Moriyama, 2005). Namun biasanya jika yang berfoto adalah intelektual, ada buku di atas meja itu yang ditekan dengan telapak tangannya, penanda keintelektualannya. Dalam foto Abdul Gani ini (dan juga foto-foto yang lain) tidak ada buku tampak di meja. Mungkin ini menunjukkan bahwa orang kaya Koto Gadang ini adalah seorang pengusaha, bukan intelektual. Foto, sebagaimana halnya media yang lain, merekam semangat zamannya. Gaya pakaian dua orang terkemuka Koto Gadang di abad ke-19 ini tampaknya merefleksikan posisi sosialnya sebagai bangsawan pribumi yang sampai batas tertentu sudah dipengaruhi pula oleh budaya Belanda.
Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto:KITLV Leiden) | Singgalang, Minggu, 19 Mei 2013
May 13, 2013
Sastra, Etnisitas, Agama dan Kebangsaan
Kesusastraan Indonesia sudah lama berperan sebagai sarana bagi penyemaian semangat kebangsaan. Di zaman kolonial, karya sastra telah ikut memberi andil dalam melahirkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang akhirnya berhasil mengusir penjajah. Para founding fathers Republik Indonesia umumnya adalah intelektual pribumi yang memperoleh semangat anti penjajahan lewat beragam bacaan sastra. Para penentang gigih kolonialisme itu adalah pelahap teks-teks sastra yang kebanyakan berasal dari khazanah sastra Eropa. Sebagian bahkan juga menulis karya-karya sastra tempat mereka memijahkan dan menggelorakan semangat nasionalisme kaum bangsanya guna membebaskan diri dari belenggu penjajahan.
Melani Budianta dalam artikelnya “Diverse voices: Indonesian literature and nation-building” (2007:57) mengatakan bahwa proses nation-building dalam wacana sastra tidak bersifat linear dan singular yang cenderung membawa masyarakat kesatu entitas politik yang bersifat tunggal dan seragam. Sebaliknya, ia menyediakan ruang untuk diskusi dan dialog yang terus-menerus guna memperkaya dan mematangkan konsepsi dan perasaan kebangsaan itu.
Dalam konteks sejarah sastra Indonesia modern, dua aspek lokalitas yang sering di dekonstruksi dan direpresentasikan dalam teks sastra untuk membina perasaan kebangsaan itu adalah hubungan antar etnis dan antar agama. Namun, harus diakui bahwa sampai sekarang belum banyak sastrawan Indonesia yang secara sadar dan dengan visi yang kuat mencoba menggarap kedua elemen ini untuk mendialogkan gagasan kebangsaan dengan khalayak pembaca.
Jika kita menengok kemasa akhir zaman kolonial, usaha untuk membebaskan diri dari eksklusivisme etnisitas guna mematangkan semangat keindonesiaan itu telah dirintis oleh beberapa pengarang, khususnya yang berasal dari latar belakang budaya Minangkabau. Karya-karya mereka mengusung cita-cita keindonesiaan yang member ruang bagi penguatan dan pemesraan hubungan antar etnis dan antar agama dalam semangat pluralitas, seperti antara lain terefleksi dalam judul roman karya S. Hardjosoemarto dan Aman Dt. Madjoindo, Rusmala Dewi: Pertemuan Jawa dan Andalas (1932).
Pembinaan rasa kebangsaan dari perspektif relasi antar etnis itu sering digambarkan melalui hubungan perkawinan, seperti dapat dikesan melalui pasangan Nurdin (Minangkabau) dan Rukmini (Sunda) dalam Darah Muda oleh Djamaluddin Adinegoro (1927) dan Rustam (Minangkabau) dan Dirsina (Sunda) dalam Asmara Jaya (1928) yang juga merupakan karya Adinegoro. Nur Sutan Iskandar juga menggarap tema ini melalui tokoh Amiruddin (Minangkabau) dan Astiah (Jawa) dalam Cinta Tanah Air (1944), sebuah roman berlatar perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda.
Hamka menggugah keindonesiaan khalayak pembaca melalui kisah cinta dan perkawinan yang tragis antara tokoh Poniem (Jawa) dan Leman (Minangkabau) dalam Merantau ke Deli (1940). Lewat novel ini Hamka tidak saja mengeritik adat Minangkabau, tetapi juga berusaha memperkenalkan kemungkinan membina Indonesia baru melalui perkawinan antar etnis. Hamka kembali mengetengahkan tema ini dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk (terbit pertama kali dalam bentuk feuilleton dalam berkala Pedoman Masjarakat di Medan, 1938). Dalam novel tersebut Hamka menggayutkan tema ini melalui tokoh Hayati (Minangkabau) dan Zainuddin, pemuda Bugis yang berayah Minangkabau dan beribu Bugis (Menurut sistem mantrilineal Minangkabau, Zainuddin adalah orang Bugis, bukan orang Minangkabau; lihat Kato 1982).
Menarik untuk dicatat bahwa narasi karya-karya Nur Sutan Iskandar dan Adinegoro yang disebutkan di atas menghadirkan perspektif yang berbeda dengan karya-karya Hamka. Dalam karya-karya Nur Sutan Iskandar dan Adinegoro cerita berakhir dengan happyending: tokoh-tokohnya yang berbeda etnis hidup berbahagia. Pemberontakan mereka terhadap adat etnis masing-masing berhasil. Hal sebaliknya terjadi dalam karya-karya Hamka: cerita berakhir dengan sadending. Pasangan Leman-Poniem dalam Merantau ke Deli dan pasangan Zainuddin - Hayati dalam Tenggelamnya Kapal van der Wijck mengalami nasib tragis: perkawinan yang mereka cita-citakan (di)gagal(kan). Pemberontakan mereka terhadap adat etnis masing-masing gagal.
Keindonesiaan
Menurut saya, ini siratan bahwa keindonesiaan yang bhinneka dalam masyarakat Indonesia yang begitu heterogen dari segi budaya dan agama masih harus terus dipupuk dan didewasakan. Lepas dari gerakan romantisme yang menjadi trend dalam dunia sastra pada zaman itu, karya-karya di atas menyiratkan betapa masih diperlukan perjuangan berat untuk mendewasakan bangsa Indonesia. Sekat-sekat etnisitas yang eksklusif harus dibuka tanpa harus menimbulkan chaos politik.
Nur Sutan Iskandar (Maninjau, 3/11/1893 - Jakarta, 28/11/1975), Adi Negoro (Talawi, 14/08/1904 - Jakarta, 8/01/1967) dan Hamka (Maninjau, 17/02/1908 - Jakarta, 24/07/1981) adalah tiga sastrawan Indonesia awal yang menganut paham terbuka. Primordialisme etnisitas mereka mencair karena sering bersentuhan dengan berbagai kebudayaan lain yang dimungkinkan oleh budaya merantau etnis Minangkabau, sebuah pretext bagi hadirnya kesadaran keindonesiaan yang lebih jelas dalam karya-karya mereka. Dalam bukunya, Kembali dari Perlawatan ke Europa, Djilid I. (1930:5), Adinegoro menulis: “Kalau anak-anak moeda angkatan sekarang dan angkatan jang akan tiba, berladjar memandang tanah airnja selebar Indonesia Raja, tidaklah akan dapat ganggoean tetek bengek kalau ia hendak merantau ketanah seberang, karena tanah seberang itoe, baik Soematra, baik Borneo, baik Selebes atau Nieuw Guinea, ialah tanah airnja semata-mata, bangsa-bangsa jang diam diatasnja tidak lagi akan disangkanja orang asing, melainkan saudaranja”.
Hubungan perkawinan antar agama juga belum banyak dieksplorasi oleh sastrawan Indonesia. Contoh dari sedikit novel yang membahas tema ini adalah Orang Buangankarya Harijadi S. Hartowardojo (1971; pertama kali terbit tahun 1967 dengan judul Munafik) yang menampilkan tokoh Tantri (Islam) dan Hiang Nio (Khatolik). Demikian juga halnya novel Keluarga Permana karya Ramadhan K.H. (1978) yang menampilkan tokoh Ida (Islam) dan Sumarto (Khatolik).
Selama Zaman Orde Baru (1967-1998) teks-teks sastra Indonesia sepi dari tema hubungan antar agama karena kaum sastrawan terkena sindrom ranjau SARA. Dewasa ini makin banyak novel-novel Indonesia yang menampilkan tokoh-tokoh dari beragam etnis dan agama, satu aspek struktur yang membedakannya dengan novel-novel tahun 1980-an dan 90-an. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam Saman karya Ayu Utami (1998) dan 1998 karya Ratna Indraswari Ibrahim (2012) - untuk sekedar menyebut contoh. Namun, keberagaman latar belakang etnis dan agama tokoh-tokohnya itu belum menjadi isu sentral dan tematik dalam narasi novel-novel tersebut sehingga kontribusinya tidak begitu signifikan dalam rangka dialog literer seputar gagasan-gagasan mengenai kebangsaan.
Kaum sastrawan khususnya dan seniman Indonesia pada umumnya seyogianya terus berusaha mengakomodasikan gagasan-gagasan mengenai kebangsaan dalam karya-karya mereka. Harus diakui usaha ini memang tidak mudah, sebab etnisitas dan religiositas adalah dua elemen yang inheren dan sensitive dalam diri mayoritas rakyat Indonesia. Kaum seniman harus cerdik, halus, dan ekstra hati-hati mengolah kedua elemen budaya ini untuk mendewasakan bangsanya. Jika tidak, alih-alih memberikan pencerahan, mereka malah bisa dituduh sebagai agen penyebar ideology asing dan pengacau sebuah etnis, seperti yang baru-baru ini dituduhkan kepada HanungBramantyo, sutradara film Cintatapi Beda.
Suryadi, Dosen Studi Indonesia di Leiden University Institute for Area Studies, Leiden, Belanda | Kompas, Minggu 12 Mei 2013, Hlm. 20
May 12, 2013
Minang Saisuak #134 - Perkampungan Cina di Padangpanjang
Migrasi orang Cina ke Minangkabau tidak lepas dari dunia perdagangan. Orang Cina dan dunia perdagangan ibarat lepat dengan daun. Di kalangan orang Indonesia sendiri ada mitos bahwa tanpa orang Cina sebuah kota tidak akan bisa berkembang.
Kedatangan orang Cina di Sumatera Barat sama tuanya dengan pembentukan kota-kota pantai di rantau barat Minangkabau. Buku Erniwati Asap hio di Ranah Minang: komunitas Tionghoa di Sumatra Barat (Yogyakarta: Penerbit Ombak dan Yayasan Nabil, 2007) mengungkapkan sejarah komunitas Tionghowa - sebutan untuk Cina pendatang di Indonesia - di Sumatera Barat. Namun, banyak hal yang belum digali dari sejarah kedatangan orang Cina di Ranah Minang.
Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan satu kodak klasik perkampungan orang Cina di Padangpanjang. “Straatgezicht in de Chinese wijk van Padangpandjang” (Pemandangan jalan di perkampungan Cina di Padangpanjang), demikian judul foto yang berukuran 10,2 x 12, 7 cm. ini. Foto ini dibuat sekitar 1895 atau mungkin lebih awal. Tidak ada keterangan siapa mat kodak-nya. Di latar belakang tampak perbukitan, mungkin kawasan Bukit Tui.
Belum ada kajian yang mendalam tentang sejarah kedatangan orang Cina di Padangpanjang. Ini kesempatan bagi mahasiswa (pintar) dari UNAND dan UNP untuk menelitinya. Kedatangan orang Cina di Padangpanjang didorong oleh peran baru yang dimainkan oleh kota itu sebagai kota transit perdagangan antara darek dan rantau barat Minangkabau pada pertengahan abad ke-19. Hasil bumi dan barang-barang yang diproduksi di darek ditumpuk dulu di Padangpanjang sebelum diangkut ke kota-kota pantai seperti Padang dan Pariaman. Begitu juga sebaliknya: Padangpanjang menjadi tempat menumpuk barang-barang yang diproduksi di daerah pantai seperti ikan asin, minyak kelapa, dan garam, sebelum didistribusikan ke kota-kota lain di darek. Hal diceritakan oleh Muhammad Saleh Dt. Urang Kayo Basa, pedagang besar Pariaman di abad ke-19, dalam otobiografinya, Riwajat Hidoep dan Perasaian Saja (1914). Pembukaan jalan Lembah Anai yang kemudian disusul dengan pembukaan jalur kereta api dari darek ke Padang pada 1890-an makin membuat Padangpanjang maju dan menjadi titik vital perdagangan di pinggang Bukit Barisan.
Seperti di kota-kota lainnya di Indonesia, orang Cina berperan penting dalam pemribumian teknologi Barat (lihat misalnya Karen Strassler, 2010). Di Padang Panjang mereka juga aktif dalam bisnis ini, seperti fotografi, barang-barang elektronik, perbioskopan, dan lain-lain. Sekarang entah berapa banyak orang Cina yang masih tinggal di Padangpanjang. Yang jelas, kawasan Pecinan, dengan kontruksi fisik dan suasananya yang khas, selalu menjadi tempat yang menarik dan menjadi daya tarik tertentu bagi-kota-kota di dunia. Ia merupakan aset pariwisata sebuah kota.
Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 12 Mei 2013
May 6, 2013
TRANSFORMASI FUNGSI DAN MAKNA HUTAN SIBERUT
 Judul buku : Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi
Judul buku : Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi
Penulis : Darmanto dan Abidah B. Setyowati
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia dan UNESCO
Cetakan : 1, Oktober 2012
Tebal : xxxvi + 458 halaman
Peresensi : Suryadi, Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Leiden, Belanda
Dalam wacana keindonesiaan kita yang hiruk-pikuk oleh euforia politik perkotaan, berita mengenai korupsi, pertelingkahan antara berbagai ’sekte’ agama dalam mengklaim siapa di antara mereka yang paling tahu tentang Tuhan dan yang paling berhak menjadi ahli sorga di akhirat nanti, dan mental xenosentrik yang sudah mewabah dalam semua lapisan sosial masyarakat, nama Siberut mungkin berada di tempat marginal.
Fenomena ini tidaklah aneh, mengingat negara sendiri cenderung mengembangkan pola pembangunan bangsa yang lebih memperhatikan pusat dan oleh karenanya sering mengabaikan wilayah-wilayah pinggiran seperti Siberut, walau sebenarnya dari segi sumber daya alam kontribusi wilayah-wilayah pinggiran itu sangatlah besar.
Berebut Hutan Siberut mungkin dapat mengingatkan kita kembali kepada pulau luar di lepas pantai barat Sumatera yang lebih dikenal oleh para penantang ombak besar dari mancanegara itu. Buku ini merupakan rekaman dinamika sosial masyarakat adat di Pulau Siberut sejak 50 tahun terakhir. Dalam 10 bab buku ini, kedua penulis, yang merupakan aktifis lingkungan yang lama bekerja di Siberut, menggambarkan secara kronologis ’sejarah akses dan kontrol [terhadap] hutan siberut’ (h.23).
Bab 1 memaparkan posisi teoretis buku ini yang berangkat dari perspektif politik ekologi dengan orientasi untuk mengidentifikasi pentingnya peran institusi dan relasi sosial dalam dinamika sosial politik dan ekonomi yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam (h.19). Selanjutnya, dalam Bab 2 penulis mendeskripsikan kondisi geografis dan geologi Pulau Siberut serta penduduknya yang rupanya bukanlah sebuah entitas tunggal. Bab 3 menjelaskan hubungan orang Siberut dengan alam lingkungannya, khususnya hutan, sebelum datangnya intervensi politik, ekonomi, dan budaya dari orang-orang ‘tanah tepi’ (istilah orang Mentawai untuk penduduk Sumatera) pada dekade 1970-an.
Bab 4 memaparkan hutan Siberut dalam incaran ‘kekuasaan dari luar’. Tahun 1970-an Rezim Orde Baru mulai memberikan konsesi kepada kapitalis kota untuk menggarap hutan-hutan Pulau Siberut. Siberut kemudian menjadi salah satu pulau terluar Indonesia yang menjadi target garapan kelompok penguasa yang berkolaborasi dengan pengusaha dan para pemburu uang dari ‘tanah tepi’, baik mereka yang berkuasa di Padang maupun di Jakarta.
Seperti sudah sama kita ketahui, pemberian konsesi itu menimbulkan dampak sosial dan ekologis: ekosistem pulau Siberut terancam rusak. Tekanan-tekanan dari kalangan akademisi, LSM (nasional dan internasional) serta berbagai pihak lainnya yang peduli pada kelestarian ekologi dan budaya masyarakat adat di Siberut telah memaksa pemerintah menghentikan konsesi penebangan hutan di Siberut pada 1993. Namun, setelah Orde Baru jatuh beberapa pengusaha dari Padang dan Jakarta mendapat konsesi lagi untuk mengekploitasi hutan Siberut. Kali ini, sebagai efek dari regionalisasi politik zaman Reformasi, izin-izin pengekploitasian hutan Siberut itu dikeluarkan oleh Bupati. Dalam bab ini pula didekripsikan interaksi orang Siberut dengan pasar produk hutan global.
Silang pendapat di antara berbagai unsur pemerintahan dan intelektual terhadap ekploitasi hutan Siberut didisekrisikan dalam Bab 5. Pada titik ini muncullah gerakan konservasi yang wacananya kemudian meluas ke tingkat nasional dan internasional. Berbagai LSM dalam negeri menjadikan isu Siberut sebagai proyek mereka. Begitu juga beberapa organisasi internasional seperti WWF dan UNESCO. Upaya-upaya konservasi difokuskan pada dua aspek: menjaga kekayaan spesies endemik kepulauan Mentawai dan menjaga keaslian kebudayaan penduduk aslinya.
Bab 6 menjelaskan munculnya kesadaran kolektif baru penduduk asli Siberut. Kedua penulis berpendapat bahwa munculnya kesadaran identitas baru itu dipantik oleh intervensi orang luar tadi (baik dalam artian privat maupun negara). Gerakan-gerakan ini didampingi oleh berbagai LSM. Regionalisme politik yang terjadi di Indonesia menyusul jatuhnya Rezim Orde Baru telah memunculkan isu-isu yang lebih santer mengenai hak-hak masyarakat adat yang bersambut dengan kemunculan wacana indigenous people di tingkat global di mana banyak organisasi-organisasi non pemerintah yang memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal yang terpinggirkan oleh kekuasaan negara, modernisasi, dan intervensi kapitalisme global.
Bab 7 menguji asumsi-asumsi kebijakan desentralisasi melalui analisa tentang tatakelola hutan di Siberut setelah terbentuknya Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 1999. Penulis menggambarkan percaturan antar berbagai pihak dalam konteks politik lokal dalam memanfaatkan hutan untuk ‘pembangunan’ masyarakat. Bersamaan dengan itu transformasi identitas tanah bagi orang Mentawai sendiri tentu terus berlanjut, seiring dengan makin dalamnya penetrasi negara, misalnya melalui kebijakan-kebijakan agraria dan lain sebagainya.
Bab 8 memaparkan gerakan-gerakan masyarakat lokal di Siberut dalam menuntut klaim kepemilikan atas hutan dan tanah. Penulis mengatakan bahwa dalam konteks ini orang Siberut menggunakan wacana adat. Dalam memperjuangkan tuntutan ini mereka juga bekerjasama dengan aktivis-aktivis pendamping dari luar, baik yang berasal dari LSM maupun organisasi-organisasi lainnya. Namun kurang jelas bagaimana fungsi tradisi lisan (oral tradition) dalam konteks ini, terutama tentang cerita-cerita keluarga milik kelompok-kelompok kekerabatan (kin groups) di Siberut dalam menentukan klaim-klaim mereka terhadap kepemilikan tanah. Juniator Tulius dalam disertasinya, Family Stories: Oral Tradition, Memories of the Past, and Contemporary Conflict over Land in Mentawai - Indonesia (Leiden University, 2012), menunjukkan pentingnya cerita-cerita keluarga tersebut dalam menentukan klaim atas tanah/hutan di kalangan kelompok-kelompok kekerabatan penduduk asli Kepulauan Mentawai, dan rupanya cerita-cerita itu juga berperan penting dalam penyelesaian konflik-konflik yang menyangkut klaim atas tanah di antara kelompok-kelompok kekerabatan itu sendiri.
Dinamika internal di kalangan penduduk Siberut sendiri dalam menyikapi berbagai wacana (ekonomi, politik, kekuasaan) mengenai hutan dibahas dalam Bab 9. Penulis menggambarkan agenda-agenda lokal yang menonjol seputar isu ini dan resistensi terhadap komponen-komponen dari luar yang ditunjukkan oleh masyarakat Siberut sendiri. Bab penutup (10) menarasikan hubungan hutan dan kekuasaan. Bab ini menyimpulkan bentuk-bentuk reaksi orang Siberut dalam menghadapi jaringan kekuasaan dari luar.
Buku ini merupakan satu satu karya penting mengenai sejarah politik ekologi mengenai Kepulauan Mentawai, bahkan mungkin yang terlengkap untuk studi mengenai dinamika pulau-pulau terluar Indonesia. Melaluinya kita dapat melihat cara pandang dan cara tindak bangsa Indonesia terhadap tanah airnya sendiri. Harus diakui bahwa kesadaran kita sebagai bangsa untuk memelihara alam tanah air ini masih sangat rendah. Orang-orang pintar di kota justru menjadi perusak paling hebat. Mereka, yang hanya memikirkan uang, sesungguhnya lebih bodoh dari masyarakat lokal.
Selain menggambarkan kompleksitas dinamika penduduk Siberut dalam rangka survival for the fittest di era global ini, buku ini setidaknya memberi pesan: bumi Indonesia yang makin bopeng-bopeng ini, Siberut khususnya, harus segera diselamatkan sebelum semuanya menjadi terlambat.
* Resensi ini dimuat di harian Padang Ekspres, Minggu, 5 Mei 2013
May 5, 2013
Minang Saisuak #133 - Mak Itam Minangkabau (ca. 1922)
Belum lama berselang sebuah lokomotif uap yang pernah dipakai di darek pada awal abad ke-20 dikembalikan dari Jawa ke Sawahlunto. Di zaman saisuak orang Minang menyebutnya “Mak Itam”, lantaran lokomotif uap umumnya dicat dengan warna hitam. Kini “Mak Itam” yang sudah dikembalikan ke Sawahlunto itu telah diaktifkan menyemarakkan pariwisata Kota Tambang itu.
Lokomotif uap, sebagaimana halnya kapal uap, adalah salah satu penemuan teknologi yang makin menciginkan gerak revolusi industri di Barat pada abad ke-19, sehingga makin menggema ke seluruh dunia. Lokomotif uap ditemukan oleh George Stephenson di Inggris pada tahun 1813. Dia membuatnya dengan teknologi sederhana, sebagian malah dikerjakan dengan tangan. Lokomotif pertama bikinan Stephenson itu, yang diberi nama ‘Blucher’, dites di jalur rel Cillingwood tgl. 25 Juli 1814.
Penemuan lokomotif uap oleh Stephenson terkait erat dengan penambangan batubara. Stephenson lahir di daerah tambang batubara di Wylam, dekat Newcastle, Inggris, pada 9 Juni 1781 (dia meninggal thn. 1848). Ayahnya, Robert Stephenson, adalah buruh tambang batubara yang miskin yang menghidupi keluarganya dengan upah menarik gerobak berisi batubara sebesar 12 shilling per minggu. George mendapat inspirasi untuk menciptakan lokomotif uap setelah melihat konstruksi lokomotif sederhana bikinan William Hedley dan Timothy Hackworth yang digunakan untuk mengangkut batubara di tambang Wylam. George membuat jalur kereta api pertama dari Stockton ke Darlington pada 1825 dan dari Liverpool ke Manchester pada 1830.
Tahun 1869 teknologi kereta api sudah sampai di Jawa, dan pada 1890-an “Mak Itam” sudah mencuit-cuit mengepulkan asap hitam di Ombilin dan Sawahlunto. Sekarang kita mengerti mengapa lokomotif di zaman dulu dicat dengan warna hitam. Itulah warna yang asosiatif dengan warna batubara, produk pertambangan yang erat terkait dengan kelahiran lokomotif uap.
Foto “Mak Itam” yang kami sajikan dalam rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini dibuat sekitar 1922 atau lebih awal. Lokasinya mungkin di Sawahlunto. Foto ukuran 24 x 29,8 cm. ini seperti membawa kita menapaktilasi masa-masa jaya perkeretaapian Sumatera Barat sampai tahun 1970-an. Kini hanya tinggal sisa-sisa kejayaan itu, sementara jalur relnya menuju beberapa kota di darek sudah tertimbun kenangan dan perumahan penduduk.
Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 5 Mei 2013
Suryadi's Blog
- Suryadi's profile
- 15 followers