Teguh Affandi's Blog: arsip alterteguh, page 3
September 22, 2019
(Tak) Berharap pada Sastra Koran
Pernah pada masanya penerbit buku Kompas dengan rajin mengeluarkan buku kumpulan cerpen yang rata-rata berbasis pada cerpen-cerpen yang dimuat media massa, baik Kompas maupun media massa lainnya. Pada masa itu banyak cerpenis mengeluarkan buku kumpulan cerpen, misalkan Triyanto Triwikromo, Yusrizal KW, A Mustofa Bisri, Jujur Prananto, Agus Noor. Era-era itu bolehlah saya sebut sebagai era keemasan sastra koran, cahayanya terang dan memberi banyak pengaruh pada penulis pada masa itu.
Masa kejayaan sastra koran setidaknya membuat banyak buku bagus terbit dan memberi warna tersendiri. Misalnya, Tabir Kelam (2003) karya Herlino Soleman, Dari Bui Sampai Nun (2004) karagan Agus Vrisaba, Cerita-Cerita dari Negeri Asap (2005) kumpulan cerita milik Radhar Panca Dahana. Tiga judul ini mungkin mewakili buku cerita yang bagus yang mungkin luput dibaca secara masif. Selain tiga tersebut, masih banyak judul kumpulan cerpen yang terbit di masa itu. Juga kumpulan cerpen pada masa itu pernah mendapatkan penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa, Bibir dalam Pispot (2003) milik Hamsad Rangkuti yang beroleh penghargaan pada tahun 2003.
Beberapa tahun terakhir, mungkin kita telah masuk pada era, ketika kita tidak lagi bisa menggantungkan koran dan majalah sebagai habitat sastra, terutama cerpen. Ada beberapa alasan yang membuat saya—yang mungkin gegabah—menyimpulkan hal ini.
Koran dan majalah diakui atau tidak sedang mengalami era disrupsi ketika media digital menantang kecepatan media cetak. Banyak koran dan majalah dengan lantang menutup rubrik budaya mereka. Terakhir kita saksikan pengumuman resmi dari The Jakarta Post menutup kolom cerita pendek. Dan sebelum itu banyak yang telah mendahului.
Di tengah krisis rubrik cerpen di media, banyak sekali penulis yang berhasrat ingin menjadi cerpenis. Dengan antusiasme publik yang demikian besar, lahan untuk menanam sekarang semakin sempit. Maka yang perlu dilakukan penulis adalah menyesuaikan “selera” koran yang menampung demi sebuah predikat “telah dimuat koran”. Bila suatu kali redaktur cerpen mengatakan cerpen yang dimuat haruslah yang bertema lokalitas, atau mengusung sejarah kelam bangsa, atau bertema perempuan. Bisa dipastikan penulis cerpen yang banyak dan berhasrat besar masuk koran itu akan berbondong-bondong menulis cerpen sesuai “pesanan” redaktur tersebut. Seperti rombongan pelamar pekerjaan yang memoles cv demi dilirik bagian hrd.
Mungkin belum disadari, tetapi bila demikian dibiarkan terus menerus alangkah monotonnya cerita pendek kita. Seolah patron cerpen koran menjadi sajian dalam perkembangan cerpen kita. Dan itu jelas merusak iklim cerpen kita. Cerpen-cerpen tidak lagi berani bergerak di luar “pakem cerpen koran”. Alice Munro penulis cerpen dan peraih nobel sastra bila hidup di Indonesia, saya rasa karirnya tidak akan sampai puncak seperti itu.
Belum selesai soal tema dan bentuk, koran secara tidak sengaja juga melakukan penyeragaman panjang. Tidak bisa dikhianati, sebab koran punya keterbatasan ruang. Dan cerpen yang dimuat harus disesuaikan.
Di era sekarang, kita bahkan tidak menemukan buku kumpulan cerpen sekuat Orang-Orang Bloomington-nya Budi Darma. Panjang cerpen-cerpen dalam buku itu jelas jauh dari maksimal cerpen koran, tema-tema juga bukan “umum” untuk cerpen koran. Tapi keberanian cerpen-cerpen itulah yang membuat Orang-Orang Bloomington terus dibicarakan sampai sekarang.
Saya sebagai penikmat cerita pendek, selain menanti cerpen yang tayang di koran setiap minggu, juga diam-diam menantikan ada cerpen dari penulis baru yang punya suara baru. Berharap suatu kali muncul yang berada di luar pakem, yang menggembirakan bagi iklim cerpen di negeri ini. Menantikan kemunculan satrio piningit yang menggairahkan kembali iklim cerpen kita.
Bagi penjaga gawang cerpen di koran, saya paham betul “penat”-nya membaca kiriman cerita setiap harinya. Tapi berkat ketekunan dan persistensi, siapa tahu menemukan suara baru, bentuk baru, yang menggembirakan.
Bagi para penulis cerpen, mungkin sesekali harus berpikir untuk tidak menjadikan rubrik cerpen koran sebagai patron utama. Sastra bergerak bebas dan universal. Dimuat atau tidak dimuat koran bukan jaminan kualitas bagus dan kalau dibukukan akan dipuji banyak orang. Sastra bergerak dalam cerita rekaan yang berani menerabas batas dan sesekali berbeda. Andai tidak memiliki keberanian untuk menjadi beda dari kebanyakan, tentu Danarto tidak akan menulis kumpulan cerpen Godlob yang mencengangkan publik itu. []
Gerundelan ini disiarkan di Suara Merdeka, 22 September 2019. Saya sadar tulisan ini seketika mengandung paradoks sebab seolah mengkritik “sastra koran”, tetapi tetap disiarkan di koran. Namun, maksud saya adalah hendak membuka diskusi lebih panjang.
September 15, 2019
Luka itu Bernama Sita
Koran Tempo, 14-15 September 2019.
Membaca Ramayana maupun Mahabharata, sejatinya adalah membaca manusia. Dari negara asalnya, India, epos-epos ini menjelajah ke penjuru dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara dan juga Indonesia. Di berbagai kawasan epos itu kemudian disesuaikan dengan kearifan lokal. Misalkan kisah Ramayana di Bali dan Jawa memiliki sedikit perbedaan. Namun dari ragam versi itu, dalam cerita perempuan selalu ditempatkan di belakang—konco wingking, dan seolah tak memiliki peranan besar dalam garis cerita.
Dalam khazanah sastra Indonesia, telah banyak sastrawan yang menginterpretasikan ulang bagian atau potongan baik dari epos Ramayana. Misalnya novel Anak Bajang Menggiring Angin (1983) Sindhunata, yang mengambil sudut penceritaan dari sisi Anoman. Atau Kitab Omong Kosong (2004) milik Seno Gumira Ajidarma yang mengupas Sinta selepas upacara obong dan hidup di pengasingan bersama dua anak kembarnya serta Empu Walmiki.
Cok Sawitri menghadirkan karya baru berupa tafsir dan penceritaan ulang atas kisah Rama, Sita, dan Rawana dalam tajuk Sitayana (2019)
Sita adalah simbol luka dan perlawanan perempuan. Sita dipertemukan dengan Rama bukan oleh Tuhan, melainkan sayembara pernikahan. Siapa saja—terutama dari kalangan bangsawan dan ksatria, yang bisa mengangkat gandiwa berhak memiliki Sita. Semua pembesar baik raja maupun putra makhota berebut menjajal digdaya. Namun hanya satu yang berhasil, Rama. Sita berakhir sebagai hak milik Rama.
Rawana yakin Sita adalah titisan Banowati, dewi yang dia cintai namun memilih menceburkan diri ke dalam api ketimbang dipersunting Rawana. Raja yang kasar dan mampu menggegerkan bumi langit.
Cok Sawitri sebagai dalang dalam lakon Sitayana menempatkan garis demarkasi yang membedakan cinta Rama dengan Rawana terhadap Sita. Bila kebanyakan Rama diposisikan sebagai lelananging jagat, pahlawan, dan kekasih idaman. Rama dalam lakon ini tampil sebagai lelaki pengecut, penakut, dan berlindung di bawah ketiak bernama ‘kebenaran norma pada umumnya.’
Sebaliknya, Rawana tampil sungguh-sungguh mengasihi Sita, hanya sedikit terlambat sehingga tampak seolah Rawana merebut Sita dari Rama. Namun, berkali-kali Rawana mengutarakan bahwa cintanya kepada Sita jauh lebih tulus dan suci dibandingkan cinta Rama kepada Sita.[image error]
Cinta yang kupilih adalah cinta yang tak terbalas. Tak ada yang paham akan hal ini. Semua mengira ini urusan cinta semata, tetapi aku adalah Dasamuka, yang mengubah takdir kematianku, yang mengubah kuasa surga dan membuat para dewa kehilangan sombongnya. Namun, aku hampir ratusan tahun tak bisa mengubah takdir asmara. (hal.84)
Perubahan sikap sangat kentara tatkala Rawana menjadi sangat peduli pada rakyat dan Alengka. Dilukiskan dengan apik, bahwa setelah menculik Sita, Rawana membuatkannya sebuah taman indah, Rawana kembali sering mengunjungi rakyat, dan semakin peduli pada urusan negara.
Rama yang mendapatkan hadiah berupa Sita, justru membuatnya harus turut diasingkan, kemudian terlunta-lunta dan terbuai-mabuk oleh kehidupan asmara. Dengan hasutan orang di sekitarnya, Rama justru meragukan kesucian Sita dan meminta Sita melakukan upacara obong. Maka tidak aneh bila kemudian Sita justru menaruh hormat dan ketakjuban kepada Rawana.
Di mana pun engkau, Rawana berada, terima kasih. Dengan caramu membuatku belajar memahami apa yang yang seharusnya kujalani sebagai perempuan. (hal.100)
Puncak dari ketidakterimaan Sita adalah ketika Sita mendeklarasikan kemandirian atas dirinya, anak kembarnya Kusa dan Lawa, meminta Rama tak usah mengusik atau mencoba membantu. Sita dan kedua anaknya terbebas dari Rama. Perempuan itu kini merdeka meski luka dan lebam di dadanya tak beranjak. “Jadilah anak ibu, bukan anak siapa pun, selain anak ibu.”(hal.130) Sita menegaskan Kusa dan Lawa anaknya, bukan anak Rama.
Kavita A Sharma dalam Queens of Mahabharata (2006) menyebut banyak sekali perempuan yang dikesampingkan dalam cerita, namun sejatinya adalah penggerak cerita atau awal sebuah perang besar dalam sebuah epos. Keberpihakan hanya kepada sosok-sosok hero berjenis kelamin laki-laki tidak lain pengaruh patriarki yang mengakar dalam benak masyarakat, baik di India maupun Indonesia. Sosok bahwa pahlawan dan yang mengambil peran penting selalu laki-laki.
Dalam mitologi India, istri adalah shakti bagi suami. Istri adalah daya kekuatan bagi kesuksesan seorang suami. Rama dalam hal ini membutuhkan Sita untuk sebuah kedigdayaan. Dalam bahasa Cok Sawitri, dalam tradisi sayembara, maka pihakmu (Sita) yang mengawini Rama. (hal.164) Tak terampuni bilamana Rama yang justru menyia-nyiakan sumber digdaya itu.
Melalui lakon Sitayana, Cok Sawitri menegaskan apa yang diyakini Sharma. Berada dalam bayang-bayang patriaki, seorang perempuan harus mampu menyampaikan suara baik dalam hal urusan asmara, keluarga, maupun masa depan anak-anaknya. Bukan karena perempuan tidak punya suara, hanya suaranya kerap tertutup dominasi parau laki-laki.
Sita dalam rekaan Cok Sawitri adalah perempuan yang kemudian menyadari kebebasan untuk menentukan sikap. Termasuk di suatu titik dengan tegas menolak undangan Rama saat Kusa dan Lawa anak kembar mereka. Penolakan ini adalah gambaran jelas bagaimana Sita ingin bebas dari jerat patriaki Rama.
Dalam novel ini Cok Sawitri jelas melakukan dekonstruksi atas kisah Ramayada terutama Rama-Sita dengan cukup besar. Sebuah usaha untuk memberi tafsir baru atas kisah Rama-Sita. Sita menampik Rama dan kemudian digambarkan dengan halus bahwa Sita sadar sejatinya yang mencintainya dengan tulus adalah Rawana.
“Apakah kini engkau masih mencintaiku?” tanya Sita kepada Rawana.
“Apakah cinta mengenal kata masih? Ia tak pernah bersifat sementara dan juga tidak seperti musim. Hanya yang tertipu birahi yang mengira cinta dapat datang dan pergi dari hatinya, lalu seolah setia disebabkan ikatan yang ditindas oleh norma dan etika.” (hal.280)
Akhir novel ini seperti kembali putar balik ke garis awal. Semua usaha dan sikap keras Sita nyatanya harus kembali dicengkeram Rama. Dunia masih ditutupi bayang-bayang patriaki. Sekeras apa pun suara perempuan pada ujungnya suara lelaki masih saja mendapatkan tempat utama. Sampai novel ini tamat, kisah Sita selalu terjungkang dengan tatu batin, sebab Sita adalah luka itu sendiri. []
July 13, 2019
Nelayan Boleh Berhenti Melaut, Penulis Tidak
Basabasi, 13 Juli 2019.

‘Buku-buku terbaik di seluruh dunia’ hampir semua terbit di tangan penerbit kecil, penerbit independen, setidaknya pendapat ini diukur dari penghargaan Man International Booker Prize di 2019. Saat Guardian menurunkan berita tersebut, daftar panjang pemenang sudah menguatkan pendapat spektakuler yang harusnya menambah energi pada pegiat penerbitan independen. Dari tiga belas judul, hanya ada dua judul yang diterbitkan oleh penerbit nonindie. Sebelas judul tersebut muncul dari penerbit indipenden seperti Fitzcarraldo Editions, Sandstone Press, Granta, dan Other Stories and Scribe. Maureen Freel—penulis, penerjemah, sekaligus salah satu panel juri dalam penghargaan tersebut, berujar dengan santainya, “Penerbit besar harus berusaha lebih.”
Di luar penerbit independen (kita tidak akan membahas bagaimana yang independen dan tidak independen) teruji memiliki taji dalam percaturan literasi dunia. Namun bagaimana dengan Indonesia, yang sudah menjadi rahasia umum bahwa “semua orang bisa menerbitkan buku dan punya penerbitan”? Lantas, mampukah buku terbitan penerbit independen yang hendak dibahas ini menunjukkan taji?
Sudah menjadi pengetahuan publik, penerbitan buku secara independen atau secara istilah sederhana adalah tiras yang tidak begitu banyak. Yang sedikit itu tetap diharuskan berkancah dalam rimba judul buku yang terbit setiap minggunya. Secara serampangan penerbit independen luar negeri yang mampu menyuguhkan judul-judul yang diperhitungkan dalam penghargaan sastra, pastilah bukan sekadar beralasan “dicetak sendiri, disesuaikan jumlah modal kita saja.” Itu terlalu remeh. Bisa dipastikan kurasi, penyuntingan, pengemasan, dan pemasaran independen mereka jauh-jauh-dan-sangat-jauh bila dibandingkan dengan sistem independen milik kita.
Selain harus mampu memberi warna baru yang tidak biasa, yang tidak jamak, yang tidak pasaran, penerbitan independen tidak boleh melewatkan ketatnya kurasi, primanya penyuntingan, dan jempolnya pengemasan. Karena bak makanan, mau di emperan, mau di swalayan, makanan enak tetap menuai pujian.
Buku Nelayan Itu Berhenti Melaut (2019) adalah karya perdana Safar Banggai, salah satu nama yang lebih saya kenal sebagai kerani di Radio Buku. Kumpulan cerpen perdananya ini sekaligus menunjukkan kemampuan dan keberanian menjajal sebagai pencerita. Pembahasan penerbitan indipenden di awal adalah terkait dengan pilihan Safar Banggai untuk hadir lewat penerbit independen. (Karena indie, buku ini takkan ada di toko buku kebanyakan, harus berburu secara daring).
Baca selengkapnya: https://basabasi.co/nelayan-boleh-berhenti-melaut-penulis-tidak/
June 30, 2019
Dunia Biner Kementerian Maha Kebahagiaan
Jawa Pos, 30 Juni 2019.
Praktis setelah merilis debut terbaiknya sebagai novelis lewat judul The God of Small Things, Arundhati Roy mengambil jeda cukup panjang. Selama reses tersebut Roy memilih fokus pada aktivitas sosial-kemanusiaan dan menulis beberapa judul buku nonfiksi. Tak bisa disangkal, debut Roy itu pula yang mengantarkannya menjadi salah satu nama yang diperhitungkan dalam sastra dunia. Memenangkan Man Booker Prize tahun 1997, menjadi judul best seller dunia, dan diterjemahkan ke berbagai bahasa.
Dua dekade rehat, 2017 Roy menerbitkan novel keduanya The Ministry of Utmost Happiness—Kementerian Maha Kebahagiaan. Publik tentu antusias menantikan gebrakan apa yang akan dihadirkan Roy setelah cukup lama rehat, dan apa novel keduanya ini mampu menggetarkan dunia sebagaimana novel pertamanya.
Roy menggunakan dua lema yang berlawanan dalam dua judul novelnya. Bila pada novel pertama Roy menggunakan frase ‘small things’ maka kali ini Roy mempergunakan ‘ministry’. Kementerian bisa diartikan sebagai istilah kelembagaan yang mencakup urusan banyak orang dan banyak hal, yang pasti lebih besar dari ‘small things’. Bila dalam novel pertama akan diungkap detail-detail kecil dusun Ayemenem, perkara domestik keluarga, dan cerita terfokus pada dua suadara kembar Estha-Rahel yang karena ulah kecil keduanya muncul guncangan besar di keluarga dan tatanan masyarakat. Urusan kecil yang kemudian merembet pada urusan kasta, ideologi, gender, dan seksualitas.
Sebaliknya dalam novel keduanya ini, melalui pilihan judul kementerian Roy memotret lanskap yang jauh lebih luas, mencakup urusan lebih banyak orang. Bisa dipastikan Roy kali ini melebarkan kamera pengawasan dalam menulis cerita.
Novel memang berpusat pada sosok Anjum, seorang hijra asal Kashmir. Apa itu hijra? Hijra adalah istilah bahasa India untuk kaum transgender. Meski Anjum bukan sebagaimana transgender pada umumnya. Ia adalah seorang hermafrodit. Lahir sebagai bayi lelaki bernama Afdal di tengah pasangan Janahara Begum dan Mulaqat Ali yang sudah mengidamkan anak lelaki begitu lama. Bidan menyebut “laki-laki”, namun Janahara Begum tak menemukan onderdil-otong pada Afdal, melainkan onderdil-upik.
Ketidakberesan ini kemudian menekan Afdal untuk terus menyembunyikan dirinya. Hingga kemudian dia bertemu perempuan transgender Bombay Silk dan memantapkan identiasnya, sebagai Anjum.
Lingkungan mengolok-olok Anjum dengan, Dia laki yang perempuan. Dia tak laki tak perempuan. Dia laki dan perempuan. Perempuan-Laki, Laki-Perempuan. Ketersingkiran Anjum semakin menjadi ketika dia sadar bahwa semua makhluk hidup dan benda mati dalam bahasa Urdu, memiliki jenis kelamin. Anjum yang hijra tak menjadi bagian dunia normal.
Keterasingan identitas ini kemudian memaksa Anjum menyingkir. Pertama dia pindah ke pondokan khusus kaum hijra, Khwabgah. Setelah tak lagi nyaman, Anjum justru pindah ke perkuburan dan menjadi bakal sebuah sebuah usaha mengurus jenazah kaum terpinggirkan. Sebuah simbol yang begitu satire dari Roy, bahwa tak masuk kelompok normal maka tempatnya adalah perkuburan, mati.
Kematian identitas Afdal-Anjum dimulai bahkan saat Janahara Begum mengetahui ketidaklaziman fisiknya. Bertahun-tahun dianggap sebagai laki-laki, kemudian identitas semu itu disempurnakan, dan lahirnya Anjum. Menyepi di perkuburan adalah kematian kesekian Anjum.
Dunia normal di luar Anjum adalah dunia biner. Sebagai mana jenis kelamin, tak mengenal kelamin antara. Pun demikian dengan persoalan lain yang dibawa Roy dalam buku ini. Selain perkara identitas dan gender, Roy memaparkan ragam perkara lain. Mulai konflik Islam-Hindu, India-Kashmir, India-Pakistan, dan beragam peristiwa berdarah yang terjadi di India.
Kerangka besarnya masih soal gesekan antara mayortitas dan minoritas. Seperti Anjum yang tertepikan di perkuburan, orang-orang minoritas yang bukan bagian mayoritas seolah berhak dihabisi. Tampak dari rentetan pembakaran kereta di Kashmir oleh kelompok Hindu keras, dan ragam serangan balik lainnya.
Sebagai negara dengan multi-etnis dan agama, India tak luput dari konflik horizontal yang menjadi bagian kelam dalam sejarah India. Pada 2019, dirilis film Hotel Mumbai yang terinspirasi atas peristiwa terorisme kelompok radikal-militan muslim Pakistan ke Mumbai, India. Sekelumit potret betapa India adalah negara dengan kemungkinan munculnya konflik besar.
Selain kekuatan isu yang diangkat, Roy dikenal memiliki kekhasan alur dan bahasa indah. Bahasa Roy adalah alur novel itu sendiri. Bahasa Kementerian Maha Kebahagiaan tidak serumit The God of Small Things. Permainan kedekatan bahasa, permainan sudut pandang, ragam teknik penceritaan mulai dari potongan koran, buku harian, yang membuat penikmat karyanya dapat merasakan jejak Roy.
Bila dalam novel perdananya, pembaca akan mudah menyerah membaca dengan alur yang mirip rumah siput. Berkelindan dan memutar. Jajaran waktu tidak linier, penceritaan bolak-balik tanpa penanda waktu. Sulit tapi memang demikianlah ciri khas Roy. Cacahan alur rumit tak ditemukan dalam novel ini. Memiliki bentangan waktu yang cukup panjang, namun kisah disusun linier. Secara struktur Roy membuat kisah dengan banyak tokoh dengan ragam sebutan. Dalam Kementerian Maha Kebahagiaan ini Roy membangun kisah besar berdasar banyak kisah minor setiap tokoh. Cerita milik Anjum, S.Tilottama, Nagaraj Hariharan, Biplab Dasgupta, atau Musa Yeswi. Di setiap tokoh Roy mengisahkan hidup dan perkara.
Meski disusun sedikit kurang rapi bahkan tampak seperti potongan puzzle yang belum sempurna disatukan hingga muncul rongga, Kementerian Maha Kebahagiaan tetap sebuah karya dengan kepadatan isu dan gaya penceritaan mengagumkan. Publik memang tidak akan berhenti membandingkan dua novel Roy. Namun tampak tidak adil bila pembaca ikut-ikutan berpikir biner dalam menilai novel ini, bila tidak sebagus yang sebelumnya kemudian dienyahkan. Bagaimanapun, Roy telah mengemas isu mahabesar dengan bahasa dan alur tak ala kadarnya.[]
NB: saya tampilkan semua, karena versi cetak terjadi pemangkasan. Dan saya sedikit malas menyunting sesuai versi koran. Membaca versi koran bisa diklik tautan berikut: https://www.jawapos.com/minggu/buku/30/06/2019/dunia-biner-kementerian-maha-kebahagiaan/
May 5, 2019
Mesin Penjual Otomatis
Jawa Pos, 5 Mei 2019
TENGGOROKANKU begitu sensitif, mudah radang dan batuk bila menelan minuman atau penganan mengandung sakarin. Termasuk penganan yang biasa dibawa Jilung sekembalinya dari jogging pagi hari. Jilung selalu beralasan tidak enak melewati penjual kue yang bengong menanti kedatangan pembeli yang juga tak pasti. Keramahan Jilung juga sakarin.
Genggaman tangan Jilung mengendur. Udara dingin mengisi sela-sela jemari kami. Aku tak habis pikir, pagi ini batuk dan radang berubah menjadi batu yang merangsek dada. Ruangan serba putih tak berhasil membuat mendung menyingkir dari ruangan ini. Jilung mengelus-elus punggungku. Aku tak menangis. Aku lebih ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan Jilung setelah diperdengarkan vonis.
“Semua akan baik-baik saja,” Jilung mengusap ujung mata.
Aku terhenyak. Telingaku seolah disiram kemerduan yang lama tak keluar dari mulut Jilung.
“Benar, belum terlalu parah. Kita akan melakukan pengobatan kimia. Mencegah penyebaran sel kanker,” suara dari balik baju putih itu akhirnya keluar.
“Alat-alat medis sudah canggih,” Jilung kembali menguatkan.
Segala macam kalimat lenyap. Aku bingung harus membalas bagaimana. Bahagia karena sel kanker yang membercaki paru-paruku masih ada kemungkinan bisa dilenyapkan. Ataukah sedih, ternyata hobiku merokok dan minum alkohol membawa ampas buruk di saat usiaku belum terlampau jauh berjalan dari angka empat puluh.
Aku izin keluar ruangan Dokter Kartolo. Aku butuh sesuatu yang mampu mengangkat semua kegundahan. Plang berisi nama Dokter Kartolo spesialis onkologi mendadak lebih jelas terlihat. Ketika aku dan Jilung beberapa jam lalu masuk, tak sekali pun kucermati. Yang mencuri perhatianku tadi ialah bangku-bangku warna putih yang sepi dan sendirian. Juga lorong panjang yang hanya menggaungkan suara-suara dari sisi lain rumah sakit. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja, bilamana setiap hari harus bertemu keganjilan seperti ini.
Aku melangkah mendekati ujung koridor yang bertemu dengan kaca jendela. Mungkin aku bisa melihat lapangan parkir atau sekadar jalan raya yang pasti penuh kendaraan bermobil. Saat mataku melongok, kusaksikan taman kecil di sisi rumah sakit. Beberapa orang duduk menatap bunga, suster menemani. Juga beberapa kursi roda yang terparkir tepat di depan perdu bunga krisan.
Mereka sedang masa penyembuhan. Tapi apa juga harus dirundung kemurungan?[image error]
Tak ada kursi. Sehingga aku hanya mengamati mereka dari kejauhan dan mencoba mencermati seorang wanita yang dari atas tampak kurus sekali. Dia tak berkutik. Seorang lelaki di sisinya. Juga diam. Hanya angin yang menggerak-gerakkan selang infus yang tergantung di sisi wanita itu. Aku kalau pun sakit parah, tak mau memamerkan penderitaan. Di taman?
Jilung pernah menemaniku duduk di taman sore-sore, menyaksikan gelandangan diusir. Kalimat Jilung waktu itu masih terus kuingat, meski sekarang mulai tak lagi Jilung katakan. “Kalau umur kita sampai tua, aku ingin yang lebih dulu mati. Tidak tahu harus bagaimana andai kamu lebih dulu meninggalkanku. Aku tidak ingin merasakan kehilangan dan kesepian tanpamu.”
Suara tangisan, membuatku terhenyak. Selain sarang rasa sakit, bangunan lantai delapan belas ini adalah pusara tangisan. Tangisan menyaksikan kematian. Tangisan mendengarkan vonis. Atau tangisan karena tak mungkin lagi ada mayat yang bisa menangis.
Aku berbalik menuju koridor lain, mencari minuman dingin di vending machine.
Aku tak membawa tas. Aku meraba saku, dan kutemukan selembar dua puluh ribu di saku belakang celana. Kuperhatikan daftar harga. Bila aku beli kopi atau jus dingin, aku bisa dapat dua. Tetapi yang menyita perhatianku adalah bir dingin di rak paling bawah. Memang tertulis 0% alkohol, tapi baru sekali ini aku menemukan ada rumah sakit yang meloloskan suplier memasukkan bir dingin dalam daftar jualannya. Uangku tidak cukup untuk membelinya.
Sebelum aku memencet pilihan, Jilung mendadak muncul di sampingku.
“Dokter Kartolo memanggilmu,” Jilung menarik lenganku tanpa mempersilakanku untuk memencet minuman kaleng lebih dahulu. Seharusnya dia tahu betul, orang yang sudah berdiri di depan vending machine dan menggenggam uang pasti ingin membeli barang satu.
“Kamu tidak boleh stres. Emosimu harus stabil, kata dokter. Kafein bikin degup jantungmu semakin cepat, bukan?” Jilung memblokade usahaku.
Aku ingin sekali memotong tindakan Jilung bahwa aku sedang ingin minum bir dingin tanpa alkohol. Dan persetan pula dengan degup jantung yang melaju semakin cepat, bila semua akhirnya akan berhenti berdegup.
Tak ada kegiatan berarti selain mendengarkan saran Dokter Kartolo. Level stres harus dijaga. Sel kanker akan mudah menyebar berbarengan kondisi psikis. Juga dijadwalkan rutin periksa tiap kamis pagi. Selembar resep yang harus ditebus. Dan tak lupa selengkung senyuman dan ucapan doa agar tetap sehat, yang seolah menjadi penutup wajib kunjungan dokter.
***
“Aku haus.”
“Aku ke bagian farmasi dulu. Duduk di sana ya,” kata Jilung menunjuk bangku yang tak jauh dari vending machine. Masih dalam radius pandangan Jilung saat mengantre menebus resep. Seolah Jilung tak mau menyaksikanku sekarat seorang diri.
Jilung pasti akan marah bila aku meminta tambahan uang untuk beli bir dingin 0%. Dengan uang yang kupunya, aku memilih jus jeruk dalam kemasan. Kurasa minuman itu akan aman tanpa menimbulkan silang emosi dengan Jilung.
Aku lebih ingin Jilung yang kemarin, atau dua hari yang lalu. Tak terlalu peduli kepadaku. Tak ingin tahu banyak atas kondisiku. Dan itu membuatku lebih menjadi aku. Diperhatikan tak ubahnya dikekang oleh batasan.
***
“Kamu tidak boleh terlalu lelah. Kamu tidak boleh merokok, no alchohol, no fast food. Kamu harus puasa dari kebiasaanmu yang asal-asalan. Ini demi kesehatanmu,” Jilung mengoceh di balik kemudi mobil SUV, bonus setelah menang tender proyek pemerintah. Semua biaya kesehatan kami, masih dalam pembiayaan tempat Jilung bekerja.
Aku tak berkutik. Sisa-sisa jus jeruk yang tersangkut di sela-sela gigi kusesapi. Masih ada manis. Selebihnya rasa gurih saliva.
“Sudah kuminta Lucy untuk membantumu di rumah. Aku tak ingin kamu lelah karena mengurus rumah sendirian. Kita fokus pada pemulihan kesehatanmu,” Jilung sesekali menoleh ke diriku. Sedangkan aku, lebih ingin melihat jalan dan deretan pertokoan yang bergantian lebih cepat.
Lucy sudah berulang kali diperkenalkan sebagai sepupu jauh Jilung. Benar atau tidak bukan kewajibanku untuk melakukan kroscek. Setiap kali Lucy mampir ke rumah, Jilung akan berlagak lebih romantis. Meladeniku minum, nada kalimatnya mendayu-dayu, juga tangan Jilung tak bisa lepas dariku. Aku tak tahu maksudnya. Hanya saja semua yang dilakukannya itu serba mendadak dan membuatku tersedak.
“Lucy kapan datang ke rumah?”
“Sore nanti dia sudah bisa membantumu. Dia kusarankan menginap. Akan tidak enak kalau dia bolak-balik ke rumahnya. Cukup jauh,” Jilung memutuskan. Sejak aku memutuskan pensiun muda di saat karirku selangkah lagi mencapai posisi manager, aku seperti hewan peliharaan Jilung. Semua keputusan ada di tangannya. Aku seperti bawahan yang harus siap menjalankan semua keputusan.
“Kita mampir ke toko bunga. Aku akan membelikan beberapa pot tanaman. Stress healing,” Jilung kembali memutuskan.
Bunga sebagai pengusir stres? Aku memang mencintai bunga. Tapi aku lebih memilih bir dingin untuk stress healing. Tak benar bahwa bila aku memandangi bunga mekar saban pagi, maka perasaan akan damai. Tak bergejolak. Dan menjadi jaminan sel kanker dalam paru-paruku tak berpinak. Aku lebih tahu apa yang disukai tubuhku.
Mobil berhenti tepat di sebuah toko bunga dan tanaman hias. Kaktus besar yang berbunga mencuri perhatianku. Namun, Jilung pasti tidak akan mengizinkan mobil SUV barunya terbaret duri kaktus.
“Kamu tidak ikut turun?”
“Aku di sini saja. Kamu sudah tahu bunga apa yang kusuka,” jawabku singkat.
“Mau kubelikan minuman dingin?” Jilung menoleh-noleh sekitar, mencari toko kelontong terdekat.
Aku lebih ingin tenang. Semuanya serba mendadak hari ini. Kanker. Lucy. Dan toko bunga.
Kanker dan kematian, yang meski Dokter Kartolo yakin akan bisa mengusirnya dengan pengobatan canggih, diam-diam menggusarkan. Yang membuatku semakin takut ialah mengetahui bahwa prasangkaku selama ini kalau ada sesuatu antara Jilung dan Lucy terbukti. Aku ingin menjadi buta dan tuli untuk persengkokolan mereka. Lucy bisa jadi akan menggantikanku bila kanker dalam paru-paruku berubah menjadi malaikat penjemput maut.
“Itu ada vending machine,” Jilung menunjuk toko kelontong seberang toko bunga. Agak mengherankan ada mesin canggih di jalanan sepi begini.
Setelah Jilung masuk, aku keluar dari mobil. Berjalan bertelanjang kaki menyeberang jalan. Kali ini sudah kubawa dompetku sendiri. Andai ada bir dingin segera kupencet sebelum Jilung memergoki.
Pagi memang belum beranjak terlalu siang. Namun aspal jalan telah menyimpan percik-percik panas. Embun dan dingin beku telah paripurna menguap bersama angin. Aku berjalan berjingkat, dengan menumpu telapak kaki bagian depan. Sesekali setengah berlari. Di belakang kusaksikan Jilung mengamatiku. Aku terkikik. Seolah telah berhasil mengelabuinya.
Setelah sampai di vending machine, tubuh seketika kusandarkan. Napas terengah-engah. Ada keceriaan bersama degup jantungku. Terlebih di rak bagian bawah bir dingin tersedia.
Aku tergesa memasukkan uang ke dalam mesin. Ketika sekaleng bir dingin jatuh, segera kurogoh. Tanpa berpikir panjang segera kubuka. Namun, lantaran tanpa perhitungaan seperempat bir muncrat ke dadaku. Bukannya mengumpat, aku justru tertawa keras. Seketika mengingat pengalaman pertama ketika aku masih SMA dan mencuri sekaleng bir Ayah di kulkas. Ledakannya seperti kembang api, meledak-rusak tapi membuat dada dibuncahi bahagia.
“Hati-hati,” suara pemuda, yang kutaksir berusia tak lebih dari tiga puluh tahun, mengagetkanku. Aku melongo.
Tanpa diduga pemuda meraih tisu dari saku celana dan mengelap baju bagian dadaku. Dadaku semakin terguncang. Tanpa meminta izin, tangannya telah menjelajah area dada yang lengket akibat muncratan bir. Dia tersenyum. Aku tersenyum. Lantas kudengar suara Jilung.
“Ah, terima kasih. Aku teledor,” kataku gugup.
“Ini, pakai saja,” dia menyerahkan beberapa lembar tisu lagi kepadaku.
Mata pemuda itu tak beranjak dari dada dan wajahku. Aku semakin salah tingkah.
“Ada yang melambai-lambaikan tangan. Mungkin memanggil, Anda,” katanya.
Aku menoleh. Jilung dari kejauhan pasti meneriakkan larangan.
“Ah, aku tidak kenal.”
Pemuda itu kembali tersenyum. Tangannya menyentuh punggung tanganku saat hendak membantu mengelap untuk ke sekian kali.[]
April 13, 2019
Sekali Lagi untuk Hindia
Koran Tempo, 13-14 April 2019
Iksaka Banu kembali menghadirkan kumpulan cerpen berlatar era kolonialisme atau bahkan jauh sebelumnya. Apa yang baru?
Ketika kumpulan cerita pendek Iksaka Banu Semua untuk Hindia (2014) terbit, banjir pujian mengiringi buku tersebut. Judul itu pulalah yang mengantarkannya memperoleh penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa kategori prosa pada tahun yang sama. Iksaka Banu mengembuskan gaya baru dalam menulis cerpen. Meski bukan dituturkan dengan gaya yang mendobrak kebiasaan menulis cerita pendek, ia berhasil menghadirkan corak baru lewat cerpen-cerpen kolonialisme. Mengambil latar ketika era penjajahan, mengambil tokoh serta peristiwa yang benar hidup dalam sejarah, dan tidak jarang suara Iksaka Banu memilih menyaru menjadi suara penjajah, memilih sudut pandang orang Belanda.
Lima tahun kemudian, Iksaka Banu kembali menghadirkan kumpulan cerpen berlatar era kolonialisme atau bahkan jauh sebelumnya: Teh dan Pengkhianat. Tak jauh berbeda dengan kumpulan cerpen terdahulu, Iksaka Banu masih menyorot potongan-potongan sejarah yang dielaborasikan dengan racikan fiksi, berlatarkan era kolonialisme Belanda dengan rentang pengisahan yang cukup lebar.
Menarik mencomot kembali apa yang disampaikan Iksaka Banu dalam pengantar buku ini, bahwa kesulitan utama seorang penulis cerita dengan latar kolonialisme adalah keseimbangan antara fakta dan fiksi. Bila terlampau rinci dan komplet menyuguhkan fakta, cerita akan menjemukan bak membaca diktat sejarah. Sebaliknya, bila terlalu mengada-ada dengan porsi fiksi terlampau dominan, tentu akan mendapatkan beragam protes dari pembaca kritis atau yang paham sejarah.
Tidak aneh bila cerita dalam buku ini cenderung bergerak dalam domain aman, tak beranjak dari titik tengah bahkan seolah mengulang pola yang senada dengan Semua untuk Hindia.
Tiga belas cerita dalam buku ini masih berlatar era kolonialisme dan menyoroti sosok orang Belanda baik yang murni maupun yang sudah berdarah campuran. Tidak jarang orang-orang kulit putih ini mendapatkan lampu sorot utama dan suara lebih dominan.
Iksaka Banu memotret bagaimana kecintaan terhadap Hindia Belanda tidak hanya tumbuh di dada pribumi. Tak terkecuali mereka yang berkulit putih. Sebagian adalah murni Belanda dan tak sedikit berdarah campuran lahir di Hindia Belanda. Dalam cerpen pembuka Kalabaka misalnya. Kebencian terhadap VOC Belanda dan simpati terhadap orang pribumi ditunjukkan oleh ia yang murni Eropa.
Kita akan berjumpa dengan Hendriek Cornelis Adam, mantan schutterij (milisi) merangkap seorang juru tulis dan asisten pribadi Tuan Nicolas van Waert. Dalam sebuah ekspedisi ke Pulau Banda, ia menyaksikan betapa kejinya VOC membalas dendam dan melumpuhkan penduduk lokal. Kemungkinan besar kita akan langsung menghadapi pertempuran brutal di Banda. (hal.5)
Dan benar, penduduk Banda hampir bersih dibunuh dengan cara biadab. Belanda totok ini mengambil sikap berseberangan dengan pihak berkuasa saat itu. Dia melawan demi menyaksikan pembantaian keji itu, Kuhampiri Gubernur Snock. Kuayunkan kepalan tangan ke dagunya. (hal.15)
Sebelum dieksekusi mati karena dinilai melawan, ia menyampaikan nasihat penting kepada anaknya di Belanda, buatlah dunia Barat yang pongah ini mengerti, betapa berdosa merampas hak hidup seseorang. (hal.16)
Di cerpen lain, Teh dan Pengkhianat, sikap membela humanisma dan kecintaan seorang Belanda Totok tak hanya tertuju pada pribumi, juga para buruh perkebunan Cina. Kapten Simon Vastgebonden, pejabat perkebunan justru melawan pendapat rekannya asli Belanda yang menyalahkan pemberontakan buruh Cina di perkebunan teh. Dan menurut Tuan, orang Belanda tak ada yang licik? (hal.36)[image error]
Sikap kecintaan pada Hindia Belanda, anti pada tindak kekejian, dan pembantaian yang tidak manusia yang tampak betul ingin disampaikan oleh sikap semua tokoh dalam buku ini.
Lantas apa orang-orang Belanda keji tidak layak untuk dijadikan suara utama? Apa nama-nama seperti Tuan Snock hanya boleh hidup sebagai tokoh utama dalam buku sejarah? Dunia yang dibangun Iksaka Banu terlalu putih untuk sebuah fiksi. Benar bahwa manusia hidup—dan orang-orang Belanda masuk di dalamnya, selalu ada pihak protagonis dan antagonis. Tetapi akan menjadi tantangan besar bagi Iksaka Banu untuk menghidupkan tokoh bengis, licik, yang selama ini selalu ia jauhi. Jauh akan menarik sesekali Iksaka Banu menulis sosok yang kejam, culas, atau setidaknnya punya prasangka jahat, laiknya sifat manusia pada umumnya.
Pembaca pasti jemu bila tiga belas cerpen dalam buku ini mengisahkan hal-hal yang bergelut dengan perang ataupun tragedi berdarah. Meski tokoh-tokoh Iksaka Banu bukanlah tokoh familier dalam sejarah kolonialisme. Tokoh sempalan yang sangat mungkin sekadar rekaan Iksaka Banu. Hal ini yang membuat fiksi Iksaka Banu terhindar dari menceritakan kembali potongan sejarah.
Pun beberapa cerpen dalam buku ini justru menyorot hal lain selain perisiwa berdarah. Cerpen Tegak Dunia membahas bagaimana penemuan globe mengkhawatirkan kaum gereja di Batavia, yang masih meyakini geosentris dan bumi datar. Atau cerpen Variola menyorot wabah cacar yang menghebohkan Hindia Belanda dan usaha vaksinasi ditolak oleh pihak gereja. Juga cerpen segar Di Atas Kereta Angin yang jauh dari kesan sebuah cerita kolonialisme. Seorang budak pribumi diizinkan menaiki sepeda lama juragannya yang orang Belanda. Jelas ini menimbulkan keresahan, karena sepeda hanya untuk kaum juragan.
Hal demikianlah yang membuat buku ini punya warna yang sedikit berbeda dengan Semua untuk Hindia. Iksaka Banu seperti sedang memutar kamera pengawas ke sudut lain, dan menangkap pemandangan baru yang segar dengan tetap menggaungkan humanisme. Sekaligus menegaskan bahwa era kolonialisme, pascakolonialisme, atau periode-periode lainnya sekadar zona waktu yang sangat fleksibel. Penulis boleh mengambil di zona mana ia akan berkisah. Namun, aktor utama adalah manusia. Kisah manusia yang harus menjadi pokok sebuah kisah.
Yang demikian yang membuat Teh dan Pengkhianat tak terjebak menapak di jalan yang sama dengan Semua untuk Hindia. []
April 4, 2019
Mengabarkan Kematian
Solo Pos, 24 Maret 2019
Bukan kematian yang kukhawatirkan, melainkan mengabarkan kematian yang sudah diam-diam kutampik ini kepada Norman, suamiku. Dua minggu lalu aku sengaja tak menyampaikan kepadanya, bahwa Dokter Siwon ingin mengangkat gumpalan lemak di perutku. Gumpalan yang semula sebesar biji rambutan, lama kelamaan membesar. Sebesar telur puyuh, dan membesar kembali hingga seukuran bola golf, dan membuat Dokter Siwon memutuskan untuk mengangkat gumpalan lemak itu.
“Tumor tidak ganas,” Dokter Siwon menyimpulkan. Karena memang benar, tidak ada kesakitan yang kurasakan. Semula kusangka gumpalan itu sekadar beberapa gram lemak yang tak berhasil kubakar setiap pagi dengan lari mengelilingi perumahan kita. Tapi Dokter Siwon merasa gumpalan itu harus diangkat demi tindakan pencegahan agar tidak menganggu rongga tempat bayi kelak tumbuh, terlebih aku dan Norman sedang program kehamilan.
“Bedah minor,” kata Dokter Siwon. Aku mengiyakan. Dua hari lalu, tanpa sepengetahuan Norman, aku dibawa di ranjang operasi di bawah sorot lampu Dokter Siwon mengangat tumot sebesar bola golf itu. Yang Norman ketahui bahwa aku sedang mengambil cuti dua sampai tiga hari dengan menginap di rumah Kakakku Jihan.
Setelah bola golf itu diangkat dari perutku, Dokter Simon menemuiku dengan wajah yang berduka. Ditekuk dengan kerut di sekitar mata yang mendadak tumbuh lebih banyak. Dokter Siwon mengajakku berbincang perlahan, seolah telapak tangannya yang lembut dan berbulu jarang itu merasuk ke dadaku dan meremas perlahan. Dokter Siwon ingin aku tidak terkejut dan sedih yang kurasakan bertahap.
“Apa ini akan tetap akan kamu rahasiakan?” tanya Dokter Siwon.
Aku masih belum memutuskan. Mendengar berita darinya saja sudah membuat semua kata-kata di kepalaku acak dan tercecer di lantai. Aku tidak menangis. Hanya remasan Dokter Siwon di dadaku membuat sesak, dan luka jahitan di perutku mendadak lebih sakit. Berkali-kali lipat.
“Apa operasi kemarin gagal, Dok?” tanyaku.
“Bukan, demikian. Ada jaringan kanker yang ternyata sudah menyebar lebih cepat. Gumpalan itu bagian lain. Limfoma. Yang….,” Dokter Siwon tak berani melanjutkan.
“Lebih ganas, lebih mematikan. Aku hanya punya waktu enam bulan hidup?” aku menyela dan mungkin Dokter Siwon kesulitan mencari kata-kata yang pas, tidak terlalu kasar, dan menumbuhkan semangatku.
“Kita bisa terapi….”
Aku diam. Kalimat Dokter Siwon lebih mirip sekadar formalitas. Aku tak tahu seganas apa kanker yang ternyata justru muncul setelah tumor sebesar bola golf diangkat, dan menyebarkan aroma kematian yang mendadak lebih dekat dari bibir atasku.
Aliran deras di mataku dimulai ketika aku beranjak dari ruangan Dokter Siwon. Saat pintu metal lift terbuka. Wajahku terpantul kurang sempurna di dinding dalam lift. Rambut kucepol ke atas. Syal ungu tua yang kulingkarkan di leher, jatuh tidak sempurna di bagian dada. Aku menyaksikan tubuhku yang kehilangan hampir seratus gram potongan lemak berbentuk bola golf. Namun ditumbuhi lemak lain yang ini lebih dahsyat, lebih kisut, dan lebih memastikan bahwa aku tidak lebih dari setahun lagi akan menyusul Ibu.
Aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku tidak akan menghadiri upacara kematian setelah Ibu terbujur kaku di dalam peti mati di hadapanku dua puluh tahun lalu. Saat aku dan Jihan masih sama-sama belum mengerti apa itu kematian, Ibu lebih dulu memaparkan seberapa dalam kematian itu menghunjami dadaku, Jihan, dan Ayah yang kala itu masih segar dan bugar.
Ayah tak menjelaskan mengapa kematian Ibu begitu cepat, bahkan beberapa kudengar kematian Ibu terbilang mendadak. Ayah, satu-satunya yang ingin kudengar menjelaskan apa itu kematian dan apa penyebab Ibu mati begitu cepat, hanya mengatakan dengan bahasa metafora. Ada bom yang meledakkan tubuh bagian bawah Ibu.
Jihan meledak tangisnya. Dia tentu membayangkan tubuh bagian bawah Ibu tercecer, menjadi serpihan akibat ledakan, mirip adegan di film yang kami tonton di Minggu Siang. Aku diam dan menerima pelukan Ayah yang terisak lebih kuat. Aku duduk di samping Jihan, berusaha mundur beberapa senti di belakang Jihan. Kemudian menerima telapak tangan, pelukan hangat, dan sesekali isakan tamu yang mengantarkan bela sungkawa ke keluarga kami.
Di ujung keberangkatan Ibu, aku diminta menyaksikan wajah Ibu untuk terakhir kali. Tubuh Ibu terbalut kain dan menyisakan sepotong wajah Ibu—lebih pucat, lebih biru, dan bibir Ibu tetap merah, untuk kusaksikan terakhir kali. Aku ingin memeluk Ibu, tapi Ayah gegas menghalangiku. Aku hanya ingin memastikan tubuh Ibu bagian bawah tidak rusak. Tetapi tak bisa. Mereka menutup tubuh Ibu, seolah bagian bahwa tubuh Ibu memang rusak akibat bom dan tak layak disaksikan oleh banyak orang.
Aku menjerit karena dilarang. Aku menangis karena hanya asumsi bahwa tubuh bagian bawah Ibu rusak berkeping-keping akan mendiam lama di kepalaku. Semakin aku menangis, bukannya semakin diperbolehkan, aku justru dibawa masuk ke kamar oleh tangan-tangan wanita yang tak kukenal. Disusul Jihan yang tangisannya tak lagi bersuara, tapi wajahnya basah sebasah-basahnya. Semenjak itu aku tak mau menghadiri upacara kematian, siapa pun itu. Kematian kerap menyisakan asumsi yang membuat kita jauh lebih sedih, dari sekadar ditinggal orang yang kita kasihi selamanya.
Bila sanak, kawan, kolega, atau tetangga wafat lebih dahulu. Aku dan Norman sepakat untuk mengirim salam dan karangan bunga, dengan Norman akan menjadi wakilku itu pun bila dia tak sedang disibukkan agenda firma hukum yang belakangan kerap digoyang isu-isu tidak sedap.
Tapi nazarku akan segera terpatahkan. Aku akan menghadiri kematian sebentar lagi. Aku akan menghadiri kematianku sendiri, setelah kematian Ibuku. Aku akan segera mati seperti Ibu.
Sepanjang perjalanan dari rumah sakit, aku hanya membayangkan bagaimana Norman akan hidup setelah aku mati. Norman yang berulang kali mengatakan, takkan terpikirkan untuk hidup seorang diri, dan bisa mati juga kalau harus berpisah denganku. Kamu tahu, yang kuinginkan adalah aku bisa lebih dulu mati daripada kamu. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Tanpa berpikir bahwa ditinggal Norman juga pastilah membuatku kelimpungan, tetapi kalimat Norman kala itu sudah cukup membuatku yakin bahwa dia adalah yang paling benar sebagai suamiku.
Norman tidak seperti Ayah, yang meski ditinggal Ibu begitu kuat mengasuh aku dan Jihan. Bahkan kami punya Ibu baru, setelah aku dan Jihan masuk kampus. Ayah butuh kawan berbincang. Dan mungkin izin dan pelukan hangat dariku dan Jihan adalah balasan atas kesetiannya kepada mendiang Ibu dan kerja keras membesarkan dua gadis paling rewel sedunia ini. Tapi Norman? Bukan, dia tipe lelaki kuat yang selalu tergantung padaku. Mencocokan warna dasi dan kemeja saja masih belum mahir, apalagi hidup selepas aku mati. Begitu kokoh di luar, tapi lembut dan mudah tersentuh di bagian dalam.
Tangisanku semakin terisak. Norman yang kucintai dan juga mencintaiku sebentar lagi akan menjadi duda. Aku yakin Norman takkan menunjukkan tangis kepada orang-orang. Sekilas saja. Tapi aku bisa membayangkan bangun tengah malam untuk menemukannya terisak tanpa suara di depan layar komputer di ruangan kerjanya. Dengan hanya diterangi lampu dari layar komputer, tubuhnya berguncang menahan isakan.
Dadaku sesak. Semakin sesak bahwa sebentar lagi aku harus mengabarkan kematian itu kepada Norman.
Petang mulai menggelap. Lampu teras rumah belum dinyalakan. Norman belum pulang. Aku menghapus air mata dan gegas masuk ke rumah. Meski kematian yang akan kukabarkan, wajahku tak boleh runyam di depan Norman. Lambung rumahku lengang dan disusupi kedinginan yang merasuk ke sela-sela kulit.
Tanganku beberapa menyambar sakelar lampu. Kemudian duduk di meja makan. Aku menelungkupkan wajah di atas meja. Dan kembali terisak begitu keras sendirian.
“Norman? Norman?” suaraku di tengak isakan. Aku tak mengira sekelebat bayangan itu adalah Norman.
“Lucia… “ Norman mendekatiku. Wajahnya nanar tak bisa menyumbunyikan kekagetan. “Apa kamu sudah mengetahuinya?”
Aku kelu. Apa Norman sudah tahu tentang kabar kematianku dari Dokter Siwon? Bukankah seharusnya catatan medis tak boleh mudah bocor kepada siapa saja, tanpa izin dariku. Tetapi Dokter Siwon pastilah memiliki alasan kuat, terlebih melihatku limbung saat meninggalkan ruangannya. Dan Norman adalah satu-satunya nama orang terdekatku yang Dokter Siwon ketahui.
“Ya, aku sudah tahu semuanya. Aku terpukul, Norman!” aku ingin meraih tubuhnya untuk mendiamkan ombak di dalam dadaku. Tetapi, Norman justru menjauh. Seolah aku tak pantas dipeluk.
“Ya, ampun. Padahal aku tidak ingin kamu mengetahui dengan cara seperti ini, Lucia. Apakah Leo yang mengabarkannya?”
Aku terdiam. Aku tidak mengerti mengapa Norman harus menceritakan semua ini kepada Leo. Meski aku tahu betul, keduanya akrab bahkan semenjak aku mengenal Norman.
“Lucia, aku telah memulai konseling Senin lalu. Dan aku akan menemukan jawaban atas kegelisahanku ini?” Norman tak berani mengangkat mata.
Aku tahu kesedihan pasca mengetahui tenggat akhir kematianku begitu besar dan mengguncang. Tetapi apa perlu Norman melakukan bimbingan psikolog. Bukankah aku yang seharusnya membutuhkan?
“Lucia, mungkin aku sedang dilanda kegundahan soal orientasi seksual. Aku di tengah ombak keraguan. Mungkin….”
Sampai titik itu, apa-apa yang dikatakan Norman tak bisa kucerna sempurna, namun penuh mahadaya menghantamku. Dia sinting? Dia gila! Aku tahu pemanasan global akibat ulah manusia telah mencairkan ribuan kubik gletser. Populasi China meledak dan angka ketersediaan pangan tak mencukupi. Dan cinta memang kerap membuat buta. Tapi apa harus dia menyampaikan di saat seperti ini.
“Norman!” Tanganku meraih garpu dan sekelebat aku menancapkannya ke telapak tangan Norman. “Aku baru saja kehilangan simpati darimu. Dan …..”
Kalimatku tak kuteruskan. Aku menangis, entah karena kematian yang dekat atau gegap berita yang lebih dahsyat dari bom Hiroshima itu. Dan Norman kusaksikan terisak, entah karena penyesalan atau garpu di telapak tangannya yang kuyakin mulai menyebarkan ngilu dan sembilu ke seluruh tubuhnya. []
February 17, 2019
Belum Ada Judul
Tribun Jabar, 17 Februari 2019
[image error] sumber: behance.net
Dengkur istrinya di ruang sebelah disahut dengkur yang lebih halus dari anak pertamanya. Suasana malam telah menjadi kemul yang menggumuli isi rumah, petak jalanan, dan setiap lorong. Hanya matanya yang belum rela dia katupkan. Dia masih menghadapi layar komputer yang menjadi sumber satu-satunya cahaya terang di ruangan kecil yang sudah lama dia sulap sebagai perpustakaan sekaligus ruang kerjanya, tempat dia menulis dari selepas makan malam, kira-kira jam sembilan hingga maksimal tengah malam. Begitu dia mematok jadwal bekerjanya sebagai penulis.
Namun, berbeda dari biasanya, kali ini semua mandek di ujung-ujung garis akhir. Dia sadar, dia bukan Derek Redmond yang meski gagal di menjelang garis finis, bantuan datang dari luar pagar pengaman. Dia penulis paruh waktu yang bekerja sendiri, tidak ada pertolongan kecuali dari Tuhan atau Setan. Berjam-jam dia telah menulis cerita, kemudian berhenti ketika dia kesulitan menemukan sepotong judul paling tepat untuk seluruh tubuh ceritanya.
Tidak seperti biasa. Ketika memasuki jam kerja sebagai penulis, dia akan membawa notes kecil warna cokelat tua. Dari sana biasanya dia menggunakan daftar kata-kata paling indah yang ditemukan di sembarang waktu-tempat untuk dijadikan judul. Ini trik yang dia dapatkan ketika menghadiri diskusi buku bersama Kurnia Effendi, yang dari kisahnya kerap mencatat semua kata-kata indah untuk dijadikan awalan menulis.
Berbekal kisah itu, saban hari ke mana pun dia mengantongi notes kecil itu. Bila menemukan kata-kata indah, dia akan mencatatkannya. Nantinya saat di rumah, dari salah satu kata yang ada dari dalam notes dia akan kembangkan menjadi sebuah cerita. Dari judul terpilih, dia bisa meneteskan kalimat-kalimat hingga terbangun cerita padu.
Kali ini dia berkebalikan. Selepas makan malam, yang entah mengapa kali ini istrinya menghidangkan bihun dengan kuah pedas yang dilengkapi dengan bokcai dan beberapa iris dada ayam dengan bumbu ekstra pedas. Dia dapat melihat irisan cabai rawit dan bumbu tabur level 30. Tidak biasa memang. Tetapi kelezatan ayam dan bihun kuah pedas membuat dua mangkuk tandas sekali menunduk. Istrinya berkomentar kalau makanan pedas selain menghilangkan stres juga meningkatkan mood menulis.
Beranjak dari meja makan, seketika perutnya berontak. Dia lari ke kamar mandi, yang disusul tawa keras istri dan anaknya. Di kamar mandi itulah cerita berkembang di kepalanya. Suara kran air yang menetes, wangi barus yang tergantung dekat pintu, keramik putih yang mulai berbercak oleh cipratan odol dan sabun cair mendadak menumbuhkan sebuah kisah yang tak dapat dia kendalikan lajunya. Urusan perut selesai, cerita di kepalanya berontak ingin dituliskan.
Seperti dirasuki taksu, dia menyalakan komputer dan mulai mengetik. Suara tekanan ujung jemari di atas tombok huruf keyboard menutup liang telinga, hingga tanpa sadar ketika cerita selesai malam sudah masuk ke pertengahan. Tapi PR paling penting belum dia selesaikan. Soal judul.
Dia harus menemukan sepotong frasa, istilah, atau metafora paling indah untuk menggambarkan cerita yang kali ini dia berhasil tulis. Beberapa frasa yang dipilihnya sedetik kemudian dihapus. Itu tidak cocok. Terlalu picisan. Terlalu visual dan kurang misterius. Bukan judul yang pas untuk sebuah cerita sastra.
Dia mengembuskan napas. Sejam setelah cerita rampung ditulis, dia bertanya kepada malam yang kali ini mulai mengejek kedunguannya. Apa pentingnya sebuah judul? Bukankah cerita akan tetap bagus kalau kisahnya padu dan tetap menarik dibaca. Kemudian suara lain menentang pikiran busuk itu. Judul itu seperti tampilan luarmu! Dia saja setiap pagi mencatut dirinya hampir setengah jam di depan cermin untuk mengaca dan menata tampilan. Jadi kalau cerpen kamu bagus tapi judul kamu busuk, itu mirip politisi. Mungkin maksud tujuannya baik, tapi cara dan ucapannya muslihat macam nenek sihir.
Dia beranjak dari kursi. Tubuh dia renggangkan. Punggung dia luruskan. Jemari dia lemaskan. Dan dia hirup dalam-dalam udara lepas tengah malam yang mulai digelayuti embun, meski tipis. Dia berjalan sebentar ke sekeliling meja kerjanya. Menyimak judul-judul buku yang dia punyai. Kemudian matanya terhenti dua buku dengan judul yang sama oleh dua pengarang dunia yang berbeda generasi. Men Without Women.
Ah, kenapa tidak meniru cara Murakami menulis judul, pikirnya. Toh Murakami sah-sah saja bila harus meminjam judul Ernest Hemingway, George Orwell, Raymond Carver, atau mencuri nama Scheherazade dari Kisah Seribu Satu Malam. Kalau tidak begitu, meminjam judul lagu sebagaimana Murakami meminjam judul lagu-lagu The Beatles.
Dia coba memikirkan sebuah judul milik orang lain yang sekiranya tepat untuk dijadikan judul cerpennya, tentu yang mewakili cerita yang baru saja dia bikin. Hampir dia menulis judul Namaku Merah, sebelum dia ingat tokoh utama dalam ceritanya adalah seorang nenek yang hanya dia sebut sebagai Perempuan Tua yang Ingin Cantik. Beberapa judul milik orang lain yang dia coba pun selalu buntu. Tidak cocok. Memang lebih nyaman memilih judulnya sendiri, bukan meminjam punya orang.
Dia kembali menatap layar komputer dengan kursor berkedip tanpa lelah. Sebuah ide bergerak dalam kepalanya. Dia membuka playlist dalam iTunes, meneliti satu demi satu judul lagu yang kerap dia pergunakan sebagai latar menulis cerpen. Tangannya bergerak cepat tak menemukan satu pun yang menarik. Ternyata memilih jauh lebih sulit. Tidak semudah membiarkan musik-musik itu menyusuri parit syaraf dan mengairi lubang telinga. Dia kembali mendengus.
Matanya semakin berat, dia sudah bekerja lembur untuk sebuah cerita. Sedangkan besok, dia harus kembali bekerja di kantor dengan tuntutan yang berbeda. Dia tidak mau enjakulasi dini karena tak berhasil merampungkan cerita dengan hanya menyisakan pemberian judul. Bukan hanya sejatinya.
Bila cerita yang sudah jadi itu dia biarkan, sama saja membiarkan sepiring bihun goreng basi tanpa disentuh. Itu bukan sifat aslinya.
Karena judul adalah pertaruhan pertama di depan pembaca. Dia sendiri yakin, pemilihan judul adalah cara pertama membuat redaktur jatuh cinta pada tulisan kita. Dan bila dia memakai cara Murakami dengan meminjam judul orang, redaktur akan jengah dan bisa-bisa berpikir ini penulis kreatif tapi kreativitasnya tumpul. Dia menggeleng.
Dia mengetuk-ngetukkan kepalan tangan pada tengkorak kepala. Berharap sebuah kata mbrojol keluar dari lipatan neuron kepalanya. Pasti ada kata, frasa, istilah, metafora yang pas untuk setubuh ceritanya yang dia sangat yakin bagus tersebut.
“Kamu belum tidur?” suara itu mengagetkannya.
Dia memutar pandangan. Istrinya menguap berdiri di ujung pintu.
“Belum selesai.”
“Dan sebentar lagi azan subuh,” istrinya menimpali. “Kamu bisa kena masalah kalau ngantuk di kantor.”
Dia melihat empat angka di pojok bawah layar komputer. Sudah lewat jam 4 pagi. Dia belum tidur dan ceritanya belum rampung. Dia gagal menemukan judul.
“Judulku hilang. Aku belum nemu judul yang baik.”
“Memang ceritamu soal apa?” istrinya mendekat dan membaca enam halaman ceritanya di layar komputer. Dia menanti reaksi paling pertama dari istrinya. Tersenyum. Kemudian tertawa lepas.
“Ini tentang perempuan tua itu? Kalau begitu enggak perlu diberi judul. Kisahnya sudah menggelikan.”
Tidak menyelesaikan persoalan, pikirnya. Dia begitu kesal, entah kepada dirinya yang kali ini tumpul ide judul, kepada istrinya yang tak membawa penyelesaian, kepada malam yang berlari begitu cepat, atau kepada tokoh ceritanya yang memang menyebalkan sedari awal.
Dia mematikan layar komputer. Dia berkeyakinan cerita soal perempuan tua itu memang cerita yang belum ada judul. Diam-diam dia berharap dapat bersua dengan editor atau redaktur untuk meminta usulan judul. Atau mungkin Anda, pembaca budiman, bisa memberikan usul judul apa sekiranya yang tepat untuk sebuah cerita seorang perempuan tua delapan puluh tahun yang datang ke dokter kecantikan minta dioperasi agar lebih mudah, lebih cantik dari putrinya. Silakan! Dia pasti senang menerima usul dari Tuan dan Puan Budiman. []
February 4, 2019
Kisah dari Bandar Rempah
KOMPAS, 2 Februari 2019
Novel tebal ini baru saja diganjar Kusala Sastra Khatulistiwa 2018, salah satu penghargaan sastra bergengsi di negeri ini. Azhari Aiyub sejatinya bukan nama baru dalam dunia susastra Indonesia. Kumpulan cerpen pedananya, Perempuan Pala juga pernah menjadi nominasi di ajang yang sama pada tahun 2004. Azhari selama ini memang lebih dikenal publik sebagai penulis cerita pendek, yang menyabet penghargaan atau dimuat di berbagai media massa nasional. Novel ini menjadi buah perbincangan lantaran keunikan sekaligus ketekunan Azhari dalam merajut kisah. Beberapa potongan dalam novel ini juga pernah tersiar sebagai cerita pendek di beberapa media massa.
Novel yang mulai dianggit semenjak 2006 ini paripurna menjumpai pembaca setelah lebih dari satu dekade dijahit oleh penulisnya. Masa sepanjang itu dapat dikategorikan cukup panjang dan sia-sia belaka bila hanya menghasilkan karya biasa saja. Namun juga bisa dikategorikan cukup pendek untuk menghasilkan karya besar. Sebagai pembanding misalkan, Gabriel Garcia Marquez menulis judul kanonisnya, One Hundred Years of Solitude selama enam tahun, dimulai tahun 1961 hingga terbit pertama kali dalam bahasa Spanyol pada tahun 1967.
Azhari membuktikan dalam novel ini bahwa satu dekade waktu yang sepadan untuk menghasilkan kisah menakjubkan ini. Novel setebal hampir seribu halaman ini, juga merentang kisah dalam kurun waktu yang terbilang panjang. Ketebalan novel ini berhasil mengalahkan rekor beberapa novel sastra tertebal sebelumnya, Arus Balik setebal 760 halaman, atau Ular Tangga milik Anindita S. Thayf dengan tebal 736 halaman.
Bukan hanya berhalaman paling banyak, Kura-Kura Berjanggut pun membentangkan kisah dengan titimangsa latar cerita yang sangat panjang. Kisah ini berangkat dari dunia rekaan di abab ke-16, kemudian sempat melompat hingga awal abad ke-21, ketika seorang peneliti dari Belanda, Tobias Fuller melacak catatan demi catatan perihal sebuah kitab Kura-Kura Berjanggut.
Kisah panjang Azhari digerakkan oleh sebuah motif pembunuhan Sultan Nurruddin, dari Bandar Lamuri, oleh Si Ujud. Si Ujud sendiri adalah seorang sangkilat, mata-mata yang ditempatkan Sultan Nurruddin di salah satu menara demi mengamati pergerakan kapal pedangang rempah dan perompak yang menguasai lautan. Jauh sebelum menjadi sangkilat, Si Ujud adalah seorang penjelajah hingga kawasan Timur Tengah dan Istamboel untuk belajar. Dalam pengembaraan itulah, kabar bahwa keluarga dan semua penduduk di tempat tinggalnya dibasmi oleh kaki tangan Sultan Nurruddin. Dendam ini kemudian membawanya kembali ke Bandar Lamuri, dan memaksanya merangsek ke barisan kepercayaan Sultan Nurruddin.
Satu motif ini kemudian Azhari timpa dengan beragam kisah dan plot sempalan yang sama-sama kuat. Azhari menyentil pergolakan politik di Istana Darud Dunya, para pedagang rempah, serta komplotan bajak laut yang trengginas dan ganas. Kisah-kisah pendukung Si Ujud ini membuat bangunan kisah dalam novel komplit nan menawan.
Kisah Si Ujud selesai di bagian satu, Buku Si Ujud, yang memakan dua per tiga keseluruhan halaman novel. Sultan Nurruddin berhasil tewas dan dendam Si Ujud terbayar lunas. Tiga abad kemudian seorang peneliti dari Belanda, Tobias Fuller melakukan penelitian perihal beberapa kematian orang Belanda yang tak tercatat oleh pemerintahan Hindia Belanda. Penelitian ini kemudian menyingkap betapa ajaibnya kitab penuh misteri bernama Kura-Kura Berjanggut, yang dipercaya memiliki andil dalam kematian Sultan Nurruddin di bagian satu. Buku catatan ini dimulai 3 Mei 1914 dan ditutup dengan penuh misteri pada tanggal 1 Oktober 1915.
Sedangkan di bagian tiga, Lubang Cacing, adalah bagian yang sebenarnya tidak menjadi bagian pokok cerita Si Ujud. Tetapi memiliki kedudukan untuk menjelaskan beberapa bagian pada dua bagian sebelumnya, sehingga catatan-catatan pelengkap ini penting untuk menutup lubang yang belum sempat ditutupi di bagian satu dan dua.
Semenjak membuka halaman pertama, dunia niskala rekaan Azhari membentang untuk dijelajahi. Di setiap kelokan, Azhari menyisipkan kisah-kisah dan interteks dengan sejarah dan tokoh pada dunia nyata. Dalam novel ini Azhari secara tersirat menyinggung beberapa nama yang memang benar ada dalam sejarah, misalkan Hamzah dari Fansur atau menyenggol tokoh Snouck Hurgronje ketika era kolonialisme Belanda.
Novel ini menjadi pembuktian penting seorang penulis. Masa panjang dalam proses penulisan bukan hanya membuat novel ini kaya akan data, hasil riset penelitian demi membangun novel, juga bagaimana Azhari tekun merangkai cerita. Menilik jumlah halaman yang tebal, akan menjadi bumerang bila kisah-kisah dalam novel sekadar tempelen hasil riset.
Azhari tidak bermaksud menjadikan Kura-Kura Berjanggut sebagai sebuah kumpulan hasil riset belasan tahun, yang perlu dibaca dengan kacamata seorang peneliti. Novel ini adalah fiksi seratus persen. Novel ini adalah dongeng yang enak dibaca pembaca, yang tak butuh bekal pengetahuan sejarah. Penulis adalah pencerita ulung yang membuat pembaca betah membuka hampir seribu halaman, karena kerapian berkisah, jalinan cerita menegangkan, dan misteri yang tak bosan diikuti.
Ini juga menjadi pembeda dari kebanyakan novel yang berangkat dari kejadian sejatinya. Bila kebanyakan novel berusaha mendekonstruksi sejarah, hingga kisah sejarah tampak seolah fiksi. Azhari membalik, kisah yang murni dongeng dalam Kura-Kura Berjangut justru berhasil membuat pembaca turut membayangkan Bandar Lamuri dan Istana Darud Dunya, seolah semua dongeng adalah fakta.
Keberhasilan Azhari berkisah perlu diberi angkatan topi dan apresiasi tinggi. Kesabaran menjahit cerita dengan riset yang sangat kuat tanpa celah, memantaskan Kura-Kura Berjanggut sebagai salah satu novel terbaik sepanjang 2018 dan sebagai nominasi kuat untuk kategori prosa pada Kusala Sastra 2018. Penulis yang pernah dianugerahi Free World Award dari Poets of All Nation (PAN) Belanda ini benar-benar seorang pendongeng ulung, di mana kisah sepanjang hampir seribu halaman, tak sekali pun menumbuhkan rasa bosan. []
January 19, 2019
Hidup Minimalis: Bahagia Tanpa Benda
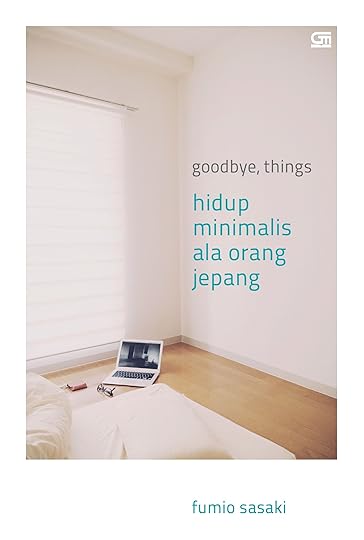
“Hidup Minimalis hanya satu cara agar hidup lebih bahagia. Jadi bila ada yang memiliki banyak barang di rumah, tetapi tetap menjaga hubungan baik dan merasakan kebahagiaan, saya rasa itu luar biasa,” demikian Fumio Sasaki berujar saat diwawancarai Cosmopolitan. Hidup Minimalis yang diusung Sasaki dalam Goodbye, Thingsmemang mencoba melepaskan manusia dari “bahagia yang bergantung benda” yang mungkin dinilai banyak orang begitu hardcore.
Fumio Sasaki dan buku ini menjadi serentetan “kampanye hidup minimalis” yang belakangan digemari banyak orang. Marie Kondo telah lebih dahulu mengkampanyekan seni berbenah agar rumah lebih lengang dalam The Life-Changing Magic of Tidying Up. Francine Jay juga menyerukan hidup minimalis dengan metode STREAMLINE lewat Seni Hidup Minimalis.
Namun, yang dilakukan Sasaki boleh dikatakan lebih ekstrem dari dua “kakaknya” tersebut. Sasaki bukan sekadar merapikan ruang, melainkan benar-benar membuang barang, melepaskan diri dari kebendaan. Tidak ayal, tips pertama yang dianjurkan adalah buang satu barang sekarang juga. Jika menunggu ada waktu, percayalah itu tidak akan terlaksana. Sebab waktu yang ditunggu itu tidak akan pernah ada.



