Teguh Affandi's Blog: arsip alterteguh, page 7
January 21, 2018
ORIGIN: Biasa Templatenya, Megah Idenya
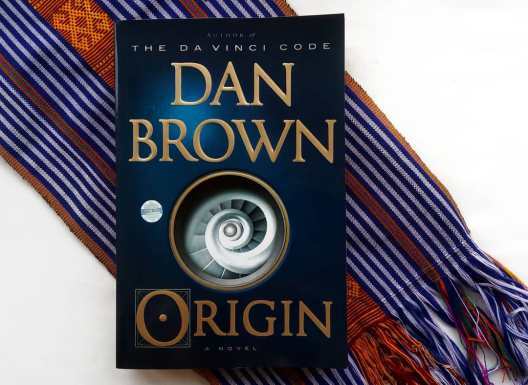
sumber gambar: instagram
Saya membaca Dan Brown pertama kali di buku The Da Vinci Code, lama sekali. Waktu itu hak terjemahan bahasa Indonesia masih di Serambi, dan saya baca dengan terkantuk-kantuk di sepanjang kereta Jakarta-Jogja. Mungkin karena saya masih cupu dan bodoh, saya tidak terlalu paham dengan ide-ide Dan Brown. Terlebih waktu itu internet masih jauh dari genggaman tangan, hingga harus duduk di depan PC untuk mencari informasi lengkap terkait lokasi, karya seni, atau kode-kode ajaib dalam buku tersebut. Namun, saat buku itu dialihwahanakan menjadi film dan saya sudah ‘rodo nggak cupu’ saya baca kembali novel itu dan memang penulis ini ‘gila’. Obsesi dan bagaimana keutuhan risetnya adalah yang juara. Meskipun saya tidak mengikuti semua judul Dan Brown secara rutin, tapi secara ide-ide dalam bukunya selalu mencengangkan.
Dan harus diakui kalau teman-teman membaca (tidak harus semua judul Dan Brown) alur perjalanan dan pengungkapannya tidak terlalu jauh berbeda. Ya 11-12 gitu. Dan novel “Origin” menurut saya juga demikian. Saya bahkan di awal sempat kesal, “ini penulisnya ngapain sih, berlarat-larat ingin lama dengan narasi tidak terlalu penting.” Namun, yang harus dikagumi adalah bagaimana ide Dan Brown. Apalagi ‘kegelisahan’ dalam buku ini, beberapa kali saya temukan di buku lain atau film yang lain. Bahkan di beberapa bagian saya sempat berpikir, jangan-jangan agama hanya alusi manusia karena tidak mampu menjelaskan sesuatu yang megah-besar. Soal penciptaan dan akhir dunia. Makanya mereka menyerahkan kepada kekuatan maha yang di dogma itulah kita bersandar. “Tuhan yang bertindak di balik semua ini.” (untung saya tidak jadi ateis setelah membaca buku ini)
Dari mana kita berasal? dan Kemana kita setelah ini?
Dan Brown mencoba menjawab pertanyaan itu dengan hati-hati dengan temuan Edmond Kirsch!
Ulasan saya ada di Jurnal Ruang.
December 31, 2017
Melodrama Superhero
Tribun Jabar, 31 Desember 2017
Mimpiku? Sama. Sejak kecil aku bermimpi menjadi superhero dengan kostum paling gagah yang bisa kubayangkan. Tubuh terjiplak ketat dengan simbol kebanggan di tengah dada. Aku ingin menjadi superhero. Hingga bisa terbang menyelamatkan gadis yang tergantung di beranda apartemen, membantu kasir toko emas saat ditodong perampok, atau sekadar membunyikan lonceng tahun baru atas undangan khusus walikota.
Impian itu menjadi kenyataan ketika aku sedang terpuruk akibat persoalan asmara. Kekasihku menikah dan tanpa mengirim pesan pernyataan berpisah. Aku merasa seperti sebentuk bayangan yang tanpa pernah dikehendaki kehadirannya. Dia, kekasihku yang selalu kukirimi pesan pengingat makan, ternyata lebih memilih orang lain. Aku memutuskan untuk mengakhiri hidup saja. Tidak ada lagi orang yang akan kukirimi pesan pengingat makan siang.
Aku pergi ke Bukit Golgota. Aku ingat, di sana ada pohon yang lekuk tajuknya mirip bentuk kepala Kumbakarna. Di sanalah salah seorang kawanku menggantungkan diri. Aku ingin mengikuti dia. Meski aku tahu, Bukit Golgota itu sekarang tak lagi sama dengan sepuluh atau lima belas tahun lalu. Lantaran seorang pebisnis batubara berhasil menemukan kandungan timah yang cukup banyak, 300 meter di bawah Bukit Golgota. Akibatnya, mobil pengeruk, kemah penambang, bangunan kantor menutup sebagian Bukit Golgota. Walaupun pohon yang mirip kepala Kumbakarna itu masih ada, aku tetap harus memutar jauh agar tidak harus melewati pengamanan tambang timah.
Setelah berjalan lebih dari setengah jam, kakiku kesemutan. Aku duduk di atas batu besar, pohon yang mirip kepala Kumbakarna masih jauh di ujung pandangan. Dua hasta di depan saya, jurang yang menjadi penanda penambangan menganga. Tak dalam. Mungkin 10 atau 15 meter. Napasku satu-dua, keluar seperti seorang kakek yang diminta mengangkut sekarung beras. Mungkin aku akan mengkahiri hidup di sini saja. Bila kehidupan sudah terlalu perih, lantas mengapa harus membiarkan hidup merasakan kesakitan lebih.
Aku tidak membawa pisau, racun serangga, atau senjata tajam. Hanya tali tambang untuk menggantung tubuhku di pohon yang mirip kepala Kumbakarna. Sebaiknya aku tali saja sebongkah batu dan aku pukul-pukulkan ke batok kepala. Kalau pun aku tidak mati, pastilah aku kehabisan darah, payah, akibat luka bentur yang aku ciptakan sendiri. Kemudian mati oleh dingin atau ikut tergerus akibat Bukit Golgota yang hancur oleh tambang.
Dalam masa pencarian itulah mataku menangkap sebuah kerlip yang sedikit berbeda. Warnanya hitam mengilat, seperti adonan dodol yang pekat bila terkena kerlip matahari. Ukuran batunya tidak besar. Hanya sebesar genggaman tangan. Posisi ada di bawah bongkahan besar yang kuniatkan sebagai senjata untuk melukai diri sendiri. Batu apa gerangan? Mungkinkah itu bagian dari batubara yang mencelat dari jurang tambang? Kupungut. Kutimang-timang. Debu-debu kuusap dengan kaos bagian dalam. Kemudian kilatnya semakin cerlang.
Batu apa gerangan? Tekstur permukaannya sehalus batu akik yang sudah diasuh sekiah ratus kali. Begitu jernih seperti kolam ikan yang baru saja dibersihkan. Mataku mengintip sesuatu bentuk yang tersimpan di dalam batu itu. Seranggakah itu? Atau fosil nyamuk purbakala? Andai ini benar-benar fosil seekor nyamuk zaman purbakala, aku akan bahagia karena menjadi kaya meski cintaku tak menghadirkan bahagia.
Saat, mata masih mengamati. Mendadak Bukit Golgota diguncang lindu. Aku bisa merasakan skalalnya cukup besar. Batu besar menggelinding dan jatuh ke jurang. Kemudian dahan-dahan berguncang. Tubuhku pun ikut limbung. Batu kusakui dan kuikuti goyangan gempa. Tubuh saya jatuh ke dalam jurang.
***
“Selamat datang, Jason!” suara itu membangunkanku.
Mataku sayup-sayup. Kesadaranku masih belum optimal 100%. Ketika mata sudah terbuka sempurna, aku menangkap sebuah robot kecil dengan bentuk kepala ceper mirip piring terbang dengan lampu-lampu merah berkelap-kelip. Kakinya berbentuk roda dan dua tangan berbentuk supit. Aku terkesiap. Aku berdiri dan kemudian melangkah dua tiga langkah mundur. Mengambil ancang-ancang. Aku lebih memilih untuk mengkahiri hidup sendiri daripada harus mati di tangan robot yang tak punya hati.
“Jason! Selamat datang di Kapal Rangers,“ suaranya tersendat-sendat serupa pita kaset yang tergores ujung pena.
“Kalian makhluk apa?” suaraku terbata.
“Tenang Jason! Aku tidak akan membunuhmu!”
“Bagaimana aku bisa masuk ruangan ini?” tanyaku.
“Kristal Merah yang telah kamu temukan. Kamu terpilih! Kamu terpilih! Kamu yang kedua setelah Zack!”
Kemudian robot itu berkisah dengan bantuan muka seseorang yang terpahat di dinding kapal. Robot itu bernama Alpha 5 dan muka yang terjiplak dalam kapal adalah Zoron. Mereka berdua sedang mengumpulkan satu demi satu Ranger. Sekawanan superhero yang dipilih Zoron untuk mengembalikan Kristal Aurora miliknya, yang apabila tidak, bumi bisa hancur.
Dadaku seketika terkesiap. Aku menjadi superhero. Aku menjadi pahlawan.
“Benar!” sahut Alpha 5.
“Tapi kita harus menunggu tiga kawan lagi. Aku ranger hitam dan kamu ranger merah,” Zack lelaki yang sejak pertama kali kutemui tak sekali pun mau mengenakan kaos itu.
“Sudah berapa lama kamu di sini?” tanyaku kepada Zack.
“Mungkin dua minggu,” jawabnya.
Dua minggu sampai aku datang bergabung. Aku tentu tidak akan menceritakan alasanku pergi ke Bukit Golgota, hingga menemukan batu merah yang kemudian terpilih secara acak menjadi ranger merah.
Selama masa penantian, Zoron dan Alpha 5 bergantian melatih kami berdua. Zack dan aku diajar bagaimana berubah menjadi ranger. Kami dibekali keahlian membangkitkan kekuatan dan memanggil robot sebagai bala bantuan. Robot itu adalah potongan-potongan dari bagian pesawat tempat Zoron dan Alpha 5 berdiam.[image error]
Ternyata menjadi superhero sama saja dengan sebuah menang undian. Aku sendiri tak pernah membayangkan menjadi superhero akan semudah ini. Tanpa sengaja menemukan batu merah, terjerembab dalam kapal, kemudian dilatih mempergunakan kekuatana dan aneka robot buatan Zoron dan Alpha 5. Bahkan bila kelak dalam pertempuran kami hampir saja mati, Zoron memberitahukan bahwa ada satu tombol yang itu berfungsi untuk memanggil Zoron, sumber segala kedigdayaan kami. Kemudian Zoron melawan dan memberi jurus paripurna penghabisan musuh. Ah, ternyata begitu gampang menjadi pahlawan.
“Gampang. Tapi Zoron baru akan melepaskan kita sebagai pahlawan bila kita sudah genap lima. Power ranger harus lima,” Zack menegaskan suatu kali seusai latihan.
“Sekarang kita sudah satu bulan di kapal ini,” jawabku.
“Kamu bosan? Menyerah jadi pahlawan?” kalimat Zack penuh sindiran.
“Tidak. Menjadi pahlawan dan superhero adalah impianku. Dan di luar sana, akan banyak orang yang menanti pertolongan Power Ranger,” timpaku.
Zack berdiri, tangan kirinya menyambar sebotol minuman khusus yang dibuat Alpha 5. Kita tak pernah tahu bahannya apa. Tapi berhubung rasanya nikmat dan membuat badan terasa ringan dan lebih kuat, aku dan Zack tak mengajukan protes.
Meskipun kami disibukkan latihan dan strategi perang, menunggu tiga batu lainnya–batu biru, kuning, dan merah muda ditemukan adalah pekerjaan yang sangat tidak kusukai. Aku sudah berulang kali bertanya kepada Zack apakah sudah ada tanda akan ada penemu batu lagi. Zack hanya menggeleng.
Apakah di luar sana orang sudah tidak membutuhkan pahlawan? Apakah dunia sudah begitu aman-damai-sentosa sehingga pahlawan dihapus dari kamus besar mereka. Aku takut, impianku menjadi pahlawan justru akan mengurungku di kapal ini dan membuatku mati tua karena menunggu.
“Zack? Apakah superhero dan pahlawan harus menunggu sebegini lama?”
“Seharusnya tidak! Zoron dan Alpha 5 saja yang sepertinya salah perhitungan dan mendarat di Bukit Golgota,” kalimat Zack membuat badanku tegak.
Bukit Golgota pasti sekarang telah hancur oleh penambangan? Batu-batu kecil pastilah sudah lumat atau terendam lebih dalam. Bagaimana tiga batu berwarna lainnya akan ditemukan, kalau Bukit Golgota saja sudah raib oleh penambangan. Lantas bagaimana nasib power ranger yang aku dan Zack impikan.
“Nasib kita akan semakin tua di sini,” kataku.
“Aku akan protes kepada Zoron dan Alpha 5,” Zack seketika berdiri dan menuju ruang utama di mana Zoron dan Alpha 5 berada.
Protes Zack ternyata hanya ditanggapi untuk menunggu. Aku mengumpat sekali. Zack menyumpahi kemudian menendang meja dan membanting tubuh Alpha 5.
Aku dan Zack meyingkir dari ruang utama. Pertengkaran bukan tabiat seorang superhero. Kami berdua duduk di dapur, tempat kami makan. Zack memilih anggur putih meski siang masih belum menandakan turun.
“Bajingan mereka berdua!”
“Aku juga bisa merasakan, usaha menjadi superhero ini sia-sia saja. Tidak ada yang butuh superhero.”
“Apalagi kalau semua orang sudah menjadi bandit, tak butuh pengusir bandit,” Zack menenggak segelas anggur sekaligus.
Aku biarkan Zack menghabiskan satu botol anggur putih. Hanya dua gelas yang berhasil aku teguk, itu pun sekadar menemani Zack yang benar-benar kalut. Pikiranku sudah kalut sejak lama. Aku lebih ingin mengingat kembali bagaimana hidupku bisa sedemikian tak beruntung. Semua ini lantaran keinginan mati dan melupakan luka akibat patah hati. Benar kata orang, kalau patah hati adalah luka yang dalam dan terbawa sampai mati.
Sekarang nasib akan kuhabiskan di kapal ranger ini dengan impian menjadi menjadi Ranger Merah terwujud. Yang itu entah kapan. Dalam hitunganku sekarang sudah masuk bulan ke delapan. Menjadi pahlawan ternyata melelahkan.
“Jason, apa kamu pernah terpikir mengapa aku bisa terjerembab di kapal ini?” Zack mulai terpengaruh alkohol. Kujawab dengan gelengan.
“Pacarku selingkuh di depan mataku sendiri.”
“Kita sama, Zack!”
“Ternyata permasalan pokok manusia termasuk superhero adalah asmara,” Zack meniriskan botol anggur putih. Tak ada setetes pun yang tersisa.
“Mengapa tidak kita selesaikan saja persoalan itu sekarang?” Zack mulai mengibul.
Mataku kemudian menatap bibir Zack yang begitu merah oleh sapuan anggur. Kemudian ada sesuatu yang hidup dalam diriku ketika menyaksikan tubuh Zack. Mimpi? Sekarang aku bisa menggenapi mimpi. Bukan superhero, memang. Ini perihal asmara. []
Untuk film Power Ranger (2017)
sumber gambar: Behance, Dan Mora


December 18, 2017
Bacaan 2017
Seberapa banyak buku yang kamu baca di 2017? Saya termasuk yang sangat lambat membaca. Sampai kos kadang sudah tepar atau kadang disibukkan dengan tontonan. Heeeheee ^^
Pola genre masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, ada genre baru yang saya sukai thriller di 2017. Saya kutip dari akun Goodreads sayaternyata bacaan saya cuma segini setahun. Duuuuh, malas banget saya yaaa tahun ini.


December 13, 2017
Memikat Tanpa Muslihat
Beberapa kali saya ditanya buku fiksi apa yang paling membuat terkesima sepanjang 2017 untuk buku fiksi Indonesia, maka saya akan dengan tegas menjawab Muslihat Musang Emas (Penerbit Banana, 2017) milik Yusi Avianto Pareanom. Meksipun saya tahu, saya tidak punya kapasitas mengkritik buku sastra, saya[image error] hanya berusaha membaca buku sastra dan sedikit mengocehkannya. Dan sayangnya, kemampuan membaca saya juga tidak paripurna. Banyak sekali buku sastra yang terbit dan saya tidak membaca semuanya. Beli online dong, Teguh? Sayanganya lagi, saya termasuk orang yang konvensional dalam membeli apa saja. Jadilah, saya kerap mengandalkan toko buku fisik dan toko buku online yang kerap saya ‘titipi’ untuk beli buku yang tidak ada di toko buku fisik. Sehingga kesimpulan pertama saya memilih Muslihat Musang Emas, masih sangat personal dengan keterbatasan cakupan bacaan saya.
Tetapi, dibandigkan Rumah Kopi Singa Tertawa (Terbit pertama 2011 dan diperbaharui 2017) saya jauh lebih terpuaskan dengan Muslihat Musang Emas. Cerpen-cerpen dalam buku ini tidak sekadar cerpen yang telah dimuat di media massa dan kemudian diikat menjadi buku, sebagaimana kebiasaan buku kumpulan cerpen kita. Paman Yusi seolah benar-benar membuat ceritanya baru dan tidak terendus oleh pembaca sebelumnya. Kecuali satu cerpen, Ia Pernah Membayangkan Ayahnya adalah Hengky Tornando, yang pernah masuk dalam antologi buku tentang Tubaba. Selebihnya adalah cerpen-cerpen baru yang membahagiakan. Mengapa membahagiakan? Kisah-kisah sial dalam buku ini benar-benar bikin kita terpingkal. Apalagi sesuatu yang kalau dalam bahasa stand up comedy, punch line yang bikin terbahak.
Sedikit curhat saya setelah membaca Muslihat Musang Emas dimuat di Jurnal Ruang.


December 10, 2017
Misi Baik Dalam Komedi
Koran Tempo, 9-10 Desember 2017
Pengarang Amerika Serikat Charles Dickens mengatakan orang-orang di negaranya tidak memiliki humor, labil, mudah marah, dan itu membuat daratan Amerika tampil menyeramkan. Namun bukan berarti semua orang Amerika tidak memiliki selera humor. Terbukti, dari negara tersebut muncul salah satu gaya lelucon yang digemari di seluruh dunia bernama stand-up comedy.
Stand-up comedy atau komedi tunggal disukai, ditayangkan di berbagai acara stasiun televisi, dan menjadi pilihan anak muda untuk mengekspresikan kegelisahan mereka. Terbukti, banyak generasi muda yang kemudian menjadi komika—sebutan bagi pelakon komedi tunggal.
Komedi tunggal pertama kali muncul di Amerika Serikat pada 1950-an. Sebagaimana sejarah musik jazz, komedi tunggal bermula dari tradisi kelompok imigran, khususnya Afro-Amerika, yang lantas merebak ke berbagai lapisan masyarakat.
Di Indonesia, nama Pandji Pragiwaksono tak boleh lewat bila membicarakan komedi tunggal. Pandji juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Maka tidak mengherankan, bila menonton tayangan komedi tunggalnya, akan ditemukan kritik dan sindiran di tengah lawakannya.
Komedi tunggal menjadi salah satu cara Pandji menyampaikan suaranya. “Komitmen gue adalah menggunakan komedi sebagai alat perjuangan. Perjuangan untuk mencerahkan banyak orang, membuka wawasan orang,” ujar Pandji.
Tema-tema yang diangkat Pandji ke panggung bukan sekadar omong kosong, melainkan membangun kesadaran penonton. Dia tidak segan membawa isu hak asasi manusia di panggung komedi. Untuk memperkaya materi, Pandji dengan serius melakukan riset bersama Kontras dan aktivis dalam aksi Kamisan.
Komedi adalah cara yang mudah dan enak untuk menyampaikan sesuatu yang berat. Komedi membuat semua hal menjadi mudah diterima. Pandji bermaksud menggelindingkan bola salju dan membiarkan penikmat komedinya menerima efek berantai dalam pikiran masing-masing.
Pandji adalah komika yang mendobrak pakem. Dia memilih tema yang berbeda dari komika lain. Dia juga berani mempertontonkan komedinya di panggung dunia melalui Juru Bicara World Tour di 24 kota dan lima benua. Pandji bukan sekadar ingin naik ke tingkat internasional, tapi juga ingin membuka peluang bagi orang asing untuk belajar dan mengerti Indonesia.
Pandji menggunakan bit atau materi humor yang ditemukan di lokasi pementasan. Misalnya, ketika di Cina, ia menemukan soal kebiasaan buang angin warga setempat. Dalam tradisi Cina, angin buruk tidak boleh ditahan terlalu lama di dalam tubuh. Harus dikeluarkan, baik berupa kentut maupun serdawa. Hal ini kemudian menjadi materi pertunjukannya di Negeri Panda. “Saat berada di lift, ada seorang nenek yang buang angin dengan santainya tanpa memperlihatkan perasaan bersalah sama sekali. Kentut yang keluar pun sangat keras.”[image error]
Dalam tur dunia ini, Pandji menggunakan bahasa Indonesia. Ia tidak ingin menerjemahkan materi-materi komedinya ke dalam bahasa Inggris atau bahasa lokal. Menurut dia, dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia, penonton yang mungkin orang asing akan belajar tentang budaya Indonesia. Sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia percaya diri dengan identitasnya di hadapan majelis internasional. “Tidak perlu khawatir untuk berkarya dalam bahasa Indonesia. Berkaryalah dalam bahasa ibu untuk memukau dunia.”
Pandji dan timnya membuka jalan bagi seniman atau komika lain untuk menginjakkan kaki ke panggung internasional. Dalam buku ini, Pandji menegaskan, selain kerja keras, kerja sama tim, impian, dan keteguhan untuk berjuang harus terus diupayakan. Karena itulah buku ini diberi judul Persisten, yang bermakna bahwa mimpi dan misi baik harus terus diupayakan.
Pandji dan komedi-komedinya bukan sekadar menawarkan canda tawa pelepas penat. Dalam guyonannya terselip isu-isu sosial. Seperti menegaskan kembali kalimat Pandji: merdeka dalam canda, merdeka bersuara. []


October 30, 2017
Pohon Randu Wangi
“Aku pasti pulang, Ibu.”
Tanpa harus kusampaikan, janji itu kutanam bersama sebiji randu di pekarangan depan. Kuharapkan janji itu akan tumbuh bersama akar-akar randu. Menguat dan kokoh tidak goyah. Lalu pada masanya ketika dia pulang, pohon itu akan tumbang bersama rindu yang sudah lunas terbayar. Semacam dendang gembira Pak Tani mendorong luku di persawahan.
***
Kudekap erat potret sepia terbingkai figura. Beberapa bagian geripis digerus usia. Kuelus sebingkai foto, seperti mengelus pipinya yang gempil dan jerawat ranum yang tumbuh di sekitar hidung. Rindu sudah sedemikian menyerangku. Aku tak lagi bisa mengontrol jatuhnya air mata. Hingga tanpa harus terisak-isak dan meraung-raung, air mataku menuruni tulang pipi hingga membasahi dagu. Aku benar-benar rindu.
Walaupun rabun, masih bisa kuamati saksama pohon randu yang sedemikian tua itu. Pohon randu alih wujud gundukan rinduku padanya. Akarnya mulai keropos dan berongga. Kadang kala kusaksikan dari rongga di pokok randu itu, muncul hewan melata. Mungkin sanca atau boa yang menyeret hasil buruan berupa tikus dan anak ayam. Kapuk-kapuk yang dahulu biasa kupanen dan kujual sebagai isian kasur bantal, kini sudah lama tidak muncul. Memang masih berbunga, namun usia tua seolah tak lagi kuasa menjaga karuk yang merimbuni dahan. Kini pohon randu hanya menyisakan ranting-ranting kering dan lelah menopang sisa daun. Hijau keabu-abuan.
“Lik Pasini, bagaimana boleh ditebang?”
Lamunanku buyar. Kuletakkan figura di meja hati-hati. Tanganku bergetar. Menik berdiri di depan pintu menunggu jawabanku. Tangannya disangkutkan di pinggang. Dia sudah berkali-kali menyampaikan, mau tidak mau, pohon randu itu akan ditebang. Apa gunanya menyimpan sebatang pohon randu yang untuk mempertahankan hidupnya saja sudah kembang kempis? Pohon randu itu juga sudah urung menghasilkan kapuk. Pohon tua tak berbuah tak elok dipertahankan lama-lama. Seperti memelihara babon ayam tanpa pernah menghasilkan telur. Tak menguntungkan. Justru bisa mencelakakan.
Menik berhasrat sekali merubuhkannya. Rumah Menik bersebelahan dengan rumahku. Hanya dibatasi pagar dari perdu beluntas yang menempel di toko kelontong dan gudang gas LPG miliknya. Setiap hari selasa, akan ada truk besar datang mengganti tabung kosong dengan tabung hijau-biru baru.
“Menik, anakku belum kembali.” Aku membela.
“Kalau nanti pulang, suruh dia menanam durian saja. Atau jati. Harganya jutaan bila dijual,” tukas Menik.
Kukulum bibir bawah. Kurasakan kasar keriputnya. Dulu bibir ini biasa kupulas gincu. Banyak lelaki tertarik dengan ranum bibirku. Sekarang, tidak ada yang suka dengan bibir kering dan keriput meski dipulas dengan rona merah merona.
“Menik, kalau kamu butuh untuk kayu bakar, ambil saja. Suruh suamimu memotong dahan-dahan tua.”
“Lik Pasini, sekarang sudah nggak zaman pakai kayu bakar. Gas yang lebih bersih. Anti jelaga.”
“Kalau begitu, tunggu saja sampai anakku kembali. Biar dia yang menebangnya sendiri.”
“Pohon itu sudah tua, Lik Pasini.”
Tetapi kenangan dan sedompol rinduku masih ada di pohon randu itu. Kalimat itu berhenti di langit-langit mulut. Dan yang keluar justru, “lalu untuk apa harus di tebang buru-buru?”
“Apa membuat anak tertimpa sempalan batang dan harus dijahit kepalanya, atau jadi sarang sanca, tidak cukup untuk membuatmu rela merubuhkannya? Bisa jadi pohon randumu jadi istana genderuwo dan wewegombel.” Kalimat Menik terdengar sangat keras. Dadaku sesak mendengarnya, seperti ada ketam yang diam-diam mencungkili setiap bagiannya.
Aku mafhum sifat dan tujuan Menik menebang pohon randu. Wataknya tidak jauh berbeda dengan ibunya yang culas. Meskipun aku dan Menik tetangga berimpit, tetap saja aku jadi sasaran perilaku licik Menik. Dia selalu berusaha mengambil untung dariku yang meski lemah tetapi belum pikun ini. Aku memang sudah lemah untuk menjaga tanah dan merawat rumah. Menik memanfaatkan semua itu. Merasa berada di atas, ketika harus melawanku.
Dulu pernah beberapa petugas listrik dan telepon berseragam mendatangiku. Mereka meminta izin untuk menebang pohon nangka dan pakel di pekarangan sisi jalan besar. Akan didirikan tiang listrik dan telepon baru. Aku setuju saja. Kesempatan itu menguntungkan Menik. Kedatangan chainsaw, dimanfaatkan Menik untuk menggunduli lima batang pohon jati di halaman belakang. Lalu tanpa meminta izin, menjualnya sebagai modal mendirikan warung. Aku lebih memilih diam. Buat apa beradu mulut dengan Menik yang sudah kupastikan akan menang bila melawanku? Aku lebih ingin legowo dengan tidak membebani perasaanku sendiri.
Maka keinginannya menebang pohon randu tentu memiliki motif yang menguntungkan baginya. Saat pohon randu besar yang tepat di pagar antara rumahku dengan Menik tumbang, dia tentu dengan leluasa menggeser patok tanahnya. Bisa kupastikan setelah pohon randu tua itu menghilang, luas tanah Menik akan bertambah luas.
“Pohon itu sudah membahayakan banyak orang,” Menik menguatkan. Kini nada bicaranya diperhalus. Tapi semakin direndahkan, nadanya menghunjam ke dadaku.
Seminggu lalu seorang tukang tambal panci mengomeliku. Batang randu yang melengkung di jalan tiba-tiba sempal dan jatuh tepat di depannya. Meski batang itu tidak sempat membuat kepalanya robek, tetapi ranting yang mencuat menjatuhkan topi dan membuatnya kaget dan memaki. Dia mengatakan kalau sudah tua dan tidak lagi bisa digunakan, sebaiknya ditebang. Buat apa memelihara pohon randu tua yang aku sendiri tak mampu menjaganya dan justru jadi petaka bagi orang lain. Aku hanya diam. Kalimat-kalimat cadasku sudah habis. Hanya tersisa kalimat maaf yang terus kuulang agar tukang tambal panci itu mengikhlaskan salahku.
“Menik, tunggulah. Sebentar lagi anakku pulang.”
“Kapan?”
Aku bisu.
“Lik Pasini, sebelum musim penghujan pohon itu harus ditebang. Kalau tidak, bisa membahayakan. Pohon tua itu bisa rubuh diterjang angin.”
***
Anakku tak ubahnya anak-anak muda di kampung ini. Beranggapan bahwa kota akan membuat mereka kaya. Sawah, ladang, dan kebun tak menjanjikan di mata mereka. Biarlah orang-orang tua, semacam aku, yang mengurus dan bila sudah tak mampu, tanah-tanah itu akan dijual pula oleh mereka yang mencintai kota melebihi kasur tempat darahnya tumpah pertama.
Aku sadar betul, meski dia lahir dari rahimku. Dia sejatinya anak alam dan nalurinya adalah mengembara. Apa yang bisa aku pertahankan, bila kemerdekaan baginya adalah muara kebahagiaan?
Janji untuk sesekali pulang, janji untuk sesekali mengirimi pesan, janji untuk kembali turun ke persawahan. Semua seperti gelembung sabun yang diembus angin. Dia yang kusayang-sayang, bahkan tak tampak membela saat Menik semakin merangsek memaksakan kehendak.
“Lik Pasini!” Menik teriak dari pekarangan.
Aku berjalan perlahan menahan kakiku yang gemetar. Aku berdiri bersandar di pintu.
“Ini lihat. Suamiku menangkap kobra dari rongga pohon randumu.”
Bangkai ular itu digenggamnya. Lalu dilempar persis di depan kakiku. Itu bukanlah ular yang kecil dan bisanya tentu cukup mengakhiri nyawa belasan orang.
“Lusa mereka akan datang. Mau tidak mau pohon randu itu harus ditebang. Aku tidak mau anakku dipatok ular atau kejatuhan cabang pohon.”
“Menik….” Belum rampung kalimatku, Menik sudah menimpali dengan kalimat-kalimat bernada tinggi.
Menik melengos balik, menuju rumahnya. Aku tidak enak hati menjawab semua perkataannya. Mata para tetangga seperti besi berani yang jeli dan teliti menangkap semua berita. Dengan tidak sabar lantas menyebarkannya ke semua penjuru.
Seharian aku duduk menatap pohon randu itu. Semakin lama waktu memaksa semuanya menjadi tua. Hanya sekantung rindu yang kutanam yang akan terus menunggu kapan dia pulang.
***
Di luar, suara mesin mobil berhenti. Itu pasti penebang sewaan dengan chainsaw suruhan Menik. Puluhan tahun lalu ketika aku masih segar bugar saja, tidak bisa kutahan anakku pergi jauh. Dan tidak kembali. Apalagi sekarang. Mana mungkin aku bisa menghentikan semua keinginan Menik, ketika kakiku goyah tak mampu menopang badan.
Dengan tenaga yang tak seberapa, aku pergi keluar. Ingin kusaksikan pohon randu itu jatuh. Ingin kulihat bagaimana wujud rindu yang dahulu kutanam bersama biji randu.
Suara mesin gergaji menderu. Tambang-tambang dikaitkan agar pohon randu itu jauh di pekarangan rumahku yang lapang. Jangan sampai merubuhi warung Menik atau melintang di jalan. Tak butuh berjam-jam, mesin chainsaw berhasil membuat pokok randu goyang. Lalu sebentar sudah benar-benar jatuh berdebam di pekarangan. Ranting-ranting dipotong-potong. Menik dan suaminya mengumpulkan potongan-potongan itu dengan rupa bahagia. Dalam hati pasti mereka bahagia, karena semua berjalan sesuai rencana.
Air mataku jatuh. Rindu itu sekarang sudah rubuh. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk menanti dia pulang dan menjaga rindu di tunggak randu. Dadaku penuh oleh kesedihan. Dari pokok rindu itu terlihat sayap-sayap kecil beterbangan.
“Kok randu ini beraroma wangi?” Menik sekilas mencium aroma itu. Namun dada Menik sudah kadung dibuncahi bahagia, hingga enggan memedulikan wangi itu terlalu lama menusuk indera penciuman. Bahkan Menik tak lagi mau melirik diriku.[]
Catatan:
Luku: alat bajak. Karuk: nama bunga pohon randu.
Cerpen ini dimuat di Pikiran Rakyat 29 Oktober 2017. Sebelumnya cerpen ini memenangi sayembara Green Pen Award Perhutani dan masuk dalam seleksi Kampus Fiksi Emas.
October 22, 2017
Papua dari Mata Bocah
Koran Tempo, 21-22 Oktober 2017.
Novel ini diperbincangkan setelah menjadi naskah unggulan Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2016 dan masuk lima besar Kusala Sastra Khatulistiwa 2017. Kombinasi bergengsi dalam khazanah sastra Indonesia. Apalagi bila menengok nama Nunuk Y. Kusmiana yang terbilang baru sebagai penulis sastra.
Kekuatan terbesar novel ini adalah penggunaan latar lokasi yang memikat. Nunuk mengungkapkan kenangan masa kecilnya ketika mengikuti orang tuanya pindah tugas ke Papua, setahun setelah Operasi Trikora. Kala itu, situasi politik dan ekonomi di sana belum stabil. Ayahnya termasuk kelompok tentara yang pertama dikirim ke Papua setelah Presiden Sukarno mencanangkan Trikora.
Nunuk membuka kisah melalui bocah kecil bernama Kinasih Andarwati alias Asih dengan sebuah misteri bernama tukang potong kep. Dia adalah seorang lelaki yang membawa parang serta kerap memotong kepala anak-anak dan disimpan di karung. Konon, kepala itu akan digunakan sebagai fondasi jembatan. Sejenis dongeng yang diciptakan untuk menakut-nakuti bocah, membuatnya menuruti perkataan orang tua.
Asih membawa kita menengok Papua dan persinggungan budaya antara pendatang dan penduduk lokal. Termasuk bagaimana dia berkawan akrab dengan bocah seusianya bernama Sendy. Sendy adalah teman pertamanya di Papua. Asih menganggap penting untuk menjadi teman sepadan baginya.
Melalui kacamata anak-anak, Nunuk membuka kenangan masa kecilnya dan bagaimana perkembangan sosial Papua. Dari Asih dan Sendy yang memanen buah karsen di kandang babi hingga kemudian bertemu dengan peliharaan Sendy, si burung kasuari. Juga gambaran Tante Tamb, tetangga di depan rumah Asih, yang kerap memanfaatkan kepolosan bocah itu. Tante Tamb sering mengendap-endap untuk mencuri bumbu dapur, minyak tanah, dan es batu dari rumah keluarga Asih.
Keluarga Asih telah membawa budaya baru yang berdampak besar terhadap budaya di sekitar perumahan mereka. Ibu Asih membuka toko kelontong, berbisnis minyak tanah, dan juga menjual es batu. Kekurangannya, Nunuk tidak menjabarkan lebih detail apa dampak budaya yang dimaksud.[image error]
Pengaruh keluarga Asih terhadap lingkungan sekitar sejatinya adalah sekadar gambaran mikro dari proses Jawanisasi di Papua. Contoh yang cukup kentara ialah perihal dongeng tukang potong kep yang bersumber dari cerita tanah Jawa. Secara tidak langsung, penulis ingin menyampaikan bahwa budaya Jawa soal tumbal kepala anak-anak yang kerap muncul di tengah pembangunan jembatan juga menyebar ke Pulau Papua. Siapa lagi pembawanya, selain para tentara atau perantau dari Jawa. Salah satunya tentu keluarga Asih.
Nunuk memang tidak sedang menulis novel yang mengeksplorasi budaya Papua. Lengking Burung Kasuari hanya meminjam lokasi Papua. Ia lebih banyak menarasikan kenangan masa kecil di Papua. Sebelum Nunuk, kita lebih dulu mengenal Seri Kenangan milik N.H. Dini yang jauh lebih kompleks dan komplet dalam mendedah kenangan masa kecil penulisnya. Dini tidak lupa menyinggung pergerakan sosial di sekelilingnya, yang menjadikan novel kenangan sejenis ini tidak hanya rentetan kisah masa kecil.
Sepanjang novel, masih banyak pertanyaan yang belum tuntas dijawab Nunuk. Selain tidak hadirnya rasa Papua, Nunuk melupakan bagaimana nasib tukang potong kep yang disajikan di awal. Sosok misterius ini hanya disinggung di beberapa halaman awal, kemudian pembaca digiring ke fragmen-fragmen geli, lucu, dan manis masa kecil Asih. Dan baru dibuka kembali menjelang kepindahan keluarga Asih. Itu pun dengan beberapa baris saja.
Nunuk terlena menggali kenangan tanpa berusaha setia pada alur yang disajikan kepada pembaca. Papua yang dikisahkan dari kacamata Asih juga masih kurang kuat. Kita hanya meraba-raba Papua kala itu sedang giat membangun jembatan, mengaspal jalan, dan memasukkan benda-benda modern, termasuk kulkas, ke pelosok Papua.
Lengking Burung Kasuari menjadi naskah unggulan sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2016 bersama tiga naskah lainnya, yakni Tanah Surga Merah, Curriculumvitae, dan 24 Jam Bersama Gaspar. Adapun juara pertamanya adalah novel Semua Ikan di Langit karya Ziggy Zezsyazeovien-nazabrizkie.
Kantor berita Antara menyebutkan, dewan juri sayembara yang terdiri atas Bramantio, Seno Gumira Ajidarma, dan Zen Hae memutuskan tidak ada pemenang kedua dan ketiga. Alasannya, ada perbedaan mutu yang tajam antara pemenang pertama dan 316 naskah lain yang berkompetisi.[]
LENGKING BURUNG KASUARI | Nunuk Y Kusmiana
Gramedia Pustaka Utama | Pertama, 2017 | 224 hal
9786020339825


October 3, 2017
Berayun ke Dunia Terabithia
Belakangan saya suka sekali membaca buku-buku anak. Beberapa menghibur, bahkan tidak jarang justru menghadirkan nuansa sedih dan nglangu. Tapi yang saya sukai dari buku anak-anak adalah kepolosan tokoh, dan disini penulisnya haruslah secerdas mungkin membuat karakter yang kuat. Di Indonesia memang belum banyak sastra atau buku yang khusus untuk anak. Dan kalau pun ada kebanyakan sesak dengan muatan dan pesan moral yang ingin dijejalkan penulis. Kalau di luar mah, bodo amat! Cerita ya cerita. Menarik untuk anak, asyik dibaca, dan menghibur. Salah satunya Birdge to Terabithia, meskipun buku ini terselip maksud tertentu dari penulis. Tapi sebagai cerita anak, nuansa yang hendak digambarkan penulis sangatlah berbeda. Bahkan akhir cerita buku ini sangatlah berbeda untuk bacaan anak-anak. Tapi mengingat latar cerita buku ini hadir, maka wajarlah bila endingnya bikin nglangu, sedih-haru.
Ulasan saya atas novel Bridge to Terabithia dimuat di Jurnal Ruang, 4 Oktober 2017. Novel ini diterbitkan Noura Books.
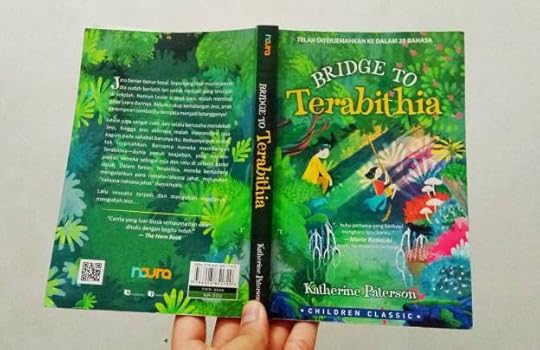


October 1, 2017
Dalam Gulungan Papier Keretek
(Jawa Pos, 01 Oktober 2017)
Salah satu tokoh penting yang diakui memeliki pengaruh terhadap industri rokok di Kudus ialah Nitisemito, pengusaha yang kemudian dijuluki oleh Ratu Wilhelmina De Kretek Konning (Raja Keretek). Sosok ini kemudian dituangkan Iksaka Banu dalam novel terbarunya Sang Raja.
Pasca kemenangan Semua Untuk Hindia (2014) sebagai prosa terbaik dalam Kusala Sastra Khatulistiwa, Iksaka Banu diakui publik sebagai sastrawan dengan titik fokus tema seputar kolonial. Dan bila biasanya berkutat dalam cerpen, sekarang Iksaka Banu diuji ketahannya dalam menulis prosa panjang, novel, tentang sosok dan pabrik rokok dalam sejarah keretek Kudus.
Novel ini memiliki tiga suara tuturan, yaitu Bardiman Sapari wartawan dari Koran Matahari Timur, Filipus Retchterhand dan Goenawan Wirosoeseno. Dua nama terakhir adalah pegawai NV Nitisemito saksi jatuh-bangun pabrik rokok itu.
Filipus dan Wirosoeseno adalah dua kutub berbeda. Filipus adalah orang Belanda yang mendapat kepercayaan dalam bidang akuntansi NV Nitisemito. Sedangkan Wirosoeseno anak seorang priyayi Yogyakarta, yang berhasil ngenger dan kemudian bekerja sebagai salah tim promosi. Di tengah keadaan di mana garis demarkasi antara pribumi-belanda menebal, keduanya justru rukun dan bekerja demi ribuan buruh Nitisemito. Kami bisa bersatu dan saling menghargai. Timur dan Barat, demikian tegas Filipus. Bercampurnya unsur barat dan timur di NV Nitisemito semakin menasbihkannya sebagai raja keretek. Selain tentu jumlah karyawan dan produksi rokok Bal Tiga NV Nitisemito menguasai lapisan masyarakat Kudus kala itu.
Menarik menggaris-bawahi sebuah kalimat dalam novel ini, semua priyayi wajib ngeses (baca: merokok) (hal.45). Kalimat ini disampaikan Romo dari Wirosoeseno beberapa saat sebelum ngenger, belajar ke kota. Semua ciri sebuah tatanan khas milik sebuah kelas, yakni priyayi. Dijelaskan pula kemudian, bahwa setiap orang punya ciri khas masing-masing dalam campuran taburan atau wur sebelum menggulung tembakau di dalam daun klobot. Antara lain, rajangan klembak, kemenyan, kayu manis, pala, atau cendana.
Daun klobot berisi aneka campuran itu kemudian digulung dengan hati-hati, membentuk pipa kerucut. Setelah gulungan terlihat rapi, ujung dan pangkal klobot diikat dengan benang agar isinya tidak berantakan. (hal.43)
Wirosoeseno menyaksikan bahwa rokok pabrikan berbeda dengan upacara ngeses yang diajarkan Romonya. Pembungkusnya kertas papier, kemudian ditambah saus khusus Nitisemito.
Kondisi ini yang kemudian menjadi daya tarik semua kalangan, terutama kaum non-priyayi yang lebih mengedepankan rokok bukan sebagai simbol. Kepraktisan rokok pabrikan dan rasa saus yang nikmat, membuat Rokok Tjap Bal Tiga menguasai pasaran rokok kala itu.
Dalam catatan Sander L. Gilman and Zhou Xun, Smoke: A Global History of Smoking (2004), usaha Nitisemito telah lebih dahulu dilakukan oleh Haji Djamari pada akhir abad ke-19. Konon rokok dimulai dengan keampuhan minyak cengkeh menyembuhkan sakit. Kemudian Haji Djamari bereksperimen merajang cengkeh dan mencampurnya dengan tembakau untuk dilinting menjadi rokok. Dengan resep saus khusus, Nitisemito mengeluarkan merek rokok tjap kodok nguntal ulo, kemudian diganti tjap bal tiga.
Kemegahan pabrik NV Nitisemito mulai digoyang beberapa halangan. Guncangan pertama ialah ketika telah terjadi kegagalan besar panen cengkeh di Zanzibar dan Madagaskar. Harga satu pikul cengkeh naik dari f.75 menjadi f.160 (hal.167). kondisi makin parah ketika pada 18 Desember 1930, Gunung Merapi meletus. Kata-kata sudah dianggap terlalu sulit untuk menjelaskan keadaan, belakangana kabar murung itu lebih banyak hadir dalam wujud grafik dan angka. (hal.168)
Lubang jarum pertama lolos dilewati Nitisemito. Lubang kedua ialah ketika pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan accijn, cukai rokok yang menembus 40% harga jual. Imbas dari kebijakan belasting ordoniante, mengembalikan kas kerajaan Belanda akibat perang dan krisis malaise secara global (hal.85). Hampir-hampir terjadi massa-onstlag, pemecatan massal di NV Nitimsemito.
Ujian kedua lolos dengan ide-ide brilian dari tim promosi Wirosoeseno. Namun ujian terberat adalah ketika terjadi konflik kepentingan dalam keluarga Nitisemito. Antara Karmain dan Akoean Markoem. Aneka gosip dan isu berembus di kalangan karyawan. Pak Nitisemito yang gemar main perempuan, persekongkolan dengan kelompok Sarikat Dagang Islam dan Soekarno. Hingga penahanan Karmain atas tuduhan penggelapan rokok tanpa kertas cukai.
Ini adalah mula jatuhnya NV Nitisemito. Konflik keluarga dan munculnya pesaing kuat merek Minak Djinggo pada tahun 1930. Pemilik rokok ini, Kho Djie Siong, adalah mantan agen Bal Tiga. Kho Djie Siong mempelajari rahasia racikan dan strategi dagang dari Karmain.
Sebagai novel sejarah, Sang Raja bisa dinikmati sebagai karya fiksi dengan tuturan tenang dan penggambaran detail yang memperkokoh latar sejarah pra-kemerdekaan. Namun lebih dari itu, Iksaka Banu telah berhasil memberi alternatif membaca biografi dan sejarah Nitisemito, sang raja keretek.
Nitisemito sosok pengusaha bertangan dingin. Mempekerjakan ribuan karyawan, mampu merajai pasaran rokok, dan satu-satunya yang membuat pribumi dan kulit putih bekerja di bawah satu atap Nitisemito. Sebuah capaian yang mengokohkan sang raja.
Kedekatan dengan kelompok nasionalis, Soekarno dan Sarikat Islam masih terlalu samar dalam novel ini. Iksana Banu belum mengulas lebih seberapa jauh Nitisemito, sebagai pengusaha sukses memiliki peran dalam pergerakan nasional pra kemerdekaan.
Rokok telah menjadi budaya sekaligus identitas bangsa. Meleburkan strata, menghapus kelam sejarah. Mengutip kalimat Mark Hanusz dalam bukunya Keretek-The Cultural and Heritage of Indonesia’s Clove Cigarettes, ‘keretek bukan hanya simbol masyarakat dan budaya, rokok perwajahan sebuah bangsa. []

NB: yang dimuat di Jawa Pos, beberapa dikurangi oleh redaktur.


September 18, 2017
Novel Metropop Tema Politik
Saya perlu akui, novel Sophismata punya tema yang berbeda untuk kategori metropop, bukan sastra. Ya, novel ini bertemakan politik, meski porsinya tidak terlalu banyak dan kurang membuka lapisan politik lebih dalam. Kalau saya mungkin menyebut novel populer bertemakan politik yang lebih enak yaaa punya Tere Liye, Negeri Para Pedebah. Atau punya Okky Madasari yang 86 dan Kalatida punya Seno Gumira Ajidarma, dan dua judul terakhir memang lebih sering dianggap orang sebagai tema berat yang nyastra (padahal sejatinya saya tidak sepakat dengan demarkasi sastra dan non-sastra). Tapi, yaaaa Sophismata punya blue-ocean yang berbeda.
Cinta Serumit Politik
(Padang Ekspres, 17 September 2017)
“Politik itu soal kekuasaan dan kepentingan. Aku pengin bisa memperjuangkan kepentingan orang banyak, tapi untuk bisa memperoleh itu, ya aku harus punya kekuasaan dulu. Jalan menuju hal itu panjang dan berliku.” (hal.234)
Untuk sebuah novel metropop, Sophismata menghadirkan sebuah tema yang tidak biasa. Bila kebanyakan cerita mengisahkan cinta dibalut kehidupa urban nan kosmopolit, dalam novel ini kisah cinta justru berpusar di antara carut-marut politik di negeri ini.
Menarik mencari arti kata dari judul yang dipergunakan penulis. Sophismata lebih dikenal sebagai salah satu arti dalam dunia filsafat. Secara harfiah kata ini memiliki padaan ambiguitas dari sebuah keadaan yang kemudian membuat seseorang tidak jernih dalam berpikir (logical fallacies) hingga salah dalam mengambil kesimpulan (false conclusions). Arti judul ini, sama dengan nuansa yang hendak dibangun penulis. Cinta dan politik yang dicertiakan sedang dalam nuansa ambiguitas.
Sigi dan Timur. Demikian dua tokoh yang jatuh cinta di tengah napas politik, anggota dewan. Sigi sudah tiga tahun bekerja sebagai staf anggota DPR, tapi tidak juga bisa menyukai politik. Ia bertahan agar dapat belajar dari atasannya, mantan aktivis 1998 yang ia idolakan, Johar Sancoyo. Selain berharap bisa dipromosikan menjadi tenaga ahli. Namun, semakin hari dia justru dipaksa menghadapi berbagai intrik yang baginya terasa menggelikan. Tak ada kawan dan lawan abadi dalam politik.
Hari-harinya hanya diisi dengan memantau berita di media, agenda kerja atasannya, hingga memesan makanan bagi atasan dan dua koleganya. Sigi merasa dirinya tidak bisa berkembang dan memuluskan cita-citanya untuk bisa berbuat banyak kepada negara. Ia pernah membicarakan keinginannya bergabung sebagai tenaga ahli kepada sang atasan, tapi belum juga dikabulkan. Salah satu alasannya ialah dalam peraturan tentang tenaga ahli di DPR/MPR harus berijazah S-2. Meski ia mendapat penolakan, keinginannya tak surut. Ia mulai banyak belajar dari buku-buku mengenai kebijakan publik pun dengan program yang sedang digagas atasannya.
Apalagi ketika dirinya kembali menemukan Timur, kakak angkatan sewaktu SMA yang juga pernah dikagumi lantaran keberaniannya untuk memimpin dan memiliki gagasan cerdas, Sigi mulai merasa mendapat banyak pelajaran dan pengetahuan lain seputar perpolitikan, meskipun tetap ia tak menyukai hal tersebut. Perbincangan tentang politik sering dilakukannya dengan Timur karena teman lama yang baru ditemukannya tersebut akan segera mendeklarasikan partai baru dengan konsep kesetaraan bagi siapapun. Keter tarikannya terhadap Timur tak juga bisa lepas sejak masih di bangku SMA, ia menganalogikan perihal ekspresi Timur yang berbinar-binar saat menjelaskan kondisi perpolitikan dengan dirinya saat menimbang dan membuat kue.
Kehadiran Timur (baca: cinta) nyatanya membuka sebuah prespektif baru pada Sigi. Ia semakin bersemangat untuk menunjukkan kapabilitas dalam dunia politik di depan atasannya, Johar. Sigi memberikan ulasan dan ide tentang konsep koperasi yang digagas atasannya tersebut. Meskipun tak ada apresiasi yang menggembirakan, Sigi tak menyangka idenya tersebut dipaparkan dalam rapat pertemuan dengan Staf Unit Kepresidenan Cipta Dirgantara.
Sebagaimana sudah sering diketahui, sosok Sigi akan selalu terbentur oleh elitis dan sistem senioritas yang kaku. Hingga di titik ini, Sigi harus membenarkan apa yang pernah dinasihatkan oleh ayahnya, Menepati Janji di Jakarta adalah hal yang sulit.
Sigi semakin tegas mengambil sikap untuk tidak menyukai politik dan terlibat di dalamnya. Namun, cintanya justru tertambat pada laki-laki yang bercita-cita untuk masuk dalam ranah yang kerap disapa abu-abu. Ia kerap skeptis menanggapi obrolan tentang perpolitikan dengan Timur, tapi lawan bicaranya tersebut justru merasa mendapat pandangan baru dan tidak menyalahkan atas apa yang dipikirkan perempuan pecinta warna hitam dan putih itu.
Intensitas pertemuan pun dengan obrolan seputar politik dan pekerjaan membawa keduanya asyik dalam hubungan percintaan ala anak muda. Keduanya merasa sebanding, memiliki teman bercerita dengan kemampuan yang mumpuni. Karena itu, Sigi dan Timur tak pernah bosan untuk bertemu, berbagi cerita tentang pendirian partai, kebimbangan Sigi untuk bertahan dan menerima tawaran pekerjaan yang membebaskannya dari sengkarut politik, ataupun sekadar berbicara tentang kisah kasih masa lalu. Berbagi pandangan berbeda dengan balutan rasa cinta menjadikan Timur bisa mengevaluasi atas apa yang sudah dilakukannya untuk terjun ke dunia politik.
Politik dan perempuan sepertinya sesuatu yang saling mengikuti. Banyak politikus kita sering terjerat urusan perempuan. Dan kebiasaan ini sepertinya sudah menjadi rahasia umum. Sigi pun menemukan hal demikian. Atasannya mudah tergoda dengan perempuan berparas cantik. Seorang perempuan, Megara yang berusia lebih muda dari Sigi datang dan mengatakan ingin bertemu Johar. Hal mengerikan selanjutnya adalah teror surel berisi berisi foto-foto akibat perlakuan mesum atasannya.
Anak Muda dan Politik
Sikap Sigi sepertinya adalah wakil suara mayoritas anak muda. Apatis kepada politik, tidak percaya parpol, dan asumsi pertama adalah politik itu kotor dan korup. Namun keseharian kita tidak bisa lepas dengan yang bernama politik. Politik adalah nadi kehidupan. Politik selalu berada di balik keberlangsungan kehidupan. Politik sebetulnya sungguh-sungguh perlu diperhatikan, karena yang berlangsung dalam dunia politik akan menentukan kehidupan semua orang.
Setidaknya novel ini kembali mengenalkan dunia politik dan intrik yang ada di dalamnya. Cinta dan dunia urban mileneal menjadi backbone utama yang menjadi magnit anak muda. Alanda Kariza lewat Sophismata, begitu gamblang mengungkap hal-hal seputar dunia politik dan interaksi di dalamnya, termasuk perempuan dan permainan uang.
Tema politik dan anak muda dalam novel ini juga bisa menjadi bahan bacaan bagi kedua kubu yang kerap berseberangan, anak muda yang gemar berpolitik dan tidak menyukai sama sekali. Pandangan lain yang diutarakan akan membawa kita pada kemampuan untuk tidak saling membandingkan pilihan, tetapi tetap dapat mengevaluasi.
Selain itu, sosok Sigi juga menjadi menarik untuk dibicarakan. Perempuan dalam politik kita memang masih sebesar 30%. Namun setidaknya penulis mendedah bahwa perempuan berhak memilih di bidang apa ia hendak berkiprah. Termasuk politik dan carut-marut dunia anggota dewan. Politik kerap memberikan banyak ruang dalam ketidakjelasan. Apa cinta juga kerap ambigu dan membingungkan kita? []
[image error]







