Dion Yulianto's Blog, page 10
October 12, 2011
Dua Ibu
Judul : Dua IbuPenulis : Mbak SowiyahPenyunting : Puitika StudioCetakan : 1, April 2011Penerbit : Pustaka PuitikaTebal : 591 halaman
[image error]
Menghadirkan kontradiksi untuk memulai sebuah novel panjang memang trik jitu untuk memancing keingintahuan pembaca. Namun, teknik ini juga riskan membuat pembaca menjadi kritis dan seperti mencoba mencari "kelemahan" dari teknik ini. walau bagaimanapun, sebuah kontradiksi tidak selamanya akan menarik. Jika penulis tidak mampu mengolahnya menjadi sesuatu yang wajar, atau tidak piawai dalam mencari pembenaran dari asal-muasal kontradiksi tersebut, maka novel itu akan langsung diletakkan bahkan sebelum 100 halaman pertama. Untunglah, hal ini tidak terjadi pada novel panjang Dua Ibu, hasil buah tangan Mbak Sawiyah atau yang dalam akun Facebooknya mengaku sebagai Penulis Kacangan ini. Dan, setelah saya membaca novel yang dengan penuh kepercayaan dipinjamkan kepada saya ini, saya berani mengatakan kalau Mbak Penulis Kacangan alias Mbak Sowiyah bukanlah seorang penulis kacangan. Novel Dua Ibu ini membuktikannya.
Dibuka dengan antiklimas, Iqbal terpaksa kehilangan kekasihnya, layla, karena pengkhianatan yang ia lakukan dengan perempuan bernama Gaya. Lebih miris lagi, ayah Iqbal kemudian meminang Layla sebagai istrinya. Jadilah Iqbal memiliki dua ibu, satu ibu kandung dan satu lagi ibu muda. Satunya ibu yang sakit-sakitan, satunya lagi ibu yang maish muda, segar, dan cantik-mempesona. Dua ibu, keduanya berbeda usia namun satu kemiripan: keduanya adalah wanita shalihah yang luar biasa berbakti kepada suami—yakni ayah Iqbal. Bayangkan bagaimana emosi saling bercampur baur dalam diri Iqbal ketika setiap hari harus melihat mantan kekasihnya kini melayani ayahnya sendiri. Pembaca mungkin bertanya-tanya, kok bisa Layla dilamar ayah Iqbal? Apakah mereka tidak tahu kalau Iqbal dan Layla itu berpacaran? Jawabannya dijelaskan oleh Mbak Sawiyah dengan tekun dan simpel melalui lembar demi lembar halaman novel ini. Memang membaca harus agak bersabar, namun di sela-sela itulah pembaca akan menemukan nilai-nilai kesederhanaan nan sering kali kita lupakan.
Dua Ibu seolah menyentil pembaca modern yang sering kali didera oleh virus galau yang sepertinya terlalu sering kita besar-besarkan. Betapa masalah sms tidak dibalas pacar, atau cemburu melihat orang lain malam mingguan sama pacar dan kita tidak; masalah-masalah "sosial" itu sudah lebih dari cukup untuk membuat anak-anak muda zaman sekarang galau dan risau, membuat resah dan tidak produktif. Dua Ibu menyentil kegalauan tersebut lewat sosok Iqbal, bagaimana pemuda 28 tahun itu harus kehilangan kekasih yang kini menjadi ibu keduanya, betapa Iqbal juga dipaksa menikah dengan Gaya dengan ancaman Gaya akan bunuh diri.Bahkan ketika Gaya telah resmi menjadi istrinya, dan Iqbal dengan sabar berusaha mencintai wanita yang tidak ia cintai itu; cobaan masih belum berakhir. Gaya bukanlah sosok muslimah seperti Layla. Gaya terlalu asing dengan keluarga Iqbal, dan sekarang tugas Iqbal bertambah—untuk mendidik Gaya menjadi istri yang sesuai dengan syariat yang diajarkan Islam. Selain itu, masih banyak permasalahan lain yang harus dilalui Iqbal, yang semuanya benar-benar menunjukkan situasi ketika manusia benar-benar harus bersikap kesatria dan memilih, tentu dengan segenap konsekuensinya. Semua alur dan kisah rumit yang berjalinan dalam Dua Ibu dapat bermuara pada satu ungkapan: Allah Swt. mencintai hamba-hamba-Nya yang sabar dalam menjalankan ketentuannya.
Lalu, bagimana nasib perkawinan Iqbal dan Gaya? Mengapa Iqbal tidak pernah mampu memanggil istri muda ayahnya itu dengan panggilan "Ibu"? Apakah Iqbal selamanya akan hidup bersama wanita yang tidak ia cintai? Apakah Dua Ibu hanya akan berakhir dengan ending yang membuat pembaca ikut-ikutan bersabar. Owww …ternyata tidak. Mbak Sowiyah sudah menciptakan kejutan-kejutan kecil namun sanggup membolak-balik alur panggung dalam novel ini. Semua keruwetan yang seolah tak berujung dalam jalan hidup Iqbal mulai terurai dengan tersibaknya sebuah rahasia, Latika—saudari kembar Layla. Lalu, siapakah Layla yang ibu kedua Iqbal? Apakah Layla itu Layla atau Atika? Satu bocoran deh, Iqbal akhirnya bercerai dengan Gaya, dan dua hati yang lama terpisah oleh lautan rindu akhirnya duduk bersama dalam singgasana bertabur mawar, dengan kuncup butik dan taburan benangsari yang menumbuhkan violet nan manis dan riang. Saya agak sempat tersedu-sedu (sedikit kok) saat sampai di akhir penjalanan membaca alur hidup Iqbal dan Latla. Dua hati akhirnya bertaut dalam nyala abadi. Salut dah untuk cinta mereka.Satu hal yang agak kurang berkenan dari novel ini adalah ketebalannya yang adoh dah ampon sangat tebal untuk novel drama. Mohon maaf, saya sering melompat-lompat halaman pada bagian tengah ketika menjumpai struktur cerita yang agak melenceng dari jalur utama. Namun, ketebalan ini tertutup oleh diksi-diksi sederhana namun mengena yang dipakai oleh penulis. Nasihat dan pepatah di dalamnya juga disampaikan secara simpel, tidak terkesan tinggi dan menggurui. Saya kudu banyak belajar nih dari Mbak Sowiyah.
Betapa pahala sabar itu luar biasa manis pada akhirnya.
"Dekatkanlah senantiasa hati dan jiwamu kepada Tuhan, Ia akan memudahkanmu dalam segala persoalan." (hlm. 560)
Tentang Penulis: Sowiyah, penulis yang juga seorang tenaga kerja wanita di Hongkong ini lahir di Cilacap pada tahun 1982. Ia tidak pernah menjadikan nasibnya yang hanya lulus MI sebagai penghalang untuk mendulang kesuksesan. Melalui ketekunan dalam berlatih dan belajar, mbak Sowiyah membuktikan bahwa dirinya juga mampu menulis sebuah novel. Saya sangat salut dengan perjuangan beliau dalam melawan ketidak-PD-an saat menyelesaikan novel indah ini. Dari perbincangan di media FB, saya mengenal mbak Sowiyah (yang dengan majas eufemisme memilih nama akun Penulis Kacangan) sebagai seorang yang suka membaca. Luar biasa. Saya sangat salut pada beliau, sungguh tidak bisa dibandingkan dengan saya yang sampai saat ini belum bisa menghasilkan satu novel pun. Selamat kepada Mbak Sowiyah atas Dua Ibu. Semoga saya bisa meniru dan meneladani Mbak dalam melawan kemalasan dan ketidakpedean. Terus berkarya ya Mbak! Semangat!

[image error]
Menghadirkan kontradiksi untuk memulai sebuah novel panjang memang trik jitu untuk memancing keingintahuan pembaca. Namun, teknik ini juga riskan membuat pembaca menjadi kritis dan seperti mencoba mencari "kelemahan" dari teknik ini. walau bagaimanapun, sebuah kontradiksi tidak selamanya akan menarik. Jika penulis tidak mampu mengolahnya menjadi sesuatu yang wajar, atau tidak piawai dalam mencari pembenaran dari asal-muasal kontradiksi tersebut, maka novel itu akan langsung diletakkan bahkan sebelum 100 halaman pertama. Untunglah, hal ini tidak terjadi pada novel panjang Dua Ibu, hasil buah tangan Mbak Sawiyah atau yang dalam akun Facebooknya mengaku sebagai Penulis Kacangan ini. Dan, setelah saya membaca novel yang dengan penuh kepercayaan dipinjamkan kepada saya ini, saya berani mengatakan kalau Mbak Penulis Kacangan alias Mbak Sowiyah bukanlah seorang penulis kacangan. Novel Dua Ibu ini membuktikannya.
Dibuka dengan antiklimas, Iqbal terpaksa kehilangan kekasihnya, layla, karena pengkhianatan yang ia lakukan dengan perempuan bernama Gaya. Lebih miris lagi, ayah Iqbal kemudian meminang Layla sebagai istrinya. Jadilah Iqbal memiliki dua ibu, satu ibu kandung dan satu lagi ibu muda. Satunya ibu yang sakit-sakitan, satunya lagi ibu yang maish muda, segar, dan cantik-mempesona. Dua ibu, keduanya berbeda usia namun satu kemiripan: keduanya adalah wanita shalihah yang luar biasa berbakti kepada suami—yakni ayah Iqbal. Bayangkan bagaimana emosi saling bercampur baur dalam diri Iqbal ketika setiap hari harus melihat mantan kekasihnya kini melayani ayahnya sendiri. Pembaca mungkin bertanya-tanya, kok bisa Layla dilamar ayah Iqbal? Apakah mereka tidak tahu kalau Iqbal dan Layla itu berpacaran? Jawabannya dijelaskan oleh Mbak Sawiyah dengan tekun dan simpel melalui lembar demi lembar halaman novel ini. Memang membaca harus agak bersabar, namun di sela-sela itulah pembaca akan menemukan nilai-nilai kesederhanaan nan sering kali kita lupakan.
Dua Ibu seolah menyentil pembaca modern yang sering kali didera oleh virus galau yang sepertinya terlalu sering kita besar-besarkan. Betapa masalah sms tidak dibalas pacar, atau cemburu melihat orang lain malam mingguan sama pacar dan kita tidak; masalah-masalah "sosial" itu sudah lebih dari cukup untuk membuat anak-anak muda zaman sekarang galau dan risau, membuat resah dan tidak produktif. Dua Ibu menyentil kegalauan tersebut lewat sosok Iqbal, bagaimana pemuda 28 tahun itu harus kehilangan kekasih yang kini menjadi ibu keduanya, betapa Iqbal juga dipaksa menikah dengan Gaya dengan ancaman Gaya akan bunuh diri.Bahkan ketika Gaya telah resmi menjadi istrinya, dan Iqbal dengan sabar berusaha mencintai wanita yang tidak ia cintai itu; cobaan masih belum berakhir. Gaya bukanlah sosok muslimah seperti Layla. Gaya terlalu asing dengan keluarga Iqbal, dan sekarang tugas Iqbal bertambah—untuk mendidik Gaya menjadi istri yang sesuai dengan syariat yang diajarkan Islam. Selain itu, masih banyak permasalahan lain yang harus dilalui Iqbal, yang semuanya benar-benar menunjukkan situasi ketika manusia benar-benar harus bersikap kesatria dan memilih, tentu dengan segenap konsekuensinya. Semua alur dan kisah rumit yang berjalinan dalam Dua Ibu dapat bermuara pada satu ungkapan: Allah Swt. mencintai hamba-hamba-Nya yang sabar dalam menjalankan ketentuannya.
Lalu, bagimana nasib perkawinan Iqbal dan Gaya? Mengapa Iqbal tidak pernah mampu memanggil istri muda ayahnya itu dengan panggilan "Ibu"? Apakah Iqbal selamanya akan hidup bersama wanita yang tidak ia cintai? Apakah Dua Ibu hanya akan berakhir dengan ending yang membuat pembaca ikut-ikutan bersabar. Owww …ternyata tidak. Mbak Sowiyah sudah menciptakan kejutan-kejutan kecil namun sanggup membolak-balik alur panggung dalam novel ini. Semua keruwetan yang seolah tak berujung dalam jalan hidup Iqbal mulai terurai dengan tersibaknya sebuah rahasia, Latika—saudari kembar Layla. Lalu, siapakah Layla yang ibu kedua Iqbal? Apakah Layla itu Layla atau Atika? Satu bocoran deh, Iqbal akhirnya bercerai dengan Gaya, dan dua hati yang lama terpisah oleh lautan rindu akhirnya duduk bersama dalam singgasana bertabur mawar, dengan kuncup butik dan taburan benangsari yang menumbuhkan violet nan manis dan riang. Saya agak sempat tersedu-sedu (sedikit kok) saat sampai di akhir penjalanan membaca alur hidup Iqbal dan Latla. Dua hati akhirnya bertaut dalam nyala abadi. Salut dah untuk cinta mereka.Satu hal yang agak kurang berkenan dari novel ini adalah ketebalannya yang adoh dah ampon sangat tebal untuk novel drama. Mohon maaf, saya sering melompat-lompat halaman pada bagian tengah ketika menjumpai struktur cerita yang agak melenceng dari jalur utama. Namun, ketebalan ini tertutup oleh diksi-diksi sederhana namun mengena yang dipakai oleh penulis. Nasihat dan pepatah di dalamnya juga disampaikan secara simpel, tidak terkesan tinggi dan menggurui. Saya kudu banyak belajar nih dari Mbak Sowiyah.
Betapa pahala sabar itu luar biasa manis pada akhirnya.
"Dekatkanlah senantiasa hati dan jiwamu kepada Tuhan, Ia akan memudahkanmu dalam segala persoalan." (hlm. 560)
Tentang Penulis: Sowiyah, penulis yang juga seorang tenaga kerja wanita di Hongkong ini lahir di Cilacap pada tahun 1982. Ia tidak pernah menjadikan nasibnya yang hanya lulus MI sebagai penghalang untuk mendulang kesuksesan. Melalui ketekunan dalam berlatih dan belajar, mbak Sowiyah membuktikan bahwa dirinya juga mampu menulis sebuah novel. Saya sangat salut dengan perjuangan beliau dalam melawan ketidak-PD-an saat menyelesaikan novel indah ini. Dari perbincangan di media FB, saya mengenal mbak Sowiyah (yang dengan majas eufemisme memilih nama akun Penulis Kacangan) sebagai seorang yang suka membaca. Luar biasa. Saya sangat salut pada beliau, sungguh tidak bisa dibandingkan dengan saya yang sampai saat ini belum bisa menghasilkan satu novel pun. Selamat kepada Mbak Sowiyah atas Dua Ibu. Semoga saya bisa meniru dan meneladani Mbak dalam melawan kemalasan dan ketidakpedean. Terus berkarya ya Mbak! Semangat!
Published on October 12, 2011 02:59
October 5, 2011
Orang Kristen Naik Haji
Orang Kristen Naik Haji
Judul : Orang Kristen Naik Haji Penulis : Augustus RalliPenerjemah : Taufik Damas
Penyunting : Adi TohaPemeriksa aks : Dian PranasariCetakan : 1, Agustus 2011Tebal : 371 halamanPenerbit : Serambi Ilmu Semesta
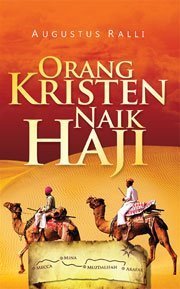
Membaca judulnya saja sudah sangat kontroversial, dan isinya ternyata jauh lebih kontroversial lagi. Pembaca, termasuk saya, sekilas mungkin akan mengira bahwa buku ini hendak membahas tentang kisah-kisah para mualaf yang berkesempatan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, ternyata tidak demikian—malah jauh lebih seru dari itu. Judul bahasa Inggris dari buku ini mungkin lebih mampu menggambarkan isi sebenarnya dari buku yang ditulis pada tahun 1901 ini, Christian at Mecca. Buku ini sendiri merupakan kompilasi atau kumpulan kisah dari sejumlah individu-individu dari Barat yang sempat merasakan pahit-getir-manis-panas dan berbahayanya petualangan mengunjungi kota paling disucikan oleh umat Islam, Makkah, ratusan tahun yang lalu.
Makkah dan Madinah, antara abad ke 15 – 19, masih dan tetap merupakan dua kota suci yang menjadi idam-idaman bagi seluruh umat Islam di kolong jagat untuk bisa mengunjunginya. Bedanya, saat itu belum ditemukan transportasi modern yang bisa mengangkut jamaah haji dengan mudah dan cepat. Para jamaah harus melewati jalur darat menembus padang gurun pasir nan gersang dengan terik matahari yang membakar. Lebih dari itu semua, para peziarah juga harus menghadapi ancaman dari suku Badui gurun, perampok, penipu, bahkan kaum Wahabi ekstrem yang waktu itu menguasai kota Madinah. Kaum Wahabi ini begitu rupa ekstremnya sampai-sampai melarang jamaah haji untuk menziarahi makam Baginda Nabi Saw. Jika bagi umat muslim saja sudah begitu sulit, bayangkan bagaimana sulitnya memasuki Mekkah bagi orang Eropa yang non Muslim?
Seperti telah kita ketahui, ajaran Islam melarang orang yang beragama selain Islam untuk memasuki kota suci Makkah. Bagi yang melanggar, hukumannya pada masa itu adalah digantung atau dipenggal. Apalagi Saudi Arabia kala itu dikuasai oleh kaum Wahabi yang terkenal sangat ekstrem dalam urusan ajaran agama. Namun, yang namanya manusia memang makhluk yang selalu haus akan petualangan. Apa yang dilarang terkadang malah semakin membuatnya semakin tertarik untuk melanggarnya. Makkah yang begitu tertutup bagi Eropa, yang hanya segelintir orang di barat yang mengetahui kondisi dan situasi di dalamnya, menjadikan kota suci ini sebagai tujuan eksotis nan menantang bagi para petualang Eropa. Bahkan, hukuman mati bagi mereka yang ketahuan mengaku sebagai muslim di Makkah tidak mampu menghalangi jiwa-jiwa yang penuh rasa ingin tahu itu untuk menguak rahasia-rahasia dari agama ini, langsung dari tempat di mana Islam pertama kali diturunkan.
Satu per satu, bab-bab dalam buku ini menguraikan siapa dan bagaimana kisah perjalanan nekat mereka saat menyamar sebagai muslim demi bisa memasuki Makkah. Mulai dari Ludovico Bartema yang pertama kali menginjakkan kaki di Makkah pada 18 Mei 1503, hingga seorang Snouck Hurgronje (yang namanya sudah tidak asing lagi); mereka meninggalkan limpahan arsip dan catatan penting mengenai ritual haji dan pandangan mata dari kota suci ini beserta penduduknya sejak abad ke-15 hingga menjelang Perang Dunia I. Beberapa dari petualang itu, seperti Vincent le Blanc (1568), Johann Wild (1697), dan Joseph Pitts (1680) menggambarkan petualangan ke Makkah itu sebagai perjalanan paling mengerikan di dunia. Pitts dan Wild bahkan sempat menjadi budak, tertawan di penjara, dan terombang-ambing tak menentu di kawasan Timur Tengah selama belasan tahun sebelum mereka bisa kembali ke Eropa. Ullrich Jasper Seezen bahkan tewas diracun akibat prasangka keliru atau mungkin karena intrik politik.
"Orang itu memperingatkan Keane (John Fryer Keane) bahwa orang Inggris yang menyamar sebagai muslim hanya untuk melihat prosesi haji lalu menuliskan buku tentangnya sudah ada tiga orang, dan ketiganya dirantai besi pada lehernya dan diborgol di tengah-tengah perbukitan" (halaman 278).
Para penjelajah paling awal, mengingat pengalaman buruk yang mereka alami dan mungkin juga karena pendapat pribadi mereka, menggambarkan ritual haji dan kota Makkah dengan kecenderungan agak negatif. Makkah digambarkan sebagai lembah tandus yang kering kerontang, dipenuhi dengan para fakir yang meminta sedekah, serta para penipu licik yang siap memangsa para jamaah yang lengah. Perjalanan menembus padang gurun digambarkan seperti neraka dunia, bahkan mereka juga menghina air zamzam. Entah karena siksaan yang mereka hadapi saat berpetualang, ataukah hal ini kian menegaskan kesucian kota ini bagi nonmuslim, para petualang ini rata-rata kapok setelah satu kali berkunjung ke sana. Deskripsi yang lebih netral tentang Makkah diberikan oleh John Ludwig Burckhardt dan Sir Richard Burton. Keduanya dikenal mampu menghasilkan sebuah bunga rampai perjalanan ke Makkah yang ditulis secara objektif dan minim prasangka. Penggambarannya atas Masjid Besar sangat sempurna. Burckhardt jarang menyinggung pengalaman personal dan lebih suka menghimpun berbagai kebenaran dan fakta. Melalui tulisannya, kita bisa mengetahui bagaimana keadaan kota suci ini di abad 19.
"Ia menyebut Makkah sebagai kota yang indah, panjangnya sekitar 1.500 langkah. Pembatas alami berupa perbukitan menjadi ganti dari pagar-pagar buatan. … Rumah-rumah dibangun dari batu abu-abu gelap, berbeda dengan rumah-rumah di Jeddah yang dibangun dari batu-batu putih mencorong….tidak ada rumah yang umurnya lebih dari 4 abad….Jalan-jalan menjadi gelap gulita di waktu malam…(113 - 114).
Dari Bartema, kita bisa mengira-ngira bagaimana bentuk bangunan Masjidil Haram pada abad ke-16:
"Tempat peribadatan berada di tengah-tengah kota, seperti Colossus di Roma dan stadion Roma. Tempat-tempat ibadat ini tidak dibangun dari marmer atau batu pahat, tapi dari batu bata yang dipanggang (dibakar). Di pintu masuk, terdapat dinding-dinding berlapiskan emas yang berkilau dari segala arah, terlihat sangat indah dan tiada tandingannya. Di bawah tempat-tempat melengkung, terlihat kerumunan banyak orang, …" (halaman 40).
Petualangan yang paling akbar dicatatkan oleh Sir RIcard Burton yang menulis ulang petualangannya ini dalam tiga jilid tebal autobiografinya Pilgrimage to AL-Madinah and Meccah yang mendapatkan sambutan di Barat maupun di Timur karena narasinya yang memukau bak novel petualangan, yang dikisahkan dengan begitu indah:
"Saat itu bulan hampir penuh, menyinari bangunan Ka'bah yang mirip peti bergaris warna perak. Bangunan ini kelihatan jelas, bahkan lebih jelas daripada waktu siang hari. Di sanalah bangunan itu berada, sendirian, seolah-olah perwujudan keesaan dan keagungan Yang Esa, inti semua ajaran Islam." (halaman 237).
Walaupun dengan segala kesulitan dan ancaman yang harus dihadapi, nyatanya jamaah haji terus berdatangan dari seluruh penjuru dunia ke kedua kota suci ini. Panggilan Ilahi begitu sulit untuk mereka tolak, karena pahala dan ganjaran Surga memang jauh melampaui kesulitan-kesulitan duniawi yang menghadang para jamaah untuk berkunjung ke Baitullah. Dari para petualang Eropa ini, kita bisa mengetahui rekam jejak ibadah haji dari masa ke masa, tentang kesulitan yang menghadang dan juga keberkahan yang telah menanti para tamu Allah ini. Saksikan bagaimana kesaksian Burckhardt ketika melihat tulusnya seorang jamaah haji dari Darfur, Sudan, yang langsung gemetar ketika akhirnya ia bisa melihat Ka'bah yang agung itu setelah menempuh perjalanan menembus gurun nan gersang, "Ya Allah, ambillah nyawaku sekarang, ia berseru. Ini adalah surga!"

Judul : Orang Kristen Naik Haji Penulis : Augustus RalliPenerjemah : Taufik Damas
Penyunting : Adi TohaPemeriksa aks : Dian PranasariCetakan : 1, Agustus 2011Tebal : 371 halamanPenerbit : Serambi Ilmu Semesta
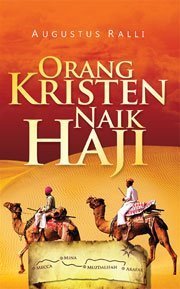
Membaca judulnya saja sudah sangat kontroversial, dan isinya ternyata jauh lebih kontroversial lagi. Pembaca, termasuk saya, sekilas mungkin akan mengira bahwa buku ini hendak membahas tentang kisah-kisah para mualaf yang berkesempatan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, ternyata tidak demikian—malah jauh lebih seru dari itu. Judul bahasa Inggris dari buku ini mungkin lebih mampu menggambarkan isi sebenarnya dari buku yang ditulis pada tahun 1901 ini, Christian at Mecca. Buku ini sendiri merupakan kompilasi atau kumpulan kisah dari sejumlah individu-individu dari Barat yang sempat merasakan pahit-getir-manis-panas dan berbahayanya petualangan mengunjungi kota paling disucikan oleh umat Islam, Makkah, ratusan tahun yang lalu.
Makkah dan Madinah, antara abad ke 15 – 19, masih dan tetap merupakan dua kota suci yang menjadi idam-idaman bagi seluruh umat Islam di kolong jagat untuk bisa mengunjunginya. Bedanya, saat itu belum ditemukan transportasi modern yang bisa mengangkut jamaah haji dengan mudah dan cepat. Para jamaah harus melewati jalur darat menembus padang gurun pasir nan gersang dengan terik matahari yang membakar. Lebih dari itu semua, para peziarah juga harus menghadapi ancaman dari suku Badui gurun, perampok, penipu, bahkan kaum Wahabi ekstrem yang waktu itu menguasai kota Madinah. Kaum Wahabi ini begitu rupa ekstremnya sampai-sampai melarang jamaah haji untuk menziarahi makam Baginda Nabi Saw. Jika bagi umat muslim saja sudah begitu sulit, bayangkan bagaimana sulitnya memasuki Mekkah bagi orang Eropa yang non Muslim?
Seperti telah kita ketahui, ajaran Islam melarang orang yang beragama selain Islam untuk memasuki kota suci Makkah. Bagi yang melanggar, hukumannya pada masa itu adalah digantung atau dipenggal. Apalagi Saudi Arabia kala itu dikuasai oleh kaum Wahabi yang terkenal sangat ekstrem dalam urusan ajaran agama. Namun, yang namanya manusia memang makhluk yang selalu haus akan petualangan. Apa yang dilarang terkadang malah semakin membuatnya semakin tertarik untuk melanggarnya. Makkah yang begitu tertutup bagi Eropa, yang hanya segelintir orang di barat yang mengetahui kondisi dan situasi di dalamnya, menjadikan kota suci ini sebagai tujuan eksotis nan menantang bagi para petualang Eropa. Bahkan, hukuman mati bagi mereka yang ketahuan mengaku sebagai muslim di Makkah tidak mampu menghalangi jiwa-jiwa yang penuh rasa ingin tahu itu untuk menguak rahasia-rahasia dari agama ini, langsung dari tempat di mana Islam pertama kali diturunkan.
Satu per satu, bab-bab dalam buku ini menguraikan siapa dan bagaimana kisah perjalanan nekat mereka saat menyamar sebagai muslim demi bisa memasuki Makkah. Mulai dari Ludovico Bartema yang pertama kali menginjakkan kaki di Makkah pada 18 Mei 1503, hingga seorang Snouck Hurgronje (yang namanya sudah tidak asing lagi); mereka meninggalkan limpahan arsip dan catatan penting mengenai ritual haji dan pandangan mata dari kota suci ini beserta penduduknya sejak abad ke-15 hingga menjelang Perang Dunia I. Beberapa dari petualang itu, seperti Vincent le Blanc (1568), Johann Wild (1697), dan Joseph Pitts (1680) menggambarkan petualangan ke Makkah itu sebagai perjalanan paling mengerikan di dunia. Pitts dan Wild bahkan sempat menjadi budak, tertawan di penjara, dan terombang-ambing tak menentu di kawasan Timur Tengah selama belasan tahun sebelum mereka bisa kembali ke Eropa. Ullrich Jasper Seezen bahkan tewas diracun akibat prasangka keliru atau mungkin karena intrik politik.
"Orang itu memperingatkan Keane (John Fryer Keane) bahwa orang Inggris yang menyamar sebagai muslim hanya untuk melihat prosesi haji lalu menuliskan buku tentangnya sudah ada tiga orang, dan ketiganya dirantai besi pada lehernya dan diborgol di tengah-tengah perbukitan" (halaman 278).
Para penjelajah paling awal, mengingat pengalaman buruk yang mereka alami dan mungkin juga karena pendapat pribadi mereka, menggambarkan ritual haji dan kota Makkah dengan kecenderungan agak negatif. Makkah digambarkan sebagai lembah tandus yang kering kerontang, dipenuhi dengan para fakir yang meminta sedekah, serta para penipu licik yang siap memangsa para jamaah yang lengah. Perjalanan menembus padang gurun digambarkan seperti neraka dunia, bahkan mereka juga menghina air zamzam. Entah karena siksaan yang mereka hadapi saat berpetualang, ataukah hal ini kian menegaskan kesucian kota ini bagi nonmuslim, para petualang ini rata-rata kapok setelah satu kali berkunjung ke sana. Deskripsi yang lebih netral tentang Makkah diberikan oleh John Ludwig Burckhardt dan Sir Richard Burton. Keduanya dikenal mampu menghasilkan sebuah bunga rampai perjalanan ke Makkah yang ditulis secara objektif dan minim prasangka. Penggambarannya atas Masjid Besar sangat sempurna. Burckhardt jarang menyinggung pengalaman personal dan lebih suka menghimpun berbagai kebenaran dan fakta. Melalui tulisannya, kita bisa mengetahui bagaimana keadaan kota suci ini di abad 19.
"Ia menyebut Makkah sebagai kota yang indah, panjangnya sekitar 1.500 langkah. Pembatas alami berupa perbukitan menjadi ganti dari pagar-pagar buatan. … Rumah-rumah dibangun dari batu abu-abu gelap, berbeda dengan rumah-rumah di Jeddah yang dibangun dari batu-batu putih mencorong….tidak ada rumah yang umurnya lebih dari 4 abad….Jalan-jalan menjadi gelap gulita di waktu malam…(113 - 114).
Dari Bartema, kita bisa mengira-ngira bagaimana bentuk bangunan Masjidil Haram pada abad ke-16:
"Tempat peribadatan berada di tengah-tengah kota, seperti Colossus di Roma dan stadion Roma. Tempat-tempat ibadat ini tidak dibangun dari marmer atau batu pahat, tapi dari batu bata yang dipanggang (dibakar). Di pintu masuk, terdapat dinding-dinding berlapiskan emas yang berkilau dari segala arah, terlihat sangat indah dan tiada tandingannya. Di bawah tempat-tempat melengkung, terlihat kerumunan banyak orang, …" (halaman 40).
Petualangan yang paling akbar dicatatkan oleh Sir RIcard Burton yang menulis ulang petualangannya ini dalam tiga jilid tebal autobiografinya Pilgrimage to AL-Madinah and Meccah yang mendapatkan sambutan di Barat maupun di Timur karena narasinya yang memukau bak novel petualangan, yang dikisahkan dengan begitu indah:
"Saat itu bulan hampir penuh, menyinari bangunan Ka'bah yang mirip peti bergaris warna perak. Bangunan ini kelihatan jelas, bahkan lebih jelas daripada waktu siang hari. Di sanalah bangunan itu berada, sendirian, seolah-olah perwujudan keesaan dan keagungan Yang Esa, inti semua ajaran Islam." (halaman 237).
Walaupun dengan segala kesulitan dan ancaman yang harus dihadapi, nyatanya jamaah haji terus berdatangan dari seluruh penjuru dunia ke kedua kota suci ini. Panggilan Ilahi begitu sulit untuk mereka tolak, karena pahala dan ganjaran Surga memang jauh melampaui kesulitan-kesulitan duniawi yang menghadang para jamaah untuk berkunjung ke Baitullah. Dari para petualang Eropa ini, kita bisa mengetahui rekam jejak ibadah haji dari masa ke masa, tentang kesulitan yang menghadang dan juga keberkahan yang telah menanti para tamu Allah ini. Saksikan bagaimana kesaksian Burckhardt ketika melihat tulusnya seorang jamaah haji dari Darfur, Sudan, yang langsung gemetar ketika akhirnya ia bisa melihat Ka'bah yang agung itu setelah menempuh perjalanan menembus gurun nan gersang, "Ya Allah, ambillah nyawaku sekarang, ia berseru. Ini adalah surga!"
Published on October 05, 2011 22:20
October 2, 2011
Peradaban Atlantis Nusantara
Judul : Peradaban Atlantis Nusantara, Berbagai Penemuan Spektakuler yang makin Meyakinkan KebenarannyaPenulis : Ahmad Yanuana Saamantho dkkPenyunting : Mayang Sari AriawanTebal : 540 halamanCetakan : 1, Juli 2011Penerbit : Ufuk PressHarga : Rp 74.000,00

Membicarakan mengenai Atlantis seolah memang tidak akan pernah ada habisnya. Atlantis sendiri secara tidak langsung melambangkan masyarakat utopis yang luar biasa ideal, dan inilah sebabnya peradaban ini menjadi salah satu yang paling menarik untuk terus diteliti dan diperbincangkan. Tempat ini disebutkan pertama kali oleh filsuf Plato dari Yunani Kuno sekitar abad 4 SM, dan sampai sekarang tidak kurang dari 500 buku dan film telah ditulis dan diangkat berdasarkan benua legendaris yang konon ditenggelamkan di dasar samudra. Selain keberadaannya yang seolah "ada tapi tiada", kontroversi ini juga berkaitan dengan letak sesungguhnya dari benua yang ditenggelamkan ini. Plato sendiri dalam karyanyaTimeaus and Critias (ditulis pada 360 SM) menjelaskan bahwa pulau Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules (yang selama ini dianggap sebagai semenanjung Gibraltar karena menghadap langsung ke samudra Atlantik). Pulau makmur ini tenggelam ke laut hanya dalam waktu satu malam akibat hukuman para dewa yang murka kepada penduduk Atlantis. Entah Atlantis versi Plato ini hanya melambangkan suatu konsep Philosopher King dalam Republic-nya, ataukah dulu Atlantis ini memang benar-benar ada, yang jelas pencarian terhadap lokasi Atlantis tidak pernah berhenti.
Beragam dugaan tentang letak tepat dari benua Atlantis pun bermunculan. Berbagai klaim dan perkiraan diajukan, di antaranya di Samudra Atlantik, di laut Mediterania, di pulau Siprus, hingga di laut Karibia di benua Amerika. Masalahnya, pada masa Plato (dan juga pada masa Herodotus dan Aristoteles), Atlantik digunakan untuk merujuk pada seluruh samudra atau lautan di seluruh dunia. Bahkan, Plato merujuk kata "Atlantik" ini kepada Samudra Hindia sekarang. Seolah semua kontroversi itu belum cukup, pada tahun 2005 seorang profesor geologi dari Brazil yang bernama Prof. Dr. Aryo Santos meluncurkan bukunya Atlantis, the Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization (buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Ufuk) yang tidak kalah menghebohkan dunia. Santos, melanjutkan hipotesis Oppenheimer, mengajukan klaim bahwa Atlantis itu terletak di Nusantara, tepatnya di paparan Sunda atau laut dangkal antara pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan dan India.
Alkisah, sekitar 10.000 tahun SM, ketika Bumi mengalami zaman es yang terakhir, diperkirakan memang ada sebuah peradaban besar yang maju. Karena saat itu kawasan Amerika Utara, Asia, Timur Tengah, Eropa dan sebelah Selatan Afrika masih tertutup oleh tudung es yang luas, maka satu-satunya daratan yang memungkinkan munculnya peradaban adalah di wilayah tropis yang suhu udaranya hangat di samping datarannya yang luas. Dugaan ini lah yang digunakan Santos untuk mengajukan klaim bahwa Atlantis dulunya berada di kawasan Sundaland, sebuah dataran luas yang menyatukan India, Sumatra, Jawa dan Kalimantan. Kondisi geografis Indonesia yang bergunung-gunung serta keadaan alamnya yang subur juga semakin menguatkan klaim Santos. Ledakan Megavolcano Toba, Krakatau, Tambora dan gunung-gunung lain di Nusantara Purba inilah yang kemudian menyebabkan tenggelamnya Atlantis.
Buku Peradaban Atlantis Nusantara karya Ahmad Y. Samantho dan Oman Abdurahman et. All ini ibarat bunga rampai yang sangat komprehensif untuk menguak misteri keberadaan benua Atlantis, terutama kaitannya dengan klaim bahwa Atlantis dulunya memang berada di Nusantara Purba. Bagi Anda yang merasa buku Oppenheimer dan Santos—yang harganya di atas ratusan ribu—terlalu mahal, maka buku ini bisa menjadi semacam penghalang dahaga keingintahuan yang sangat memuaskan. Di dalamnya, kita bisa membaca rangkuman atau mungkin malah pemaparan secara lebih komprehensif mengenai karya Oppenheimer Eden in the East dan karya Santos Atlantis, Lost Continent finally Found.Lebih keren lagi, di buku ini juga ditampilkan sejumlah tulisan yang lebih lokal, yakni terkait dengan dugaan-dugaan dan/atau temuan-temuan sejumlah pakar Indonesia dari beragam ranah keilmuan yang intinya hendak mendukung klaim bahwa Atlantis itu berada di Nusantara atau Sundaland. Misalnya saja, adanya kemiripan bentuk candi Sukuh yang menyerupai piramida bangsa Aztec, juga sebuah bukit di Jawa Barat yang diperkirakan adalah sebuah piramida yang tertimbun tanah karena bentuknya yang sangat simetris.
Bagian paling menarik dari buku ini bisa ditemukan pada bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, dan 13. Dengan tidak memungkiri pentingnya bab-bab yang lain; membaca bab-bab favorit di atas bisa diibaratkan seperti memutar film tentang Atlantis, mulai dari kemunculannya dalam karya Plato, hingga klaim bahwa Atlantis itu memang berada di Sundaland. Dalam bab-bab ini, pembaca akan menemukan jawaban dari mengapa peradaban yang besar itu bisa musnah tanpa meninggalkan jejak, sedahsyat apa bencana yang terjadi kala itu, apa keterkaitan antara tenggelamnya Atlantis dengan penyebaran atau diaspora penduduk dunia, benarkan nenek moyang bangsa-bangsa India dan Mesopotamia itu berasal dari Nusantara, bagaimana kisah terbentuknya selat Sunda terkait dengan tenggelamnya Atlantis, apakah pilar-pilar Herkules yang dimaksud Plato itu adalah gunung-gunung di Sumatra dan Jawa, dan masih banyak lagi tema-tema menarik seputar Atlantis yang luar biasa menarik untuk dibaca.
Karena formatnya yang berupa bunga rampai, mungkin sejumlah pembaca agak kecewa karena buku setebal 540 halaman ini tidak melulu membahas Atlantis. Beberapa bab di bagian belakang, bahkan membahas ranah filsafat ala Yunani yang mungkin sengaja dimasukkan dalam buku ini karena keterkaitan erat antara Atlantis, Plato, dan Yunani. Selain itu, masih dijumpai typo serta kekurangsempurnaan editan di halaman 70–90. Namun, secara garis besar, buku ini sangat memuaskan dahaga intelektual para pembaca yang mengidam-idamkan tema-tema Atlantis yang dibahas secara komprehensif dan ilmiah. Dan, para penyusun yang turut menyumbangkan tulisannya dalam buku ini pun sudah terbukti keandalannya dalam ranah masing-masing. Inilah yang membuat buku ini begitu bermutu dan berbobot. Sungguh sebuah karya yang niscaya akan mengajak kita untuk meneguhkan kembali jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Dengan membaca buku ini, sejarah Nusantara mungkin harus sedikit direvisi.


Membicarakan mengenai Atlantis seolah memang tidak akan pernah ada habisnya. Atlantis sendiri secara tidak langsung melambangkan masyarakat utopis yang luar biasa ideal, dan inilah sebabnya peradaban ini menjadi salah satu yang paling menarik untuk terus diteliti dan diperbincangkan. Tempat ini disebutkan pertama kali oleh filsuf Plato dari Yunani Kuno sekitar abad 4 SM, dan sampai sekarang tidak kurang dari 500 buku dan film telah ditulis dan diangkat berdasarkan benua legendaris yang konon ditenggelamkan di dasar samudra. Selain keberadaannya yang seolah "ada tapi tiada", kontroversi ini juga berkaitan dengan letak sesungguhnya dari benua yang ditenggelamkan ini. Plato sendiri dalam karyanyaTimeaus and Critias (ditulis pada 360 SM) menjelaskan bahwa pulau Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules (yang selama ini dianggap sebagai semenanjung Gibraltar karena menghadap langsung ke samudra Atlantik). Pulau makmur ini tenggelam ke laut hanya dalam waktu satu malam akibat hukuman para dewa yang murka kepada penduduk Atlantis. Entah Atlantis versi Plato ini hanya melambangkan suatu konsep Philosopher King dalam Republic-nya, ataukah dulu Atlantis ini memang benar-benar ada, yang jelas pencarian terhadap lokasi Atlantis tidak pernah berhenti.
Beragam dugaan tentang letak tepat dari benua Atlantis pun bermunculan. Berbagai klaim dan perkiraan diajukan, di antaranya di Samudra Atlantik, di laut Mediterania, di pulau Siprus, hingga di laut Karibia di benua Amerika. Masalahnya, pada masa Plato (dan juga pada masa Herodotus dan Aristoteles), Atlantik digunakan untuk merujuk pada seluruh samudra atau lautan di seluruh dunia. Bahkan, Plato merujuk kata "Atlantik" ini kepada Samudra Hindia sekarang. Seolah semua kontroversi itu belum cukup, pada tahun 2005 seorang profesor geologi dari Brazil yang bernama Prof. Dr. Aryo Santos meluncurkan bukunya Atlantis, the Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization (buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Ufuk) yang tidak kalah menghebohkan dunia. Santos, melanjutkan hipotesis Oppenheimer, mengajukan klaim bahwa Atlantis itu terletak di Nusantara, tepatnya di paparan Sunda atau laut dangkal antara pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan dan India.
Alkisah, sekitar 10.000 tahun SM, ketika Bumi mengalami zaman es yang terakhir, diperkirakan memang ada sebuah peradaban besar yang maju. Karena saat itu kawasan Amerika Utara, Asia, Timur Tengah, Eropa dan sebelah Selatan Afrika masih tertutup oleh tudung es yang luas, maka satu-satunya daratan yang memungkinkan munculnya peradaban adalah di wilayah tropis yang suhu udaranya hangat di samping datarannya yang luas. Dugaan ini lah yang digunakan Santos untuk mengajukan klaim bahwa Atlantis dulunya berada di kawasan Sundaland, sebuah dataran luas yang menyatukan India, Sumatra, Jawa dan Kalimantan. Kondisi geografis Indonesia yang bergunung-gunung serta keadaan alamnya yang subur juga semakin menguatkan klaim Santos. Ledakan Megavolcano Toba, Krakatau, Tambora dan gunung-gunung lain di Nusantara Purba inilah yang kemudian menyebabkan tenggelamnya Atlantis.
Buku Peradaban Atlantis Nusantara karya Ahmad Y. Samantho dan Oman Abdurahman et. All ini ibarat bunga rampai yang sangat komprehensif untuk menguak misteri keberadaan benua Atlantis, terutama kaitannya dengan klaim bahwa Atlantis dulunya memang berada di Nusantara Purba. Bagi Anda yang merasa buku Oppenheimer dan Santos—yang harganya di atas ratusan ribu—terlalu mahal, maka buku ini bisa menjadi semacam penghalang dahaga keingintahuan yang sangat memuaskan. Di dalamnya, kita bisa membaca rangkuman atau mungkin malah pemaparan secara lebih komprehensif mengenai karya Oppenheimer Eden in the East dan karya Santos Atlantis, Lost Continent finally Found.Lebih keren lagi, di buku ini juga ditampilkan sejumlah tulisan yang lebih lokal, yakni terkait dengan dugaan-dugaan dan/atau temuan-temuan sejumlah pakar Indonesia dari beragam ranah keilmuan yang intinya hendak mendukung klaim bahwa Atlantis itu berada di Nusantara atau Sundaland. Misalnya saja, adanya kemiripan bentuk candi Sukuh yang menyerupai piramida bangsa Aztec, juga sebuah bukit di Jawa Barat yang diperkirakan adalah sebuah piramida yang tertimbun tanah karena bentuknya yang sangat simetris.
Bagian paling menarik dari buku ini bisa ditemukan pada bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, dan 13. Dengan tidak memungkiri pentingnya bab-bab yang lain; membaca bab-bab favorit di atas bisa diibaratkan seperti memutar film tentang Atlantis, mulai dari kemunculannya dalam karya Plato, hingga klaim bahwa Atlantis itu memang berada di Sundaland. Dalam bab-bab ini, pembaca akan menemukan jawaban dari mengapa peradaban yang besar itu bisa musnah tanpa meninggalkan jejak, sedahsyat apa bencana yang terjadi kala itu, apa keterkaitan antara tenggelamnya Atlantis dengan penyebaran atau diaspora penduduk dunia, benarkan nenek moyang bangsa-bangsa India dan Mesopotamia itu berasal dari Nusantara, bagaimana kisah terbentuknya selat Sunda terkait dengan tenggelamnya Atlantis, apakah pilar-pilar Herkules yang dimaksud Plato itu adalah gunung-gunung di Sumatra dan Jawa, dan masih banyak lagi tema-tema menarik seputar Atlantis yang luar biasa menarik untuk dibaca.
Karena formatnya yang berupa bunga rampai, mungkin sejumlah pembaca agak kecewa karena buku setebal 540 halaman ini tidak melulu membahas Atlantis. Beberapa bab di bagian belakang, bahkan membahas ranah filsafat ala Yunani yang mungkin sengaja dimasukkan dalam buku ini karena keterkaitan erat antara Atlantis, Plato, dan Yunani. Selain itu, masih dijumpai typo serta kekurangsempurnaan editan di halaman 70–90. Namun, secara garis besar, buku ini sangat memuaskan dahaga intelektual para pembaca yang mengidam-idamkan tema-tema Atlantis yang dibahas secara komprehensif dan ilmiah. Dan, para penyusun yang turut menyumbangkan tulisannya dalam buku ini pun sudah terbukti keandalannya dalam ranah masing-masing. Inilah yang membuat buku ini begitu bermutu dan berbobot. Sungguh sebuah karya yang niscaya akan mengajak kita untuk meneguhkan kembali jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Dengan membaca buku ini, sejarah Nusantara mungkin harus sedikit direvisi.
Published on October 02, 2011 19:00
September 29, 2011
Letters to Sam
Judul : Letters to SamPenulis : Daniel GottliebPenerjemah : Windy AriestantyEditor : Ninus D. AndarnuswatiProofreader : Christian SimamoraPenata Letak : Nopianto RicaesarDesain Sampul: Dwi Anissa AnindhikaCetakan : Pertama, 2011Tebal : 217 halamanPenerbit : Gagas MediaHarga : Rp 45.000,00
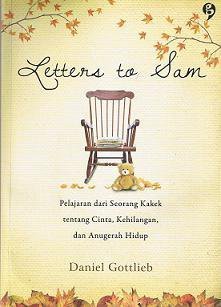
Apa yang akan tercipta ketika seorang kakek lumpuh yang jago psikologi, seorang cucu yang mengalami gangguan autisme, dan syair Rumi nan indah tentang "penyambutan tamu" saling dipertemukan? Tidak lain tidak bukan, hasilnya adalah kumpulan goresan indah tentang pelajaran kehidupan yang terangkum Letters to Sam, Pelajaran dari seorang Kakek tentang Cinta, Kehilangan dan Anugerah Hidup. Sebuah buku yang akan mengubah pandangan kita akan sosok-sosok yang selama ini terabaikan karena mereka asyik dengan dunianya sendiri.
20 Mei 2000, penulis buku ini mengalami salah satu momen paling luar biasa dalam kehidupannya, yakni hadirnya seorang cucu bernama Sam—yang kelahirannya ke dunia seolah memang telah ditakdirkan untuk membuat sang Kakek dan jutaan orang lain di dunia menjadi lebih memahami apa makna sesungguhnya dari kehidupan. Bahwa kehidupan itu memang sempurna, tapi tidak apa-apa jika ada sejumlah ketidaksempurnaan di dalamnya karena kehidupan itu sendiri selalu sempurna bagi mereka yang mampu menjalaninya dengan penuh rasa syukur.
Menjadi lumpuh akibat kecelakaan mobil, seorang Daniel Gottlieb harus mengalami lagi satu ketidaksempurnaan dalam hidup, cucunya—yakni si Sam—didiagnosis mengalami gangguan psikologis yang oleh orang awam dikenal sebagai autisme. Namun, alih-alih membuatnya depresi, dua ketidaksempurnaan besar dalam kehidupan ini malah semakin membuat sang Kakek bijak lebih menghargai hidup. Dari kedua ketidaksempurnaan itu, ia mampu memeras intisari dari nilai-nilai kehidupan; yang seharusnya kita sibuk mengisinya dengan hasrat dan harapan, bukannya sibuk mewarnainya dengan keluhan dan ketidakbahagiaan.
"Dengan cedera tulang belakangku dan autisme yang kau miliki, kita terlihat berbeda dan bertindak berbeda. Tapi, kita juga bisa mengajari orang lain, sebagaimana Norma telah mengajariku, bahwa apapun yang terjadi dengan tubuh atau pikiran kita, jiwa kita akan tetap utuh." (halaman 71).
Bahwa bukan kehidupan itu yang harus kita paksa agar sesuai dengan harapan kita, tapi lebih pada bagaimana kita mengubah pandangan kita terhadap kehidupan itu sendiri. Kakek si Sam telah mempelajari hal ini sebagai salah satu cara untuk "mensyukuri" kelumpuhannya, yang semoga saja juga kelak digunakan oleh cucunya untuk "mensyukuri" autisme yang ia alami. Buku Letters to Sam adalah kumpulan dari surat-surat Daniel Gottlieb kepada cucunya, Sam. Ia berharap, melalui buku ini kelas sang cucu terkasih akan mampu memandang dunia sebagaimana kakeknya memandang dunia ini dengan penuh rasa syukur.
Dengan bahasa akrab khas seorang kakek yang tengah berbicara kepada cucunya, buku ini akan mengajak pembaca untuk sejenak menenggok ulang apa dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama ini. Apakah selama ini kita memandang "hidup adalah rangkaian masalah sulit yang harus dipecahkan dengan sedikit kesenangan" ataukah ia memandang "hidup adalah harta karun yang harus disyukuri; keduanya akan menghasilkan pemaknaan dan penghayatan yang berbeda tentang kehidupan itu sendiri. Apakah kita menyibukkan hidup dengan selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, apakah kita sibuk mencemburui kelebihan orang lain ketimbang mensyukuri kelebihan dalam diri? Hidup sebagaimana yang diajarkan oleh kakek si Sam adalah dengan menghargai ketidaksempurnaan-ketidaksempurnaan kecil dan lebih mensyukuri kehidupan yang sebenarnya sudah luar biasa sempurna.
Disusun dengan model buku surat, setiap bab dalam buku ini adalah sepucuk surat yang ditulis sendiri oleh Daniel Gottlieb untuk cucunya. Masing-masing bab berisi secuil pengalaman sang penulis, yang kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek psikologi modern, sehingga menghasilkan untaian kisah-kisah bijak yang bisa juga dipelajari oleh semua orang. Hanya saja, ada beberapa anjuran atau kisah-surat dalam buku ini yang sifatnya terlalu "khusus", seolah solusi yang ditawarkan masih terlalu "Amerika" sehingga kurang sreg jika diterapkan oleh pembaca dengan latar budaya yang berbeda. Beberapa perilaku atau kebiasaan yang dijadikan sebagai contoh pun ada beberapa yang terasa kurang pas untuk diterapkan secara "saklek" di budaya kita. Entahlah, mungkin hanya karena perbedaan latar belakang dan budaya semata.
Namun, terlepas dari itu semua, satu pelajaran terbaik dari buku ini terselip dengan begitu manisnya pada sebuah paragraf di halaman 198.
"Sering sekali, orang yang melangkah keluar dari dirinya dan mulai membantu orang lain akan mengalami perasaan yang jauh lebih baik dengan cepat. Mereka menjadi bagian dari dunia yang lebih luas. Masalah-masalah mereka tidak lagi memenuhi hidup mereka."(halaman 198).
Kalau yang ini saya setuju!
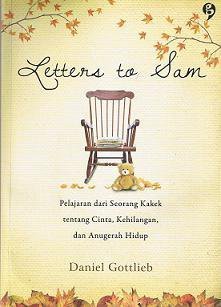
Apa yang akan tercipta ketika seorang kakek lumpuh yang jago psikologi, seorang cucu yang mengalami gangguan autisme, dan syair Rumi nan indah tentang "penyambutan tamu" saling dipertemukan? Tidak lain tidak bukan, hasilnya adalah kumpulan goresan indah tentang pelajaran kehidupan yang terangkum Letters to Sam, Pelajaran dari seorang Kakek tentang Cinta, Kehilangan dan Anugerah Hidup. Sebuah buku yang akan mengubah pandangan kita akan sosok-sosok yang selama ini terabaikan karena mereka asyik dengan dunianya sendiri.
20 Mei 2000, penulis buku ini mengalami salah satu momen paling luar biasa dalam kehidupannya, yakni hadirnya seorang cucu bernama Sam—yang kelahirannya ke dunia seolah memang telah ditakdirkan untuk membuat sang Kakek dan jutaan orang lain di dunia menjadi lebih memahami apa makna sesungguhnya dari kehidupan. Bahwa kehidupan itu memang sempurna, tapi tidak apa-apa jika ada sejumlah ketidaksempurnaan di dalamnya karena kehidupan itu sendiri selalu sempurna bagi mereka yang mampu menjalaninya dengan penuh rasa syukur.
Menjadi lumpuh akibat kecelakaan mobil, seorang Daniel Gottlieb harus mengalami lagi satu ketidaksempurnaan dalam hidup, cucunya—yakni si Sam—didiagnosis mengalami gangguan psikologis yang oleh orang awam dikenal sebagai autisme. Namun, alih-alih membuatnya depresi, dua ketidaksempurnaan besar dalam kehidupan ini malah semakin membuat sang Kakek bijak lebih menghargai hidup. Dari kedua ketidaksempurnaan itu, ia mampu memeras intisari dari nilai-nilai kehidupan; yang seharusnya kita sibuk mengisinya dengan hasrat dan harapan, bukannya sibuk mewarnainya dengan keluhan dan ketidakbahagiaan.
"Dengan cedera tulang belakangku dan autisme yang kau miliki, kita terlihat berbeda dan bertindak berbeda. Tapi, kita juga bisa mengajari orang lain, sebagaimana Norma telah mengajariku, bahwa apapun yang terjadi dengan tubuh atau pikiran kita, jiwa kita akan tetap utuh." (halaman 71).
Bahwa bukan kehidupan itu yang harus kita paksa agar sesuai dengan harapan kita, tapi lebih pada bagaimana kita mengubah pandangan kita terhadap kehidupan itu sendiri. Kakek si Sam telah mempelajari hal ini sebagai salah satu cara untuk "mensyukuri" kelumpuhannya, yang semoga saja juga kelak digunakan oleh cucunya untuk "mensyukuri" autisme yang ia alami. Buku Letters to Sam adalah kumpulan dari surat-surat Daniel Gottlieb kepada cucunya, Sam. Ia berharap, melalui buku ini kelas sang cucu terkasih akan mampu memandang dunia sebagaimana kakeknya memandang dunia ini dengan penuh rasa syukur.
Dengan bahasa akrab khas seorang kakek yang tengah berbicara kepada cucunya, buku ini akan mengajak pembaca untuk sejenak menenggok ulang apa dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama ini. Apakah selama ini kita memandang "hidup adalah rangkaian masalah sulit yang harus dipecahkan dengan sedikit kesenangan" ataukah ia memandang "hidup adalah harta karun yang harus disyukuri; keduanya akan menghasilkan pemaknaan dan penghayatan yang berbeda tentang kehidupan itu sendiri. Apakah kita menyibukkan hidup dengan selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, apakah kita sibuk mencemburui kelebihan orang lain ketimbang mensyukuri kelebihan dalam diri? Hidup sebagaimana yang diajarkan oleh kakek si Sam adalah dengan menghargai ketidaksempurnaan-ketidaksempurnaan kecil dan lebih mensyukuri kehidupan yang sebenarnya sudah luar biasa sempurna.
Disusun dengan model buku surat, setiap bab dalam buku ini adalah sepucuk surat yang ditulis sendiri oleh Daniel Gottlieb untuk cucunya. Masing-masing bab berisi secuil pengalaman sang penulis, yang kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek psikologi modern, sehingga menghasilkan untaian kisah-kisah bijak yang bisa juga dipelajari oleh semua orang. Hanya saja, ada beberapa anjuran atau kisah-surat dalam buku ini yang sifatnya terlalu "khusus", seolah solusi yang ditawarkan masih terlalu "Amerika" sehingga kurang sreg jika diterapkan oleh pembaca dengan latar budaya yang berbeda. Beberapa perilaku atau kebiasaan yang dijadikan sebagai contoh pun ada beberapa yang terasa kurang pas untuk diterapkan secara "saklek" di budaya kita. Entahlah, mungkin hanya karena perbedaan latar belakang dan budaya semata.
Namun, terlepas dari itu semua, satu pelajaran terbaik dari buku ini terselip dengan begitu manisnya pada sebuah paragraf di halaman 198.
"Sering sekali, orang yang melangkah keluar dari dirinya dan mulai membantu orang lain akan mengalami perasaan yang jauh lebih baik dengan cepat. Mereka menjadi bagian dari dunia yang lebih luas. Masalah-masalah mereka tidak lagi memenuhi hidup mereka."(halaman 198).
Kalau yang ini saya setuju!
Published on September 29, 2011 18:57



