Lutfi Retno Wahyudyanti's Blog, page 6
February 24, 2014
Harga Sebuah Karya
Seorang teman, sebut saja Entus, bercerita kalau menerima tawaran untuk mengerjakan sebuah program TV. Entus sempat menolak mengerjakan tontonan tersebut karena anggarannya terlalu kecil. Ia akhirnya mengambil program tadi karena timnya sedang membutuhkan uang.
Saya jadi teringat saat membaca majalah milik sebuah perusahaan beberapa waktu lalu. Majalah yang dikelola seorang penulis senior di sebuah komunitas tadi tampilannya jelek. Warna dan foto yang dipakai seperti asal pasang. Sebagian besar artikelnya berantakan. Banyak salah ketik dan tulisannya tidak menarik. Terlalu fatal mengingat penanggung jawabnya bukan penulis kemarin sore.
Saya kemudian bertanya, apakah pembuatan terbitan tersebut mepet waktunya? Si penulis dengan santainya menjawab jika perusahaan pemesan majalah tidak menghargai seni. Mereka membayar rendah satu paket mulai dari penulisan, editing, hingga desain majalah. Saya, langsung tidak menaruh hormat pada penulis tadi. Menurut saya, saat mengatakan iya untuk sebuah pekerjaan artinya tidak ada lagi alasan untuk mengerjakan dengan separuh hati. Kata iya artinya saya tidak lagi memikirkan berapa banyak saya dibayar. Bagaimanapun juga, nama saya akan tercantum di karya tadi. Bukankah pekerjaan yang bagus bisa saya pakai untuk mencari klien baru?
Saya dan penulis tadi kemudian ngobrol tentang hal lain. Ia menawarkan jasanya jika suatu saat nanti saya membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan komunitas buku. Saya hanya tersenyum dan berkata sedang tidak punya rencana. Padahal, kalaupun ada, saya tidak tertarik mempekerjakan orang yang hanya semata-mata bekerja untuk uang. Saya tidak yakin hasil kerjanya akan bagus.
Di lain waktu, seorang teman bercerita kalau ia gagal psikotes di sebuah perusahaan media. Saya heran, setahu saya, ia baru satu bulan bekerja di tempat sekarang. Terlalu cepat untuk melamar kerja di tempat lain. Menurut Anggi, tempat kerjanya sekarang menyenangkan. Sayang gajinya terlalu kecil. Saya kemudian bertanya, mungkin tidak untuk menego gaji? Anggi bilang, kemungkinan tersebut ada setelah program yang ia tangani sekarang selesai.
Kami kemudian ngobrol tentang bekerja sebaik mungkin sebagai bukti kalau kita menyukuri apa yang kita punya. Bukankah saat kita senang bekerja, sesuatu akan terasa lebih ringan? Bukankah karya yang bagus pasti akan menarik perhatian orang? Kalau sudah saatnya, tawaran akan datang sendiri kok. Bukankah suatu pekerjaan yang baik akan membawa kita naik kelas? Yang artinya, ada orang yang mau membayar lebih mahal.


February 19, 2014
Right to Copy or Copy Right?
Beberapa hari lalu, berbagai media massa memuat berita pernyataan pengunduran diri Anggito Abimanyu sebagai staf pengajar di UGM. Hal tersebut berkaitan dengan dengan opininya di sebuah media nasional yang dituduh menjiplak karya orang lain. Banyak orang, termasuk saya menyayangkan penjiplakan tersebut. Tapi kemudian saya berpikir, kenapa saya mempersoalkan hak cipta? Toh sehari-harinya saya dan semua orang yang menyalahkan Anggito Abimanyu terbiasa dengan barang-barang hasil jiplakan. Bukankah di Indonesia (hampir) semua laptop atau komputer pasti ada sistem operasi, lagu, atau film bajakan? Sandal atau sepatu yang beredar di pasaran juga hasil meniru merk-merk terkenal? Bukankah memakai barang bajakan sama saja mengijinkan pelanggaran hak cipta?
Secara pribadi, saya tidak setuju dengan hak cipta. Setahu saya, itu usaha dari para pemilik modal untuk melindungi (baca: memperkaya) dirinya. Saat ada pemilik hak cipta, orang harus membayar saat menggunakan barangnya. Sebagai seorang penganut Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Aneh saja kalau ada orang yang memperkaya diri sendiri dari hasil memodifikasi ide-ide yang ada sebelumnya.
Bukankah saat menciptakan sesuatu, seseorang pasti punya referensi dari hal yang sudah ada sebelumnya? Kita pakai contoh saja tulisan. Saat saya atau orang lain menulis, ia mengumpulkan ide-ide orang lain yang sebelumnya pernah ia baca, dengar, atau lihat. Jika saya meniru banyak kalimat dari orang lain, sebisa mungkin saya mencantumkan sumber. Sayangnya, ingatan saya terbatas. Saat saya membuat tulisan, bisa jadi idenya berasal dari sumber yang saya baca, lihat, atau dengar puluhan tahun lalu. Atau gabungan dari beberapa ide. Dan saya lupa mana yang saya kutip.
Sebagai seorang muslim, saya percaya kalau ilmu termasuk amal jariah. Ibadah yang tidak akan putus pahalanya meski pemberinya meninggal. Jadi, kalau misalnya ada tulisan, foto, atau film saya dipakai orang lain, saya seharusnya senang. Saya punya sesuatu yang berguna. Kalau untuk masalah rejeki, bukankah itu sudah ada yang mengatur? Saat tahu karya saya dibajak, saya akan berusaha membuat karya yang lebih baik lagi.
Saya beberapa kali menemukan seorang blogger berteriak-teriak di media sosial gara-gara tulisan atau fotonya dikutip orang lain. Meminjam kata Ken Terate, teman saya yang penulis, menaruh sesuatu di dunia maya itu artinya mengijinkan publik mengonsumsinya. Wajar saja kalau nanti ada yang menjiplaknya. Bukankah itu sudah menjadi barang publik? Kalau tidak mau ditiru, ya simpan saja di laptop.
Gara-gara menulis ini, saya jadi penasaran dan membaca tulisan Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan yang katanya dijiplak Anggito Abimayu. Terlalu mirip sekali. Sepertinya sudah tidak etis saat tidak menyebutkan sumber.


February 16, 2014
Buku yang Membuat Bodoh
Saat berkunjung ke sebuah taman bacaan bersama beberapa rekan, penjaganya bercerita tentang pengunjung yang tidak lagi datang. Bocah SD tersebut dilarang orangtuanya membaca buku selain buku pelajaran. Menurut orangtuanya, buku cerita hanya akan mengganggu konsentrasi belajar si anak. Harus dihilangkan supaya nilainya baik.
Sering mendengar komentar senada tidak? Atau bahkan pernah ada di posisi bocah SD tadi? Saya juga sempat mengalami hal tersebut. Dulu, orangtua saya melarang membaca komik di luar hari libur. Mendekati ujian, orangtua saya bahkan mengancam akan membakar koleksi komik saya kalau saya menyentuhnya. Berhubung dulu tidak ada larangan main ke rumah teman, biasanya saya pergi berjam-jam untuk membaca buku. Dan, ada banyak rekan mengalami kejadian serupa saat kecil.
Saya jadi ingat waktu menjadi narasumber di sebuah stasiun radio. Seorang pendengar mengeluhkan budaya membaca yang rendah di Indonesia. Ia menyayangkan hal tersebut karena ada banyak pengetahuan tersimpan dalam buku. Saya menjawab wajar saja kalau budaya membaca rendah. Budaya membaca buku terbentuk dari kebiasaan dan harus diupayakan sejak kecil. Membaca tidak harus dimulai dari mengonsumsi buku-buku berat. Saya jadi teringat waktu akhir tahun lalu harus mengakhiri kegiatan membacakan buku di sebuah tempat penitipan anak. Tahu tidak alasannya? Ibu pengawas tempat penitipan anak tersebut menganggap membaca buku tidak ada hubungannnya dengan kurikulum. Bagaimana membaca bisa jadi budaya kalau begitu?
Dahulu, buku-buku awal yang saya baca juga bukan buku bermutu. Kebanyakan komik yang isinya hanya hiburan dan bisa dibilang tidak mendidik. Tapi, hal tersebut membuat saya tahu buku itu menyenangkan. Semakin dewasa, buku bacaan saya berkembang. Saya mulai meninggalkan komik dan berubah membaca novel. Baru akhir-akhir ini saya tertarik segala macam buku mulai dari antropologi, filsafat, psikologi, sampai geografi. Nah, kalau saat masih kecil saja dilarang-larang membaca, mana mau mereka membaca buku yang lebih berat setelah dewasa.

Kenapa ada pelabelan buku yang boleh dibaca dan tidak untuk anak-anak? Banyak orangtua yang memaksa anak-anaknya menghapal buku pelajaran yang bisa meningkatkan nilai anaknya di sekolahan. Tapi tidak untuk semua buku di luar hal tadi. Sebagian besar orangtua terlalu khawatir tentang masa depan anaknya. Mereka was-was kalau anaknya tidak mendapat sekolah yang baik, saat dewasa mereka tidak akan mendapat pekerjaan yang baik. Yang nanti tidak cukup untuk membayar tagihan dan biaya hidup yang semakin melambung.
Berhubung pendidikan di Indonesia masih menganut sistem menyediakan pekerja untuk industri, ada kasta dalam kurikulum. Hal-hal matematika, kedokteran, fisika, dan teknik menjadi lebih tinggi daripada seni atau bahasa yang katanya “tidak punya masa depan cerah”. Buntutnya, sekolah kemudian mencetak orang-orang yang tidak peka dengan kondisi lingkungannya. Karena mereka tidak diajar untuk berpikir tentang siapa dirinya. Juga apa yang harus ia lakukan untuk menyikapi lingkungannya.
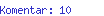

February 13, 2014
Dongeng Tentang Hutan Indonesia
Di web Greenpeace Indonesia, saya membaca tulisan lama tentang Indonesia yang pernah tercatat sebagai negara dengan tingkat kehancuran hutan tercepat di Guinness World Records. Tahun 2000 hingga 2005, laju deforestasi Indonesia berkisar pada angka 1,8 juta hektar/ tahun. Angka tadi menyebabkan banyak hutan alam musnah. Setengah dari sisanya masih terancam keberadaannya antara lain oleh penebangan komersil, kebakaran hutan, dan pembukaan hutan untuk kebun kelapa sawit.
Saya jadi teringat waktu ke Flores. Saya dan beberapa teman menyusuri Flores dari Maumere ke Labuhan Bajo. Sebelumnya, saya pernah beranggapan seluruh Flores kering kerontang. Ternyata saya salah! Kami melewati gunung-gunung hijau. Bahkan, teman saya yang aktivis lingkungan di Austaria berkali-kali takjub dan bilang tempat ini keren.

Kota Bajawa di Flores
Sayangnya, di daerah Manggarai, hutan cantik tadi berlubang-lubang akibat tambang. Karena ingin tahu kondisi masyarakat di sekitar tambang, saya mengikuti Pater lokal ke desa untuk sosialisasi tolak tambang. Kami berangkat malam-malam ke pertemuan warga. Di sana, Pater sempat berdebat dengan beberapa warga. Salah satunya, seorang bapak yang barusan pulang merantau. Dia bilang, desanya nggak maju-maju dan penduduknya semiskin saat dia pergi merantau. Menurutnya, kalau ada tambang mangan, orang-orang akan dapat pekerjaan. Perusahaan juga akan membangun jalan untuk penduduk desa.

Flores, Manggarai
Saya sempat gondok banget. Enak aja dia bikin seolah-olah perusahan tambang itu pahlawan. Beberapa penduduk desa, termasuk tetua yang mabuk termakan ucapannya. Saya lalu cerita tentang liburan saya ke Bangka beberapa waktu sebelumnya. Di sana, dua teman saya membuat film dokumenter tentang tambang. Ada banyak lubang-lubang besar bekas tambang di mana-mana. Apakah penduduk lokal bisa kaya dari tambang? Tidak. Yang diuntungkan dari tambang cuma pemilik modal. Penduduk lokal memang mendapat upah dan pekerjaan. Tapi resikonya tinggi. Banyak yang meninggal kerena kecelakaan. Setelah timah di suatu tempat habis ditambang, si pemilik modal pergi. Mana mau mereka mengeluarkan uang untuk mengembalikan lubang-lubang tadi.
Pagi harinya, Pater Simon mengisi kebaktian minggu di Gereja dekat calon tambang. Pater yang berceramah tentang bahaya tambang menyuruh saya bergabung. Saya sempat bengong waktu Pater meminta saya maju ke mimbar. Saya tidak menyangka bakal ditodong “memberi pencerahan”  Selain ini kali pertama saya ke gereja, saya nggak pede karena belum mandi. Di depan mimbar, saya bingung dilihatin sekitar 70an orang asing. Akhirnya saya bilang kira-kira seperti ini: “Hai, saya Lutfi, dari Jogja. Kemarin, dalam perjalanan kemari saya lewat hutan-hutan. Hutan tadi cantik, beda banget dengan hutan-hutan di Jawa. Di tempat kami, sebagian besar hutan isinya tanaman sejenis. Banyak yang gundul malah. Sayang saja kalau hutan tadi harus ditebangi karena mau ditambang. Buat nanam pohon sampai besar saja butuh puluhan tahun. Apalagi sampai nanti jadi ekosistem lengkap dengan hewan didalamnya. Saya tidak tahu berapa uang yang dibutuhkan untuk mengembalikan hutan ini seperti semula.”
Selain ini kali pertama saya ke gereja, saya nggak pede karena belum mandi. Di depan mimbar, saya bingung dilihatin sekitar 70an orang asing. Akhirnya saya bilang kira-kira seperti ini: “Hai, saya Lutfi, dari Jogja. Kemarin, dalam perjalanan kemari saya lewat hutan-hutan. Hutan tadi cantik, beda banget dengan hutan-hutan di Jawa. Di tempat kami, sebagian besar hutan isinya tanaman sejenis. Banyak yang gundul malah. Sayang saja kalau hutan tadi harus ditebangi karena mau ditambang. Buat nanam pohon sampai besar saja butuh puluhan tahun. Apalagi sampai nanti jadi ekosistem lengkap dengan hewan didalamnya. Saya tidak tahu berapa uang yang dibutuhkan untuk mengembalikan hutan ini seperti semula.”
Ya, saat hutan rusak, ada binatang yang terancam punah. Greenpeace memilih harimau sumatra sebagai maskot protect paradise karena sekarang jumlahnya tinggal 400an ekor. Bisa jadi, kalau hutan rusak, mereka akan menyusul harimau jawa yang punah duluan. Waktu ke Aceh, saya dan beberapa teman sedih melihat sisa hutan dibakar. Sayang banget, padahal hutan tadi sepertinya dulu keren. Selama di Aceh, kami lewat banyak hutan lain yang masih bagus. Kami sering mampir ke hutan untuk menghirup udara segar atau iseng bermain. Semoga saja tidak menyusul hutan yang dibakar tadi. Kata penduduk sekitar, hutan yang dibakar tadi akan diubah menjadi perkebunan sawit. Dulu, saat hutannya masih bagus, katanya sering ada harimau lewat di jalan setapak tengah hutan. Entah sekarang mereka ada di mana.
Cerita tadi hanya segelintir dari dongeng sedih hutan. Ada jauh lebih banyak cerita lain yang infonya hanya diketahui di lingkup kecil. Data Departemen Kehutanan tahun 2012 menyebutkan jika 136.173.847,98 hektar lahan (60%) dari luas Indonesia adalah hutan negara. Dari keseluruhan lahan yang berada di bawah Dephut tersebut, 33.915.418 hektar ijin pengelolaannya ada dikuasai oleh 535 perusahaan. Banyak kasus kejahatan kehutanan di sana. Lalu, bagaimana cara kita ikut ambil bagian dalam menghentikan kerusakan hutan? Sesuatu yang mungkin menurut kita nun jauh di sana. Ada banyak cara kok. Salah satunya dengan menyampaikan berita tentang hutan. Saat suatu isu dibicarakan banyak orang, para pengambil kebijakan akan lebih berhati-hati untuk memutuskan sesuatu. Karena mereka merasa diawasi. Kita juga bisa mulai mencari daftar produk yang dihasilkan dari perusakan hutan. Jika ada banyak orang mengurangi pemakaian produk tadi, produsennya pasti akan berusaha lebih ramah bumi.


February 9, 2014
Dress to Impress
Seorang teman bercerita dia baru saja mengunjungi sebuah mall di Bekasi. Di pusat perbelanjaan tadi ada ketentuan untuk berbaju rapi. Teman saya sempat melihat seorang ibu-ibu dengan baju daster dan sandal jepit diusir oleh satpam. Padahal, bisa jadi kan si ibu tadi bermaksud belanja? Tidak seperti teman saya yang berbaju keren tapi nggak punya duit dan cuma sekadar cuci mata? 
Saya jadi teringat kata dua mantan bos saya. Mereka sangat memperhatikan penampilan. Menurut keduanya, bagaimana seseorang bisa dinilai isinya jika sampulnya saja sudah tidak menarik dilihat. Meskipun saya tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat tadi, saya senang terlihat cantik. Sekarang, saya merasa baju yang baik itu penting untuk kenyamananan kita. Catat, bagus tidak ada hubungannya dengan merk. Juga tidak harus barang mahal. Menggunakan barang-barang yang baik merupakan penghargaan ke diri sendiri. Rasa nyaman dengan yang kita pakai akan meningkatkan rasa percaya diri. Dan, secara tidak langsung akan membuat kita melakukan sesuatu dengan lebih baik.
Teman-teman sering merasa tidak, ada banyak orang masih memakai baju dalam yang sudah lusuh atau bahkan berlubang. Mereka beranggapan baju tadi ada di dalam dan tidak kelihatan. Sayangnya, banyak yang tidak sadar kalau badan kita juga punya perasaan. Coba deh bandingkan saat memakai baju dalam yang sudah tidak layak pakai dengan yang masih bagus. Beda kan?
Tapi, saya juga tidak tertarik dengan orang yang cuma bagus luarnya saja. Fisik keren, percuma kalau tidak diimbangi dengan otak yang bagus dan kelakuan yang menyenangkan. Siapa sih yang mau berlama-lama berkumpul dengan mahluk cantik yang nggak nyambung diajak ngobrol? Ok, mahluk yang fisiknya indah memang menyenangkan dilihat, tapi kalo kelakuannya nggak asyik, siapa yang mo dekat-dekat?
Meskipun saya memilih baju untuk kenyamanan diri sendiri. Kadang ada aturan dari luar yang mau nggak mau “harus” ditaati. Saat ada di lingkungan pesantren, saya yang biasanya memakai rok pendek berganti baju panjang. Dan sepertinya, saya mulai harus mempertimbangkan untuk memakai sepatu di acara resmi. Beberapa waktu lalu, saat mengerjakan publikasi untuk acara peresmian CSR sebuah bank, saya sempat ditegur karena memakai sandal. Menurut si bapak, untuk acara formal seharusnya mengenakan sepatu. Kalo bukan klien, saya akan bilang, saya mikir pakai otak bukan dengan sepatu. Tapi, sepertinya saya perlu berjaga-jaga kalau lain kali ada acara resmi lain. Bisa jadi sandal yang saya anggap sopan tidak berlaku di mata orang lain. Mungkin, saya nyari sepatu di web zalora saja ya? Sepertinya akan lebih irit waktu daripada harus keluar-masuk beberapa toko untuk memilih model yang cocok.


February 6, 2014
Antara Hadiah, Suap, dan Ucapan Terimakasih
“Tidak, terimakasih. Saya sedang bekerja. Saya sudah digaji,” tutur Yamada, seorang staf Kedutaan Jepang saat teman saya memberikan batik. Ia berkali-kali mengucapkan terimakasih atas perhatian teman saya. Dan tetap tidak mau menerima hadiah tersebut meski teman saya berkata itu hanya sekadar cindera mata. Menurut teman saya, suatu hal yang wajar memberikan kenang-kenangan saat mengakhiri sebuah kerjasama. Hal tersebut bukan suap karena ia memberi hadiah setelah kerjasamanya berakhir. Bukan dalam bentuk uang atau barang berharga.
Saya salut dengan Yamada yang tegas menolak pemberian dalam bentuk apapun. Teman saya bercerita, sebelumnya Yamada pernah datang meninjau bantuan. Saat itu, teman saya mengundang makan. Bukankah di Indonesia saat kita kedatangan tamu dan menjamu adalah hal wajar? Tapi Yamada menolak, dia berkata dia mendapat biaya perjalanan dan menawarkan untuk membayari teman saya makan.
Keren ya? Berani menolak hadiah? Kalau saya pribadi, saya masih menerima hadiah selama itu masih wajar dan diberikan setelah kerjasama berakhir. Beda cerita kalau ada iming-iming di muka. Dulu, saya pernah mencetak kop surat untuk sebuah lembaga. Saya pergi ke sebuah percetakan yang sebelumnya pernah menawarkan kerjasama. Pemilik percetakan tadi tahu kalo lembaga tersebut akan mencetak publikasi lain dan saya yang mengerjakannya. Sewaktu membayar, pemilik percetakan tersebut berkata ada diskon yang tidak ia tulis di nota. Diskon tersebut untuk saya sebagai pembawa order. Ia juga berpesan supaya saya menggunakan jasanya saat mencetak untuk lembaga lain. Suatu ketika, saya butuh percetakan. Saat ada beberapa yang memberikan penawaran harga, saya langsung mencoret percetakan tadi dari daftar. Kalau cara dia mendapatkan sesuatu saja tidak jujur, saya tidak yakin jika nanti kami bekerjasama dia tidak memberikan barang dengan mutu lebih rendah.
Saya sering mendengar cerita tentang kewajiban memberi ucapan terimakasih saat mengerjakan proyek. Ada saja orang-orang yang meminta uang lelah padahal ia sama sekali tidak terlibat mengerjakan proyek tersebut. Kadang ada yang bercerita si pemberi pekerjaan mematok harus ada sekian persen dana yang diberikan ke kas pribadinya. Ada juga tidak menyebut angka tapi secara halus berkata pemberi proyek sudah melebihkan anggaran sehingga ada angka yang bisa untuk mereka. Saya sering heran mendengar alasan seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Katanya, gajinya terlalu kecil dan tidak cukup untuk gaya hidupnya (catat: bukan kebutuhan). Saya cuma diam, sebenarnya saya ingin bertanya: kalau memang gajinya kecil kenapa tidak mencari pekerjaan lain? Ada banyak orang yang mau menggantikan dirimu kok. Dan memang apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga meminta dibayar besar? Kenapa tidak mencari hal lain untuk menambah pemasukan?


February 2, 2014
Berbuat Baiklah dan Dunia akan Membalas, Begitu Juga Sebaliknya
“Hah, kamu kok betah jalan sama orang itu?” komentar seorang teman saat saya bercerita pergi dengan seseorang. Teman-teman yang lain kemudian menimpali dengan komentar sejenis. Kenalan kami, sebut saja Anggun, kami labeli sebagai pembuat masalah. Ia suka seenaknya mengatur orang lain. Anggun juga labil, ia tidak segan-segan memaki jika orang lain bertindak tidak sesuai yang dia inginkan.
Saya kemudian bercerita tentang Anggun yang tidak punya teman. Saya kasihan, dia tidak pernah mendapat contoh bagaimana memperlakukan orang lain. Wajar saja kalo kemudian Anggun menjadi orang yang menyebalkan. Mungkin, jika ada yang mau jadi temannya, Anggun jadi anak yang lebih ramah. Komentar semua teman yang pernah berinteraksi dengan Anggun sama: “Siapa sih yang mau temenan dengan mahluk labil seperti itu.”
Di sisi lain, Anggun pernah bercerita, dia menjadi korban bullying di kampusnya. Saya tidak pernah bertemu dengan teman di kampusnya, tapi melihat cara dia membentak-bentak semua orang, siapa sih yang tidak balas berteriak? Lalu, biasanya orang akan berkata ke orang lain, jangan dekat-dekat mahluk satu itu.
Anehnya, Anggun sama sekali tidak pernah merasa jika ia bermasalah. Dia tidak pernah sadar kalau orang akan membalas perlakuannya. Ada hukum timbal balik di dunia. Apa perlakuan kita terhadap dunia, akan dibalas dengan dengan hal setimpal. Jadi, kalau ada seseorang yang selalu bermasalah dengan orang lain, yang salah dia, bukan dunia.
Bukan hanya Anggun, orang cenderung menyalahkan dunia luarnya. Dulu, saya juga pernah mengalami hal tersebut. Hampir tiap tahun saya pindah kerja karena saya tidak menyukai orang-orang yang ada di sekeliling saya. Memang sebagian orang yang pernah bekerja dengan saya menyebalkan. Tapi, level menyebalkan mereka bisa jadi berkurang jika saya bisa menahan diri. Kalau saya tidak menyerang balik, orang pasti akan bertingkah laku lebih baik.
Tapi sepertinya lebih mudah menyalahkan dunia, menyalakan orangtua, dan menyalahkan pemerintah atas semua hal yang terjadi pada diri kita. Saya jadi ingat minggu lalu waktu saat menjadi narasumber di acara “Blogger bicara Hutan” yang diselenggarakan Greenpeace. Seorang mahasiswa bertanya, apakah saya pernah membuat tulisan-tulisan yang mempertanyakan kebijakan pemerintah. Saya balik bertanya, kenapa harus menunggu kebijakan pemerintah? Sepertinya, orang-orang yang ada di pemerintahan terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kenapa kita tidak mulai membuat perubahan yang kita inginkan dari diri kita sendiri? Kalau kita blogger, tulis itu di blog. Ajak orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau semua orang menunggu pemerintah berbuat sesuatu, kapan ada perubahan.


January 27, 2014
Infotainment yang tidak menghibur apalagi memberi pengetahuan
Seorang teman di kantor tiba-tiba iseng menyetel TV. Kami yang sedang bosan akhirnya ikut-ikutan menonton. Lebih dari setengah jam, kami menghabiskan waktu untuk melihat acara nggak penting: berita keretakan rumah tangga Farat Abbas. Di layar kaca, sama sekali tidak ada pernyataan dari Farhat atau pun istrinya kalau pernikahan mereka bermasalah. Si pembuat berita seenaknya menafsirkan hal tersebut dari Farhat yang tidak datang ke acara pernikahan putrinya. Aneh bukan? Menyimpulkan sesuatu tanpa ada sumber. Lalu, berkali-kali si pembawa acara menggunakan kata “mungkin”. Setahu saya, itu tidak bisa dikategorikan sebuah berita.
Saya lebih heran lagi karena di Indonesia, acara sejenis itu disebut infotainment. Sepenangkapan saya, info itu artinya sesuatu yang penting atau membuat cerdas. Si A ribut dengan si B, perselingkuhan si C, koleksi tas D, liburan si E, bagian mana yang membuat penontonnya pintar ya? Penting? Tanpa tahu itu pun hidup saya masih baik-baik saja. Lalu kata entertainment. Itu lebih aneh lagi, mendapat hiburan dari kabar perceraian. Yang sakit itu yang meliput atau yang menonton ya?
Sepertinya, hampir tiap hari, stasiun-stasiun TV nasional menayangkan hal tersebut. Karena mengejar rating? Saya lupa siapa yang pernah berkata kalau stasiun TV malas berpikir jika selera pasar bisa dibentuk. Bukankah penonton TV menyukai infotainment karena mereka disuguhi hal tersebut berkali-kali. Seorang kenalan mengiyakan kalimat tadi. Setelah menikah, ia keluar dari pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga. Di rumah, dia hanya punya dua teman: wajan dan remote TV. Tidak ada pilihan lain (mungkin lebih tepatnya tidak ada ide lain) untuk membunuh waktu sambil menunggu suaminya pulang. Bisa jadi, hal yang sama terjadi di penonton-penonton acara nggak jelas tadi. Hanya karena stasiun TV menyuguhkan. Bukankah sesuatu yang dilakukan berkali-kali akan menciptakan kebiasaan?
Beberapa hari lalu, seorang teman membuka percakapan dengan berita jika Cristine Junsung bercerai lagi. Dengan berapi-api dia berkomentar tentang pernikahan Cristine yang baru berumur beberapa bulan. Ia juga berkomentar mengenai suami Cristine yang umurnya jauh lebih tua. Saya cuma bisa bengong. Teman saya bercerita seolah-olah dia mengenal Cristine! Padahal, bertemu saja belum pernah. Dan sepertinya cerita yang sama bisa kita temui dengan mudah di seluruh Indonesia. Saya cuma berpikir, kalau kita tiap hari sibuk menghabiskan waktu dengan hal tidak penting, kita lupa ada banyak hal penting yang seharusnya kerjakan. Saya percaya, sikap seseorang ditentukan oleh apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Kalau tiap hari diberi tontonan sampah seperti itu, bagaimana Indonesia bisa jadi bangsa yang cerdas?


January 19, 2014
Curhat Pak Tani
“Petani itu pekerjaan mulia. Mereka menyediakan pangan untuk semua orang di dunia. Tapi kok nasibnya tidak baik ya? Sengsara dan miskin. Saya sendiri mau mengaku petani rasanya kok malu. Tidak sebangga kalau punya pekerjaan lain,” tutur Sumadi, seorang petani hutan yang tinggal di daerah Panggang, Gunungkidul.
Pak Sumadi, dan hampir seluruh penduduk Desa Girisuko hidup dari bertani. Wilayah mereka, tanahnya subur. Kata Pak Sumadi, tanaman apapun bisa tumbuh dengan baik. Sayang, air hanya ada di musim penghujan. Saat musim kemarau, jangankan untuk bertani, untuk konsumsi sehari-hari pun, mereka harus membeli. Ada program bantuan air dari pemerintah dan pihak swasta. Tapi itu tidak cukup, masing-masing keluarga petani berjumlah empat orang, tiap musim kemarau harus membeli empat hingga delapan tangki air dengan harga sekitar 125 hingga 180 ribu rupiah.
Karena petani-petani di Girisuko dan sekitarnya hanya bisa bercocok tanam saat musim penghujan, mereka panen di waktu yang sama. Akibatnya, harga produk pertanian jatuh. Saya sempat bertanya kepada Pak sumadi, pernahkah mereka mencoba mencari sumber air? Bukankah jika mereka bisa bercocok tanam sepanjang tahun harga komuditas pertanian lebih stabil?
Kata Pak Sumadi, air yang ada di kawasan Panggang langsung masuk ke sungai-sungai bawah tanah. Yang dalamnya bisa sampai ratusan meter. Sejauh ini, belum pernah ada yang mencoba mengambil air tersebut. Mungkin, kalaupun bisa, biaya yang dikeluarkan akan sangat mahal, tidak terjangkau oleh petani-petani yang pendapatan per bulannya kurang dari satu juta rupiah.
Dulu, saat Habibie menjadi presiden, pernah ada pembangunan saluran air dari PDAM. Pralon tadi sudah sampai ke desa. Sayangnya, air hanya keluar saat pemasangan pralon selesai. Hingga kini, saluran air tersebut tidak pernah digunakan.
Beberapa tetangga Pak Sumadi kemudian bergabung. Kami ngobrol tentang banyak hal mulai dari tingkat pendidikan, akses jalan, akses informasi, hingga petani yang lebih memilih membeli bibit dari pabrik. Inti dari obrolan tadi, mereka memang turun-temurun miskin. Saya jadi teringat cerita tentang banyaknya program penanggulangan kemiskinan yang tidak berhasil mengurangi angka kemiskinan. Rata-rata program tadi hanya melihat kemiskinan dari satu sisi. Satu tindakan, dianggap bisa mengurangi kemiskinan. Kalau dianalogikan, seperti penderita kanker yang makan obat penghilang nyeri. Hal tersebut tidak menyembuhkan kankernya.
Selama ini saya juga sering mendengar, petani miskin karena sempitnya lahan yang dimiliki. Apakah masalah kemiskinan selesai begitu mereka diberi hak untuk memiliki atau mengelola lahan yang lebih luas? Sepertinya tidak. Saya teringat tahun 2012 lalu saat membuat film dokumenter di Desa Sambeng, Boyolali. Setelah masyarakat mendapat hak kelola hutan, masing-masing petani bisa memanfaatkan ¼ hektar lahan untuk bertani. Beberapa pengurus bahkan mendapat lahan hingga satu hektar. Apakah mereka kemudian sejahtera? Tidak juga. Petani-petani di Sambeng menanami lahannya dengan jagung, ketela, dan kacang yang harga jualnya rendah. Mereka tidak berani menanam komoditas lain yang harga jualnya lebih tinggi karena takut gagal. Juga tidak mengolah hasil panen tersebut untuk mendapat harga jual yang lebih tinggi.
Pendapatan mereka memang meningkat, mereka juga bisa menghemat pengeluaran dengan memasak sayuran dari kebun. Itu artinya mengurangi uang belanja. Tapi bagaimana dengan biaya sekolah yang harus dikeluarkan untuk anaknya? Belum lagi biaya kesehatan yang semakin mahal? Petani-petani di Sambeng menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari tambahan penghasilan. Mereka menggarap lahan Perhutani di tempat lain. Yang ditanam tetap saja jagung, ketela, dan kacang.
Saya jadi teringat dulu sewaktu masih mengelola perpustakaan keliling. Saya dan beberapa teman pernah mengajak anak-anak petani di sebuah desa untuk menggambar dan bercerita tentang cita-citanya. Guru adalah cita-cita paling banyak disebut. Kenapa? Di desa tersebut guru profesi yang terhormat. Pegawai negeri yang punya pendapatan bulanan dan ada jaminan pensiun. Banyak orangtua yang berpesan kepada anaknya, sekolah yang pintar dan setinggi mungkin. Supaya bisa mendapat pekerjaan yang baik. Jangan seperti orangtuamu yang “hanya” petani. Lah, kalau sudah tidak ada orang lagi yang mau jadi petani, nanti bagaimana kita makan? Mau impor terus-terusan?
Saya percaya kalau, nasib seseorang berubah saat ia merubah cara berpikirnya. Hal tersebut butuh proses bertahun-tahun. Ada banyak hal yang mempengaruhi cara berpikir seseorang? Lalu ini tugas siapa? Pemerintah? Bukankah seharusnya kita punya tanggung jawab sosial untuk membantu orang lain? Saya jadi kembali bertanya ke diri saya sendiri. Apa ya yang sudah pernah saya lakukan untuk mereka ya?


January 16, 2014
Perusahaan Jahat Perusak Bumi
Sewaktu Bakrie membeli saham Path, beritanya langsung ramai di media sosial. Entah berapa banyak orang sibuk mencerca, kecewa, dan bahkan mengatakan langsung meng-un-install aplikasi tersebut. Alasan orang-orang tadi kurang lebih sama. Bakrie seharusnya bertanggungjawab karena perusahaannya menyebabkan Porong terendam lumpur. Kenapa ia memilih untuk berinvestasi padahal masih punya hutang dengan penduduk yang kehilangan rumah dan lahan.
Kenapa hanya Bakrie? Bukannya ada banyak pengusaha-pengusaha yang memperkaya dirinya dengan cara menyengsarakan banyak orang? Saya bukan ahli isu perburuhan. Di logika saya, ada banyak perusahaan yang pemiliknya bergelimang harta karena mempekerjakan buruhnya dengan jam kerja panjang, gaji tidak layak, dan mungkin kesehatan mereka terganggu karena terpapar suara berisik mesin terus menerus atau bahan kimia. Nah,apakah teman-teman yakin laptop, hp, jam tangan, sepatu dan kosmetik yang kalian pakai itu dibuat dengan memperhatikan pekerjanya?
Dengan alasan kepraktisan, kadang kita suka memilih suatu barang yang kita tahu pemiliknya tidak manusiawi. Saya sendiri sampai saat ini selalu membeli air galon produk tertentu. Karena saya malas merebus air. Sebenarnya, saya bisa saja membeli penyaring air, tapi harga awalnya terlalu mahal. Padahal saya sering mendengar di tempat- tempat perusahaan tadi mendirikan pabrik, selalu muncul konflik. Setelah sumber airnya dikuasai oleh perusahaan tersebut, petani sekitar kesulitan untuk mengairi sawahnya.
Saya jadi ingat saat tahun lalu bertemu dengan banyak pegiat hutan di sebuah acara yang membahas mengenai kejahatan kehutanan. Di berbagai wilayah di Indonesia, ada banyak perusahaan yang melakukan penyerobotan lahan, pengemplangan pajak, alih fungsi lahan, hingga pembunuhan saat menjalankan bisnisnya. Mengerikan. Dan, masih banyak contoh yang bisa kita temui di sekeliling kita tentang perusahaan-perusahaan berusaha mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan efeknya.
Sepertinya, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tadi, terlalu lama. Lalu, apakah kita hanya diam saja? Tidak. Ada banyak cara yang kita lakukan untuk mengurangi dampak buruk perusahaan jahat. Menjadi konsumen cerdas. Kita berusaha sebisa mungkin menggunakan barang karena butuh,bukan karena ingin dan terlihat keren. Sebarkan hal ini ke orang-orang yang ada di lingkaran pengaruh kita. Jika membuat karya, tulis atau filmkan. Semakin banyak konsumen cerdas, sebuah perusahaan akan semakin berpikir untuk mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain.
Selama ini, saya cenderung suka menolak tawaran untuk bergabung dengan MLM. Saya hanya mau menjadi anggota mlm yang produknya memang saya butuh dan saya pakai. Saya tidak mau “memaksa” orang lain membeli barang yang mereka tidak butuh dengan iming-iming, kalau kau ikut, nanti kau bisa kaya. Sadar nggak sih berapa banyak uang yang kita dapat dan berapa yang perusahaan MLM dapat? Jika kita menjadi anggota MLM dan berhenti, tidak ada uang lagi masuk. Tapi perusahaan tetap mendapat pembelian dari orang-orang yang sudah kita rekrut.









