Arie Saptaji's Blog, page 6
June 29, 2020
Hacksaw Ridge: Senjatanya adalah Tidak Memanggul Senjata

Hacksaw Ridge menampilkan protagonis yang unik: Seorang prajurit yang terjun di medan tempur tanpa memanggul sepucuk senjata pun. Film perang ini diangkat dari kisah nyata Desmond Doss, orang Kristen dari Gereja Adven Hari Ketujuh di Virginia, AS, yang ikut berjuang pada Perang Dunia II sebagai tenaga medis. Atas jasanya, ia dianugerahi Medal of Honor oleh negaranya.
Film ini disutradarai oleh Mel Gibson, yang memperlihatkan kepiawaiannya dalam menjalin adegan-adegan keseharian dengan kengerian medan tempur. Saat diputar di Festival Film Venesia pada 4 September 2016, Hacksaw Ridge mendapatkan standing ovation selama sepuluh menit.
Hacksaw Ridge memaparkan perkembangan iman dan keyakinan Desmond Doss sebagai seorang pasifis dalam tiga tahap.
Pembentukan. Kehidupan keluarga dan ajaran agama melatarbelakangi sikapnya. Perkelahian dengan adik yang nyaris berakhir fatal mencelikkan pengertian Desmond akan perintah keenam (“Jangan membunuh”) dalam Dasa Titah. Ibunya menegaskan, pembunuhan adalah dosa terbesar di mata Tuhan. Sebuah konflik dengan ayahnya, veteran perang yang pemabuk, semakin meneguhkan tekad Desmond untuk tidak menyentuh senjata. Ia bertumbuh menjadi pemuda yang berjuang sedapat mungkin untuk menyelamatkan nyawa sesama.
Pengujian. Masa ini berlangsung selama Desmond menjalani pelatihan di barak militer. Keyakinan itu menjadikannya bahan cemooh rekan-rekannya. Di satu sisi, ia terlihat sebagai pengecut; di sisi lain, ia dianggap sosok moralistis sok suci. Tentu saja, ia juga berbenturan dengan atasannya. Dan, alih-alih dikirim ke medan tempur, ia nyaris dijebloskan ke penjara militer dengan tuduhan pembangkangan.
Penerapan. Akhirnya, ia diberangkatkan sebagai tenaga medis dan tidak perlu menyandang senjata. Ia diterjunkan di medan tempur Okinawa, yang berada di atas tebing yang dijuluki Hacksawa Ridge, dan terlibat dalam salah satu pertempuran paling sengit sepanjang Perang Dunia II. Di tengah pertempuran brutal (salah satu yang paling brutal yang pernah terpapar di layar lebar) itu, Desmond menunjukkan bahwa keyakinannya dapat diterapkan. Ketika kedua belah pihak saling membantai, Desmond berkelit di tengah deru pertempuran untuk menyelamatkan beberapa nyawa rekannya dan, kalau tidak salah, juga beberapa orang musuh. Doanya begitu indah dan menggetarkan, “Please Lord, help me get one more” (Tolonglah, Tuhan, bantulah aku menyelamatkan satu jiwa lagi). Tercatat ia sukses menolong 75 prajurit.
Menurut saya, tahap yang paling berat adalah tahap pengujian. Seperti dikatakan Dumbledore dalam serial Harry Potter, menghadapi rekan-rekan sendiri tidak jarang malah lebih berat daripada menghadapi lawan.
Hacksaw Ridge menggarisbawahi salah satu paradoks Kerajaan Allah. Jika kita ingin ditinggikan, kita justru diminta untuk merendahkan diri. Jika kita ingin menyelamatkan nyawa, kita justru diundang untuk rela menyerahkan nyawa. Jika ingin memadamkan kejahatan, kita justru mesti melimpahinya dengan kebaikan. Desmond Doss memperlihatkan bagaimana ia menang dalam pertempuran justru tanpa menyandang senjata. Ia melawan kekerasan tanpa kekerasan.
Dengan film ini, Mel Gibson, sebagai sutradara, menunjukkan perkembangan tematik yang menarik sehubungan dengan kekerasan. Dalam Braveheart (1995), ia menampilkan protagonis yang berjuang dengan mempergunakan kekerasan demi kemerdekaan bangsanya. Dalam The Passion of the Christ (2004), ia menampilkan protagonis yang menanggung kekerasan brutal demi menyelamatkan umat manusia. Dalam Hacksaw Ridge, ia menampilkan protagonis yang menolak mempergunakan kekerasan demi menyelamatkan rekan-rekan seperjuangannya. Pilihan ketiga protagonis itu erat berkaitan dengan iman dan keyakinan mereka. Baik diputar secara berangkaian atau ditonton sendiri-sendiri, ketiga film tersebut dapat menjadi bahan refleksi tentang iman dan kekerasan. ***
Published on June 29, 2020 16:00
June 28, 2020
Tergusurnya Angkot Kami

Lebaran 2017 H+7. Masih pagi di Kaliurang. Utomo (bukan nama sebenarnya) memerlukan angkutan umum untuk turun ke Yogya.
“Colt ke Yogya masih ada ‘kan?”
Utomo mengajukan pertanyaan itu kepada tiga orang, dan mendapatkan jawaban yang mirip-mirip.
“Masih kok. Cuma ya kadang-kadang.”
Ia mengerutkan kening. Seberapa lama kadang-kadang ini? Sudah setengah jam, belum ada satu pun colt yang terlihat naik atau turun.
Bukan berarti Kaliurang sepi. Sebaliknya. Dari pangkalan di dekat patung udang raksasa yang menjadi penanda wilayah, belasan Jeep Willys hilir-mudik pergi-pulang mengantar pengunjung menikmati Lava Tour Merapi. Sementara itu, berderet mobil keluarga parkir di tepi jalan. Meskipun sinar matahari lumayan menyengat, orang-orang terlihat ceria menikmati udara segar pegunungan.
Namun, colt Kaliurang-Yogya yang ditunggunya tak kunjung nongol. Sudah satu jam lebih. Setelah menumpang duduk di pos SAR, Utomo menghubungi seorang teman penarik ojek, memintanya menjemput. Posisi temannya di Bulaksumur, jadi perlu sekitar satu jam untuk sampai di tempatnya menunggu. Baiklah. Paling enggak lebih ada kepastian, pikirnya.
Kira-kira pukul 10.15 WIB—jadi, sudah dua jam lebih ia menunggu—muncullah sebuah colt angkutan umum. Namun, bukan menuju Yogya, melainkan naik ke stanplat Pasar Tlogo Putri.
Kalau menunggu colt ini kembali ke Yogya, perlu waktu berapa lama ya? Satu jam lagi? Entahlah. Utomo tidak tahu karena temannya sudah lebih dulu datang, dan ia pun membonceng motor meluncur turun.
Pesan moral cerita di atas: Sekarang ini susah mencari angkutan umum di Yogyakarta.
Mau menikmati Kaliurang dan daerah tujuan wisata lain di sekitar Yogya dengan naik kendaraan umum? Silakan. Kemungkinan besar Anda terpaksa berpanas-panas menunggu berlama-lama dan gigit jari. Jika ingin nyaman, ya Anda mesti memiliki kendaraan pribadi atau menyewanya.
Itu tadi transportasi ke daerah pinggiran. Bagaimana dengan transportasi dalam kota? Tak kalah runyam.
Saya pernah melakukan pengamatan kecil. Anak kami bersepeda ke sekolah, tetapi saya beberapa kali mengantarnya naik motor. Nah, hitung-hitung sembari mengamati situasi dan kondisi lalu lintas kota tercinta.
Jarak dari rumah ke sekolah 4,5 kilometer, dapat ditempuh dengan motor selama 25 menit. Sepanjang perjalanan saya melihat-lihat berapa banyak angkutan umum perkotaan (angkot) yang lewat. Sekalian berjaga-jaga, kalau-kalau anak kami beralangan naik sepeda dan saya tidak bisa mengantar, ada alternatif angkot.
Semula sempat terpikir naik TransJogja. Namun, halte terdekat yang memiliki tempat penitipan sepeda ada di terminal Jombor. Jaraknya dari rumah sudah separuh lebih perjalanan ke sekolah, dan malah menjauh ke utara. Dan, dari sana tidak ada jalur yang langsung ke halte di dekat sekolahnya. Entah harus loncat berapa kali, dan berapa lama bisa sampai ke tujuan. Alternatif ini terpaksa disingkirkan.
Dulu, dua puluhan tahun yang lalu, seingat saya angkot masih meraja. Ya, ketika bus kota 15 jalur dan aneka angkot alternatif lain masih berseliweran di jalan-jalan kota pelajar ini. Saya sendiri dari kos di Karanggayam ke kampus di Karangmalang biasa jalan kaki. Kalau mau pergi agak jauh bisa naik sepeda atau angkot.
Sekarang, kendaraan pribadi—termasuk motor saya—berjubel memenuhi jalan. Dalam perjalanan berangkat, saya baru bertemu dengan angkot setelah berkendara 20 menit. Dan, sampai pulang ke rumah lagi, kalau tidak salah hitung, saya hanya berpapasan dengan tujuh angkot. Itu pun kebanyakan kosong tak berpenumpang. Kalau begini caranya, angkot benar-benar menjadi pilihan paling bontot.
Tampaknya memang begitu perkembangan dua puluh tahun belakangan. Yogya tak mau kalah, mengikuti kecenderungan kota-kota besar di Indonesia. Ruang untuk kendaraan pribadi kian meruyak, sedangkan angkot kian terdesak. Dibiarkan hidup segan mati tak hendak.
Angkot kian tergusur karena warga kian makmur dan mampu membeli kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi inilah yang kini memadati jalanan. Kemacetan pun tak terelakkan. Terlebih saat akhir pekan panjang. Terlebih lagi saat libur Lebaran membentang hingga sepuluh hari. Begitulah. Yogya menambahkan satu lagi ciri keistimewaan: istimewa macetnya.
Beberapa film animasi Jepang menawarkan perbandingan yang menarik. Whisper of the Heart (1995), The Garden of Words (2013), dan Your Name (2016), misalnya. Selain terpana oleh gambar animasinya, terpikat oleh alur ceritanya, saya takjub menyaksikan tata kota tempat kisah berlangsung. Apalagi seorang teman yang pernah tinggal di Jepang menambahkan, kota-kota di sana memang seperti itu.
Sungguh senang melihat orang berjalan kaki dengan leluasa. Naik sepeda pun terlihat menyenangkan. Naik kereta tampak efisien. Dari stasiun kereta menuju sekolah, berjalan melewati taman kota yang permai. Di tengah taman ada saung di tepi danau yang elok, nyaman untuk berteduh saat kelelahan. Kurang apa lagi coba?
Takjub melihat kondisi di sebelah sana, dan mengelus dada melihat kondisi di sebelah sini. Kapan Yogya—dan kota-kota lain di Indonesia—memiliki tata kota yang memanusiakan warganya? Yang menghargai para pejalan kaki dan kaum difabel? Yang mengutamakan fasilitas transportasi umum yang manusiawi, memadai, tangguh, dan berjangkauan luas, bukan memanjakan para pemilik kendaraan pribadi?
“A developed country is not a place where the poor have cars. It’s where the rich use public transportation,” kata Enrique Penalosa, mantan walikota Bogota, Kolumbia.
Saya bukan pengamat atau aktivis tata kota. Saya hanya warga yang ingin menikmati fasilitas transportasi umum yang bagus. Namun, saya tidak seperti beberapa orang yang aktif menyerukan perbaikan tata kota dan mendukungnya dengan gaya hidup yang konsisten: bepergian dengan angkot, bersepeda, atau berjalan kaki.
Saya malah ikut andil atas makin tergusurnya angkot. Karena saya lebih suka naik motor atau taksi kalau bepergian di kota ini. Lebih nyaman dan lebih praktis. Meskipun harga yang mesti dibayar sejatinya mahal: kemacetan dan juga polusi udara yang kian parah. Ah!
Ada lagi yang hilang gara-gara tergusurnya angkot ini. Dulu, piknik umumnya adalah acara komunitas: sekolah, kantor, kampung, lembaga. Bisa dengan mengumpulkan iuran secara langsung atau lewat arisan terlebih dahulu untuk menyewa bus. Biasanya piknik bareng ini dilakukan pada musim liburan panjang. Piknik jadi ajang mempererat silaturahmi.
Kini, piknik cenderung menjadi urusan keluarga atau pribadi. Dengan kendaraan pribadi, orang leluasa piknik tiap akhir pekan, akhir pekan panjang, atau kapan saja ada kesempatan. Lalu, memajangnya di akun medsos masing-masing. Asyik sendiri-sendiri.
Yang tidak punya kendaraan pribadi? Menunggu piknik bareng—yang semakin langka. Menyewa kendaraan—merogoh dompet relatif lebih dalam. Nunut tetangga sebelah yang lebih beruntung—andaikan mereka longgar dan bermurah hati. Atau, gigit jari—ngejogrok meratapi nasib kenapa tidak ikut terangkut kereta cepat pembangunan, mengeluh kenapa fasilitas transportasi umum yang layak dan terjangkau terus terabaikan, kenapa ini kenapa itu.
Zaman melaju. Gaya hidup pun berpacu mengikutinya. Ada yang mampu beradaptasi; ada yang terpaksa mati. Sesederhana itukah? ***
Published on June 28, 2020 16:00
June 26, 2020
12 Humor Singkat
1Dokter gigi: “Menyikat gigi dengan baik itu perlu waktu kira-kira satu lagu.”
Anak kecil: “Kalau lagunya ‘Anak Ayam Turun 1.000’ bagaimana, Dok?”
2 Menegakkan benang basah sama sulitnya dengan menemukan singa yang vegetarian.
3Putri punya masalah. “Pak,” katanya, “siapa yang harus kupilih? Anton yang ganteng atau Donny yang setia?”
“Donny.”
“Kenapa?”
“Aku meminjam uangnya selama enam bulan terakhir dan ia tetap mengunjungimu dua kali seminggu.”
4Paman benar-benar pemalas. Ia suka menaruh bubuk kopi di kumisnya dan menenggak air panas.
5“Mas, tetangga sebelah itu tidak punya apa-apa, tapi kok bisa menempati rumah sebesar rumah kita ya? Mereka tidak punya mobil, tidak punya TV, tidak punya pembantu…”
“Mereka juga tidak punya utang!”
6Adik bayiku dikirim dari surga… mereka di sana pasti senang karena keadaan jadi tenang.
7“Aku mendapat gaji sejuta tiap minggu dan bos baru saja melipatgandakannya.”
“Oya? Kaudapat berapa sekarang?”
“Sejuta tiap dua minggu.”
8“Saya ingin mengeluarkan anak saya dari sekolah yang kacau ini.”
“Lho, bukankah anak Anda juara kelas?”
“Justru karena itulah, sekolah ini pasti kacau.”
9Ia memang orang yang jarang berkata-kata—namun, kalau sudah berbicara, betapa tajam perkataannya!
10Liburan: Setelah dua minggu menikmatinya, Anda merasa begitu segar sehingga siap untuk bekerja kembali—dan begitu miskin sehingga harus bekerja kembali.
11Murid: “Kemarin saya membunuh tiga lalat betina dan dua lalat jantan.”
Guru: “Bagaimana kau bisa membedakannya.”
Murid: “Yang tiga menempel di cermin, yang dua di kotak bungkus rokok.”
12“Ia berjalan ke altar dengan memegang tangan kanan ayahnya.”
“Apa yang dilakukan tangan kiri ayahnya?”
“Menyeret pengantin laki-laki.”

Anak kecil: “Kalau lagunya ‘Anak Ayam Turun 1.000’ bagaimana, Dok?”
2 Menegakkan benang basah sama sulitnya dengan menemukan singa yang vegetarian.
3Putri punya masalah. “Pak,” katanya, “siapa yang harus kupilih? Anton yang ganteng atau Donny yang setia?”
“Donny.”
“Kenapa?”
“Aku meminjam uangnya selama enam bulan terakhir dan ia tetap mengunjungimu dua kali seminggu.”
4Paman benar-benar pemalas. Ia suka menaruh bubuk kopi di kumisnya dan menenggak air panas.
5“Mas, tetangga sebelah itu tidak punya apa-apa, tapi kok bisa menempati rumah sebesar rumah kita ya? Mereka tidak punya mobil, tidak punya TV, tidak punya pembantu…”
“Mereka juga tidak punya utang!”
6Adik bayiku dikirim dari surga… mereka di sana pasti senang karena keadaan jadi tenang.
7“Aku mendapat gaji sejuta tiap minggu dan bos baru saja melipatgandakannya.”
“Oya? Kaudapat berapa sekarang?”
“Sejuta tiap dua minggu.”
8“Saya ingin mengeluarkan anak saya dari sekolah yang kacau ini.”
“Lho, bukankah anak Anda juara kelas?”
“Justru karena itulah, sekolah ini pasti kacau.”
9Ia memang orang yang jarang berkata-kata—namun, kalau sudah berbicara, betapa tajam perkataannya!
10Liburan: Setelah dua minggu menikmatinya, Anda merasa begitu segar sehingga siap untuk bekerja kembali—dan begitu miskin sehingga harus bekerja kembali.
11Murid: “Kemarin saya membunuh tiga lalat betina dan dua lalat jantan.”
Guru: “Bagaimana kau bisa membedakannya.”
Murid: “Yang tiga menempel di cermin, yang dua di kotak bungkus rokok.”
12“Ia berjalan ke altar dengan memegang tangan kanan ayahnya.”
“Apa yang dilakukan tangan kiri ayahnya?”
“Menyeret pengantin laki-laki.”

Published on June 26, 2020 16:00
June 25, 2020
The Power of Meditation

Meditasi. Ini kedengarannya seperti sebuah kosa kata asing bagi kebanyakan umat kristiani. Orang Kristen bermeditasi serasa sebagai sebuah kejanggalan, sesuatu yang tidak lazim. Kita cenderung mengaitkannya dengan spiritualitas agama-agama Timur. Nyatanya, meditasi adalah salah satu mata rantai penting dalam ibadah kristiani.
Meditasi tak lain adalah resep kesuksesan Yosua. Kitab Mazmur dibuka dengan pentingnya meditasi. Timotius didorong oleh Paulus untuk bertekun dalam meditasi guna menjaga kebugaran dan vitalitas rohaninya.
Bermeditasi dengan merenungkan firman Tuhan juga menjadi praktik keseharian jemaat Tuhan dari abad ke abad. Guigo II, seorang biarawan abad ke-12 misalnya, menguraikan ”tangga” doa sebagai lectio, meditatio, oratio, contemplatio (membaca Alkitab, bermeditasi, berdoa, berkontemplasi).
Mengapa penting bermeditasi? Charles Haddon Spurgeon (1834-1892), ”Raja Pengkhotbah” dari Inggris, memaparkan empat manfaat utama bermeditasi atau merenungkan firman Tuhan.
Pertama, bermeditasi menolong kita menemukan ”intisari” kebenaran firman Allah. Orang yang makan tidak menelan makanannya begitu saja, namun makanan itu mesti melewati proses pencernaan sejak dari mulut sampai ke usus, agar sari-sarinya dapat terserap dengan baik oleh tubuh. Gabah perlu digiling menjadi beras sebelum dapat ditanak dan kemudian dinikmati sebagai nasi.
Begitu juga dengan firman Tuhan. Tidak cukup kita hanya membaca, mendengarkan, menandai atau mempelajarinya. Kita juga perlu bermeditasi atau merenungkannya untuk meresapkan nilai-nilai kebenaran tersebut.
Kedua, bermeditasi menolong kita menanamkan kebenaran itu di dalam ingatan kita. Kita semua cenderung gampang lupa. Khotbah yang kita dengar pada pagi hari, tak jarang siangnya sudah kita lupakan. Perikop Alkitab yang kita baca sebelum mandi pagi, sehabis sarapan sudah tak kita ingat lagi. Lalu, saat kita diperhadapkan pada tantangan dan masalah hidup, kita seperti prajurit yang tidak memegang senjata–tidak tahu mesti mendayagunakan prinsip firman Tuhan yang mana untuk menyikapinya. Merenungkan firman Tuhan, mengunyahnya berulang-ulang seperti sapi memamah biak, menjadikan firman itu lekat dalam ingatan.
Ketiga, bermeditasi menolong kita menyingkapkan kebenaran dan memahami maknanya. Mungkin saja orang menemukan butiran emas di permukaan tanah, namun sebagian besar bungkahan emas terpendam di kedalaman bumi. Artinya, kita perlu menggalinya untuk mendapatkannya. Bermeditasi, dengan demikian, tak lain sebuah kerja keras untuk menggali bungkahan kebenaran yang tersembunyi di kedalaman firman Tuhan. Perlu waktu dan kesabaran.
Keempat, semakin terbiasa kita bermeditasi, semakin mudah pula kita menyambut kebenaran. Pernah memasak di tungku tanah liat? Kalau apinya masih kecil, dan Anda memasukkan kayu yang masih agak lembab, kemungkinan besar api itu akan padam. Namun, saat apinya sudah berkobar-kobar, kayu yang masih lembab pun akan disambarnya. Orang yang terbiasa bermeditasi menjaga api di tungku hatinya senantiasa menyala-nyala. Bagi orang semacam ini, khotbah yang sederhana dan disampaikan oleh pengkhotbah yang membosankan pun bukan masalah: ”kayu yang lembab” itu akan dibakarnya dan membuat hatinya kian berkobar!
Begitu besar manfaat meditasi, namun, seperti tersirat dari uraian di atas, bermeditasi juga sebuah kerja keras, suatu disiplin rohani. Meditasi bukan suatu praktik yang bisa dilakukan sambil lalu. Kita perlu meluangkan waktu khusus, dan sejenak menutup diri dari kesibukan dunia yang menuntut perhatian kita.
Tak mengherankan kalau meditasi terasa sebagai sesosok momok menakutkan bagi orang-orang modern yang supersibuk. Seperti ditengarai oleh Winkie Pratney, ”Orang sekarang ini takut akan keheningan. Orang cenderung lebih suka bergerak, bertindak, atau melakukan kesibukan apa saja, karena mereka takut mendengar suara Allah. Padahal justru kesibukan itulah yang menghambat kita untuk mengenali diri kita yang sebenarnya dan sosok Allah yang sesungguhnya.”
Karenanya, kehadiran buku semacam ini kiranya menggugah gairah pembaca untuk mengembangkan disiplin rohani bermeditasi, untuk meluangkan waktu khusus guna bersaat teduh. Renungan dalam buku ini dimaksudkan untuk menemani—bukan menggantikan—waktu teduh Anda sepanjang tahun ini. Anggaplah renungan ini sebagai hasil pembacaan seorang sahabat yang rindu untuk membagikan apa yang ditemukannya dalam perenungan atas suatu perikop Kitab Suci. Seorang sahabat yang berharap apa yang dibagikannya itu memperkaya perenungan pribadi Anda.
Saat kita merenungkan firman Tuhan dengan tekun, dari hari ke hari kita akan menemukan iman yang segar dan kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. ***
Published on June 25, 2020 16:00
June 24, 2020
Amsal Sebuah Buku
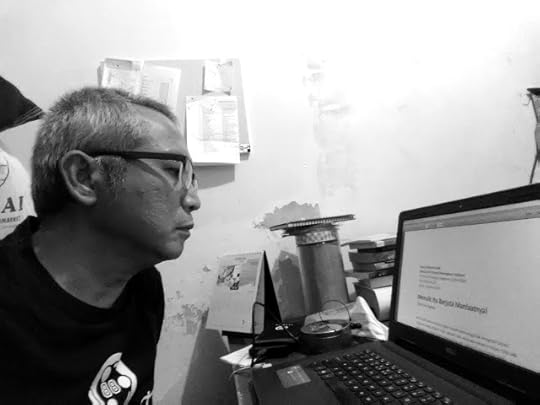
Buku mengekalkan Pertanyaan-Pertanyaan pengantar tidur
: Kenapa gadis korek api akhirnya mati? Terbuat dari apakah sepatu Cinderella: kaca atau kecemasan? Apakah yang bisa menghilangkan bekas luka di kening Sangkuriang? Sebuah ciuman, mungkin? Terasi Timun Mas? Mereka bukan saudara kandung, kenapa nama mereka serupa dan saling mendengki–Bawang Putih dan Bawang Merah? Bagaimana warna menumbuhkan kebencian? Di bawah laut, musik bertalu-talu, seorang ratu memimpin pasukannya menuju puncak gunung, apakah engkau melihat wajahnya bercahaya matahari tujuh ganda?
: Apakah badan Petrus–murid Tukang Kayu itu–berbau ikan, garam, gosong oleh terik matahari? Dalam bahasa apakah ular mengelabui Hawa? Di luar taman, siapa yang berinisiatif membudidayakan apel? Apakah cintamu pada-Ku lebih besar dari bahtera Nuh, dari paus yang menelan Yunus? Berapakah kecepatan kuda-kuda yang berkepala singa, yang dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang? Apa warna rambut Simson? Kapankah kekekalan berakhir? Berapa kali Aku harus disalibkan: sampai tujuh puluh kali tujuh kali?
: Benarkah pengkhianatan memisahkan sepasang sahabat lebih lekas dari kecepatan cahaya? Apakah Bruce Lee tidur dengan memeluk boneka beruang? Apa jadinya jika bom Hiroshima meledak di Lautan Teduh? Apakah Jojon tertawa ketika melihat kumisnya sendiri di cermin? Siapakah orang kafir itu? Apakah agamamu? Apakah yang ada dalam pikiranmu? Who, what, when, where, why, how–katanya sekarang bertambah wow? Tahukah kamu siapakah aku: Semakin cepat kamu berlari, semakin sulit kamu menangkapku? Manakah yang lebih dulu: Ayam atau Telur?
: Kenapa makin sedikit bus antarkota yang singgah di stanplat ini dan kondektur garang itu tidak lagi mampir beli kuaci? Di mana mayat gelandangan dikuburkan? Kenapa embun begitu bening dan begitu sekejap? Kenapa anak anjing dan anak kucing suka berantem? Pertanyaan apakah yang tidak pernah dibisikkan kepala kepada bahu yang menjadi sandarannya? Lagu apakah, menurutmu, lagu yang paling sedih di dunia? Kapan aku punya rumah sendiri–kecil saja–dara gepak di kampung yang tenteram? Hampir malam di Yogya, jam berapa keretamu tiba?
Buku menghantui tidurmu dengan Mimpi-Mimpi sialan
Published on June 24, 2020 16:00
June 23, 2020
Francis A. Schaeffer: Pembelaan Rasional bagi Injil

Di Philadelphia pada akhir tahun 1920-an, seorang remaja memutuskan bahwa ia tidak memerlukan Tuhan. Ia telah mencoba ke gereja, namun gereja tidak memberinya jawaban yang dia harapkan.
Setelah beberapa waktu hidup sebagai orang agnostik (orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan dapat diketahui), ia memutuskan untuk membaca Alkitab, mulai dari Kitab Kejadian. Ia ingin menguji sendiri, apakah Allah itu benar-benar ada. Dalam waktu enam bulan, ia pun diyakinkah bahwa Allah itu nyata dan Alkitab Firman yang diwahyukan-Nya bagi umat manusia. Tahun 1930, Francis August Schaeffer yang berumur delapan belas tahun berdoa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya.
Sejak hari itu, selama lebih dari lima puluh tahun, Schaeffer berkomitmen untuk memberitakan Injil dan membelanya secara rasional. Ia menjadi salah satu pemikir dan ahli apologetika terkemuka abad ke-20. Dua puluh empat buku yang dia tulis telah diterjemahkan ke dalam lebih dari dua puluh bahasa. Pesan pokok yang Schaeffer sampaikan: Firman Allah adalah satu-satunya penuntun yang manusia perlukan untuk menafsirkan masa lalunya dan menyelesaikan persoalan-persoalan masa kini.
Ketika Schaeffer lulus dari Faith Theological Seminary tahun 1938, Amerika Serikat tengah menghadapi berbagai persoalan sosial dan keagamaan yang baru dan membingungkan. Gerakan Injili terancam oleh ideologi liberal, yang berpendapat bahwa Alkitab itu bukan sumber kebenaran yang dapat diandalkan. Ia dan isterinya Edith, yang dijumpainya dalam sebuah acara debat di gereja, sama-sama tergugah oleh kesempatan untuk menyampaikan pembelaan bagi doktrin-doktrin konservatif.
Mendirikan L'Abri
Sebagai pendeta sejumlah gereja di Pennsylvania dan Missouri, Schaeffer sedih menyaksikan kompromi yang berlangsung di banyak denominasi Protestan. Kemudian, pada akhir tahun 1940-an, ia berkeliling Eropa sebagai utusan American Council of Christian Churches. Betapa terkejutnya ia ketika menyaksikan bahwa kebutuhan rohani di benua itu jauh lebih besar. Ia pun pindah ke Swis untuk melayani kaum muda.
Schaeffer mendirikan pelayanan Children for Christ pada tahun 1948 di Lausanne. Memiliki tiga orang puteri, Schaeffer mengenal dengan baik tantangan-tantangan untuk mengajar anak muda. Selain itu, ia terus, berkeliling, memberi kuliah serta mempelajari sejarah dan filsafat.
Tahun 1951, hati Schaeffer menjadi gelisah. Ia tidak yakin kalau Allah sedang menuntunnya, dan ia mempertanyakan keyakinan-keyakinannya. Ia mengenang, "Saya merasakan beban yang sangat kuat untuk berdiri bagi Kekristenan historis, dan bagi kemurnian gereja yang kelihatan. Saat saya memikirkan kembali alasan-alasan saya menjadi orang Kristen, saya kembali melihat bahwa ada alasan yang sepenuhnya memadai untuk mengetahui bahwa Allah yang berpribadi dan tidak terbatas itu benar-benar ada dan Kekristenan itu benar."
Namun, apakah cara terbaik untuk menjangkau budaya yang begitu tertutup terhadap Firman Allah? Schaeffer tergugah untuk memulai langsung di tempatnya berada, di Swis. Tahun 1955, ia secara resmi membuka vila kecil mereka di Huemoz sebagai "pondok" pengajaran Alkitab yang kokoh. Siapa saja boleh datang dan menyimak analisis Kitab Suci yang menggugah pemikiran. Tempat peristirahatan dan pencarian rohani ini dikenal sebagai L'Abri (Tempat Perlindungan).
Sepanjang 1950-an, dan khususnya 1960-an, ketika kaum muda banyak menggugat otoritas dan "kaum mapan," L'Abri dikunjungi ribuan orang. Bagaimana mereka menjalankannya? Edith Schaeffer menjelaskan, "Kami berdoa agar Tuhan membawa orang-orang yang Dia pilih... mengirimkan dana yang kami perlukan untuk menunjang semuanya ini, dan membuka rencana-Nya bagi kami."
Mereka memang harus membayar harga yang sangat mahal dengan membuka pintu rumah mereka ini. Francis mengenang, "Dalam kira-kira tiga tahun pertama menjalankan L'Abri, semua kado perkawinan kami terkuras habis. Permadani kami berlubang-lubang bekas terbakar. Ada tirai yang nyaris terbakar seluruhnya karena ada orang yang merokok di ruang keluarga kami... Narkoba masuk ke tempat kami. Orang-orang muntah di kamar-kamar kami."
Pendeta dan penulis Dr. Harold Brown mengatakan, "Pada mulanya dampak teologis L'Abri tidak berlangsung secara institusional... namun secara tidak langsung, melalui orang-orang yang dijumpai oleh keluarga Schaeffer dan kemudian kehidupan mereka diubahkan."
Kembali ke Amerika Serikat
Tuhan terus menyingkapkan maksud-Nya. Tahun 1968, Schaeffer menerbitkan dua buku pertamanya, Escape From Reason dan The God Who Is There. Di situ ia mengupas bagaimana filsafat-filsafat lain gagal untuk menyodorkan jawaban yang memadai bagi masalah-masalah riil di dunia ini. Secara bertahap, karya yang telah dikembangkan oleh Schaeffer selama bertahun-tahun ini pun mulai dikenal, khususnya di Amerika Serikat.
Tahun 1973 Mahkamah Agung A.S. mengeluarkan keputusan atas kasus Roe vs. Wade, yang membuka pintu bagi legalisasi aborsi. Inilah terutama yang mendorong Schaeffer untuk kembali ke Amerika. Dalam buku How Should We Then Live?, Schaeffer membahas masalah-masalah pokok yang menyebabkan merosotnya penghargaan terhadap nilai kehidupan manusia ini.
Schaeffer kerap dikritik oleh orang-orang non-Kristen, namun juga oleh orang-orang Kristen yang cemas oleh pendiriannya yang tegas, berani dan konsisten dalam menerapkan Alkitab tersebut. Profesor Dr. Gene Veith, Jr. berkomentar, "Schaeffer memperlihatkan bahwa Kekristenan ortodoks... cukup kuat untuk menantang gagasan-gagasan sekuler."
Pengaruh Schaeffer sangat luas dan menjangkau kalangan yang beragam, seperti Jack Sparks, penggerak Jesus People; musisi Larry Norman dan Mark Heard; politisi Jerry Falwell, Pat Robertson, Jack Kemp, Chuck Colson, Randall Terry, C. Everett Koop, Cal Thomas, serta Tim dan Beverly LaHaye; juga ilmuwan Harold O. J. Brown, Os Guinness, Thomas Morris, Clark Pinnock, dan Ronald Wells.
Ketika Schaeffer didiagnosis terkena kanker pada tahun 1981 dengan kemungkinan masa hidup hanya tinggal enam bulan, ia tidak berhenti bekerja. Tuhan memberinya tiga tahun lagi, dan ia terus aktif dalam pengajaran dan pelayanan. Penyakitnya, dengan pengobatan yang berkepanjangan dan sering menguras tenaga, membukakan kesempatan baginya untuk berbicara kepada kalangan medis nasional.
Schaeffer meninggal di rumahnya pada 15 Mei 1984. Presiden Ronald Reagan mengatakan, "Jarang kita bisa mengatakan bahwa kehidupan seseorang telah menyentuh banyak kehidupan lainnya dan mempengaruhi mereka untuk menjadi lebih baik. Namun, tentang Dr. Francis Schaeffer, kita dapat mengatakan bahwa kehidupannya telah menyentuh jutaan jiwa dan membawa mereka kepada kebenaran tentang Pencipta mereka." ***
Published on June 23, 2020 16:00
June 22, 2020
Kolya: Malaikat Kecil Pembawa Transformasi

Karena asal berkicau di depan polisi rahasia, Louka kehilangan posisi terhormatnya di Czech Philharmonic Orchestra. Untuk mengongkosi hidupnya, ia hanya bisa bermain selo mengiringi upacara kremasi, dan kadang-kadang membersihkan batu nisan. Kalau ada yang bertanya, dia menjawab dirinya bermain di semacam ensambel. Di usia 55 tahun, ketika semestinya ia mengecap masa kejayaan, hidupnya malah macet.
Di sisi lain, bujangan bersosok ala Sean Connery itu mirip ABG yang tengah ditimang-timang oleh pubertas. Meski baginya menjadi musisi berarti siap melajang, toh bukan berarti ia tak bisa menjawil sejumlah wanita. Dengan santainya ia mencemol bokong Klara yang tengah menyanyikan Mazmur 23 dengan khidmat. Ketika menerima murid perempuan, tak ayal gadis manis itu menjadi sasaran rayuannya. Singkatnya, kehidupan cintanya tanpa pelabuhan.
Di luar itu, ia, tentu saja, membenci Rusia, yang tengah menginjak-injak negerinya. Ironisnya, justru dari Rusialah datang sebuah rahmat terselubung bagi kebuntuan hidupnya.
Seorang teman menawarinya untuk pura-pura menikahi perempuan Rusia yang memerlukan kewargaan Cheska, agar tidak ditundung balik ke Rusia. Ia akan mendapatkan bayaran lumayan untuk itu. Namun, alih-alih kemudian bercerai seperti direncanakan semula, perempuan itu minggat ke Jerman menyusul pacarnya. Sialnya (atau, untungnya?), perempuan itu juga meninggalkan bocah laki-laki berumur lima tahun, Kolya, ke dalam penjagaan Louka. Tentu saja Louka berusaha secepatnya lepas dari si bocah, namun keganjilan pun terjadi: semakin keras Louka berupaya, semakin erat keduanya melekat.
Kisah selanjutnya, bisa ditebak, memaparkan dinamika hubungan Louka-Kolya yang mendatangkan transformasi bagi keduanya. Keunggulan Jan Sverak dan penulis skenario Zdenek Sverak (ayahnya, yang sekaligus berperan sebagai Louka) terlihat dalam membubuhkan detil-detil yang bersahaja namun mengena. Kolya mendesak Louka nonton film kartun Rusia; Louka mengajak Kolya ke rumah ibunya, yang sengit rumahnya disinggahi bocah Rusia; Kolya menelepon neneknya dari bathtub; Kolya mendampingi Louka menjalani interogasi di kantor polisi; Kolya menirukan ritual kremasi. Semua itu ditopang akting menonjol para pemainnya. Selain Zdenek Sverak, Andrej Chalimon sebagai Kolya dan Libuse Safrankova sebagai Klara tampil mantap. Oscar untuk Film Berbahasa Asing Terbaik pun disematkan pada film ini.
Titik balik bagi Louka berlangsung ketika Kolya terserang demam tinggi. Kamera berputar menggambarkan rasa pusing yang mendera Kolya, namun juga mewakili kamar (baca: dunia) Louka yang terputar berbalik arah. Setelah beberapa waktu mengasuh Kolya, Louka menemukan sebuah tataran baru: bahwa cinta tidak diraihnya dengan merenggut, melainkan dengan merengkuh dan menyambut. Bahwa cinta bukan sekadar perkara syahwat, namun soal komitmen dan tanggung jawab. Dengan mempedulikan dan melindungi si bocah, ia menemukan sisi kepriaan dirinya yang selama ini terkubur oleh gaya hidup sembrono. Ia mendapati dirinya menjadi sesosok bapak.
Menariknya, transformasi pribadi tersebut secara halus ditautkan dengan transformasi nasional yang berlangsung di latar belakang. Melalui Revolusi Beludru pada 1988, Republik Cheska mengibaskan cengkeraman komunisme.
Ketika film berakhir, Kolya kembali terbang ke Rusia, mengangkasa seperti malaikat kecil. Louka kembali menjadi musisi terhormat, dan telah menikah. Istrinya berdiri di antara penonton konser dalam keadaan hamil. Sebuah kehidupan baru siap merekah ***
Published on June 22, 2020 16:00
June 21, 2020
Yang Bukan Seleb Tidak Usah Ambil Bagian!

Setelah sekian tahun memerintah dan mereguk manis-getirnya kehidupan, Raja Salomo (Sulaiman) menyimpulkan salah satu pengamatannya, yang menunjukkan betapa ia semakin arif memahami perjalanan hidup manusia. Dalam Kitab Pengkhotbah ia menulis, “Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari: ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan;—untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan?–Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan.”
Umberto Eco, ahli semiotik dan novelis Italia, membuat pengakuan menggelitik. “Saya ingin membuat sebuah buku dan seorang anak, sebab hanya dengan cara itulah kita bisa mengatasi kematian: benda yang terbuat dari kertas dan benda yang terbuat dari daging. Permainan cinta semata-mata, hanya demi kenikmatan belaka, merupakan hal yang tolol; tidak ada hasil yang bisa diperoleh dari hal itu. Tetapi kematian saya bisa mempunyai makna kalau seseorang menggantikan saya dan meneruskan kehidupan saya. Dan saya menulis buku, bukan untuk memperoleh sukses sekarang, tetapi dengan harapan bahwa seribu tahun yang akan datang buku itu paling tidak masih masuk dalam daftar kepustakaan atau dalam catatan kaki.”
Baik Salomo maupun Eco menangkap kegelisahan dan pergumulan manusia untuk memaknai hidupnya, menghitung hari-harinya. Benang merahnya adalah: Setiap orang ingin dikenang.
Namun, ada orang yang “sendirian; tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki”. Ini simbol orang yang egois—hidup hanya untuk diri sendiri. Perspektif mereka sempit, serba mengejar kenyamanan dan sukses sesaat.
Sebaliknya, banyak pula orang yang berusaha "mengatasi kematian". Mereka melakukannya dengan berbagai cara. Ada orang yang menulis buku atau menghasilkan karya seni. Ada yang membangun gedung, lalu menamainya menurut nama mereka. Ada yang memberikan sumbangan besar kepada suatu lembaga, sehingga nama mereka tertera pada piagam penghargaan. Ada pula yang mendirikan yayasan, seperti Yasayan Nobel.
Suatu jalan untuk “mengatasi kematian” yang kian mencuat dan kian marak pada era medsos ini tidak lain adalah: budaya selebritas.
Era Para Seleb
Selebritas, menurut pakar sejarah Daniel Boorstin, adalah "seseorang yang dikenal karena keterkenalannya." Zaman dulu, nama seseorang tidak akan bisa dikenal luas kecuali kalau ia memberikan contoh kebesaran dirinya dalam satu atau lain hal. Dengan kata lain, keunggulan karakter seseoranglah yang benar-benar diperhitungkan. Namun, sepanjang abad kedua puluh, semakin lama semakin rancu pengertian antara pemujaan terhadap selebritas dan pemujaan terhadap para pahlawan yang meneladankan keunggulan karakter. “Kita semua sudah rela disesatkan, sehingga percaya,” kata Boorstin, “bahwa kemasyhuran—keterkenalan—masih menjadi tanda kebesaran.”
Bukan hanya para bintang dalam industri hiburan, tetapi pengusaha, pengacara, dokter, ekonom, penulis, pendidik, pemimpin agama sampai presiden pun bisa tergoda mengenakan selubung selebritas yang serba kemilau. Pejabat pemerintah dan wakil rakyat yang bukannya sibuk tebar kinerja malah hilir-mudik tebar pesona tengah berkubang dalam gebyar budaya selebritas. Dan, kita memuja-muja para pesohor itu—sosok-sosok yang oleh Boorstin disebut pseudo-people, orang-orang semu. Era ini seolah-olah berseru: Yang bukan seleb tidak usah ambil bagian!
Budaya selebritas menghancurkan realitas dan menggantinya dengan ilusi: yang disebut reality show di televisi itu tidak lain pementasan kejadian yang telah direkayasa dan diarahkan; sosok-sosok pesohor yang mondar-mandir di ruang publik itu telah dibesut sedemikian rupa sehingga menampilkan citra sesuai dengan yang diinginkan. Budaya selebritas menawari kita kemasan yang elok, dengan substansi yang bagai kucing dalam karung. Dalam budaya selebritas, prestasi bisa berkibar-kibar tanpa landasan karakter dan budi pekerti yang kokoh. Budaya selebritas, singkatnya, menawarkan perspektif yang juling: ia menyulap kesia-siaan menjadi komoditas yang menawan.
Sebagai sebentuk kesemuan, budaya selebritas tidak jarang menelan korbannya sendiri. Simaklah kisah Bimbi yang “langsung ngetop namanya” dalam lagu Titiek Puspa. Atau, simaklah kisah Howard Hughes.
Menggilas Akal Sehat
Kebanyakan orang akan menganggap ia telah berada di puncak dunia. Apa lagi yang masih kurang? Sejak kecil ia telah bermimpi—“Kalau aku besar nanti, aku akan menerbangkan pesawat tercepat yang pernah dibuat manusia, membesut film terhebat yang pernah ada, dan menjadi orang paling kaya di dunia”—dan hidupnya merupakan penggenapan dari impian tersebut. Ketika masih remaja ia telah mewarisi bisnis ayahnya yang sukses. Dengan kucuran dana yang seperti tak kunjung habis, ia mengerahkan segenap kenekatan untuk mewujudkan serangkaian ide gilanya. Dunia dibuatnya tercengang. Selebihnya, sederetan selebritas jelita jatuh ke dalam pelukannya.
Penggalan hidupnya tersebut diangkat ke dalam film The Aviator (2004) garapan Martin Scorsese. Hughes tampil sebagai sosok yang flamboyan, jenius, visioner, keras kepala, playboy, dan eksentrik. Namun, ia juga sekaligus penyendiri: Ia fobia terhadap orang dan bakteri, dan nantinya digerogoti penyakit mental dan fisik. Dalam dirinya, kita melihat batas tipis antara kejeniusan dan kegilaan.
Film ini merayakan sisi tersebut secara gegap-gempita, tetapi The Aviator berhenti saat Hughes berada di tubir ketidakwarasan. Scorsese tampaknya enggan memotret akhir tragis tokoh ini. Selama sepuluh tahun terakhir masa hidupnya sampai meninggal pada 1976, Hughes menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan menyendiri, berpindah-pindah dari penthouse hotel satu ke penthouse hotel lainnya.
Ketika selama empat tahun tinggal di Desert Inn Hotel, Las Vegas, ia suka menonton televisi mulai dari tengah malam sampai pukul enam pagi. Sayangnya, stasiun setempat hanya mengudara sampai pukul sebelas malam. Asisten Hughes berulang mendesak Hank Greenspun, pemilik stasiun, untuk menyiarkan film-film koboi dan penerbangan kesukaan Hughes pada jam-jam dini hari. Greenspun akhirnya menjawab, “Kenapa ia tidak membeli saja stasiun ini dan memutar program sesuka hatinya?” Hughes sepakat, dan ia pun mengeluarkan 3,6 juta dolar untuk membeli stasiun itu—agar dapat menyiarkan acara favoritnya dari pukul sebelas malam sampai pukul enam dini hari.
Sewaktu ia meninggal dunia, gaya hidupnya yang suka menyendiri dan penggunaan obat-obatan secara berlebihan membuat penampilannya sulit dikenali. Rambut, cambang, kuku jari tangan, dan kuku jari kakinya bertumbuh panjang tak terurus. Tubuhnya yang semula kuat dan tegap tinggal berbobot sekitar 41 kilogram. FBI mesti mengambil sidik jarinya guna mengenali identitas jenazah tersebut. Hidupnya berakhir secara mengenaskan.
Impiannya, akan pesawat yang mampu terbang di atas awan dan mengangkut banyak penumpang sekaligus, merupakan sebuah terobosan jauh ke masa depan. Di sini kita salut akan kegigihannya mewujudkan visi, berapa pun harga yang harus dibayarnya. Di sisi lain, menyimak gaya hidupnya yang serba gemerlap, tetapi sekaligus ditelikung oleh obsesi seksual, cengkeraman materialisme, dan gangguan mental, kita sedang menyaksikan drama selebritas yang getir dan mengguncangkan.
Budaya selebritas melahirkan pemaknaan yang sungsang terhadap pencapaian hidup dan kehidupan itu sendiri. Budaya selebritas memperkuat kesemuan, bukan kesejatian. Ia menawarkan sebuah gaya hidup yang menggilas akal sehat.
Makna Hidup
Orang kerap menyamakan kehidupan yang penuh makna dengan kehidupan yang sukses. Namun, bila kita renungkan lebih jauh, sukses tidak menjamin bahwa kita akan meninggalkan "warisan", sesuatu yang berharga dan akan terus dikenang oleh generasi selanjutnya.
Bahkan, kalau kita hidup hanya untuk mengejar sukses, kita akan sangat frustasi. Mengapa? Ketika kita mengukir sebuah prestasi, kita berpikir, “Aku berhasil!” Namun, beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, perasaan itu akan memudar. Maka, kita harus menetapkan sasaran lain, mengejar tantangan lain—selagi gairah dan tenaga belum loyo. Hasilnya: Sebuah lingkaran setan yang terdiri atas tidak pernah cukup dan tidak pernah puas!
Jadi, bagaimana sepatutnya kita hidup? Apakah kita akan menghabiskan hidup ini dengan dengan mengejar sukses demi sukses? Rancho dalam film 3 Idiots mengatakan, “Jangan mengejar sukses. Kejarlah keunggulan, maka kesuksesan akan mengikuti di belakangmu.” Dengan kata lain, ada perkara dalam hidup ini yang jauh lebih hakiki daripada sukses itu sendiri.
Pandangan orang-orang bijak dari zaman ke zaman menunjukkan hal tersebut. Sehubungan dengan makna hidup, mereka menyampaikan jawaban yang sederhana, tetapi sangat mendalam. Orang Yunani, misalnya, menganggap kesenangan hidup yang mendalam lebih ditentukan oleh kondisi pikiran, bukan oleh keadaan tubuh. Negarawan Romawi Cicero menyatakan, “Tidak ada orang bodoh yang bahagia, dan tidak ada orang bijaksana yang tidak bahagia.” Filsuf Yunani Epicurus menyimpulkan, orang yang paling puas mengingat masa lalu dengan penuh ucapan syukur dan menerima situasi mereka saat ini tanpa mencemburui apa yang dimiliki orang lain.
Yesus Kristus ketika mewartakan Injil menawarkan Hukum Kasih. Ia mengaitkan kesuksesan hidup bukan dengan pencapaian, kekuasaan, atau akumulasi kekayaan, melainkan dengan hubungan. Ketika ditanyai tentang perkara yang paling penting dalam hidup ini, ia menunjuk pada tiga hubungan utama dalam kehidupan kita: hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan sesama.
Dalam hubungan dengan Tuhan, kita menemukan signifikansi. Kita diterima dan dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat. Kasih Tuhan inilah sumber dan motivasi untuk memiliki hubungan yang benar dengan diri sendiri dan sesama. Brennan Manning, imam Katholik dan penulis AS, menggarisbawahi, “Definisikan dirimu sendiri secara radikal sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah identitas diri yang sejati. Identitas lainnya hanyalah ilusi.”
Dalam hubungan dengan diri sendiri, kita menemukan otentisitas. Otentisitas berkaitan dengan kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai pribadi yang unik dan diciptakan oleh Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Otentisitas ini selanjutnya menantang kita untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup, agar dapat melayani orang lain dengan lebih baik lagi.
Adapun dalam hubungan dengan sesama, kita menyatakan kasih. Kita dipanggil untuk menjadi rahmat dan berkat bagi sesama. Orang Jawa mengatakan, “Urip ikut urup” (Hidup kita hendaknya bermanfaat bagi orang lain). Bersediakah kita melayani dan menolong satu sama lain tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan? Maukah kita “memayu hayuning bawana, ambrasta dur angkara” (mengupayakan kesejahteraan bersama, melawan ketidakadilan)?
Bahwa hubungan adalah yang terutama, bukan berarti kita menafikan sukses. Hubungan dimaksudkan untuk menempatkan sukses pada perspektif yang semestinya. Sukses bukan lagi tujuan akhir; sukses hanyalah salah satu sarana untuk membangun makna hidup. Untuk setiap kesuksesan kita dapat bertanya: Apakah dengan kesuksesan ini saya semakin mensyukuri kebaikan Tuhan? Apakah saya menemukan otentisitas diri lebih jauh lagi? Apakah hal ini mendorong saya mengasihi dan melayani sesama dengan lebih baik?
Dengan memaknai hidup sedemikian rupa, sejatinya kita sedang mengatasi kematian. ***
Published on June 21, 2020 16:00
June 19, 2020
Nasib Seorang Pemulung
Seorang pemulung tua mengikuti kebaktian di sebuah gereja. Ketika pendeta menyampaikan undangan untuk bertobat, perempuan itu ikut maju. Pendeta menyimak perempuan itu menceritakan bagaimana dirinya menerima Yesus, ingin dibaptis air dan menjadi anggota gereja itu.
Pendeta itu tercenung. “Ya, ampun, jorok banget orang ini. Bau lagi! Kukunya pun hitam. Pantas pekerjaannya mengumpulkan sampah. Apa nanti kata anggota jemaat yang lain?” pikirnya. Ia lalu meminta perempuan itu pulang dan berdoa sungguh-sungguh, baru kemudian mengambil keputusan.
Minggu depannya, perempuan itu datang lagi. Ia mengatakan pada pendeta bahwa dirinya telah berdoa dan tetap ingin dibaptis. “Saya sudah sekian lama memperhatikan gereja ini. Gereja ini indah sekali, dan saya benar-benar ingin menjadi anggotanya.”
Kembali pendeta itu meminta pulang dulu dan berdoa lagi.
Beberapa minggu kemudian ketika sedang makan di restoran, pendeta itu melihat perempuan tadi. Karena tidak ingin dianggap angkuh, ia pun mendekatinya dan menyapa, “Sudah beberapa minggu saya tidak melihat Ibu. Semuanya baik-baik saja, kan Bu?”
“Oya,” jawab perempuan itu. “Saya sudah berbicara dengan Yesus, dan Ia mengatakan bahwa saya tidak perlu repot-repot berusaha menjadi anggota gereja Anda.”
“Oya? Kenapa?” tanya pendeta itu.
“Begini,” jawab perempuan itu. “Ia mengatakan bahwa Ia sendiri tidak berhasil masuk ke gereja Anda, padahal Ia sudah berusaha selama bertahun-tahun.”

Pendeta itu tercenung. “Ya, ampun, jorok banget orang ini. Bau lagi! Kukunya pun hitam. Pantas pekerjaannya mengumpulkan sampah. Apa nanti kata anggota jemaat yang lain?” pikirnya. Ia lalu meminta perempuan itu pulang dan berdoa sungguh-sungguh, baru kemudian mengambil keputusan.
Minggu depannya, perempuan itu datang lagi. Ia mengatakan pada pendeta bahwa dirinya telah berdoa dan tetap ingin dibaptis. “Saya sudah sekian lama memperhatikan gereja ini. Gereja ini indah sekali, dan saya benar-benar ingin menjadi anggotanya.”
Kembali pendeta itu meminta pulang dulu dan berdoa lagi.
Beberapa minggu kemudian ketika sedang makan di restoran, pendeta itu melihat perempuan tadi. Karena tidak ingin dianggap angkuh, ia pun mendekatinya dan menyapa, “Sudah beberapa minggu saya tidak melihat Ibu. Semuanya baik-baik saja, kan Bu?”
“Oya,” jawab perempuan itu. “Saya sudah berbicara dengan Yesus, dan Ia mengatakan bahwa saya tidak perlu repot-repot berusaha menjadi anggota gereja Anda.”
“Oya? Kenapa?” tanya pendeta itu.
“Begini,” jawab perempuan itu. “Ia mengatakan bahwa Ia sendiri tidak berhasil masuk ke gereja Anda, padahal Ia sudah berusaha selama bertahun-tahun.”

Published on June 19, 2020 16:00
June 18, 2020
Jumpalitan Berwaktu Teduh

Susanna Wesley dikaruniai 19 anak. Sembilan di antaranya meninggal ketika masih bayi. Para ibu tentu tahu benar betapa repotnya ibu yang satu ini. Toh ia termasyhur sebagai seorang yang gigih berwaktu teduh. Di tengah kesibukan mengasuh anak-anak, ia meluangkan waktu untuk membangun hubungan personal dengan Tuhan setiap hari. Bila tidak berhasil menemukan ruang yang tenang di rumah, ia akan duduk di dapur, menutupi kepalanya dengan celemek. Anak-anaknya sudah diberi tahu, bila ibu sedang berkerudung seperti itu, ia tidak boleh diganggu. Ia sedang menikmati waktu teduhnya dengan Tuhan.
Kisah yang inspiratif, ya? Atau... justru malah tidak? Bagi saya, terus terang, kisah semacam itu membuat saya terayun antara terinspirasi dan terintimidasi. Di satu sisi saya berdecak kagum, ”Wah, hebat ya Susanna Wesley. Ia memang patut diteladani. Aku berharap bisa seperti itu.” Di sisi lain, saya tersipu malu, ”Aku ini belum sesibuk Susanna. Anak baru dua, tapi kok jumpalitan, susah menjaga konsistensi dalam berwaktu teduh.” Atau lalu malah putus asa, ”Bertahun-tahun sudah aku berusaha berwaktu teduh, belum juga aku mencapai taraf kegigihan seperti itu. Berwaktu teduh secara konsisten itu memang jatah khusus para raksasa iman. Apalah awak ini.”
Untunglah, Michael Phelps – ya, jawara renang dari Amerika Serikat yang menyabet delapan medali emas dalam Olimpiade Beijing 2008 itu – menyadarkan saya. Saya, terus terang, sampai saat ini belum bisa berenang. Tetapi, saya ingin belajar berenang. Nah, kalau tujuan saya belajar berenang adalah dalam waktu setahun dua tahun ke depan bisa menyamai prestasi Phelps, betapa bodohnya saya! Bisa dijamin, saya bisa menyerah sebelum jalan. Tetapi, kalau tujuan saya kira-kira dalam waktu sebulan dua bulan paling tidak saya sudah bisa mengapung dan menggerakkan tubuh di air secara benar, puji Tuhan, saya berada di jalur yang tepat.
Dari situ saya mendapatkan pencerahan: saya perlu berfokus pada tujuan pokok sesuatu. Kalau saya berolahraga dengan harapan meraih medali Olimpiade, besar kemungkinan saya akan patah semangat – bukankah tidak setiap orang berbakat dan dipanggil untuk menjadi atlet dunia? Namun, kalau saya berolahraga untuk menjaga kebugaran dan keseimbangan tubuh, saya akan bisa mengalami olahraga sebagai aktivitas menyenangkan yang diperlukan setiap orang yang ingin sehat.
Mirip dengan waktu teduh. Waktu teduh adalah suatu disiplin kerohanian, semacam cabang olah raga rohani. Bagusnya, tidak ada arena Olimpiade Rohani yang menantang kita berkompetisi dengan saudara seiman yang lain. Jadi, saya pun sebetulnya tidak perlu terintimidasi oleh kinerja Susanna Wesley atau pendekar waktu teduh lainnya. Saya hanya perlu berfokus pada tujuan pokok waktu teduh: menjalin hubungan personal dengan Tuhan. Bukankah itu sebuah tujuan yang melegakan, sebuah tujuan yang oleh anugerah Tuhan disediakan bagi setiap orang beriman, bukan hanya bagi rohaniman elit?
Setelah mantap dengan tujuan itu, disiplin berwaktu teduh dapat dijalani kira-kira seperti disiplin berolahraga. Suatu ketika, saya mencoba mulai berolahraga jalan cepat (catatan: sebelumnya saya tidak terbiasa berolahraga). Pakar kesehatan menyarankan, untuk mencapai taraf kebugaran minimal, saya harus berjalan kaki sejauh 3,2 km dalam waktu kurang dari 30 menit dan melakukannya paling sedikit tiga kali seminggu. Namun, saya malah bisa terkapar sakit bila berusaha mencapai taraf kebugaran itu dalam minggu pertama. Bukan begitu caranya. Melainkan, saya harus mengawalinya dengan berjalan cepat 10 menit pada minggu pertama, menambah porsi 5 menit pada minggu berikutnya, 5 menit lagi minggu depannya, dan seterusnya. Meningkat secara bertahap, sedikit demi sedikit – itu dia kuncinya!
Tantangan berikutnya adalah konsistensi. Ini cerita yang lain lagi. Saya berhasil memenuhi tuntutan taraf kebugaran minimal dalam waktu sekitar sebulan, kemudian asyik berjalan cepat 30 menit setiap pagi selama... sekitar empat bulan. Ketika kami sekeluarga pindah rumah, saya melupakan aktivitas jalan cepat.
Berwaktu teduh juga perlu dikembangkan secara bertahap dan secara konsisten, dan tantangan untuk konsisten saya akui lebih berat. Dalam persekutuan bapak-bapak di gereja kami, kami ditantang untuk berwaktu teduh secara rutin selama sepuluh minggu berturut-turut – dengan penegasan: tanpa bolong-bolong. Anda tentu bisa menebak apa yang terjadi: pada minggu kedua saya sudah gagal. Saya melewatkan hari tertentu tanpa berwaktu teduh. Lalu?
Di sini saya mesti berhenti membandingkan waktu teduh dengan olahraga dan kembali pada esensi waktu teduh: hubungan. Hubungan oleh anugerah Allah. Artinya, Allah yang memprakarsai, Allah yang memampukan, dan Allah yang menyempurnakan kita. Pengakuan Teresa dari Avila – ”Ya Tuhan, aku tidak mengasihi-Mu. Aku bahkan tidak ingin mengasihi-Mu. Tetapi Tuhan, aku ingin agar aku ingin mengasihi-Mu. Amin” – meneguhkan hal itu. Kita tidak dapat memantik dan mempertahankan kerinduan tersebut dengan kekuatan kita sendiri. Hubungan ini hanya mungkin diawali dan dipelihara oleh anugerah Allah.
Dalam hal ini, kesaksian orang percaya yang merindukan hubungan personal dengan Tuhan kembali menguatkan saya. Selain kesaksian kegigihan ala Susanna, saya juga menemukan pengakuan mereka yang bergumul untuk menjalani waktu-waktu persekutuan dengan Tuhan. C.S. Lewis, misalnya, secara jujur mengakui kesulitannya berkonsentrasi. ”Yang paling sering mengganggu doa pribadi saya bukanlah hambatan yang besar, melainkan hambatan yang kecil-kecil, yaitu hal-hal yang harus dilakukan atau dihindari pada jam-jam berikutnya,” katanya.
Penulis The Chronicles of Narnia ini bahkan pernah terpuruk. Ketika istrinya tercinta, Joy Davidman, meninggal karena kanker, ia sangat terpukul. Imannya terguncang, dan tak ayal hal itu berpengaruh pada hubungannya dengan Tuhan. ”Bila kita bahagia, begitu bahagia sehingga merasa tidak membutuhkan Dia, begitu bahagia sehingga tergoda untuk merasa bahwa tuntutan-Nya atas diri kita merupakan gangguan, jika Anda teringat pada diri sendiri dan berpaling kepada Dia dengan ucapan syukur dan pujian, Anda akan – atau begitulah rasanya – disambut dengan tangan terbuka. Tetapi, cobalah mendatangi-Nya sewaktu kebutuhan Anda begitu mendesak, sewaktu segala bantuan lain sia-sia saja, apa yang akan Anda temukan? Pintu yang dibanting di depan hidung dan suara gerendel dan gembok dipasang di sebelah dalam. Sesudah itu, senyap,” ungkapnya dalam sebuah buku yang sangat personal, A Grief Observed (1960).
Namun, akhirnya Lewis menemukan keteguhan. Ia menyatakan, ”Saya tahu sekarang mengapa saya tak mendapatkan jawaban apa pun. Karena Engkaulah Jawaban itu sendiri. Sewaktu saya menemukan Engkau, segala pertanyaan pun lenyaplah.”
Pengalaman Susanna dan Lewis, bagi saya, memberikan gambaran sekilas tentang potensi hubungan personal dengan Tuhan. Dengan penuh kegigihan, kita mungkin mencapai puncak gunung keintiman dengan Tuhan yang mengobarkan hati. Akan tetapi, boleh jadi pula kita malah terbanting ke dalam lembah pekat kekelaman yang menggiriskan. Satu-satunya harapan kita hanyalah: baik di puncak gunung maupun di ceruk lembah, Tuhan hadir – Dia senantiasa menyertai kita. Dia menggunakan baik ekstasi puncak gunung maupun sengsara ceruk lembah untuk membentuk dan memperkokoh iman kita.
Allah tidak murka dan memutuskan hubungan ketika saya gagal berwaktu teduh satu kali, bahkan sekalipun saya gagal ribuan kali. Dia senantiasa mengulurkan tangan. Tinggal saya memberi diri untuk direngkuh kembali oleh-Nya: menyadari ketidakkonsistenan saya, mengakui ketidakmampuan saya, dan menerima pemulihan dan pertolongan-Nya untuk mencoba lagi dengan kekuatan baru dari-Nya. Sekalipun saya gagal untuk konsisten, mudah-mudahan saya tidak pernah gagal untuk secara gigih mencoba dan mencoba lagi.
Oleh anugerah-Nya. ***
Published on June 18, 2020 16:00



